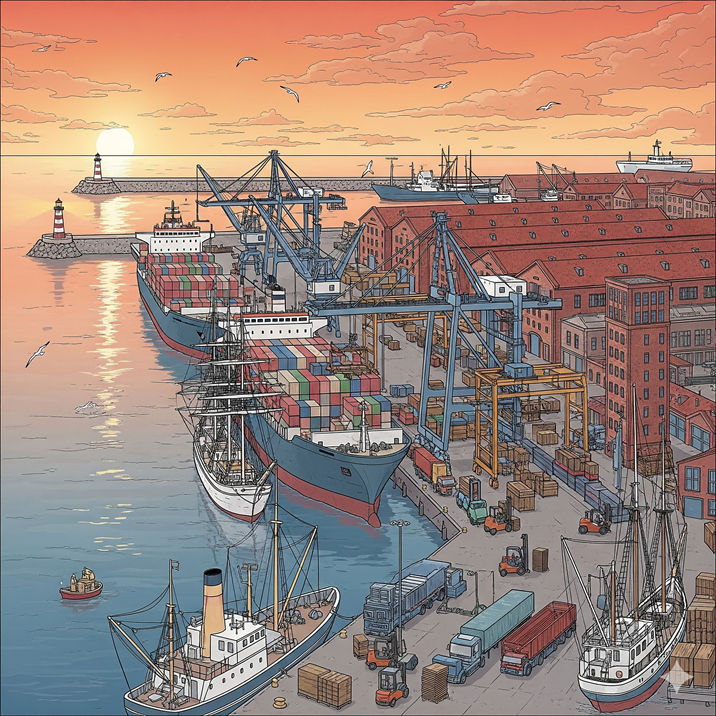Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, peran pelabuhan laut bagi Indonesia adalah fundamental dan strategis, berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi yang menghubungkan perdagangan domestik dan internasional. Pelabuhan menjadi gerbang utama bagi pergerakan barang dan penumpang, mendukung visi nasional untuk menjadi negara maritim yang berdaulat dan berkelanjutan. Namun, kompleksitas operasional, tantangan manajerial, dan hambatan struktural yang ada di sektor kepelabuhanan seringkali menghambat realisasi potensi tersebut.
Laporan ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam dan bernuansa mengenai kondisi pelabuhan laut di Indonesia, dengan fokus pada tiga pilar utama: manajemen, kinerja, dan hambatan. Analisis ini akan melampaui deskripsi faktual untuk mengeksplorasi keterkaitan antara struktur tata kelola, metrik operasional, dan tantangan yang dihadapi. Dengan mensintesis data dan temuan dari berbagai sumber, laporan ini akan mengungkap paradoks yang ada dalam ekosistem logistik maritim Indonesia serta menawarkan rekomendasi strategis untuk perbaikan di masa depan.
Lanskap Manajemen dan Tata Kelola Pelabuhan Indonesia
Manajemen pelabuhan di Indonesia diatur dalam kerangka yang memisahkan peran regulator dari operator, sebuah model yang dirancang untuk mendorong kompetisi yang sehat dan tata kelola yang transparan. Kerangka ini melibatkan dua entitas utama: pemerintah sebagai regulator dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai operator.
Peran Regulator: Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pemerintah di Pelabuhan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menempati posisi sentral sebagai regulator dan perumus kebijakan utama dalam penyelenggaraan pelabuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Menteri mengatur sepenuhnya penyelenggaraan pelabuhan dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas kepemimpinan umum, yaitu Administrator Pelabuhan atau Kepala Pelabuhan. Dalam kerangka manajemen modern, peran ini diemban oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
KSOP, sebagai perpanjangan tangan Kemenhub di tingkat pelabuhan, memiliki serangkaian fungsi vital. Tanggung jawabnya mencakup pengawasan dan penindakan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, seperti pemeriksaan kelaikan kapal dan penerbitan surat persetujuan berlayar. Selain itu, KSOP bertanggung jawab atas pengendalian lalu lintas dan angkutan laut, pemeliharaan infrastruktur dasar seperti alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di pelabuhan, seperti kepabeanan dan karantina.
Sebuah langkah signifikan dalam memperkuat peran regulator adalah penggabungan Otoritas Pelabuhan Utama dan Kantor Syahbandar Utama menjadi KSOP Utama. Restrukturisasi ini bertujuan untuk menyinergikan fungsi pengawasan dan operasional pemerintah di dalam satu institusi, sehingga menciptakan koordinasi yang lebih efektif.
Peran Operator: Transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Sejalan dengan reformasi tata kelola, peran operator pelabuhan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Berbeda dengan KSOP yang berfokus pada fungsi pemerintahan, Pelindo mengemban tugas komersial. Fungsi utamanya mencakup penyediaan dan pelayanan dermaga, bongkar muat peti kemas dan kargo lainnya, jasa pemanduan dan penundaan kapal, serta pengelolaan gudang dan fasilitas penunjang lainnya.
Strategi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Pelindo adalah melalui program merger. Pada tahun 2020, empat entitas Pelindo yang sebelumnya beroperasi secara terpisah digabungkan menjadi satu kesatuan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan entitas yang lebih terintegrasi, mampu melakukan standarisasi layanan, dan mengoptimalkan aset secara nasional, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional di seluruh pelabuhan.
Dinamika Hubungan Regulator-Operator dan Potensi Hambatan
Meskipun model pemisahan peran antara regulator dan operator secara teoritis bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang efisien, pelaksanaannya di lapangan menghadapi tantangan. Laporan dari tahun 2001 menunjukkan adanya kerancuan konsep pengelolaan pelabuhan yang diakui oleh Ditjen Perhubungan Laut, yang mana tidak dapat dipastikan apakah model yang dipegang oleh Pelindo adalah operating port atau land port.
Ambiguitas konseptual ini dapat mengarah pada tumpang tindih kewenangan dan proses perizinan yang rumit. Kondisi ini, pada akhirnya, menimbulkan hambatan birokrasi yang memperlambat arus logistik dan memicu inefisiensi. Tuntutan untuk memperjelas kerangka hukum dan memberikan payung yang lebih kuat bagi peran sektor swasta dalam penyelenggaraan pelabuhan muncul sebagai respons terhadap kerancuan ini. Kompleksitas regulasi yang ada, yang mencapai lebih dari 2.500 aturan, sering kali menjadi akar masalah utama dalam sistem logistik nasional.
Evaluasi Kinerja Pelabuhan: Indikator Kuantitatif dan Kualitatif
Kinerja pelabuhan Indonesia dapat dinilai melalui berbagai indikator, mulai dari metrik operasional mikro hingga peringkat global yang lebih luas. Terdapat sebuah paradoks yang menarik dan krusial antara perbaikan yang signifikan di tingkat mikro dengan stagnasi di tingkat makro.
Analisis Dwelling Time dan Daya Saing Global
Pada tahun 2024, rata-rata dwelling time (waktu inap peti kemas) nasional tercatat sebesar 2,88 hari, sebuah pencapaian yang memenuhi target pemerintah sebesar 2,90 hari. Kinerja ini menunjukkan efisiensi yang semakin baik, terutama di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok (2,73 hari) dan Makassar (2,26 hari). Perbaikan ini didukung oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah yang telah diterapkan dalam tujuh tahun terakhir, seperti simplifikasi perizinan, penerapan system Single Submission, dan digitalisasi proses.
Peningkatan efisiensi ini juga tercermin dalam peringkat global. Menurut Container Port Performance Index (CPPI) 2023 yang dirilis oleh World Bank Group dan S&P Global Market Intelligence, Pelabuhan Tanjung Priok berhasil melonjak drastis dari peringkat 281 pada tahun 2022 menjadi peringkat 23 dunia. Pencapaian ini menempatkan Tanjung Priok di posisi ketiga di kawasan ASEAN, di bawah Pelabuhan Tanjung Pelepas Malaysia dan Singapura. CPPI mengukur efisiensi berdasarkan waktu kapal kontainer berada di pelabuhan.
Berikut adalah tabel yang merangkum perbandingan kinerja beberapa pelabuhan utama di Indonesia:
Tabel 1 Perbandingan Kinerja Pelabuhan Utama Indonesia 2024
| Nama Pelabuhan | Rata-rata Dwelling Time 2024 (hari) | Peringkat CPPI 2023 |
| Tanjung Priok | 2,73 | 23 |
| Makassar | 2,26 | (Tidak disebutkan) |
| Belawan | 2,97 | 308 |
| Tanjung Perak | 3,04 | 101 |
| Tanjung Emas | 3,45 | 150 |
Paradoks Kinerja: Antara Efisiensi Operasional dan Biaya Logistik
Meskipun pencapaian di tingkat operasional, terutama dalam penurunan dwelling time dan peningkatan peringkat CPPI, patut diapresiasi, terdapat sebuah paradoks yang signifikan. Perbaikan ini belum secara konsisten tercermin dalam perbaikan kinerja logistik nasional secara keseluruhan. Skor Logistics Performance Index (LPI) Indonesia, sebuah indikator yang lebih komprehensif, tercatat stagnan antara 2,94 dan 3,15 dari tahun 2014 hingga 2023, bahkan mengalami penurunan 0,15 poin dari tahun 2018 ke 2023. Skor ini masih tertinggal jauh di belakang negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Fenomena ini dapat dijelaskan dengan pemahaman bahwa dwelling time hanya merupakan salah satu komponen dari keseluruhan biaya logistik. Analisis menunjukkan bahwa meskipun waktu inap di pelabuhan berkurang, biaya logistik justru meningkat akibat biaya tambahan seperti Transfer of Pile Location (PLP) atau overbridge. PLP adalah biaya yang timbul saat peti kemas dipindahkan dari tempat penimbunan sementara (TPS) awal ke lokasi lain untuk menekan kepadatan. Keberhasilan dalam memangkas dwelling time tampaknya hanya memindahkan masalah, tanpa mengatasi akar masalahnya, yaitu biaya yang terkait dengan birokrasi dan inefisiensi sistemik.
Oleh karena itu, meskipun Pelindo telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional di dalam pelabuhan—sebagaimana tercermin dalam CPPI yang tinggi—kinerja makro yang diukur oleh LPI tetap rendah karena hambatan yang ada di luar kendali operator pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa isu utama dalam logistik Indonesia tidak hanya terletak pada operasional pelabuhan, tetapi pada ekosistem yang lebih luas yang melibatkan regulasi, koordinasi, dan tata kelola.
Mengidentifikasi Hambatan dan Tantangan dalam Ekosistem Pelabuhan
Hambatan yang dihadapi dalam sektor kepelabuhanan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: teknis-operasional dan non-teknis-sistemik. Studi menunjukkan bahwa hambatan non-teknis merupakan akar masalah yang lebih dalam dan signifikan.
Hambatan Teknis-Operasional
Tantangan fisik masih menjadi kendala di banyak pelabuhan. Minimnya fasilitas dan alat pendukung, serta sarana dan prasarana yang belum sejalan dengan perkembangan volume barang, seringkali menghambat kinerja. Keterbatasan infrastruktur, seperti kedalaman alur yang tidak memadai, membatasi kapal-kapal berukuran besar untuk bersandar, yang berdampak pada efisiensi dan biaya angkut. Selain itu, masalah sedimentasi tinggi, YOR (Yard Occupation Ratio) yang melampaui ambang batas 65%, dan kurangnya lahan parkir serta konektivitas darat dari/ke daerah penyangga juga menjadi tantangan operasional yang nyata.
Hambatan Non-Teknis dan Sistemik
Masalah-masalah yang paling menghambat efisiensi logistik nasional adalah yang bersifat non-teknis. Laporan dari Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya “rapor merah” layanan publik di empat pelabuhan besar, yang ditandai dengan berbagai praktik maladministrasi.
Birokrasi dan tumpang tindih regulasi menjadi salah satu akar masalah utama. Proses perizinan impor, misalnya, belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem, sehingga membutuhkan persetujuan dari banyak instansi. Hal ini menyebabkan proses pre-clearance yang panjang, di mana importir harus menunggu persetujuan dari berbagai kementerian/lembaga.
Selain itu, kurangnya koordinasi antar-instansi, seperti antara Bea Cukai dan Karantina, menciptakan “ego sektoral” yang menghambat kelancaran proses. Contoh konkret dari masalah ini adalah kurangnya pertukaran data manifest antara kedua instansi, yang mengakibatkan peti kemas yang sudah dikeluarkan oleh Bea Cukai harus ditahan kembali untuk pemeriksaan karantina, menimbulkan risiko kontaminasi hama dan penyakit.
Masalah tata kelola juga menjadi kendala. Pungutan liar (pungli) yang membebani biaya logistik dan praktik maladministrasi, seperti perilaku lambat dan tidak peduli, ditemukan dalam investigasi Ombudsman di beberapa pelabuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem dan infrastruktur saja tidak akan cukup tanpa komitmen yang kuat untuk memberantas masalah tata kelola yang sistemik.
Tabel 2. Hambatan Non-Teknis dan Dampaknya di Pelabuhan Utama (Studi Kasus Ombudsman)
| Nama Pelabuhan | Masalah Utama | Dampak Spesifik |
| Tanjung Priok | Proses perizinan yang panjang | Keterlambatan penerbitan SPPB; waktu tunggu tiga hingga lima hari untuk inspektur |
| Kurangnya koordinasi antar-instansi | Peti kemas yang sudah keluar harus dihancurkan akibat pemeriksaan karantina yang terpisah | |
| Tata kelola yang buruk | Pungutan liar Rp200,000.00-Rp400,000.00 per peti kemas | |
| Tanjung Perak | Kurang koordinasi data manifest | Peti kemas yang sudah keluar harus diperiksa ulang, memperlama waktu |
| Pungli | Penundaan jika pungutan ilegal tidak dibayar | |
| Soekarno Hatta | Sistem yang tidak terintegrasi | Kegiatan impor/ekspor tidak terkoneksi dengan sistem INSW; kurangnya data kepabeanan |
| Fasilitas dan SDM tidak memadai | Tidak ada fasilitas pemeriksaan yang memadai di pelabuhan; pemeriksaan dilakukan di gudang swasta |
Inisiatif Strategis Pemerintah dan Evaluasi Dampak
Menyadari tantangan-tantangan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis untuk memperbaiki kinerja logistik maritim. Namun, efektivitas dari inisiatif ini bervariasi.
Program Tol Laut
Program Tol Laut, yang diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo, dirancang untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia Barat dan Timur. Program ini melibatkan rute pelayaran terjadwal yang disubsidi dan pembangunan pelabuhan peti kemas baru di daerah terpencil. Sejak diluncurkan pada tahun 2015 dengan tiga rute awal, program ini telah berkembang menjadi 39 rute yang melayani lebih dari 100 pelabuhan pada tahun 2023.
Meskipun niatnya baik, evaluasi efektivitas program ini menunjukkan hasil yang beragam. Sebuah penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat efektivitas subsidi Tol Laut dalam mengurangi disparitas harga komoditas hanya mencapai 38% dari enam rute pelayaran yang dievaluasi. Angka ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi alokasi dana pemerintah dan menyoroti perlunya skema subsidi dan program insentif yang lebih adaptif untuk meningkatkan volume muatan kapal.
Digitalisasi: Inaportnet dan Ekosistem Logistik Nasional (NLE)
Digitalisasi adalah salah satu strategi utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Inaportnet adalah sistem digital yang dikembangkan Kemenhub untuk menyederhanakan proses administrasi dan perizinan kapal, termasuk pendaftaran, pengurusan dokumen, dan pemantauan kegiatan. Penerapan sistem ini telah menunjukkan dampak yang sangat positif, di mana sebuah penelitian menyimpulkan bahwa Inaportnet berkontribusi sebesar 79,9% terhadap efisiensi Clearance in/out kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.
Inaportnet adalah bagian dari inisiatif yang lebih besar, yaitu National Logistics Ecosystem (NLE). NLE bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh rantai pasok logistik, dari perizinan hingga pengiriman, dengan harapan dapat mengatasi hambatan-hambatan sistemik dan mengurangi biaya logistik nasional.
Pencapaian Inaportnet menunjukkan bahwa inisiatif yang berfokus pada perbaikan proses spesifik dapat memberikan hasil yang terukur dan signifikan. Namun, keberhasilan ini tidak akan tercermin secara maksimal di tingkat makro jika inisiatif tersebut tidak terintegrasi sepenuhnya dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, dan jika hambatan non-teknis yang lebih besar tidak ditangani secara sistematis.
Kesimpulan
Analisis terhadap manajemen, kinerja, dan hambatan pelabuhan laut di Indonesia mengungkap sebuah narasi yang kompleks. Di satu sisi, ada perbaikan signifikan yang berhasil dicapai, terutama dalam efisiensi operasional di beberapa pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, yang terbukti dengan lonjakan peringkat globalnya. Di sisi lain, capaian ini terhambat oleh masalah-masalah struktural yang bersifat non-teknis, seperti birokrasi, tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi, dan isu tata kelola.
Paradoks kinerja ini menjelaskan mengapa perbaikan di tingkat operasional mikro belum mampu mendorong peningkatan kinerja logistik nasional secara keseluruhan (LPI) dan menurunkan biaya logistik secara signifikan. Akar masalahnya terletak pada kerancuan kewenangan, ego sektoral antar-lembaga, dan inefisiensi di luar gerbang pelabuhan. Oleh karena itu, langkah-langkah ke depan harus berfokus pada penanganan masalah sistemik ini.
Untuk mewujudkan potensi Indonesia sebagai pusat maritim global, laporan ini merekomendasikan langkah-langkah strategis berikut:
- Penguatan Kerangka Regulasi dan Tata Kelola: Perlu adanya penyederhanaan dan konsolidasi regulasi logistik yang jumlahnya mencapai ribuan. Penegasan kembali peran dan kewenangan setiap instansi, serta penghapusan tumpang tindih, harus menjadi prioritas untuk menekan praktik maladministrasi dan pungli. Akselerasi Integrasi Sistem Lintas Sektoral: Implementasi NLE harus dipercepat dan diperluas untuk mengintegrasikan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok logistik, termasuk Bea Cukai, Karantina, importir, dan bank. Integrasi ini akan meminimalkan “ego sektoral” dan menciptakan transparansi data yang krusial untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- Investasi Cerdas pada Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur tidak hanya terbatas pada pelabuhan baru atau modernisasi alat bongkar muat, tetapi juga harus mencakup peningkatan konektivitas hulu-hilir, seperti jaringan jalan dan kereta api, yang menghubungkan pelabuhan dengan daerah penyangga dan pusat produksi.
- Peningkatan Kapasitas SDM dan Standarisasi Layanan: Penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh lini, baik pemerintah maupun swasta, dan memastikan komitmen layanan 24/7 di seluruh rantai pasok. Hal ini akan menghilangkan keterlambatan dan biaya tambahan yang tidak perlu, sehingga memaksimalkan efisiensi yang telah dicapai di dalam pelabuhan.
Melalui pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis tetapi juga pada reformasi sistemik, Indonesia memiliki peluang nyata untuk mengatasi tantangan yang ada dan mengoptimalkan peran pelabuhannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan global.
Daftar Pustaka :
- PELINDO BERTRANSFORMASI TINGKATKAN LAYANAN DI SEKTOR PELABUHAN NONPETIKEMAS, accessed on September 12, 2025, https://pelindomultiterminal.co.id/news/pelindo-bertransformasi-tingkatkan-layanan-di-sektor-pelabuhan-nonpetikemas
- Tugas dan Fungsi KSOP – Kementerian Perhubungan, accessed on September 12, 2025, https://hubla.dephub.go.id/ksopkendari/page/tugas-dan-fungsi
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA KEPELABUHANAN DAN DAERAH PELAYARAN PRE, accessed on September 12, 2025, https://bphn.go.id/data/documents/69pp001.pdf
- Profil Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, accessed on September 12, 2025, https://oppriok.dephub.go.id/frontend/profil
- Otoritas Pelabuhan Utama dan Kantor Syahbandar Utama dimerger menjadi KSOP Utama, accessed on September 12, 2025, https://www.islnewstv.com/2023/08/otoritas-pelabuhan-utama-dan-kantor.html
- PM 36 TAHUN 2012 – ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN b, accessed on September 12, 2025, https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenhub/2012/permenhub_pm_no_36_tahun_2012.pdf
- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 93 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN, accessed on September 12, 2025, https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenhub/2018/permenhub_pm_93_tahun_2018.pdf
- Tentang Kami – Pelindo, accessed on September 12, 2025, https://www.pelindo.co.id/page/tentang-kami
- BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah – Badan Pembinaan Hukum Nasional, accessed on September 12, 2025, https://bphn.go.id/data/documents/pengelolaan_pelabuhan_oleh_daerah.pdf
- Perizinan dan Pungli Masalah Utama Sistem Logistik – Supply Chain Indonesia, accessed on September 12, 2025, https://supplychainindonesia.com/perizinan-dan-pungli-masalah-utama-sistem-logistik/
- Dwelling Time Tercatat Rata-Rata 2,88 Hari pada 2024 – DDTC News, accessed on September 12, 2025, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808265/dwelling-time-tercatat-rata-rata-288-hari-pada-2024
- SCI Apresiasi Pelabuhan Tanjung Priok jadi Peringkat 23 Dunia …, accessed on September 12, 2025, https://supplychainindonesia.com/sci-apresiasi-pelabuhan-tanjung-priok-jadi-peringkat-23-dunia/
- Pelabuhan Tanjung Priok Mencapai Posisi 23 Dunia untuk Pelabuhan Kontainer – Vibizmedia.com, accessed on September 12, 2025, https://www.vibizmedia.com/index.php/2024/06/12/pelabuhan-tanjung-priok-mencapai-posisi-23-dunia-untuk-pelabuhan-kontainer/
- Latest container port efficiency ratings revealed – IAPH, accessed on September 12, 2025, https://www.iaphworldports.org/news/iaphnews/18028/
- The Container Port Performance Index 2023 : A Comparable Assessment of Performance based on Vessel Time in Port (English) – World Bank Documents and Reports, accessed on September 12, 2025, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099060324114539683
- Hasil Investigasi Ombudsman Indonesia Tentang Dwelling Timedi Empat Pelabuhan Besar Indonesia, accessed on September 12, 2025, https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/305/60/541
- MANAJEMEN RISIKO PELABUHAN RAKYAT GUNA MENDUKUNG RANTAI PASOK NASIONAL – Jurnal Rekayasa Sipil, accessed on September 12, 2025, https://jrs.ft.unand.ac.id/index.php/jrs/article/download/166/124/615
- Benahi Sektor Logistik dengan Implementasi NLE – Media Keuangan, accessed on September 12, 2025, https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/benahi-sektor-logistik-dengan-implementasi-nle
- PERANCANGAN MODEL EVALUASI EFEKTIVITAS SUBSIDI TOL LAUT – Digilib ITB, accessed on September 12, 2025, https://digilib.itb.ac.id/assets/files/2020/MjAyMCBUQSBQUCAgRElDS1kgUklWQU5EQSAxIEFCU1RSQUsucGRm.pdf
- Menhub Budi Karya Dorong Penguatan Sistem Logistik Nasional lewat Digitalisasi Inaportnet – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, accessed on September 12, 2025, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menhub-budi-karya-dorong-penguatan-sistem-logistik-nasional-lewat-digitalisasi-inaportnet
- Inaportnet: Mendorong Digitalisasi dan Efisiensi Pelabuhan – Port Academy, accessed on September 12, 2025, https://portacademy.id/inaportnet-mendorong-digitalisasi-dan-efisiensi-pelabuhan/
- Pengaruh Penerapan Sistem Aplikasi Inaportnet terhadap Efisiensi Clearance In/Out Kapal PT. Pelayaran Nasional Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok – Repositori Politeknik Pelayaran Surabaya, accessed on September 12, 2025, https://repository.poltekpel-sby.ac.id/id/eprint/85/
- Tantangan Utama dan Peran Strategis dalam Operasional Pelabuhan – TransTRACK, accessed on September 12, 2025, https://blog.transtrack.co/strategi-operational/operasional-pelabuhan/
- Tantangan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan di Indonesia, accessed on September 12, 2025, https://itb.ac.id/berita/tantangan-pembangunan-infrastruktur-transportasi-berkelanjutan-di-indonesia/56543