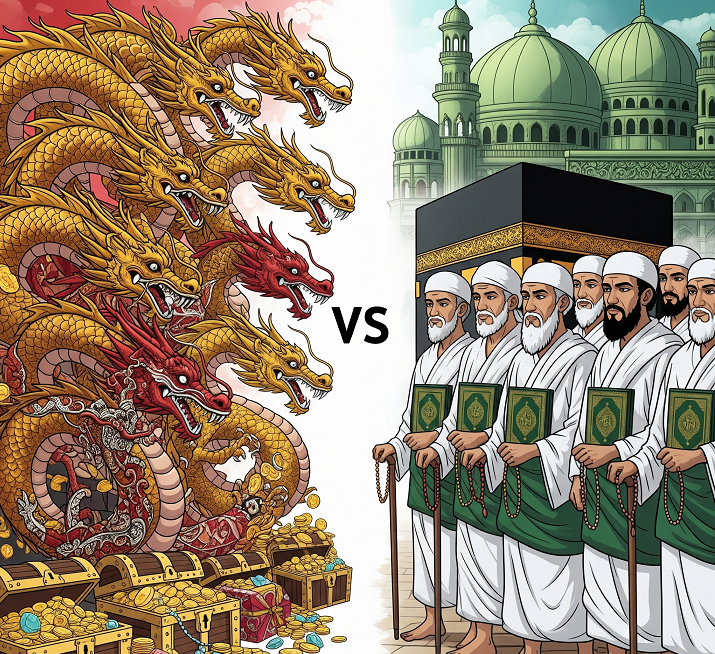Istilah “9 Naga” dan “9 Haji” telah menjadi bagian dari leksikon publik Indonesia untuk menggambarkan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil pengusaha. “9 Naga” merujuk pada sekelompok konglomerat berpengaruh keturunan Tionghoa-Indonesia yang dominan sejak era Orde Baru, sementara “9 Haji” merupakan narasi yang lebih baru, menggambarkan kebangkitan pengusaha Muslim pribumi dari daerah yang kaya sumber daya alam. Tulisan ini berargumen bahwa narasi “versus” atau “melawan” yang populer adalah sebuah penyederhanaan yang menyesatkan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah tentang persaingan antarfaksi yang sengit, melainkan dua manifestasi dari satu sistem oligarki bisnis yang terus berevolusi dan beradaptasi.
Temuan utama dari tulisan ini menunjukkan beberapa dinamika krusial. Pertama, istilah “9 Naga” adalah sebuah konsep atau arketipe, bukan organisasi formal, yang anggotanya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi dan daftar namanya pun tidak konsisten di berbagai sumber. Ini menunjukkan bahwa istilah tersebut berfungsi sebagai metafora untuk oligarki Tionghoa-Indonesia secara umum. Kedua, terdapat pergeseran model bisnis yang fundamental, dari kekayaan yang berbasis industri, properti, dan jasa yang terpusat di Jakarta (“Naga”), menuju kekayaan yang berasal dari ekstraksi sumber daya alam di daerah (“Haji”). Ketiga, munculnya “9 Haji” mencerminkan pergeseran geografis kekuasaan dari Jakarta-sentris menjadi lebih multipolar, di mana pusat-pusat kekuatan ekonomi regional semakin berperan. Terakhir, dan yang paling penting, proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) berfungsi sebagai bukti nyata bahwa kedua kelompok tidak bersaing melainkan berkoalisi. Konglomerat “Naga” yang mapan (seperti Djarum Group dan Salim Group) berinvestasi dalam konsorsium yang sama, menunjukkan adanya konsolidasi kepentingan di level elit, bukan konfrontasi.
Tulisan ini menyimpulkan bahwa narasi “9 Naga vs 9 Haji” perlu dibingkai ulang dari lensa etno-regional menjadi sebuah analisis terhadap arsitektur oligarki Indonesia yang adaptif dan persisten. Selama sistem politik masih memungkinkan kolusi antara modal dan kekuasaan, para aktornya mungkin berganti, tetapi strukturnya akan tetap ada.
Genealogi “9 Naga”: Dari Orde Baru ke Oligarki Modern
Asal-Usul dan Konotasi: Mengapa “Naga”?
Istilah “9 Naga” (九龙) merujuk pada sekelompok pengusaha Tionghoa-Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian dan politik, terutama yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan Orde Baru. Istilah ini pertama kali muncul pada era Orde Baru, di mana pada masa itu, konotasinya sangat negatif dan misterius. Kelompok ini, yang juga dikenal sebagai ‘Gang of Nine’, sering diasosiasikan dengan bisnis terlarang seperti perjudian, penyelundupan, dan perdagangan narkoba. Mereka diyakini kebal hukum karena mendapat perlindungan kuat dari pihak berwenang.
Menurut investigasi media, istilah ini diduga pertama kali dicetuskan oleh Anton Medan, seorang mantan kriminal yang kemudian menjadi pemuka agama. Nama-nama seperti Tomy Winata dan Sugianto Kusuma (Aguan) disebut-sebut sebagai “godfather” atau tokoh senior dalam kelompok ini, yang aktivitasnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Keterlibatan mereka menjadi sorotan publik setelah berita tentang keduanya yang mengambil alih Bank Propelat yang sedang kesulitan keuangan, sebuah bank yang dulunya dimiliki oleh angkatan bersenjata.
Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, konotasi istilah “9 Naga” bergeser menjadi lebih netral. Istilah ini mulai merujuk pada sekelompok pengusaha terkemuka yang mendominasi ekonomi Indonesia. Pergeseran makna ini mencerminkan pengakuan bahwa dominasi mereka merupakan hasil dari “simbiosis mutualistis” atau hubungan saling menguntungkan dengan pemerintahan Orde Baru. Evolusi narasi ini menunjukkan bagaimana sebuah istilah yang awalnya bersifat peyoratif dapat berubah menjadi simbol kekuasaan dan pengaruh yang terus berlanjut. Ini menjelaskan mengapa istilah “9 Naga” tetap melekat dalam kesadaran publik sebagai representasi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di Indonesia, meskipun sifatnya yang ambigu dan tidak terorganisir.
Peta Tokoh dan Bisnis: Menganalisis Inkonsistensi Daftar
Tidak ada daftar resmi atau yang secara universal diakui mengenai siapa saja yang termasuk dalam kelompok “9 Naga”. Berbagai media dan sumber publikasi menyajikan daftar yang berbeda, menunjukkan bahwa “9 Naga” lebih merupakan sebuah metafora atau arketipe ketimbang sebuah kelompok usaha atau organisasi yang terstruktur. Namun, beberapa nama konglomerat sering kali muncul dalam daftar yang disusun oleh media, yang secara kolektif menggambarkan oligarki bisnis Tionghoa-Indonesia. Nama-nama yang paling sering disebut antara lain:
- Robert Budi Hartono: Pemilik Djarum Group dan pemegang saham pengendali di Bank Central Asia (BCA), salah satu bank terbesar di Indonesia.
- Anthony Salim: Penerus Salim Group, sebuah konglomerasi besar dengan bisnis yang mencakup barang konsumsi (Indofood, Indomie), ritel (Indomaret), dan energi.
- James Riady: Anak dari Mochtar Riady dan pemimpin Lippo Group, yang bergerak di sektor properti, perbankan, kesehatan, dan pendidikan .
- Tomy Winata: Pendiri Artha Graha Group yang berfokus pada perbankan, properti (SCBD), dan infrastruktur.
- Dato Sri Tahir: Pendiri Mayapada Group yang memiliki bisnis di bidang keuangan, kesehatan, dan asuransi.
- Rusdi Kirana: Pendiri Lion Air Group, salah satu maskapai penerbangan terbesar di Asia Tenggara.
- Sofjan Wanandi: Pemilik Santini Group, yang memiliki saham di sektor properti, otomotif, dan pertambangan.
- Edwin Soeryadjaya: Tokoh kunci di PT Astra International Tbk dan pendiri Saratoga Investama.
- Jacob Soetoyo: Presiden Direktur PT Gesit Sarana Perkasa, yang dikenal karena jaringan internasional dan aset propertinya.
Portofolio bisnis kelompok ini sangat terdiversifikasi dan terintegrasi, mencakup sektor-sektor strategis yang merupakan pilar ekonomi nasional, seperti perbankan, properti, manufaktur, dan ritel. Keterlibatan mereka di sektor-sektor ini, yang sebagian besar berlokasi di pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta, mengukuhkan dominasi yang mereka miliki. Inkonsistensi daftar tokoh ini menegaskan bahwa “9 Naga” tidak berfungsi sebagai entitas yang terorganisir, melainkan sebuah narasi yang memungkinkan media dan publik mengelompokkan para pengusaha super-kaya yang memiliki pengaruh besar. Hal ini secara efektif memperkuat gagasan bahwa konsentrasi kekuasaan ekonomi dipegang oleh sekelompok elit yang tertutup dan nebulus.
Mekanisme Kepatronan: Kolaborasi dengan Rezim Orde Baru
Dominasi yang dinikmati oleh kelompok “9 Naga” tidak terlepas dari hubungan simbiosis yang mereka bangun dengan rezim Orde Baru. Rezim yang sentralistis dan militeristik, yang menerapkan konsep Dwi Fungsi ABRI, menciptakan lingkungan di mana kolaborasi antara pengusaha dan pihak berkuasa menjadi mekanisme utama akumulasi modal. Pengusaha Tionghoa, yang secara politik rentan sebagai minoritas, justru memanfaatkan kerentanan ini sebagai bentuk “modal sosial.” Mereka memberikan dukungan finansial dan kemitraan bisnis kepada rezim dan militer, dan sebagai imbalannya, mereka mendapatkan konsesi, lisensi bisnis, dan kekebalan dari regulasi.
Salah satu contoh paling menonjol dari model kepatronan ini adalah hubungan Tomy Winata dengan militer. Latar belakangnya sebagai pengusaha yang membangun barak militer di Singkawang memberinya akses awal ke kalangan petinggi militer. Hubungan ini semakin kuat ketika ia, bersama Sugianto Kusuma, diminta oleh yayasan angkatan bersenjata untuk menyelamatkan Bank Propelat yang sedang mengalami krisis. Winata berhasil memulihkan bank tersebut, yang kemudian menjadi Bank Artha Graha, dan kemitraan ini menjadi fondasi bagi ekspansi besar-besaran Artha Graha Network di sektor properti, keuangan, dan konstruksi, termasuk pengembangan kawasan bisnis elit Sudirman Central Business District (SCBD). Kasus ini adalah contoh yang gamblang tentang bagaimana kolusi antara modal swasta dan aparatur negara menjadi pendorong utama pertumbuhan oligarki bisnis di Indonesia.
Transformasi Pasca-Reformasi: Adaptasi Politik
Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 tidak mengakhiri dominasi “9 Naga.” Sebaliknya, mereka menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dengan hilangnya satu patron tunggal (Suharto), para konglomerat ini mendiversifikasi hubungan politik mereka dengan menjalin kontak dengan berbagai kekuatan politik baru yang muncul. Tomy Winata, misalnya, dikenal memiliki koneksi dengan mantan Presiden Megawati Sukarnoputri melalui suaminya, Taufiq Kiemas, dan juga disebut-sebut sebagai pendukung kampanye Susilo Bambang Yudhoyono.
Lebih dari sekadar lobi di belakang layar, beberapa tokoh yang dikaitkan dengan “9 Naga” juga secara langsung memasuki ranah politik. Rusdi Kirana, pendiri Lion Air, pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dan terpilih sebagai anggota DPR, serta menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. Sementara itu, Dato Sri Tahir dari Mayapada Group ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan Joko Widodo. Pergeseran ini menunjukkan transisi dari sistem patronase yang terpusat ke sistem yang lebih multipolar. Alih-alih bergantung pada satu rezim, para oligarki kini membangun jejaring hubungan yang luas dengan berbagai partai dan pemimpin politik untuk memastikan bisnis mereka terlindungi dan terus berkembang, tidak peduli siapa pun yang berkuasa.
“9 Haji”: Narasi Baru dan Kekuatan Regional yang Sedang Naik Daun
Latar Belakang Narasi: Siapa di Balik Konsep “9 Haji”?
Narasi “9 Haji” adalah fenomena yang relatif baru dalam diskursus publik Indonesia, yang muncul sebagai sebuah “penyeimbang” atau “penantang” terhadap dominasi “9 Naga”. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Mardigu Wowiek Prasantyo, seorang pengusaha dan content creator. Penciptaan narasi ini secara spesifik bertujuan untuk menjelaskan munculnya kekuatan ekonomi baru di Indonesia yang berbeda dari oligarki tradisional.
Narasi “9 Haji” ini berhasil menarik perhatian publik karena membingkai pergeseran kekuasaan ekonomi dalam bahasa yang mudah dipahami, yaitu persaingan etnis dan agama: pengusaha Muslim/pribumi dari daerah melawan konglomerat Tionghoa-Indonesia dari Jakarta. Namun, narasi ini pada dasarnya adalah sebuah konstruksi media yang mengkapitalisasi pergeseran nyata dalam lanskap ekonomi Indonesia untuk menciptakan sebuah cerita yang dramatis dan menarik bagi khalayak ramai.
Profil dan Kekayaan: Basis Ekonomi Sumber Daya Alam
Seperti halnya “9 Naga,” tidak ada daftar definitif mengenai siapa saja yang termasuk dalam “9 Haji.” Namun, nama-nama yang paling sering dikaitkan dengan kelompok ini sebagian besar berasal dari daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Beberapa nama yang sering disebut meliputi:
- Haji Isam (Samsudin Andi Arsyad): Pengusaha batu bara dari Kalimantan Selatan yang memiliki Jhonlin Group
- Haji Kalla (Hadji Kalla): Pendiri Kalla Group, sebuah konglomerasi yang berpusat di Makassar
- Haji Aksa (Aksa Mahmud): Pendiri Bosowa Group, yang bergerak di industri semen dan infrastruktur di kawasan timur Indonesia
- Haji Rasyid (Abdul Rasyid AS): Taipan kelapa sawit dari Kalimantan Tengah
- Haji Leman (Abdussamad Sulaiman HB): Pendiri Hasnur Group dari Kalimantan Selatan, yang memiliki bisnis multisektor
- Haji Ijai (Muhammad Zaini Mahdi): Konglomerat batu bara dari Tapin, Kalimantan Selatan
- Haji Anif (Musannif): Pengusaha kelapa sawit dari Sumatera Utara
- Haji Robert (Robert Nitiyudo Wachjo): Pengusaha tambang emas di Maluku Utara
- Haji Ciut (Muhammad Hatta): Pengusaha tambang dari Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai “Crazy Rich”
Secara fundamental, sumber kekayaan utama kelompok ini berbeda dari “9 Naga.” Jika kekayaan “Naga” berakar pada sektor industri, keuangan, dan properti, kekayaan “Haji” didominasi oleh komoditas dan ekstraksi sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, dan tambang emas. Haji Isam, misalnya, memulai kariernya sebagai sopir truk dan membangun Jhonlin Group dari nol menjadi konglomerat besar yang mengelola 60 perusahaan di sektor pertambangan, agribisnis, manufaktur, dan infrastruktur.
Pusat Kekuatan Baru: Pergeseran Geografis
Kemunculan “9 Haji” menandai pergeseran signifikan dalam geografi kekuasaan ekonomi di Indonesia. Jika “9 Naga” adalah oligarki yang berpusat di Jakarta, maka “9 Haji” adalah oligarki regional. Kekuatan mereka berasal dari kekayaan sumber daya alam di daerah-daerah di luar Jawa, khususnya Kalimantan dan Sulawesi. Gelar kehormatan “Haji” yang disematkan pada nama-nama ini tidak hanya menunjukkan status religius, tetapi juga berfungsi sebagai simbol keberhasilan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang menantang dominasi Jakarta.
Pergeseran ini memiliki implikasi politik yang mendalam. Akumulasi kekayaan di daerah-daerah ini telah melahirkan “raja-raja” lokal yang memiliki pengaruh besar di tingkat regional, yang kini mulai menempatkan pengaruh mereka di panggung nasional. Dinamika kekuasaan tidak lagi bersifat satu arah dari pusat ke daerah, melainkan menjadi sebuah tawar-menawar yang lebih kompleks. Munculnya kekuatan-kekuatan regional ini menunjukkan bahwa lanskap ekonomi dan politik Indonesia kini jauh lebih multipolar dan terdesentralisasi daripada era Orde Baru.
Koneksi Politik Baru: Kepatronan Era Jokowi-Prabowo
Sama seperti “9 Naga” yang membangun kekayaan mereka melalui kepatronan dengan rezim Orde Baru, “9 Haji” juga dikenal karena kedekatan mereka dengan lingkaran kekuasaan saat ini. Haji Isam, misalnya, disebut sebagai “poster boy” dari oligarki baru yang memiliki pengaruh kuat di pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ia disebut-sebut sebagai figur yang bekerja di belakang layar untuk memengaruhi politik partai di Kalimantan dan memiliki hubungan dekat dengan menteri-menteri di kabinet. Haji Kalla juga memiliki sejarah politik yang panjang, menjabat sebagai Wakil Presiden di dua periode pemerintahan yang berbeda.
Kekuatan politik yang dimiliki oleh para “9 Haji” ini menunjukkan bahwa meskipun aktornya berbeda, model dasarnya tetap sama. Kekayaan yang terakumulasi di daerah-daerah ini digunakan untuk membangun jejaring patronase politik, baik melalui dukungan kampanye, lobi, atau menempatkan orang-orang dekat di posisi-posisi strategis. Fenomena ini menunjukkan bahwa arsitektur oligarki bisnis di Indonesia tetap tangguh dan adaptif, hanya saja kini wajahnya telah berubah seiring dengan pergeseran kekuasaan politik dan pusat-pusat ekonomi baru.
Analisis Komparatif: Membedah Dinamika yang Ada
Model Bisnis dan Sumber Kekayaan
Perbedaan paling fundamental antara “9 Naga” dan “9 Haji” terletak pada model bisnis dan sumber kekayaan mereka. “9 Naga” membangun kerajaan bisnis mereka dari sektor yang terpusat di ibu kota dan membutuhkan modal besar, seperti perbankan, properti, dan manufaktur. Mereka mendirikan konglomerasi yang terdiversifikasi, seperti Djarum Group yang merambah dari rokok ke perbankan dan e-commerce, atau Salim Group yang menguasai industri makanan dari hulu ke hilir.
Sebaliknya, kekayaan “9 Haji” didominasi oleh sektor ekstraktif. Haji Isam, Haji Rasyid, dan Haji Ciut menguasai pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam. Perbedaan ini mencerminkan fase-fase pembangunan ekonomi Indonesia yang berbeda: Orde Baru yang berfokus pada pembangunan industri dan finansial yang dipimpin negara, yang kemudian diikuti oleh liberalisasi dan desentralisasi pasca-Reformasi yang memicu ledakan kekayaan berbasis komoditas. Oleh karena itu, “9 Naga” dan “9 Haji” dapat dilihat sebagai produk dari era ekonomi yang berbeda, bukan sebagai faksi yang bersaing secara langsung.
Geografi Kekuasaan
Perbedaan model bisnis secara langsung berimplikasi pada geografi kekuasaan mereka. Oligarki “Naga” secara historis beroperasi dari Jakarta, di mana mereka dapat dengan mudah mengakses pusat pemerintahan dan pasar finansial. Sebaliknya, para “Haji” membangun basis kekuatan mereka di daerah, di mana kekayaan mereka berasal. Mereka adalah “raja-raja” lokal yang kini berupaya memperluas pengaruh mereka ke tingkat nasional. Pergeseran geografis ini menunjukkan bahwa politik Indonesia tidak lagi hanya tentang pusat vs. pinggiran, tetapi juga tentang bagaimana pusat harus bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan regional yang semakin kuat.
Dimensi Etnis: Kritik atas Narasi Populer
Narasi “9 Naga vs 9 Haji” sering kali mengkapitalisasi ketegangan etnis dan agama yang telah lama ada di Indonesia, mempolitisasi isu ekonomi sebagai sebuah pertarungan antara pengusaha Tionghoa-Indonesia dan pribumi . Pendekatan ini sangat problematis karena menyederhanakan masalah struktural yang jauh lebih kompleks. Isu sebenarnya bukanlah “siapa” yang menguasai ekonomi (etnis apa), tetapi “bagaimana” mereka menguasai—yaitu melalui kolusi dan kepatronan yang sistematis.
Akademisi telah lama mencatat bahwa pengusaha Tionghoa di era Orde Baru berhasil makmur bukan hanya karena kecerdasan bisnis, tetapi juga karena sistem yang memungkinkan mereka berkolusi dengan kekuasaan. Hal yang sama kini terjadi dengan para “Haji,” yang membangun kekayaan mereka dengan koneksi politik yang kuat. Narasi yang mengedepankan persaingan etnis justru mengalihkan perhatian dari akar masalah yang sesungguhnya: sebuah sistem oligarki yang terus melanggengkan ketimpangan ekonomi dan kurangnya persaingan yang sehat, terlepas dari latar belakang etnis para aktornya.
Overlap dan Sinergi: Studi Kasus IKN
Jika narasi “9 Naga vs 9 Haji” menggambarkan konfrontasi, maka proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah studi kasus yang membantahnya. Pembangunan IKN menjadi titik temu di mana kedua kelompok ini tidak bersaing, melainkan berkoalisi untuk kepentingan bersama. Konsorsium Nusantara, yang menjadi salah satu investor lokal terbesar, dipimpin oleh Sugianto Kusuma atau Aguan, yang secara historis dikaitkan sebagai salah satu “godfather” “9 Naga”.
Konsorsium ini terdiri dari 10 perusahaan besar, termasuk konglomerat yang secara luas dianggap sebagai “Naga,” seperti Salim Group, Sinar Mas Group, dan Djarum Group. Nilai investasi yang dikucurkan konsorsium ini mencapai Rp 40 triliun, sebagian besar di sektor properti dan perhotelan. Keterlibatan Aguan dan tokoh-tokoh kunci lainnya yang berinteraksi langsung dengan pemerintah untuk membahas proyek ini menunjukkan bahwa di level elit, tidak ada pertarungan antara “Naga” dan “Haji,” melainkan konsolidasi kepentingan untuk mengamankan proyek strategis negara. IKN adalah simbol dari arsitektur oligarki baru yang inklusif dan adaptif, di mana kolaborasi mengalahkan narasi persaingan.
Berikut adalah tabel yang merangkum perbandingan analitis antara kedua narasi tersebut.
| Kriteria Perbandingan | 9 Naga | 9 Haji |
| Asal-Usul Narasi | Era Orde Baru | Pasc-Reformasi, populer oleh Mardigu Wowiek Prasantyo |
| Asal Etnis/Agama | Tionghoa-Indonesia | Muslim/Pribumi |
| Sektor Bisnis Utama | Properti, Perbankan, Manufaktur, Ritel | Sumber Daya Alam (Batu Bara, Sawit, Emas) |
| Basis Geografis | Jakarta-sentris | Regional (Kalimantan, Sulawesi, Sumatera) |
| Hubungan Politik Historis | Patronase dengan Militer/Rezim Soeharto | Patronase dengan politisi/partai era Jokowi-Prabowo |
| Status Hukum/Organisasi | Legenda urban/tidak terorganisir | Konstruksi narasi media |
Dan berikut adalah tabel yang menunjukkan konvergensi oligarki di proyek IKN.
| Konglomerat | Tokoh Kunci | Jenis Proyek di IKN | Nilai Investasi (Konsorsium) |
| Konsorsium Nusantara | Sugianto Kusuma (Aguan) | Mixed-use, Swissôtel Nusantara, Nusantara Duty Free Mall, Nusantara Apartment | Rp20 triliun |
| Agung Sedayu Group | Sugianto Kusuma (Aguan) | Hotel, Botanical Garden [29] | – |
| Salim Group | Anthony Salim | Bagian dari konsorsium | – |
| Sinar Mas Group | Franky Widjaja | Bagian dari konsorsium | – |
| Djarum Group | Robert Budi Hartono | Kantor BCA dan Banking Hall | Rp75 miliar |
| Lippo Group | James Riady | Bagian dari konsorsium | – |
Implikasi dan Kritik terhadap Narasi
Oligarki dan Kesenjangan Ekonomi
Keberadaan konglomerat super-kaya, baik yang dikelompokkan sebagai “Naga” maupun “Haji,” telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang praktik monopoli, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya persaingan yang sehat. Kekayaan bersih tokoh-tokoh ini, yang sering kali mencapai ratusan triliun rupiah, menggambarkan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang luar biasa. Masalah struktural ini adalah tantangan nyata bagi pembangunan yang inklusif. Narasi “9 Naga vs 9 Haji” berpotensi mengalihkan perhatian publik dari permasalahan fundamental ini. Alih-alih mengkritik sistem yang memungkinkan akumulasi kekayaan yang masif di tangan segelintir orang, narasi ini memfokuskan perdebatan pada persaingan antara kelompok etnis atau regional, menciptakan ilusi bahwa masalahnya terletak pada siapa yang menguasai, bukan pada bagaimana kekuasaan itu dikonsolidasikan.
“9 Naga vs 9 Haji” sebagai Alat Politik
Narasi ini juga sering digunakan sebagai alat politik. Kemunculan “9 Haji” sering kali dikaitkan dengan kedekatan mereka dengan pemerintahan yang berkuasa. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merasionalisasi transfer konsesi bisnis dan proyek-proyek strategis kepada mitra-mitra baru mereka. Dalam skema ini, para pengusaha yang loyal atau memiliki koneksi dengan rezim yang sedang menjabat diberi akses ke sumber daya dan proyek, dan narasi “9 Haji” digunakan untuk melegitimasi transfer kekayaan ini seolah-olah itu adalah sebuah pergeseran kekuasaan yang sehat dari oligarki lama ke oligarki baru. Padahal, sistem oligarki itu sendiri tetap berlanjut, hanya saja dengan wajah yang berbeda. Fenomena ini bukanlah tentang persaingan pasar yang sehat, melainkan tentang politik patronase yang terus berlanjut.
Konsolidasi Kekuasaan: Peran Oligarki dalam Kebijakan
Oligarki bisnis di Indonesia tidak hanya berinteraksi dengan pemerintah; mereka juga memainkan peran sentral dalam membentuk arsitektur regulasi dan politik itu sendiri. Para konglomerat ini menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai kampanye politik, melobi para politisi, dan bahkan menempatkan orang-orang dekat mereka di posisi strategis dalam pemerintahan. Misalnya, komposisi panitia kerja Undang-Undang Cipta Kerja disebut-sebut terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tertentu, yang membuka ruang bagi konflik kepentingan dan menunjukkan bagaimana kepentingan bisnis dapat memengaruhi produk legislasi.
Hubungan ini menciptakan lingkaran setan di mana kekuasaan ekonomi melahirkan kekuasaan politik, yang pada gilirannya mengamankan kekuasaan ekonomi. Alih-alih melemah pasca-Reformasi, oligarki bisnis di Indonesia justru semakin terkonsolidasi dan adaptif, menjalin aliansi baru dengan patron-patron politik yang muncul, termasuk di era Jokowi dan Prabowo.
Kesimpulan
Tulisan ini menyimpulkan bahwa narasi “9 Naga vs 9 Haji” adalah representasi yang menyederhanakan dinamika oligarki bisnis di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa keduanya bukanlah dua faksi yang bertarung, melainkan dua manifestasi dari satu sistem oligarki yang sama. Perbedaan utama mereka terletak pada basis kekayaan (industri/jasa vs. sumber daya alam) dan geografi kekuasaan (Jakarta-sentris vs. regional). Namun, model inti dari kekuasaan—yaitu kolusi antara modal dan negara untuk mengamankan konsesi dan kekebalan—tetap konstan. Proyek IKN menjadi bukti nyata dari konsolidasi alih-alih konfrontasi, di mana oligarki lama dan baru bersatu untuk mengamankan kepentingan mereka dalam proyek strategis nasional.
Prospek ke depan menunjukkan bahwa seiring dengan diversifikasi ekonomi dan desentralisasi, pusat-pusat kekayaan akan semakin menyebar. Namun, selama sistem politik masih memungkinkan patronase dan lobi yang kuat, arsitektur oligarki akan terus bertahan, hanya dengan aktor dan narasi yang berbeda. Diperlukan kajian lebih lanjut yang berfokus pada dinamika kekuasaan di luar narasi yang disederhanakan oleh media. Diskusi publik dan kebijakan perlu dialihkan dari persaingan etnis/regional ke perdebatan tentang bagaimana memutus rantai patronase dan mempromosikan persaingan pasar yang lebih sehat dan adil.
Daftar Pustaka :
- Tempo. (2020). Mafia Bisnis Tommy Winata.
- Setyautama, Sam. (2008). Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia.
- Tempo. (1999). Tomy Winata, Geng Naga, dan Mafia Bisnis.
- Forbes. (2024). Indonesia’s Billionaires.
- Indonesia at Melbourne. (2025). Meet Haji Isam, the new poster boy of Indonesia’s oligarchy.
- BBC Indonesia. (2018). Jusuf Kalla: ‘Saya tidak ingin menjadi presiden yang hanya melayani satu kelompok’.
- Wall Street Journal. (2014). Indonesian Tycoon’s Political Ties Raise Questions.
- Reuters. (2020). Indonesia’s New Oligarchy: How a Coal Tycoon Became a Political Player.
- The Economist. (2019). Indonesia’s democracy is being degraded by its money-grubbing oligarchy.
- Low, B. H. (2011). The Politics of Patronage: Indonesian Business and State Relations.
- Robison, Richard. (2018). Indonesia: The Rise of Capital.
- Hidayat, A. (2021). Oligarki dan Politik Kekuasaan di Indonesia.
- Syafi’ie, B. (2023). Jejak Reformasi yang Dikorupsi Oligarki.
- Kompas. (2024). Konsorsium Nusantara di IKN: Mengapa Konglomerat Bersatu?.
- CNBC Indonesia. (2024). Konglomerat IKN Kucurkan Rp 20 Triliun, Ada Djarum Hingga Salim Group.
- The Jakarta Post. (2024). Salim Group, Djarum, Sinar Mas Join Forces in IKN Consortium.
- Tirto.id. (2023). Sinergi Oligarki di IKN: Konsorsium Nusantara dan Kepentingan Elit.
- CNN Indonesia. (2024). Analisis IKN: Uji Coba Kolaborasi Oligarki Lama dan Baru.
- Tempo.co. (2023). Momen Langka Konglomerat RI Satu Meja Bahas Proyek IKN.
- Tirto.id. (2024). Sugianto Kusuma, Aguan, dan Jaringan Oligarki IKN.
- Medcom.id. (2023). Konglomerat Properti RI Investasi di IKN, Total Rp 53,5 Triliun.
- Republika.co.id. (2024). IKN: Proyek Oligarki atau Kepentingan Nasional?.
- Merdeka.com. (2023). Siapa di Balik Konsorsium Nusantara di IKN?.
- Okezone.com. (2024). Daftar Perusahaan dan Kekayaan Haji Isam.
- Antara. (2024). Jokowi Ingin Perayaan HUT RI di IKN Punya Akomodasi Memadai.
- The Conversation. (2023). The Rise of Regional Oligarchs in Indonesia.
- The Diplomat. (2024). Indonesia’s Oligarchy: A Problem of Structure, Not People.
- Inside Indonesia. (2023). Who’s Who in Indonesia’s New Oligarchy?.
- South China Morning Post. (2024). Indonesia’s New Capital Sparks Concerns Over Oligarchy.
- Kompas.com. (2024). Tiga Tahap Groundbreaking di IKN, Total Investasi Rp 40 Triliun.
- The Jakarta Globe. (2023). IKN Nusantara: A Test of Indonesia’s Political and Economic Future.
- The Australian. (2024). Indonesian Oligarchs Consolidate Power as Jokowi Era Ends.
- East Asia Forum. (2023). Oligarchy and the Future of Indonesian Democracy.
- Al Jazeera. (2024). Indonesia’s Next President Faces a Powerful Oligarchy.
- Financial Times. (2023). IKN Project Shows Unity Among Indonesia’s Tycoons.
- The Sydney Morning Herald. (2024).