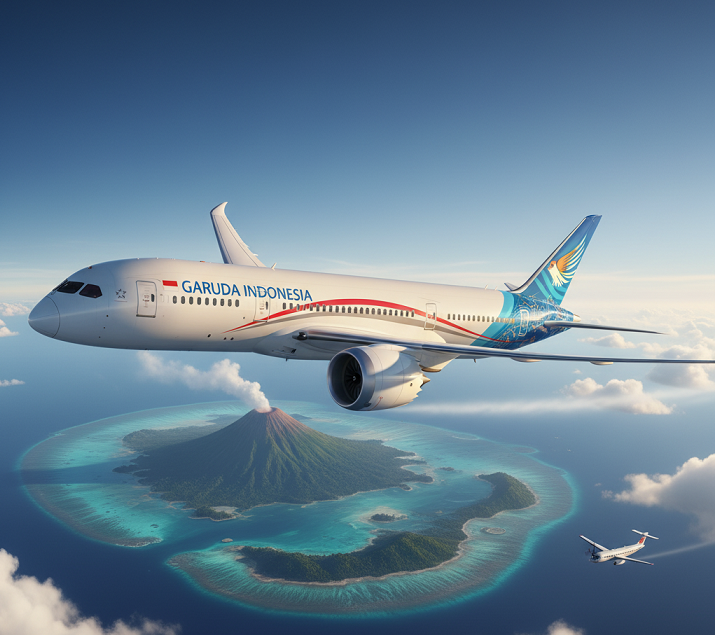Penerbangan komersial di Indonesia, menyoroti pergeseran fundamental dari sebuah layanan mewah yang eksklusif menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Perjalanan industri ini dapat diidentifikasi melalui tiga fase transformatif utama. Fase pertama, era kolonial, ditandai oleh perintisan penerbangan komersial oleh maskapai Belanda, Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM), yang melayani kepentingan elit dan profit kolonial. Penerbangan pada periode ini merupakan simbol kekuasaan dan kemewahan yang mahal dan berisiko tinggi.
Fase kedua, yang dimulai dengan periode pasca-kemerdekaan, menyaksikan transisi kepemilikan dan identitas dengan lahirnya maskapai nasional Garuda Indonesia. Fase ini mencapai puncaknya pada awal tahun 2000-an dengan kebijakan deregulasi yang memicu ledakan maskapai berbiaya rendah (LCC), secara radikal mendemokratisasi perjalanan udara dan menjadikannya dapat diakses oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Pergeseran ini secara signifikan mengubah lanskap pasar, mendorong persaingan ketat, dan memunculkan model bisnis yang inovatif.
Fase ketiga, era modern, merupakan respons terhadap tantangan abad ke-21. Industri penerbangan kini memasuki babak baru yang didorong oleh transformasi digital dan tuntutan keberlanjutan. Namun, pertumbuhan ini dibayangi oleh isu-isu kritis terkait keselamatan, peningkatan biaya operasional, dan perlunya investasi infrastruktur yang masif. Proyeksi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pasar penerbangan terbesar di dunia, tetapi realisasi potensi ini bergantung pada kemampuan industri dan pemerintah untuk menavigasi kompleksitas operasional, regulasi, dan sosial yang ada.
Fondasi Historis: Awal Penerbangan di Nusantara
Penerbangan Era Kolonial: KNILM sebagai Pelopor
Sejarah penerbangan komersial di Indonesia berakar kuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang dimulai pada awal abad ke-20. Pada mulanya, penggunaan pesawat terbang lebih dominan untuk keperluan militer dengan didirikannya dinas penerbangan militer pada tahun 1914. Namun, para pengusaha Belanda dengan cepat melihat potensi keuntungan besar dalam transportasi udara sipil, menyadari bahwa perjalanan udara dapat menghemat waktu tempuh antar kota besar secara signifikan.
Tonggak sejarah krusial dalam perintisan penerbangan komersial terjadi dengan didirikannya Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM), maskapai penerbangan Hindia Belanda, yang memulai operasinya pada 1 November 1928. Operasional perdana KNILM melayani rute dari Bandara Cililitan (kini Halim Perdanakusuma) di Batavia menuju Bandung dan Semarang. Armada awal mereka terdiri dari empat pesawat Fokker VII yang masing-masing hanya mampu menampung delapan penumpang dengan kapasitas bagasi maksimal 300 Kg.
Penerbangan pada era ini dipandang sebagai sebuah uji nyali. Selain ketiadaan standar keamanan yang memadai, seperti absennya sabuk pengaman, biaya tiket yang sangat mahal menjadikannya hanya bisa diakses oleh kalangan kaya dan sangat kaya, seperti pengusaha, pelancong, dan pejabat pemerintah. Tingkat risiko yang tinggi bahkan memunculkan plesetan nama maskapai ini menjadi Kalau Naik Ini Lekas Meninggal. Meskipun demikian, KNILM membawa dampak positif dengan melayani berbagai etnis masyarakat, termasuk Eropa, Tiongkok, dan pribumi, serta menjadi katalisator bagi pariwisata kolonial. Operasi KNILM di Hindia Belanda berakhir pada 7 Maret 1942 akibat invasi militer Jepang.
Peralihan Kekuasaan: Berdirinya Garuda Indonesia dan Peran Simbolisnya
Masa setelah kemerdekaan menandai perubahan signifikan dalam industri penerbangan Indonesia, dari orientasi kolonial menuju kedaulatan nasional. Berdirinya maskapai penerbangan nasional pertama, yang pada mulanya bernama Indonesian Airways, menjadi simbol perlawanan dan kemandirian bangsa. Maskapai ini memulai penerbangan komersial pertamanya pada 26 Januari 1949, menggunakan pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi RI 001. Dana untuk pembelian pesawat ini disebutkan berasal dari pengusaha dan rakyat Aceh, yang menunjukkan keterlibatan langsung seluruh elemen bangsa dalam mendukung mobilitas pemerintah di tengah perjuangan revolusi.
Nama Garuda diberikan langsung oleh Presiden Soekarno, terinspirasi dari sajak Noto Soeroto, seorang penyair Belanda. Kutipan sajak Ik ben Garuda, Vishnoe’s vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog bovine uw einladen atau Saya Garuda, burung Vishnu yang melebarkan sayapnya tinggi di atas kepulauan Anda mencerminkan peran maskapai ini sebagai entitas yang melambangkan identitas dan kedaulatan bangsa Indonesia, bertolak belakang dengan fungsi profit-driven KNILM di masa lalu.
Pengembangan Infrastruktur Awal
Perkembangan penerbangan komersial tidak dapat dipisahkan dari evolusi infrastruktur pendukungnya. Bandara Halim Perdanakusuma, yang dibangun pada tahun 1924 dengan nama Tjililitan Air Base, merupakan contoh infrastruktur krusial yang mengalami transformasi fungsi. Bandara ini awalnya berfungsi sebagai pangkalan operasi utama KNILM. Setelah kemerdekaan, pada 20 Juni 1950, bandara ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan diambil alih oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Bandara ini kemudian diubah namanya menjadi Halim Perdanakusuma pada 17 Agustus 1952, sebagai bentuk penghormatan kepada Abdul Halim Perdanakusuma, seorang perwira AURI yang gugur dalam tugas.
Selain perannya sebagai pangkalan militer, Bandara Halim Perdanakusuma sempat menjadi bandara internasional utama Jakarta pada tahun 1974, sebelum digantikan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1985. Sejarah bandara ini mencerminkan bagaimana infrastruktur yang dibangun di masa kolonial menjadi fondasi yang berharga bagi pengembangan penerbangan sipil di era nasional, meskipun membutuhkan adaptasi dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.
Tabel di bawah ini merangkum linimasa peristiwa kunci dalam sejarah awal penerbangan komersial di Indonesia.
| Tahun | Peristiwa Kunci | Signifikansi |
| 1914 | Dinas penerbangan militer Hindia Belanda didirikan | Perintisan kehadiran transportasi udara di Nusantara untuk kepentingan militer. |
| 1924 | Tjililitan Air Base (kini Bandara Halim Perdanakusuma) dibangun | Fondasi infrastruktur udara awal yang menjadi basis operasi KNILM. |
| 1928 | KNILM memulai penerbangan komersial pertamanya | Awal era penerbangan komersial, dengan rute Batavia-Bandung-Semarang. |
| 1928-1942 | Operasional KNILM | Penerbangan eksklusif yang mahal dan berisiko, melayani elit kolonial. |
| 1949 | Indonesian Airways memulai penerbangan komersial pertamanya | Lahirnya maskapai penerbangan nasional pertama, simbol kemandirian dan kedaulatan bangsa. |
| 1950 | Bandara Tjililitan diserahkan kepada pemerintah Indonesia | Alih kelola infrastruktur penerbangan dari kolonial ke nasional. |
| 1952 | Tjililitan Air Base diubah namanya menjadi Halim Perdanakusuma Air Base | Penghormatan terhadap pahlawan nasional, mengukuhkan identitas nasional bandara. |
Era Deregulasi: Pemicu Kompetisi dan Pertumbuhan Eksponensial
Latar Belakang dan Kebijakan Deregulasi Awal 2000-an
Lanskap penerbangan komersial Indonesia mengalami transformasi paling radikal pada awal tahun 2000-an. Pemerintah meluncurkan kebijakan deregulasi yang secara radikal melonggarkan aturan kepemilikan armada. Kebijakan ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Deregulasi yang lebih luas, dirancang untuk meningkatkan iklim investasi dan menciptakan iklim usaha yang baru dan lebih kondusif. Dengan menghapus berbagai pembatasan, tujuan deregulasi adalah untuk memicu persaingan yang sehat dan meningkatkan efisiensi di sektor penerbangan.
Deregulasi ini secara langsung mendorong munculnya pemain baru dalam industri, khususnya maskapai berbiaya rendah (Low-Cost Carrier/LCC). Sebelumnya, pasar didominasi oleh maskapai berpengalaman seperti Garuda Indonesia dan Merpati. Perubahan regulasi menciptakan kondisi pasar yang memungkinkan model bisnis LCC yang berfokus pada volume penumpang ketimbang harga (yield oriented) untuk berkembang pesat.
Ledakan Maskapai Berbiaya Rendah (LCC) dan Perubahan Perilaku Konsumen
Kebijakan deregulasi memicu lonjakan maskapai bertarif rendah. Salah satu contoh paling menonjol dari fenomena ini adalah Lion Air. Berdiri pada tahun 2000, Lion Air tumbuh pesat dengan visi “We Make People Fly” yang bertujuan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa siapapun bisa terbang dengan harga yang terjangkau. Pertumbuhan ini sangat cepat, hingga pada tahun 2007 Lion Air telah berhasil menguasai pangsa pasar maskapai nasional terbesar, menggeser dominasi Garuda Indonesia. Pada tahun 2018, Lion Air bahkan berhasil mengangkut 36,8 juta penumpang, merebut hampir 35% dari total pelancong udara di Indonesia. Keberhasilan model LCC terbukti dari data yang menunjukkan bahwa hingga tahun 2012, maskapai berbiaya rendah menguasai 78% pangsa pasar domestik. Fenomena LCC ini menyadarkan masyarakat bahwa sekarang ini semua orang bisa melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Pergeseran ini memiliki implikasi sosial-ekonomi yang signifikan, karena penerbangan tidak lagi menjadi kemewahan, tetapi sebuah alat transportasi massal yang terjangkau. Hal ini mempermudah pergerakan manusia antar kota dan antar pulau , secara langsung meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, deregulasi tidak hanya mengubah peta persaingan bisnis, tetapi juga menjadi katalisator bagi integrasi nasional dan kesetaraan mobilitas.
Lanskap Kompetitif: Dualisme Pasar dan Strategi Maskapai Utama
Analisis Strategis Garuda Indonesia Group vs. Lion Air Group
Pasar penerbangan komersial Indonesia saat ini didominasi oleh dua pemain utama yang mengoperasikan model bisnis yang berbeda secara fundamental: Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Garuda Indonesia, sebagai full-service carrier (FSC) milik negara, memposisikan dirinya untuk melayani pelancong bisnis dan internasional, dengan menekankan layanan premium dan keselamatan. Sebaliknya, Lion Air, sebagai low-cost carrier (LCC) swasta, berfokus pada penumpang yang sensitif terhadap harga dengan menawarkan keterjangkauan dan jaringan domestik yang luas.
Meskipun model LCC Lion Air cost-effective, analisis menunjukkan bahwa catatan keselamatannya dapat berdampak pada kepercayaan pelanggan. Sebaliknya, Garuda Indonesia, meskipun memiliki reputasi keselamatan yang lebih baik, menghadapi tantangan berat terkait keberlanjutan finansial. Dilema ini menyoroti bahwa dalam industri penerbangan Indonesia, persaingan tidak hanya terjadi pada harga dan layanan, tetapi juga pada elemen-elemen fundamental seperti kepercayaan dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, laporan Comparative analysis menyarankan balanced regulatory approach untuk mendukung kedua model bisnis ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Model Bisnis dan Diferensiasi: Perbandingan Strategi Dual-Brand
Sebagai respons terhadap dinamika pasar yang kompetitif, kedua grup maskapai telah mengadopsi strategi airline-within-airline atau dual-brand untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Garuda Indonesia meluncurkan anak perusahaan LCC, Citilink, sebagai upaya agresif untuk bersaing di segmen pelancong berbiaya rendah dan menggarap pasar menengah ke bawah. Citilink beroperasi dengan konsep city to city dan menerapkan strategi low cost dengan menekan biaya operasional dan efisiensi cost. Strategi ini melibatkan penghilangan fitur tambahan dan fokus pada produk utama seperti ketepatan waktu. Dalam restrukturisasi jaringannya, Garuda memindahkan rute-rute regional ke Citilink, dengan Citilink mengambil peran lebih besar di tier-one to tier-four cities dan Garuda fokus pada tier-one and tier-two cities.
Di sisi lain, Lion Air Group mendirikan Batik Air sebagai maskapai full service untuk bersaing melawan Garuda. Batik Air Malaysia (sebelumnya Malindo Air) juga merupakan bagian dari inisiatif grup untuk mengonsolidasikan maskapai full-service mereka di bawah satu identitas. Strategi Lion Air dengan Batik Air menunjukkan pembagian tugas yang jelas: Lion Air melayani LCC air travelers sementara Batik Air berperan dalam menjalankan strategi full service. Namun, riset menunjukkan adanya risiko dilusi merek dari strategi fleksibel ini: When you change strategy with flexibility, your organization will never represent anything or be good in anything. Ini menunjukkan tantangan untuk mengelola dua model bisnis yang kontras—minimalis versus premium—dalam satu grup tanpa mengorbankan identitas dan efisiensi.
| Fitur Perbandingan | Garuda Indonesia Group | Lion Air Group |
| Maskapai Utama | Garuda Indonesia (FSC) | Lion Air (LCC) |
| Maskapai Anak | Citilink (LCC) | Batik Air (FSC), Wings Air (LCC), Super Air Jet (LCC), dll. |
| Target Pasar | Pelancong bisnis, internasional, premium | Pelancong yang sadar biaya, domestik |
| Model Bisnis Utama | Full-Service Carrier (FSC) | Low-Cost Carrier (LCC) |
| Strategi Kunci | Layanan premium, keselamatan, keberlanjutan finansial | Keterjangkauan, jaringan luas, efisiensi biaya |
| Pangsa Pasar Domestik | Kombinasi Garuda-Citilink sekitar 21% (2020) | Sekitar 60% (2020) |
| Tantangan Utama | Keberlanjutan finansial, efisiensi operasional | Reputasi keselamatan, kepercayaan pelanggan |
Tantangan dan Penguatan: Keamanan, Regulasi, dan Infrastruktur
Isu Keselamatan Penerbangan: Faktor dan Statistik
Isu keselamatan telah menjadi tantangan signifikan dalam industri penerbangan Indonesia, khususnya setelah masa deregulasi yang memicu pertumbuhan pesat. Analisis menunjukkan bahwa faktor penyebab kecelakaan penerbangan di Indonesia didominasi oleh human error, dengan persentase mencapai 60% dari total kasus. Faktor manusia mencakup berbagai aspek seperti kurangnya pengalaman, kelelahan, atau bahkan penggunaan obat-obatan terlarang, serta komunikasi yang buruk antara pilot dan petugas menara kontrol.
Selain human error, kecelakaan juga disebabkan oleh faktor teknis seperti kegagalan mesin, cuaca yang buruk seperti microburst atau jarak pandang terbatas akibat kabut, dan kebijakan serta prosedur yang tidak memadai atau tidak ditaati. Contoh tragis adalah kecelakaan Lion Air JT 610 pada tahun 2018, yang investigasinya mengungkap penyebab utama adalah malfungsi sistem Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) dan kurangnya pelatihan bagi pilot dalam menghadapi sistem tersebut.
| Faktor Penyebab | Persentase / Jumlah Kasus | Contoh Insiden Terkait |
| Human Error | 60% | Komunikasi buruk, kelelahan, kesalahan keputusan |
| Teknis | Signifikan | Kegagalan mesin, malfungsi sistem (contoh: MCAS pada Lion Air JT 610) |
| Cuaca & Lingkungan | 4 kasus | Microburst, kabut, atau asap |
| Kebijakan & Prosedur | Penting | Kurangnya kepatuhan terhadap standar keselamatan |
| Sabotase & Kriminal | Jarang di Indonesia | Tindakan terorisme, pembajakan |
Respons Pemerintah dan Industri: Regulasi dan Pencabutan Larangan Terbang Uni Eropa
Pemerintah Indonesia merespons isu keselamatan dengan memperkuat kerangka regulasi. Salah satu landasan hukum yang penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab Menteri Perhubungan untuk mengawasi berbagai aspek, mulai dari rancang bangun pesawat udara, pemeliharaan, hingga operasi bandara.
Pada tahun 2007, Uni Eropa memberlakukan larangan terbang (flight ban) terhadap seluruh maskapai penerbangan Indonesia karena kekhawatiran yang mendalam tentang standar keselamatan. Larangan ini menjadi katalisator eksternal yang memaksa industri dan pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran. Setelah kerja panjang selama 11 tahun yang berfokus pada peningkatan standar keselamatan sesuai dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organisation/ICAO), Komisi Eropa mulai mencabut larangan tersebut secara parsial pada tahun 2009 dan akhirnya mencabut larangan terbang semua maskapai pada 14 Juni 2018. Pencabutan ini merupakan validasi internasional atas reformasi sistematis yang telah dilakukan dan secara signifikan meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap otoritas penerbangan Indonesia.
Peran Pembangunan Infrastruktur Bandara
Pembangunan infrastruktur bandara merupakan pilar penting dalam mendukung evolusi dan keberlanjutan industri penerbangan. Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi udara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, 27 bandar udara baru telah dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat lokal di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pembangunan bandara-bandara baru ini menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui peningkatan konsumsi lokal dan pariwisata.
Pembangunan infrastruktur ini juga sangat relevan dengan model bisnis LCC. Maskapai berbiaya rendah memiliki strategi menggunakan bandara sekunder untuk meminimalisir biaya layanan selama jam sibuk. Bandara-bandara baru yang tersebar di seluruh Indonesia memungkinkan maskapai LCC untuk memperluas jaringan rute point-to-point mereka. Dengan demikian, tercipta hubungan simbiosis mutualisme: pembangunan bandara baru menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk ekspansi LCC, sementara LCC memastikan bandara-bandara ini memiliki volume penumpang yang memadai untuk beroperasi secara ekonomis.
Penerbangan Modern: Transformasi Digital dan Keberlanjutan
Digitalisasi Layanan Penerbangan
Industri penerbangan di Indonesia kini tengah menjalani transformasi digital. Tren ini mencakup penggunaan Big Data untuk menganalisis perilaku pelanggan dan mengoptimalkan rute, adopsi Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan (AI) dalam proses pemesanan dan layanan pelanggan, serta peningkatan pengalaman pelanggan melalui aplikasi mobile interaktif. Aplikasi pemesanan tiket online, seperti BookCabin milik Lion Group, menawarkan berbagai fitur yang memudahkan penumpang, seperti pemesanan tiket, check-in online, dan upgrade kelas bisnis.
Meskipun digitalisasi meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, ia juga membawa tantangan baru. Harga tiket pesawat di aplikasi online dapat naik berkali-kali lipat karena algoritma yang mengakumulasi harga dari titik keberangkatan ke titik transit, menghasilkan biaya yang tidak masuk akal bagi konsumen. Selain itu, kurangnya pendidikan publik dalam menghadapi teknologi baru ini dapat memicu kekagetan sosial, seperti perilaku penumpang yang melanggar prosedur keamanan bandara. Oleh karena itu, inovasi teknologi harus diiringi dengan regulasi yang transparan dan edukasi konsumen yang berkelanjutan.
Menuju Industri Hijau: Eksperimen Bioavtur dan Tantangan Lingkungan
Tuntutan global untuk mengurangi dampak lingkungan seperti polusi udara dan kebisingan telah mendorong industri penerbangan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Indonesia telah mengambil langkah maju dengan berhasil melakukan uji coba bioavtur, bahan bakar nabati, pada pesawat CN-235 milik PT Dirgantara Indonesia pada Oktober 2021. Bioavtur dikembangkan dari minyak kelapa sawit, yang menunjukkan potensi besar Indonesia untuk menjadi regional SAF leader.
Namun, implementasi bioavtur secara massal menghadapi tantangan besar, terutama terkait tekanan kenaikan biaya operasional. Harga bioavtur saat ini jauh lebih mahal dibandingkan bahan bakar fosil, yang dapat mengancam model bisnis LCC yang sangat bergantung pada efisiensi biaya. Solusi untuk mengatasi tantangan ini memerlukan kebijakan lingkungan berkelanjutan yang seimbang dengan kebutuhan operasional , serta insentif dari pemerintah, seperti subsidi, dukungan harga, atau mandat pencampuran untuk menciptakan kepastian permintaan dan mendorong investasi dalam produksi bahan bakar berkelanjutan (SAF) domestik.
Proyeksi Pertumbuhan dan Prospek Pasar di Masa Depan
Prospek pasar penerbangan Indonesia di masa depan sangat menjanjikan. Laporan Commercial Market Outlook (CMO) 2025 dari Boeing memproyeksikan bahwa Indonesia akan naik ke posisi keempat pasar penumpang pesawat terbesar di dunia pada tahun 2037. Potensi ini didukung oleh faktor demografis yang kuat, terutama populasi muda dan produktif, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk memenuhi pertumbuhan yang diproyeksikan ini, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi untuk 600 pesawat baru.
Meskipun prospeknya cerah, realisasi pertumbuhan ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan yang saling terkait. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur yang memadai , menstabilkan basis biaya operasional , dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jika tantangan-tantangan ini tidak ditangani, pertumbuhan industri mungkin akan stagnan, berpotensi mengonsolidasikan menjadi lebih sedikit pemain dan mengurangi persaingan. Oleh karena itu, masa depan industri penerbangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh potensi pasar yang besar, tetapi juga oleh strategi proaktif dan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk membangun fondasi yang kuat.
Kesimpulan
Evolusi penerbangan komersial di Indonesia adalah cerminan dari perjalanan bangsa ini. Dari layanan eksklusif di era kolonial, industri ini bertransformasi menjadi utilitas massal yang didemokratisasi oleh kebijakan deregulasi. Ledakan LCC pada tahun 2000-an secara fundamental mengubah perilaku konsumen dan menjembatani konektivitas antarpulau, suatu kebutuhan krusial bagi negara kepulauan. Di masa kini, industri ini memasuki babak baru yang ditandai dengan digitalisasi, kompetisi ketat antara grup maskapai, dan dorongan menuju keberlanjutan.
Meskipun prospek pertumbuhan pasar sangat cerah, industri ini menghadapi tantangan berkelanjutan yang signifikan. Tantangan ini meliputi isu keselamatan yang didominasi oleh faktor manusia, kebutuhan akan investasi masif dalam infrastruktur dan armada, serta tekanan biaya operasional global yang mengancam model bisnis low-cost. Selain itu, industri juga harus menavigasi kompleksitas transformasi digital dan transisi menuju green aviation yang memerlukan dukungan kebijakan yang kuat.