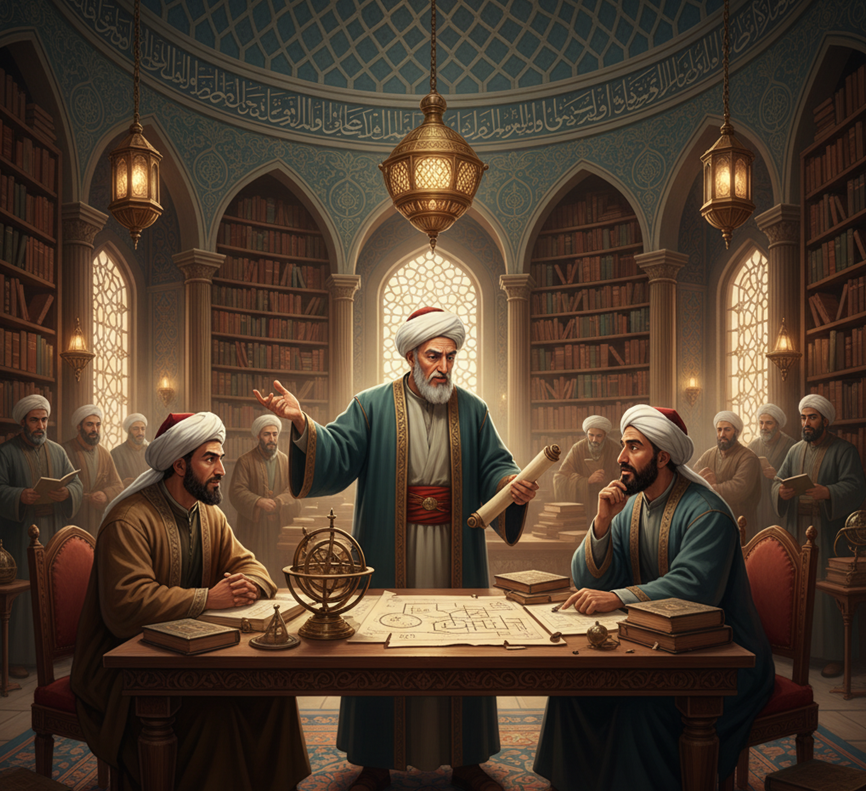Latar Belakang Sejarah dan Krisis Intelektual Abad ke-11 dan ke-12
Perdebatan filosofis antara Ab┼½ ßĖż─ümid MußĖźammad ibn MußĖźammad al-Ghaz─ül─½ (Al-Ghazali) dan Ab┼½ al-Wal─½d MußĖźammad ibn AßĖźmad ibn Rushd (Ibn Rushd) merupakan salah satu titik balik paling penting dalam sejarah pemikiran Islam dan filsafat dunia. Kajian ini berlatar belakang pada periode kritis abad ke-11 dan ke-12 Masehi, ketika Teologi Sunni Ash’ariyah, yang baru saja terkonsolidasi, menghadapi tantangan berat dari dua kekuatan intelektual: teologi Syi’ah Ism─ü’─½liyah dan tradisi filsafat Aristotelian/Neo-Platonik yang dikenal sebagai falsafa.
Gerakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab telah berhasil melakukan “naturalisasi” sains dan logika Yunani ke dalam wacana intelektual Muslim, sebuah proses yang, meskipun memperkaya keilmuan, juga menciptakan ketegangan antara demonstrasi rasional (apodeixis) dan kebenaran yang bersumber dari wahyu. Para filsuf Muslim awal, seperti Ibn S─½n─ü (Avicenna), telah berhasil mengintegrasikan pemikiran Yunani ke dalam sistem metafisika Islam, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan teolog. Di tengah ketegangan ini, Al-Ghazali muncul sebagai seorang Mujaddid (reformis). Setelah melalui krisis skeptisisme personal, Al-Ghazali bertekad mencari ŌĆÖIlm Yaq─½n (Kebenaran yang Pasti). Upayanya melibatkan pengujian metodologi berbagai kelompok, termasuk mutakallim┼½n, Syi’ah Batiniyah, filsuf, dan sufi.
Profil Tokoh Utama: Kontras antara Hujjatul Islam (Al-Ghazali) dan Komentator Agung (Ibn Rushd)
Kedua tokoh ini mewakili puncak tradisi intelektual yang berbeda dalam Islam. Al-Ghazali (c.1056ŌĆō1111), yang dijuluki Hujjatul Islam (Argumen Islam), adalah seorang teolog Ash’ariyah, ahli hukum, dan mistikus. Ia menguasai berbagai ilmu, seperti Fiqh, Uß╣Ż┼½l, Manß╣Łiq (Logika), dan Teologi, yang membuatnya mendapatkan sebutan Bahrul Mughriq (Lautan yang Menenggelamkan). Al-Ghazali menekankan pentingnya tidak mengikuti ajaran tanpa mengetahui alasannya (anti-taql─½d). Kritiknya yang paling signifikan tertuang dalam ┬ĀTah─üfut al-fal─üsifa (Inkoherensi Para Filsuf), yang menargetkan falsafa (khususnya Avicennism) dan memajukan kritik yang belakangan dikenal sebagai nominalisme di Eropa abad ke-14.
Sebaliknya, Ibn Rushd (1126ŌĆō1198), yang dikenal di Barat sebagai Averroes, adalah seorang polymath dari Andalusia. Ia berasal dari keluarga ahli hukum terpandang dan menonjol dalam hukum, fisika, dan filsafat. Kontribusinya yang paling abadi adalah melalui komentar-komentarnya yang mendalam terhadap karya Aristoteles, yang membuatnya dijuluki “The Great Commentator” di Barat. Tujuan Ibn Rushd adalah mengembalikan pemikiran Aristoteles ke bentuk murninya, membersihkannya dari distorsi yang ditambahkan oleh filsuf-filsuf sebelumnya, termasuk Ibn S─½n─ü. Penting untuk diperhatikan bahwa kritik Al-Ghazali terhadap filsafat telah mapan di Timur selama lebih dari seabad sebelum Ibn Rushd memberikan tanggapan balik dari Barat Islam.
Fungsi dan Posisi Karya Sentral
Debat intelektual ini diringkas dan diabadikan melalui tiga karya monumental:
- Tah─üfut al-fal─üsifa: Karya sentral Al-Ghazali, yang berfungsi sebagai proklamasi teologis. Di dalamnya, ia mengkritik 20 doktrin metafisika yang ia anggap bertentangan dengan ajaran Islam dan bertujuan mengekspos inkonsistensi internal dalam sistem falsafa.
- Tah─üfut al-Tah─ühut (Inkoherensi dari Inkoherensi): Respon langsung dari Ibn Rushd. Karya ini secara sistematis membongkar argumen Al-Ghazali. Ibn Rushd berusaha menunjukkan bahwa bukan filsafat yang inkoheren, melainkan metodologi Kal─üm Ash’ariyah yang fragmentaris.
- Faß╣Żl al-Maq─ül f─½ m─ü bayna al-ßĖżikmah wa ash-Shar─½ŌĆśah min Ittiß╣Ż─ül (Risalah Penentu tentang Hubungan antara Filsafat dan Syariat): Traktat legal-teologis yang mendahului Tah─üfut al-Tah─ühut. Karya ini menyediakan landasan teoretis bagi Ibn Rushd, menyatakan bahwa filsafat adalah disiplin yang dibenarkan, bahkan diwajibkan, oleh Syariat, bagi mereka yang mampu.
Landasan Epistemologis: Akal, Wahyu, dan Metode
Posisi Ash’ariyah Al-Ghazali: Prioritas Wahyu dan Keterbatasan Akal dalam Metafisika
Al-Ghazali mewakili sudut pandang yang memberikan prioritas kepada wahyu sebagai sumber utama kebenaran, terutama dalam isu-isu metafisika (Ilahiyy─üt). Ia menunjukkan skeptisisme mendalam terhadap kemampuan nalar murni (yang terlepas dari pencerahan mistis atau panduan ilahi) untuk mencapai ŌĆÖilm yaq─½n dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan.
Namun, terdapat paradoks metodologis yang melekat dalam kritiknya. Meskipun ia secara tajam menyerang kesimpulan metafisik para filsuf, Al-Ghazali adalah tokoh yang bertanggung jawab atas keberhasilan memasukkan logika Aristotelian (Manß╣Łiq) ke dalam diskursus Kal─üm Sunni. Dengan menggunakan instrumen demonstrasi rasional filsafat untuk membuktikan batasannya sendiri dalam metafisika, Al-Ghazali secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap metodologi filsafat itu sendiri. Upaya ini menghasilkan diskursus yang jauh lebih halus dan tepat tentang epistemologi dalam teologi Muslim pasca-Ghazali. Tindakan ini memastikan bahwa filsafat, dalam bentuknya yang logis dan metodologis, tidak mati, melainkan diabadikan dalam sistem teologi Sunni, mengambil peran sebagai ancilla theologiae (pelayan teologi), yang membantu menyusun argumen teologis secara lebih ketat.
Pendekatan Aristotelian Ibn Rushd: Harmoni Nalar dan Wahyu sebagai Kewajiban Syar’i
Ibn Rushd berdiri teguh pada keyakinan filosofis bahwa akal (ratio) dan wahyu (revelation) pada dasarnya tidak mungkin bertentangan, sebab keduanya bersumber dari Allah, Sang Kebenaran Mutlak. Ia berpendapat bahwa penggunaan akal adalah mutlak diperlukan untuk memahami wahyu, dan kesatuan antara pemahaman rasional dan keagamaan dapat dicapai.
Dalam karyanya, Faß╣Żl al-Maq─ül, Ibn Rushd membawa argumen ini ke tingkat hukum agama. Ia menyatakan bahwa Syariat tidak hanya mengizinkan, tetapi secara legal mewajibkan (berstatus wajib) studi filsafat (al-ßĖźikmah) bagi mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Bagi Ibn Rushd, akal adalah anugerah Ilahi. Penggunaannya untuk merenungkan ciptaan, yang merupakan inti dari filsafat melalui metode qiy─üs burh─ün─½ (silogisme demonstratif), adalah cara untuk memahami hikmah dan kekuasaan Tuhan. Pandangan ini memposisikan akal dan wahyu sebagai “saudara sesusuan” (ukht al-radi’ah), yang saling membutuhkan: wahyu membutuhkan kekuatan akal untuk dapat dimengerti, sementara akal membutuhkan wahyu untuk menjangkau permasalahan metafisik (ghayb) yang melampaui jangkauan indera.
Pembedahan Kritik Sentral Al-Ghazali: Tah─üfut al-fal─üsifa
Al-Ghazali mengelompokkan filsuf yang ia kritik menjadi tiga kategori: ad-Dahriyyun (materialis), ath-Thabi’iyyun (naturalis), dan Ilahiyyun (teistik, merujuk pada Avicenna dan Al-Farabi). Dari 20 isu yang dibahas, Al-Ghazali memfokuskan kritiknya hampir secara eksklusif pada metafisika (Ilahiyy─üt), yang ia yakini merusak pondasi keimanan umat.
Analisis Mendalam Tiga Isu Utama yang Menyebabkan Pengkafiran (Al-Mas─üŌĆÖil al-Thal─üthah al-Kufriyyah)
Al-Ghazali menetapkan bahwa para filsuf yang memegang tiga doktrin utama ini harus dihukumi kafir (unbeliever) , karena doktrin-doktrin tersebut secara langsung merusak prinsip-prinsip fundamental dogma Islam: penciptaan, kemahatahuan Tuhan, dan eskatologi.
- Keazalian Alam (Qid─üm al-‘─Ćlam / Eternity of the World)
- Kritik Al-Ghazali: Para filsuf (khususnya Avicenna) berpendapat bahwa alam itu azali (kekal) dan tidak memiliki permulaan temporal, melainkan merupakan efek yang niscaya dari Tuhan yang Abadi. Pandangan ini, menurut Al-Ghazali, bertentangan dengan konsep penciptaan ex nihilo (dari ketiadaan) pada waktu tertentu, dan yang lebih penting, merampas kehendak bebas Tuhan untuk memilih kapan dan bagaimana menciptakan. Ini dipandang sebagai kekufuran.
- Sanggahan Ibn Rushd: Perbedaan pandangan ini, menurut Ibn Rushd, hanya berkisar pada interpretasi istilah qad─½m (kekal). Filsuf tidak menyangkal bahwa alam membutuhkan Agen Abadi (Tuhan), tetapi lebih menekankan bahwa gerakan alam bersifat abadi, bukan bahwa alam tidak diciptakan sama sekali.
- Pengetahuan Tuhan tentang Hal-hal Partikular (Juz’iyy─üt)
- Kritik Al-Ghazali: Filsuf berpendapat Tuhan hanya mengetahui hal-hal universal (kulliy─üt). Pengetahuan tentang hal-hal partikular memerlukan indra dan perubahan, yang tidak sesuai dengan kesempurnaan dan kemutlakan Tuhan. Al-Ghazali menganggap pembatasan Kemahatahuan (Omniscience) ini merusak dasar takl─½f (kewajiban hukum) dan sistem syariat, sehingga juga dihukumi kafir.
- Sanggahan Ibn Rushd: Ibn Rushd menjelaskan bahwa konflik ini timbul karena Al-Ghazali menyamakan pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia tentang partikular diperoleh melalui indra dan bersifat berubah-ubah, sementara pengetahuan Ilahi bersifat unik dan merupakan sebab dari hal-hal partikular, bukan sekadar akibat dari pengamatan. Pengetahuan Tuhan melampaui dikotomi universal dan partikular yang membatasi nalar manusia.
Penolakan Kebangkitan Jasmani (Ma’─üd Jism─ün─½)
- Kritik Al-Ghazali: Filsuf cenderung menerima hanya kebangkitan jiwa (spiritual resurrection). Bagi Al-Ghazali, ini mengingkari janji eskatologis eksplisit dalam Al-Qur’an tentang Surga dan Neraka fisik (kebangkitan jasmani).
- Sanggahan Ibn Rushd: Ibn Rushd memandang kebangkitan jasmani sebagai prinsip dasar syariat yang harus diterima. Ia mengkritik para filsuf yang membahas isu sensitif ini di hadapan khalayak umum. Meskipun Ibn Rushd sendiri menekankan interpretasi (ta’w─½l) terhadap teks-teks eskatologis, ia bersikeras bahwa kebenaran Syariat terkait kebangkitan fisik tidak dapat ditolak.
Perbandingan tiga isu krusial yang mengarah pada pengkafiran oleh Al-Ghazali disajikan dalam tabel berikut:
Tabel Tiga Poin Kufriyyat Utama dan Posisi Kedua Tokoh
| Isu Sentral (Mas─üŌĆÖil al-Kufriyyah) | Pandangan Filsuf (Avicenna/Falsafa) | Kritik Al-Ghazali (Tah─üfut al-fal─üsifa) | Sanggahan Ibn Rushd (Tah─üfut al-Tah─ühut) |
| Keazalian Alam (Qid─üm al-‘─Ćlam) | Alam azali, diciptakan secara niscaya (efek abadi dari sebab abadi). | Bertentangan dengan penciptaan ex nihilo dan Kehendak Ilahi; Kufr. | Perbedaan interpretasi kata qad─½m. Alam membutuhkan Agen Abadi, yang tidak disangkal. |
| Pengetahuan Tuhan (Juz’iyy─üt) | Tuhan hanya mengetahui universal (kulliy─üt). | Mengurangi Kemahatahuan; merusak dasar takl─½f; Kufr. | Pengetahuan Tuhan adalah unik, sebab hal-hal partikular, dan melampaui dikotomi partikular/universal manusia. |
| Kebangkitan Jasmani (Ma’─üd Jism─ün─½) | Hanya kebangkitan spiritual/jiwa. | Mengingkari janji eksplisit Al-Qur’an; Kufr. | Kebangkitan fisik adalah kebenaran syarŌĆÖi yang wajib diterima. Filsafat harus diinterpretasikan untuk tidak menolaknya. |
Inti Debat Kosmologi: Kausalitas dan Kemahakuasaan Ilahi
Perdebatan tentang kausalitas (sebab-akibat) merupakan diskusi metafisik yang paling berpengaruh dalam Tah─üfut, karena menentukan hubungan antara Tuhan, alam, dan ilmu pengetahuan.
Doktrin Occasionalism Al-Ghazali
Al-Ghazali, dalam upayanya yang radikal untuk mempertahankan Kemahakuasaan Tuhan (Omnipotence), menggabungkan gagasan yang dikembangkan dalam Kal─üm untuk membentuk Okasionalisme. Doktrin ini secara eksplisit menolak kausalitas sekunder yang melekat di alam, yang dianut oleh filsuf Aristotelian.
Menurut Okasionalisme Ash’ariyah yang diikuti Al-Ghazali, tidak ada koneksi niscaya (natural necessity) antara apa yang kita amati sebagai sebab (misalnya, api) dan apa yang kita amati sebagai akibat (misalnya, kapas terbakar). Al-Ghazali berpendapat bahwa koneksi ini hanyalah ŌĆÖ─üdah (kebiasaan) yang secara konsisten diciptakan oleh Tuhan. Ketika api menyentuh kapas, bukan api yang membakar, tetapi Allah yang menciptakan peristiwa ‘kebakaran’ pada momen kontak tersebut. Inti teologis dari pandangan ini adalah untuk mempertahankan kebebasan total Tuhan. Jika benda memiliki kekuatan kausal yang melekat, Tuhan tidak akan dapat melakukan mukjizat tanpa melanggar sifat-sifat benda tersebut, sehingga membatasi kemahakuasaan-Nya.
Naturalisme Kausal Ibn Rushd
Ibn Rushd, sebagai pembela filsafat alam Aristotelian, membantah Okasionalisme secara tegas. Ia berargumen bahwa penolakan kausalitas adalah penghancuran fondasi ilmu pengetahuan dan akal sehat.
Bagi Ibn Rushd, hukum-hukum alam yang stabil dan kausalitas sekunder yang niscaya adalah manifestasi dari hikmah (kebijaksanaan) dan ketertiban Ilahi. Jika tidak ada hubungan niscaya antara sebab dan akibat, maka semua pengetahuan yang didasarkan pada observasi dan induksi menjadi tidak mungkin. Menghilangkan hukum-hukum kausal ini menghilangkan kemungkinan untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat diandalkan (ilm yaqin), dan membuat prediksi ilmiah, penalaran, atau bahkan memahami kebijaksanaan di balik ciptaan menjadi mustahil.
Implikasi Terhadap Ilmu Pengetahuan
Terdapat pandangan bahwa doktrin Okasionalisme Al-Ghazali, khususnya penyajiannya yang ditujukan untuk publik, telah berkontribusi pada stagnasi ilmu pengetahuan di dunia Islam dengan mengikis fondasi intelektual ilmu alam (yaitu, prediktabilitas dan induksi). Jika api tidak selalu membakar kapas, maka eksperimen tidak dapat menghasilkan kepastian yang demonstratif. Namun, analisis yang lebih bernuansa menunjukkan bahwa beberapa teolog Ash’ariyah pasca-Ghazali, seperti Al-Razi dan Al-Amidi, menerima kausalitas sekunder. Bahkan, beberapa penelitian berpendapat bahwa Al-Ghazali sendiri mungkin secara diam-diam lebih rasionalis, dan bahwa metodenya sebenarnya memungkinkan sains rasional dan alam diterima ke dalam wacana keilmuan Islam arus utama di kemudian hari. Meskipun demikian, dampak yang terasa di Timur adalah delegitimasi terhadap kepastian kausal yang diperlukan untuk sains independen, sementara Ibn Rushd tetap gigih membela hukum alam sebagai bukti ketertiban Ilahi.
Tabel berikut meringkas perbedaan paradigma fundamental:
Perbedaan Paradigma Kausalitas dan Hubungan Akal-Wahyu
| Dimensi | Al-Ghazali (Occasionalism Ash’ariyah) | Ibn Rushd (Aristotelian/Falsafa) |
| Hubungan Sebab-Akibat | Tidak ada koneksi esensial; Tuhan adalah satu-satunya Agen Kausal Mutlak. Hanya ŌĆÖ─üdah (kebiasaan). | Terdapat kausalitas sekunder yang niscaya, ditetapkan oleh Tuhan (Hukum Alam). |
| Kapasitas Akal | Akal terbatas; harus tunduk pada Wahyu dalam metafisika. Mencurigai nalar murni sebagai sumber kepastian. | Akal (logika demonstratif) setara dengan wahyu; wajib digunakan untuk memahami wahyu. |
| Tujuan Utama | Membela Kedaulatan Mutlak Tuhan (Omnipotensi) dan kemungkinan mukjizat. | Memperjuangkan Harmoni, Konsistensi Logis, dan Ketertiban Alam Ilahi. |
Sanggahan Rasional Ibn Rushd: Tah─üfut al-Tah─ühut
Metode Sanggahan: Dekonstruksi Argumen Al-Ghazali
Karya Tah─üfut al-Tah─ühut adalah pembelaan habis-habisan terhadap filsafat, yang dilaksanakan melalui sanggahan point-by-point yang terstruktur. Ibn Rushd tidak hanya membela filsuf dari tuduhan inkonsistensi, tetapi juga secara aktif menyerang metodologi Kal─üm.
Ibn Rushd mengklaim bahwa Al-Ghazali gagal membuktikan bahwa doktrin filsuf bersifat inkonsisten secara internal; sebaliknya, Al-Ghazali hanya menunjukkan bahwa pandangan filsuf berbeda dari pandangan mutakallim┼½n. Inti dari sanggahan Ibn Rushd adalah pembelaan terhadap konsistensi logis filsafat Aristotelian. Ia berupaya menunjukkan bahwa keraguan filosofis yang ditanamkan oleh Al-Ghazali sebenarnya berasal dari kelemahan epistemologis yang melekat dalam sistem teologi Ash’ariyah, yang didasarkan pada atomisme yang fragmentaris.
Meluruskan Pengetahuan Ilahi
Secara spesifik, dalam menanggapi isu Juz’iyy─üt (pengetahuan partikular), Ibn Rushd melakukan koreksi epistemologis yang tegas. Ia berargumen bahwa pengetahuan Tuhan tentang perincian di alam tidak dapat disamakan dengan pengetahuan manusia tentang perincian yang didapatkan melalui panca indera. Pengetahuan manusia tentang partikular bersifat berubah dan berkembang seiring waktu, sementara pengetahuan Tuhan bersifat kekal, tak terbatas, dan menjadi sebab yang menciptakan partikular itu sendiri. Dengan demikian, pertentangan antara Al-Ghazali dan filsuf timbul dari kesalahan penyamaan sifat pengetahuan Ilahi dengan keterbatasan pengetahuan manusia.
Rekonsiliasi Legal-Teologis: Ibn Rushd dan Faß╣Żl al-Maq─ül
Justifikasi Syar’i terhadap Filsafat
Faß╣Żl al-Maq─ül adalah karya paling eksplisit Ibn Rushd dalam upaya harmonisasi akal dan wahyu. Dalam karya ini, ia menggunakan kerangka hukum Islam untuk mendemonstrasikan bahwa filsafat adalah kewajiban agama. Hukum Syariah, melalui ayat-ayat Al-Qur’an yang menyerukan refleksi mendalam terhadap alam semesta, secara implisit mewajibkan bentuk refleksi yang paling sempurna, yaitu burh─ün (demonstrasi filosofis).
Ibn Rushd secara metaforis menyebut akal dan wahyu sebagai “saudara sesusuan” (ukht al-radi’ah), yang keduanya merupakan anugerah dari Tuhan dan tak mungkin terpisah. Wahyu memerlukan akal agar dapat dipahami secara mendalam, terutama ayat-ayat yang tampak bertentangan dengan nalar.
Teori Ta’wil (Interpretasi Alegoris) dan Stratifikasi Audiens
Untuk mengatasi konflik yang terlihat antara nalar dan teks suci, Ibn Rushd mengembangkan teori ta’w─½l. Prinsip ta’w─½l menyatakan bahwa jika hasil nalar demonstratif (burh─ün) bertentangan dengan makna literal teks suci, maka makna literal tersebut harus ditafsirkan secara alegoris.
Metodologi ta’w─½l ini terikat erat dengan konsep stratifikasi audiens (jenjang kecerdasan manusia). Ibn Rushd membagi publik menjadi tiga tingkatan berdasarkan kemampuan mereka dalam menerima kebenaran:
- Orang Demonstratif (Burh─ün─½): Para filsuf dan ilmuwan yang dapat memahami kebenaran melalui silogisme yang ketat.
- Orang Dialektik (Jadal─½): Para teolog dan ahli hukum yang menggunakan argumen probabilitas.
- Orang Retorik (Khiß╣Ł─üb─½): Khalayak umum (al-jumh┼½r) yang menerima kebenaran melalui persuasi dan bahasa metaforis.
Strategi ini menciptakan semacam “tembok api intelektual” yang dirancang untuk melindungi filsafat dari campur tangan publik sambil melindungi masyarakat dari potensi fitnah (kekacauan teologis) yang mungkin timbul jika interpretasi esoterik disebarkan kepada khalayak yang hanya mampu memahami makna literal. Bagi Ibn Rushd, ini adalah upaya untuk mengkompromikan dan menjalin makna yang menghormati semangat wahyu sambil meraikan tuntutan nalar murni.
Warisan dan Dampak Jangka Panjang Perdebatan
Konsekuensi di Dunia Islam Timur
Meskipun kritik Al-Ghazali sering dituduh merusak tradisi falsafa, warisannya di Timur bersifat kompleks. Pertama, ia berhasil memasukkan logika Aristotelian (Manß╣Łiq) ke dalam kurikulum teologi Sunni. Setelahnya, hampir semua teolog Muslim pasca-Ghazali menerima dan menggunakan Manß╣Łiq untuk menyusun argumen Kal─üm mereka, yang menghasilkan diskursus teologis yang lebih rasionalis dan metodologis.
Namun, dari segi substansi, vonis pengkafiran (takf─½r) terhadap tiga isu utama dan serangan terhadap kausalitas sekunder memiliki efek mendinginkan. Filsafat spekulatif (falsafa) sebagai disiplin independen, terutama metafisika, cenderung dijauhi di pusat-pusat intelektual Sunni seperti Baghdad. Meskipun Al-Ghazali sendiri tidak sepenuhnya menolak filsafat, fokusnya pada metafisika Avicennian menciptakan sentimen negatif yang mengarahkan perkembangan intelektual di Timur menuju konsolidasi teologi-sufisme, seperti yang ia jabarkan dalam karya agungnya Ihy─üŌĆÖ ŌĆśUl┼½m al-D─½n.
Pengaruh di Dunia Islam Barat dan Eropa Latin (Averroisme)
Ibn Rushd dan karya-karyanya memiliki dampak langsung yang relatif lebih kecil di Timur, tetapi dampaknya di Barat (Andalusia) dan Eropa Latin (sebagai Averroes) sangat besar. Komentar-komentar Ibn Rushd diterjemahkan secara ekstensif ke dalam bahasa Latin dan Ibrani, menjadikannya “Komentator” standar Aristoteles di Barat.
Averroisme Latin menjadi kekuatan intelektual yang signifikan dalam filosofi skolastik Abad Pertengahan Eropa. Keyakinan Ibn Rushd pada otoritas otonom demonstrasi filosofis dalam banyak domain, serta prinsip rekonsiliasi akal dan wahyu, mempengaruhi para pemikir besar, meskipun banyak yang, seperti Thomas Aquinas, kemudian menyanggah ajaran-ajarannya. Ibn Rushd tidak hanya menghidupkan kembali Aristotelianisme murni, tetapi juga meletakkan dasar bagi pengembangan rasionalitas sekuler di Eropa.
Terdapat ironi mendalam dalam warisan kontras kedua tokoh ini: Al-Ghazali memperkuat Kal─üm di Timur tetapi pada saat yang sama menyediakan kerangka kerja nominalis (melalui Okasionalisme) yang kemudian muncul kembali dalam pemikiran Eropa abad ke-14. Sebaliknya, Ibn Rushd secara efektif “mengekspor” rasionalisme Aristotelian murni ke Eropa. Perdebatan ini, yang berawal dari isu lokal mengenai kepatutan filsafat dalam Islam, akhirnya membentuk jalur yang berbeda untuk perkembangan teologi dan filsafat di dunia Islam dan Kristen.
Kesimpulan: Dialektika Antara Kehendak Mutlak dan Nalar Niscaya
Perdebatan intelektual yang diperjuangkan melalui Tah─üfut al-fal─üsifa dan Tah─üfut al-Tah─ühut melampaui sekadar perselisihan akademis; itu adalah dialektika mendasar mengenai sifat Tuhan dan hubungan-Nya dengan alam semesta. Al-Ghazali adalah juara Kehendak Mutlak Ilahi yang tak terbatas, di mana kebebasan Tuhan harus dipertahankan bahkan dengan mengorbankan kausalitas niscaya di alam. Sementara itu, Ibn Rushd adalah pembela Nalar Niscaya, meyakini bahwa keteraturan kausal adalah bukti kebijaksanaan Tuhan (hikmah) dan menuntut interpretasi fleksibel (ta’w─½l) terhadap wahyu untuk mencapai harmoni dengan kebenaran demonstratif.
Meskipun Al-Ghazali berhasil dalam memasukkan logika ke dalam teologi dan memperkuat ortodoksi Sunni melawan falsafa spekulatif di Timur, keberhasilan ini terjadi dengan biaya delegitimasi kausalitas sekunder di mata publik. Sebaliknya, Ibn Rushd gagal mengubah arus intelektual di Timur, tetapi keberhasilannya yang monumental adalah melestarikan dan mentransmisikan rasionalisme Aristotelian murni yang kemudian membentuk batu penjuru pemikiran Barat. Warisan kontras mereka menggarisbawahi tantangan abadi dalam semua tradisi agama-filosofis: bagaimana menyeimbangkan kedaulatan transenden Tuhan dengan ketertiban imanen yang dapat dipahami melalui akal manusia.