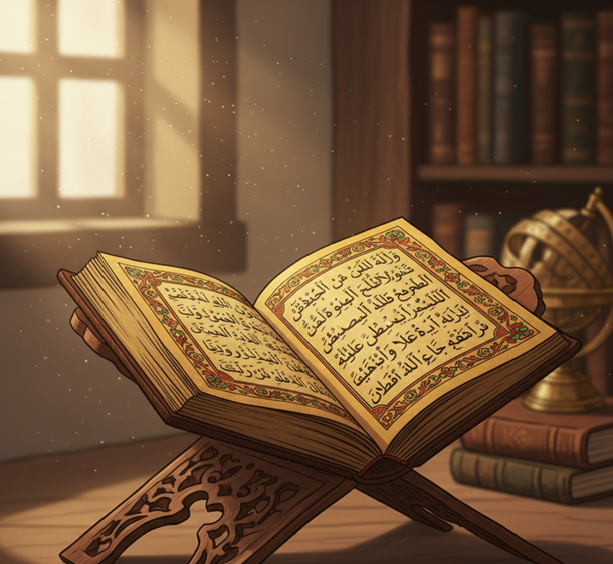Definisi, Etimologi, dan Terminologi Kitab Kuning
Istilah Kitab Kuning, atau yang juga dikenal sebagai Al-Kutub al-Turath (Kitab Warisan) atau Kitab Gundul, merujuk pada koleksi karya-karya keilmuan Islam klasik yang mayoritas ditulis oleh ulama-ulama Islam pada zaman pertengahan. Teks-teks ini mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, akidah, tasawuf, tata bahasa Arab, hingga tafsir dan hadis.
Meskipun secara harfiah merujuk pada warna kertasnya—yang secara spekulatif dikaitkan dengan penggunaan kertas berwarna kuning yang lebih tahan lama di Timur Tengah dan lebih nyaman dibaca di bawah pencahayaan tradisional—esensi utama Kitab Kuning terletak pada tradisi keilmuan yang terkandung di dalamnya, bukan pada aspek fisik cetakannya. Karya-karya inilah yang menjadi kurikulum utama di pesantren salaf dan merupakan fondasi epistemologis bagi tradisi intelektual Islam di Nusantara.
Anatomi Tekstual: Karakteristik “Kitab Gundul” dan Implikasi Linguistiknya
Ciri khas Kitab Kuning yang paling kentara adalah formatnya yang “gundul,” yaitu ketiadaan harakat (vokal pendek seperti fathah, kasrah, atau dammah) pada teks Arab. Karakteristik ini bukan sekadar ketidaklengkapan cetakan, melainkan sebuah mekanisme pedagogis yang disengaja dan sangat efektif dalam melatih kedalaman pemahaman santri.
Ketiadaan harakat ini secara langsung menuntut pembaca untuk menentukan i’rab, yaitu perubahan harakat akhir kata yang menentukan fungsi gramatikal kata tersebut dalam sebuah kalimat (misalnya, sebagai subjek, objek, atau kata sifat). Akibatnya, untuk membaca dan memahami makna yang terkandung, santri harus menguasai secara mendalam ilmu tata bahasa Arab. Ini menciptakan sebuah saringan epistemik yang disengaja. Apabila sebuah teks memiliki harakat, pembaca mungkin hanya perlu menghafal terjemahan. Namun, format “gundul” memaksa santri untuk menguasai kaidah tata bahasa secara kontekstual dan intuitif. Kemampuan analisis linguistik mandiri ini adalah prasyarat filosofis untuk berpartisipasi dalam wacana hukum yang lebih tinggi, seperti forum Bahtsul Masa’il.
Selain itu, stilistika penulisan klasik dalam Kitab Kuning sangat terstruktur tetapi berbeda dengan gaya penulisan modern. Pergeseran dari satu sub-topik ke sub-topik lainnya tidak ditandai dengan alinea baru. Sebagai gantinya, digunakan kode-kode khusus seperti tatimmah (pelengkap), muhimmah (hal penting), atau tanbih (peringatan). Penggunaan kode-kode ini menunjukkan bahwa teks tersebut disusun sebagai panduan hukum atau kaidah yang sangat terstruktur, menekankan kejelasan poin-poin hukum daripada narasi deskriptif.
Ilmu Alat (Instrumental Sciences): Peran Krusial Nahwu dan Shorof
Penguasaan Kitab Kuning adalah ukuran utama kemahiran seorang santri. Namun, kemampuan ini tidak dapat dicapai tanpa penguasaan ilmu alat (ilmu instrumental), yang paling utama adalah Nahwu (sintaksis) dan Shorof (morfologi).
Nahwu adalah ilmu yang mengkaji harakat akhir suatu kata dan struktur kalimat (i’rab), yang sangat penting untuk menentukan fungsi gramatikal kata. Tanpa Nahwu, harakat akhir kata dalam Kitab Gundul tidak dapat ditentukan dengan benar, yang secara fatal dapat mengubah makna sebuah kalimat atau fatwa hukum. Shorof berfokus pada perubahan bentuk kata (morfologi) dan juga vital untuk memahami variasi makna.
Pondok pesantren di Indonesia mengintegrasikan pembelajaran ilmu Nahwu ini secara intensif, menjadikannya fondasi dasar keilmuan bagi para santri. Pemahaman yang kuat terhadap Nahwu dan Shorof memungkinkan santri tidak hanya sekadar membaca, tetapi benar-benar menguasai maksud dan tujuan dari isi kitab tersebut. Kemampuan ini adalah kunci untuk menghasilkan otoritas keilmuan yang mandiri di kemudian hari, memungkinkan mereka untuk menganalisis teks, bukan hanya mereproduksinya.
Stilistika Hukum: Analisis Penggunaan Kode dan Rumus Fikih
Dalam bidang fikih, Kitab Kuning memiliki bahasa teknisnya sendiri. Teks-teks hukum klasik menggunakan terminologi baku yang berfungsi sebagai rumus untuk menunjukkan tingkat kekuatan dan otoritas suatu pendapat yang disajikan.
Untuk menunjukkan pendapat yang kuat (otoritatif) dalam suatu madzhab, ulama menggunakan istilah seperti Al-Madzhab, Al-Ashlah, Al-Shahih, atau Al-Rajih. Sebagai contoh, penggunaan istilah Al-Rajih (yang lebih dominan) menandakan bahwa pendapat tersebut telah melalui proses perbandingan argumen dan dinilai paling unggul. Pemilihan istilah ini sangat penting karena memandu pembaca, terutama hakim atau ahli fikih kontemporer, untuk mengetahui pandangan mana yang paling sahih dan layak dijadikan pegangan.
Lebih lanjut, kode-kode juga digunakan untuk menyatakan konsensus. Untuk menyatakan kesepakatan antar ulama dari berbagai madzhab, digunakan istilah ijtima’an. Sementara itu, jika kesepakatan itu hanya terjadi di antara ulama dalam satu madzhab, digunakan istilah ittiraqan. Struktur penulisan dan penggunaan kode yang presisi ini menunjukkan bahwa
Kitab Kuning adalah literatur teknis hukum yang membutuhkan pemahaman mendalam atas metodenya, layaknya sebuah dokumen legislatif.
Berikut adalah ringkasan istilah otoritas fikih:
Kode Otoritas dalam Kitab Kuning
| Istilah | Makna | Fungsi dalam Fikih |
| Al-Shahih / Al-Rajih | Pendapat yang paling kuat (sahih) atau dominan. | Dipakai untuk memilih pandangan yang otoritatif dalam satu madzhab. |
| Al – Madzhab | Pendapat yang menjadi pegangan resmi madzhab. | Menyatakan pandangan yang diakui sebagai doktrin utama madzhab. |
| Ittiraqan | Kesepakatan (ijmak) antar ulama dalam satu madzhab. | Menunjukkan konsensus internal dalam aliran fikih tertentu. |
| Ijtima’an | Kesepakatan antar ulama dari beberapa madzhab. | Menunjukkan konsensus yang lebih luas di antara ulama. |
Arsitektur Intelektual: Konsep Al-Kutubul Mu’tabarah dan Sanad Keilmuan
Definisi dan Kriteria Otoritas (Mu’tabarah)
Tidak semua teks klasik dianggap setara. Dalam tradisi pesantren dan Nahdlatul Ulama, ada hierarki yang ketat, di mana kitab-kitab yang dijadikan rujukan utama, terutama dalam forum Bahtsul Masa’il, disebut sebagai Al-Kutubul Mu’tabarah (Kitab-kitab yang Diakui/Otoritatif).
Konsep Mu’tabarah berfungsi sebagai mekanisme kontrol intelektual. Kriteria utama agar sebuah kitab dapat dikategorikan sebagai Mu’tabarah adalah bahwa ajaran di dalamnya harus sejalan dan sesuai dengan tiga pilar ajaran Ahlussunnah Waljama’ah (Aswaja): Akidah, Syariat (Fikih), dan Tasawuf. Dengan demikian, konsep ini memastikan bahwa tradisi keilmuan yang diajarkan tetap berada dalam koridor teologis dan yurisprudensial yang diakui oleh komunitas, menjaga integritas sanad keilmuan.
Klasifikasi Kitab Berdasarkan Bidang Studi (Fann al-Ilmi)
Kitab Kuning diklasifikasikan berdasarkan disiplin ilmu yang mendasarinya:
- Tauhid/Akidah/Kalam: Bidang ini berfokus pada keyakinan fundamental Islam. Rujukan utama diambil dari karya-karya yang mengikuti garis pemikiran Imam Asy’ari dan Imam Maturidi serta para pengikut mereka, yang merupakan penjaga akidah dari penyimpangan.
- Fiqh/Syariah (Yurisprudensi Islam): Bidang ini mendominasi kurikulum pesantren. Sumber utama berasal dari Madzahibul Arba’ah (empat mazhab fikih: Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi’i). Di Indonesia, Mazhab Syafi’i memiliki dominasi yang kuat. Contoh kitab populer yang menjadi referensi wajib termasuk Minhajut Tholibin, Fathul Qorib, Fathul Mu’in, Fathul Wahab, dan Hasyiyat I’anat al-Talibin.
- Tasawuf (Spiritualitas dan Etika): Rujukan primer dalam bidang ini adalah karya-karya yang bersumber dari Imam Ghazali (terkenal dengan Ihya’ Ulumiddin) dan Imam Al-Junaidi. Kitab-kitab tasawuf bertujuan pada pembinaan spiritual (tazkiyatun nufus) dan penyucian jiwa.
- Ilmu Tafsir dan Hadis: Kitab Kuning juga mencakup ilmu-ilmu bantu untuk memahami teks fundamental. Dalam tafsir, metode yang dipelajari mencakup Tafsir Riwayah (berbasis riwayat/otoritas) dan Tafsir Dirayah (berbasis nalar/pendekatan), dengan corak-corak spesifik seperti Tafsir Fiqhi atau Tafsir Sufi.
Konsep Sanad Keilmuan: Menelusuri Matarantai Guru-Murid
Ketergantungan pesantren dan organisasi keagamaan seperti NU pada Kitab Kuning bersifat fundamental dan didasarkan pada prinsip kesinambungan (sanad) ilmu. Filosofi yang mendasari tradisi ini adalah bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rantai ilmu (sanad) harus diketahui dengan baik dan benar, dan hanya melalui Kitab Kuning yang diwariskan oleh ulama otoritatif, sanad ini dapat dijaga. Sanad berfungsi sebagai validasi otoritas. Figur yang diakui otoritasnya dalam tradisi keagamaan adalah mereka yang memiliki rantai tradisi keilmuan keislaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Memiliki sanad yang tersambung kepada ulama klasik melalui guru dan kitab menjamin bahwa interpretasi dan metodologi yang digunakan adalah sahih.
Kontribusi Ulama Nusantara: Jembatan Tradisi Global
Jaringan intelektual pesantren di Nusantara bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan bagian integral dari tradisi Islam global. Sanad keilmuan di Indonesia banyak terhubung melalui ulama Nusantara yang pernah belajar di Haramain (Mekkah dan Madinah).
Salah satu tokoh sentral dalam sejarah ini adalah Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, seorang ulama Syafi’i terkemuka dari abad ke-12 Hijriyah yang bahkan pernah menjabat sebagai Imam Masjidil Haram. Karya-karya Syaikh Nawawi menjadi jembatan epistemologis yang signifikan, menjamin bahwa tradisi fikih Mazhab Syafi’i yang diajarkan di Indonesia memiliki akar yang kuat di pusat-pusat keilmuan Islam global.
Selain ulama asli Nusantara, ulama Timur Tengah juga memainkan peran penting. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, pengarang kitab Hasyiyat I’anatuth Tholibin (syarah dari Fathul Mu’in), merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam memberikan pelajaran kepada mukimin (penduduk) dari Indonesia. Hal ini menghasilkan banyak ulama Nusantara pada permulaan abad ke-14 H yang merupakan murid beliau, dan yang kemudian berhasil mengembangkan dan memantapkan Mazhab Syafi’i secara merata di seluruh kepulauan Indonesia. Jaringan ulama inilah yang secara historis memperkuat Mazhab Syafi’i sebagai identitas hukum kolektif dan memastikan kesinambungan sanad ilmu fikih melalui kitab-kitab yang secara otomatis menjadi Mu’tabarah di Nusantara.
Table 2: Klasifikasi Kitab Kuning Otoritatif (Al-Kutubul Mu’tabarah)
| Bidang Keilmuan | Pilar Mazhab/Akidah | Contoh Kitab Populer di Pesantren | Fungsi Utama |
| Akidah/Tauhid (Kalam) | Asy’ariyah & Maturidiyah | Jawharat al-Tawhid, Sanusiyah | Menjaga kemurnian keyakinan Aswaja. |
| Fiqh (Syariat) | Madzahibul Arba’ah (Dominasi Syafi’i) | Fathul Qorib, Fathul Mu’in, I’anatuth Tholibin, Minhajut Tholibin | Panduan hukum praktis dan ritual ibadah. |
| Tasawuf (Etika/Akhlak) | Al-Ghazali & Al-Junaidi | Ihya’ Ulumiddin, Bidayatul Hidayah | Pembinaan spiritual dan etika personal. |
Transmisi Pengetahuan: Sistem Pedagogi Pesantren
Sistem pendidikan di pesantren salaf telah mengembangkan metodologi yang unik untuk transmisi Kitab Kuning. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa transfer keilmuan tidak hanya efisien tetapi juga sangat akurat dalam menjaga sanad. Sistem ini umumnya dibangun di atas dualitas metode: Bandongan dan Sorogan. Kedua metode ini bekerja secara komplementer untuk mencapai tujuan akhir melahirkan santri yang mampu menganalisis teks secara mandiri.
Metode Bandongan (Wetonan): Efisiensi Transmisi Massal
Metode Bandongan, yang kadang disebut Wetonan, adalah sistem pengajian di mana Kiai atau Ustaz memimpin proses belajar mengajar. Dalam sistem ini, Kiai membaca kitab, menerjemahkan teks Arab tersebut, dan kemudian menerangkan maksud serta konteksnya.
Para santri atau murid memiliki peran untuk mendengarkan, menyimak, dan secara aktif mencatat apa yang disampaikan oleh Kiai. Mereka biasanya mencatat terjemahan per kata atau per frasa (makna gandul) di sela-sela baris teks asli. Kelompok kelas dalam sistem Bandongan ini disebut halaqah, yang berarti sekelompok siswa yang belajar di bawah bimbingan guru.
Keunggulan utama Bandongan terletak pada efisiensi waktu dan penyampaian materi secara massal. Metode ini praktis untuk mengajar santri dalam jumlah besar sekaligus.
Bandongan juga efektif untuk memperkenalkan struktur bahasa Arab secara langsung dan berulang, serta memudahkan santri mendalami makna kitab secara kontekstual dari penjelasan ulama secara langsung. Karena materi sering diulang-ulang, metode ini juga memudahkan pemahaman. Bandongan berfungsi sebagai input data masif (materi) yang memastikan santri menerima cakupan teks yang luas.
Metode Sorogan: Individualisasi dan Akuntabilitas Intelektual
Berbeda dengan Bandongan yang bersifat massal, metode Sorogan bersifat personal dan interaktif.
Sorogan menuntut santri untuk membaca kitab—yang umumnya masih dalam format gundul—secara langsung di hadapan Kiai atau Ustaz. Santri tidak hanya membaca, tetapi juga diharapkan mampu menerjemahkan dan menjelaskan isi kitab tersebut. Kemudian, kiai bertindak sebagai korektor, menambahkan penjelasan, atau mengoreksi kesalahan bacaan, terutama pada penentuan i’rab. Sorogan lebih cocok diterapkan untuk santri tingkat lanjut yang telah memiliki dasar bahasa Arab (Nahwu-Shorof) yang memadai dan mampu membaca kitab secara mandiri. Keunggulan pedagogis metode ini sangat krusial; ia meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan santri dalam membaca kitab, sekaligus menumbuhkan akuntabilitas karena santri bertanggung jawab penuh atas bacaan dan pemahaman mereka sendiri. Interaksi langsung dengan guru memastikan pemahaman mendalam dan koreksi yang sangat presisi, khususnya dalam menguji penguasaan ilmu alat.
Dualitas Pedagogis sebagai Jalur Otentikasi
Penggabungan Bandongan dan Sorogan menciptakan sebuah sistem pedagogi yang terstruktur secara hierarkis, dengan tujuan akhir untuk melahirkan ahli fikih (faqih) yang kompeten. Bandongan berfungsi sebagai saluran transfer keilmuan (pengetahuan awal dan kontekstualisasi), sementara Sorogan berfungsi sebagai output verifikasi dan otentikasi. Santri yang mahir di Sorogan telah membuktikan penguasaan i’rab (sintaksis) dan syarah (kemampuan menjelaskan isi kitab).
Kemampuan membaca Kitab Gundul dengan benar dan mensyarahkan isinya, yang diuji secara intensif melalui Sorogan, dianggap sebagai ukuran kemahiran tertinggi seorang santri. Proses ini merupakan tahapan awal yang disengaja menuju status faqih atau ulama, memastikan bahwa setiap otoritas keilmuan yang dihasilkan telah melalui pengujian ketat berbasis teks klasik yang otentik.
Perbandingan Metode Bandongan dan Sorogan
| Karakteristik | Metode Bandongan (Wetonan) | Metode Sorogan |
| Mekanisme Penyajian | Kiai membaca, menerjemah, dan menjelaskan. Santri menyimak dan mencatat makna gandul. | Santri membaca kitab gundul langsung di hadapan Kiai/Ustaz, menerjemahkan, dan menjelaskan. |
| Fokus Utama | Transmisi pengetahuan luas, pengenalan teks, efisiensi jumlah santri. | Pelatihan i’rab mandiri, akurasi bacaan, dan interaksi korektif presisi. |
| Tingkat Kesesuaian | Santri tingkat dasar hingga menengah (input data dan pengenalan). | Santri tingkat lanjut dengan dasar Nahwu-Shorof kuat (output verifikasi dan akuntabilitas). |
Relevansi Kontemporer dan Dinamika Hukum Islam
Kitab Kuning dalam Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU)
Kitab Kuning memiliki kedudukan sentral dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai organisasi sosial keagamaan yang secara struktural terikat dengan keempat mazhab fikih (terutama Syafi’i), NU menjadikan Kitab Kuning sebagai basis intelektual turun-temurun. Ketergantungan ini berakar pada kebutuhan untuk menjaga sanad keilmuan agar tidak terputus, memastikan bahwa setiap aktivitas intelektual dan penetapan hukum memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tradisi pembelajaran di pesantren yang sangat berorientasi pada fikih (fiqh-oriented tradition) memiliki implikasi langsung terhadap praktik penetapan hukum di kalangan NU. Keterikatan pada teks-teks klasik ini menghasilkan sebuah kerangka kerja hukum yang ketat, namun juga memunculkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum klasik dengan isu-isu kontemporer.
Analisis Bahtsul Masa’il: Forum Penentuan Hukum Berbasis Klasik
Bahtsul Masa’il (BM) adalah tradisi akademis dan forum musyawarah khas yang dimiliki oleh pesantren dan NU, di mana para ahli fikih (fuqaha) berdiskusi untuk merumuskan jawaban hukum (istinbatul hukmi) atas masalah-masalah sosial keagamaan yang berkembang. Dalam forum ini, Al-Kutubul Mu’tabarah berfungsi sebagai rujukan primer dan otoritatif.
BM menjadi cerminan dinamika intelektual di tubuh NU, menunjukkan upaya ulama untuk menerapkan kerangka hukum Islam klasik pada realitas modern. Namun, tradisi ini juga kadang menjadi sasaran kritik karena dianggap berpotensi membatasi pemikiran atau menimbulkan stagnasi karena ketergantungan yang kuat pada teks-teks terdahulu.
Metodologi Bahtsul Masa’il
Untuk menjembatani jurang antara teks klasik dan masalah modern, NU mengembangkan metodologi yang dirumuskan secara cermat, yang berpusat pada Kitab Kuning :
- Taqrîîr Jamâ’i (Penetapan Kolektif): Keputusan hukum dalam Bahtsul Masa’il ditetapkan secara bersama-sama oleh para ahli, memastikan bahwa validitas hasil keputusan diakui secara kolektif oleh komunitas ulama.
- Ilhâq al-Masâil bi Nadhâ’irihâ (Menggabungkan Masalah dengan yang Serupa): Metode ini digunakan untuk menangani masalah-masalah kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab klasik. Prosedur ini secara fungsional menggantikan istilah qiyas (analogi), yang menurut pandangan NU, merupakan kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Melalui ilhâq, masalah baru disamakan (disamakan hukumnya) dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh Kitab Kuning yang mu’tabar. Mekanisme ini adalah cara legalistik yang memungkinkan ulama NU memberikan respons terhadap isu baru tanpa mengklaim derajat mujtahid mutlak dan tanpa melanggar komitmen terhadap kerangka Syafi’i.
- Istinbât (Penggalian Hukum): Metode ini melibatkan praktik bersama atas qawâid usyûliyyah (kaidah ushul fikih) dan qawâid fiqhiyyah (kaidah fikih) yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas yang terkontrol dalam aplikasi hukum.
Tantangan Stagnasi dan Kebutuhan Rekontekstualisasi
Meskipun Kitab Kuning menawarkan landasan hukum yang kokoh, ketergantungan eksklusif pada khazanah kitab-kitab klasik dapat menimbulkan tantangan. Ketika ulama dihadapkan pada masalah yang sama sekali baru (kontemporer), keterbatasan sumber rujukan klasik yang tidak lengkap di tangan mereka terkadang dapat menyebabkan kebuntuan. Hal ini memicu kritik mengenai potensi stagnasi pemikiran dalam tradisi fikih yang terlalu berorientasi pada teks lama.
Untuk mengatasi tegangan antara otoritas teks klasik dan kebutuhan fleksibilitas kontemporer, NU berpegang pada kaidah filosofis: al-muhafadat ‘ala al-qadim al-salih wa al-akhdh bi al-jadid al-aslah (mempertahankan tradisi lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). Prinsip ini adalah dasar untuk rekontekstualisasi.
Di luar NU, beberapa institusi pendidikan Islam modern telah menunjukkan upaya adaptif dalam pengajaran Kitab Kuning. Mereka menerapkan model pembelajaran yang inovatif, menggabungkan metode tradisional dengan metode modern, bahkan mengintegrasikan pendekatan sains dalam kajian fikih, dan menyertakan perspektif lokal maupun global. Tujuan dari rekontekstualisasi ini adalah untuk menghasilkan pelajar yang moderat, kritis, dan siap menghadapi tantangan kompleks di era globalisasi, menunjukkan bahwa otoritas Kitab Kuning dapat dipertahankan sementara metodologi aplikasinya dibuat lebih dinamis.
Kesimpulan
Kitab Kuning merupakan artefak intelektual yang jauh melampaui sekadar kumpulan teks kuno. Ia adalah fondasi epistemologis dan pedagogis yang membentuk tradisi keilmuan Islam di Nusantara, khususnya melalui institusi pondok pesantren. Secara epistemologis, sifat “gundul” Kitab Kuning menanamkan kemampuan analisis mandiri yang mendalam (melalui Nahwu-Shorof), menjadikannya saringan keilmuan yang membedakan pembaca yang terampil dengan mereka yang hanya menghafal. Penggunaan kode-kode fikih (seperti Al-Rajih atau Ittiraqan) menyediakan struktur hukum yang presisi.
Secara pedagogis, dualitas antara metode Bandongan (efisiensi transmisi pengetahuan massal) dan Sorogan (akurasi individual dan verifikasi i’rab) memastikan bahwa santri tidak hanya menerima materi tetapi juga menguasai ilmu alatnya. Sistem ini secara efektif menjaga sanad keilmuan yang tersambung hingga ulama-ulama global seperti Syaikh Nawawi al-Bantani.
Dalam konteks kontemporer, Kitab Kuning terus berfungsi sebagai basis utama penentuan hukum melalui forum Bahtsul Masa’il NU. Meskipun keterikatan pada Al-Kutubul Mu’tabarah menjamin otentisitas sanad, adopsi metodologi Ilhâq al-Masâil bi Nadhâ’irihâ menunjukkan adanya mekanisme yang terkontrol untuk merespons isu-isu baru. Mekanisme ini mencerminkan komitmen terhadap tradisi yang baik (al-qadim al-salih) sambil mengadaptasi diri terhadap kebutuhan modern (al-jadid al-aslah), memastikan bahwa warisan intelektual ini tetap relevan dan memiliki otoritas dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia.