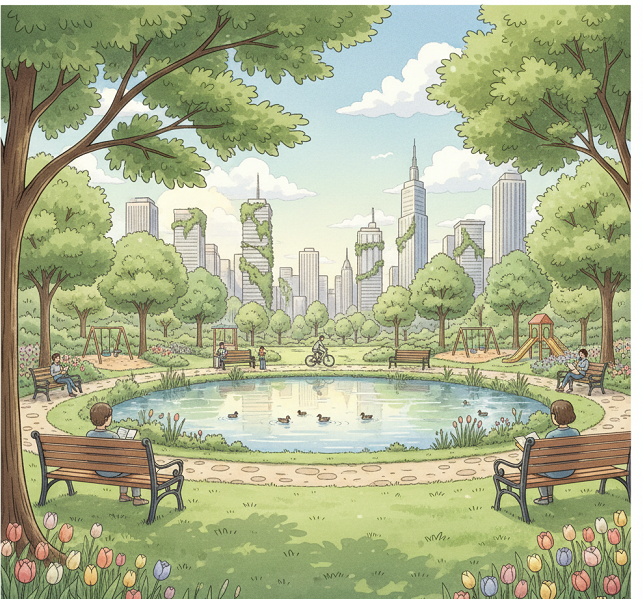Klasifikasi Taman Kota dan Mandat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Taman kota memiliki kedudukan formal yang sangat penting dalam struktur tata ruang perkotaan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, taman kota secara eksplisit termasuk dalam jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, bersama dengan taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Berdasarkan tipologinya, RTH dibagi menjadi RTH berbentuk kawasan atau areal, yang mencakup taman kota, dan RTH yang berbentuk jalur atau memanjang.
Indonesia memiliki mandat regulasi yang menuntut setiap wilayah kota menyediakan RTH Publik minimal 20% dari total luas wilayah. Meskipun fokus regulasi berada pada pemenuhan kuota luasan ini, keberhasilan fungsional taman kota—baik dari sisi ekologi, sosial, maupun ekonomi—sangat ditentukan oleh kualitas desain dan manajemennya, bukan sekadar kepatuhan kuantitatif. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan di Indonesia menuju Manajemen RTH Berbasis Kinerja yang mengukur dampak riil dari keberadaan taman.
Peran Ekologis: Paru-Paru Kota dan Adaptasi Perubahan Iklim
Secara ekologis, taman kota memainkan peran vital yang sering diibaratkan sebagai paru-paru kota. Vegetasi dan pepohonan di taman menghasilkan oksigen segar dan bertindak sebagai filter alami, menyerap gas-gas berbahaya serta partikel-partikel kecil dari udara, sehingga secara signifikan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Fungsi ini semakin krusial di tengah tantangan perubahan iklim global. Taman kota kini menjadi elemen kunci dalam strategi mitigasi dan adaptasi iklim. Desain lanskap yang efektif, mengintegrasikan konsep bioenergi dan optimalisasi penanaman, mampu mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), khususnya CO2. Strategi mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi ini meliputi penyediaan peneduh, peningkatan evapotranspirasi, dan penggunaan pelindung angin, yang secara kolektif berkontribusi untuk menciptakan “zona nyaman” termal di lingkungan binaan di tengah perubahan iklim ekstrem. Indikator kelestarian lingkungan yang digunakan untuk memandu skema sertifikasi taman mencakup kualitas tanah, kualitas air, keanekaragaman hayati, dan pengurangan emisi GRK, menekankan bahwa fungsi ekologis harus terukur.
Peran Sosial, Rekreasi, dan Peningkatan Kesejahteraan
Taman kota merupakan infrastruktur kesejahteraan (well-being infrastructure) yang esensial. Taman memberikan kesempatan bagi penduduk perkotaan untuk menikmati hubungan dengan alam dan bersantai di lingkungan yang menyenangkan, bebas dari hiruk pikuk lalu lintas. Fungsi rekreasional ini berkontribusi langsung pada peningkatan kebahagiaan hidup masyarakat.
Taman yang dikelola dengan baik menjadi pusat berkumpulnya masyarakat, memfasilitasi interaksi sosial, memperkuat ikatan komunitas, dan menciptakan rasa kebersamaan. Selain itu, taman yang nyaman dan terawat mendorong aktivitas fisik, seperti berolahraga dan berjalan-jalan di area terbuka, yang secara keseluruhan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan taman dalam menjalankan fungsi sosialnya sangat bergantung pada tingkat kenyamanan dan keamanan yang ditawarkannya, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Taman Bungkul di Surabaya, yang menjadi tempat favorit karena memiliki tingkat keamanan yang memadai bagi para pengunjung.
Peran Ekonomi: Aset Properti, Turisme, dan City Branding
Taman kota sering dijadikan sebagai “wajah kota” yang mencerminkan identitas dan meningkatkan nilai estetika daerah tersebut. Kehadiran taman bukan hanya masalah estetika, tetapi juga aset ekonomi. Taman kota dapat berfungsi sebagai pusat perekonomian dan secara signifikan meningkatkan daya tarik pariwisata.
Contoh paling jelas mengenai justifikasi investasi skala besar terdapat pada Gardens by the Bay (GBTB) di Singapura. Taman ikonik ini, yang merupakan komponen kunci dari visi “City in a Garden,” didukung oleh argumen bahwa ruang hijau ikonik terbukti meningkatkan nilai komersial pengembangan properti di sekitarnya, sekaligus memperkuat daya tarik ekonomi dan pariwisata Singapura di kancah global. Dengan demikian, investasi pada taman kota, terutama proyek-proyek ikonik, harus dipandang sebagai leveraging asset yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan mendefinisikan identitas kota di tingkat internasional, melampaui sekadar kepatuhan regulasi RTH.
Kerangka Regulasi dan Tantangan Implementasi di Indonesia: Mandat RTH Publik
Instrumen Kebijakan RTH dan Tantangan Non-Kepatuhan
Di Indonesia, instrumen kebijakan RTH meliputi berbagai peraturan, seperti peraturan zonasi untuk zona RTH, peraturan tentang penghijauan/lanskap (landscape ordinance), dan ketentuan pengembangan ruang terbuka. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali terhambat oleh masalah finansial. Salah satu persoalan utama yang kerap dijumpai di kota-kota besar Indonesia adalah bahwa taman kota seringkali dianaktirikan karena dianggap memiliki nilai finansial yang lebih kecil dibandingkan aset kota lainnya, seperti bangunan dan infrastruktur. Padahal, pemeliharaan taman yang berkualitas membutuhkan biaya yang tidak kecil. Kurangnya investasi ini membuat taman rentan terhadap penurunan kualitas dan fungsi.
Model Keberhasilan Lokal dan Prioritas Fungsional
Meskipun menghadapi tantangan pembiayaan, beberapa pemerintah kota di Indonesia menunjukkan keberhasilan dalam mengelola taman. Studi kasus Taman Bungkul di Surabaya menjadi contoh penting. Renovasi Taman Bungkul pada tahun 2007, dengan dana sekitar Rp 1,2 Miliar, berhasil menempatkan taman ini sebagai proyek penting bagi pembangunan kota. Keberhasilan ini terutama didorong oleh kemampuan manajemen dalam menyediakan tingkat keamanan yang memadai, menjadikan taman tersebut tempat rekreasi favorit masyarakat.
Selain itu, studi di beberapa kota menunjukkan bahwa fungsi kegiatan taman bervariasi tergantung skalanya. Taman dengan skala luas yang lebih menyerupai lapangan (seperti Taman Kwasaran) cenderung memaksimalkan kegiatan aktif di pagi hari oleh remaja. Hal ini berbeda dengan taman skala kecil (seperti Taman Badaan), yang menunjukkan bahwa perencanaan dan desain harus adaptif terhadap pelaku dan waktu kegiatan dominan.
Konflik Baru: Ancaman Sosial-Digital Terhadap Aset Publik
Taman kota, sebagai aset publik yang rentan, kini menghadapi tekanan baru yang tidak terduga, yaitu ancaman yang timbul dari interaksi teknologi digital dan sosial. Kasus di Surabaya baru-baru ini menyoroti fenomena perburuan “Koin Jagat” dari aplikasi game online berbasis lokasi. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan fisik pada enam taman dan beberapa jalur hijau.
Kerusakan yang diakibatkan oleh perburuan koin ini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengambil tindakan tegas, termasuk meminta pemblokiran aplikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi RI). Wali Kota Surabaya menyatakan bahwa aplikasi tersebut tidak hanya merusak fasilitas umum (fasum) tetapi juga berpotensi memicu konflik fisik antar pemburu koin, melibatkan berbagai generasi, dari milenial, Gen Z, Beta, hingga orang tua. Situasi ini memperlihatkan bahwa manajemen RTH memerlukan mekanisme Digital Governance. Pemerintah harus mengembangkan protokol regulasi untuk melindungi RTH dari dampak tak terduga yang ditimbulkan oleh tren sosial dan teknologi yang cepat (misalnya, membuat kebijakan penggunaan Location-Based Games di fasilitas publik), melengkapi fokus tradisional pada penertiban PKL.
Nilai Sejarah, Intangible Values, dan Pelestarian Warisan Budaya
Nilai Tak Berwujud (Intangible Values) sebagai Artefak Sejarah
Taman kota yang berusia panjang memiliki nilai lebih dari sekadar fungsi rekreasi; mereka adalah warisan kekayaan budaya dan aset kehidupan kota yang merepresentasikan kejayaan dan karakter kota pada zamannya. Karakteristik non-fisik (intangible) sebuah taman dibentuk oleh unsur sejarah, demografi, visual, dan kualitas pengelolaannya.
Taman kota yang telah berusia 50 tahun atau lebih dianggap sebagai artefak sejarah lingkungan, yang menyimpan bukti aktivitas dan karya masa lalu. Nilai sejarah ini muncul apabila taman memiliki kaitan erat dengan tokoh, peristiwa besar, nilai-nilai keunikan lokal (indigenous values), atau merupakan tempat bersejarah bagi warga kota. Nilai-nilai tak berwujud ini dapat dikaji dan diukur melalui metode evaluatif atau asesmen.
Studi Kontras Jakarta: Modernisasi Versus Preservasi Warisan
Kasus Taman Menteng dan Taman Suropati di Jakarta memberikan gambaran jelas mengenai konflik antara fungsionalitas modern dan pelestarian warisan budaya. Kawasan Menteng pada awalnya direncanakan sebagai kota taman pertama di Indonesia (Nieuw-Gondangdia).
- Taman Suropati: Keberhasilan Konservasi Sejarah: Taman Suropati (dahulu Burgemeester Bisschopplein) merupakan sentral dan poros perkembangan awal Nieuw-Gondangdia. Taman ini, yang terletak di kawasan yang relatif homogen dan merupakan ring 1 DKI Jakarta, berhasil mempertahankan nilai-nilai sejarahnya. Penelitian menunjukkan bahwa semua dari 9 kriteria nilai sejarah secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakteristik taman. Unsur non-fisik ini menjadi kriteria tertinggi, dan jejak sejarah, seperti Pohon Mahoni, berhasil dipertahankan.
- Taman Menteng: Eliminasi Nilai Sejarah: Sebaliknya, Taman Menteng (dahulu Lapangan Sepak Bola Persidja/Stadion Menteng, yang dibangun sejak 1920) mengalami perubahan drastis. Pada tahun 2004, terjadi perubahan total yang mengubah lapangan bersejarah tersebut menjadi ruang terbuka publik multi fungsi dengan parkir bawah tanah, berkarakter kontemporer. Desain baru ini menghilangkan artefak sejarah lingkungan yang telah berusia 92 tahun. Penilaian menunjukkan bahwa nilai-nilai sejarah yang dikandungnya kecil dan nyaris tidak dapat ditelusuri.
Faktor Pelindung dan Kerentanan Warisan
Perbedaan nasib antara kedua taman ini menunjukkan bahwa nilai sejarah sebuah taman belum menjadi pertimbangan utama dalam proses renovasi di Indonesia, menjadikannya rentan terhadap perubahan. Taman Menteng, yang terletak di area mixed-use dan menghadapi tekanan fungsional (kebutuhan parkir), lebih rentan terhadap perubahan nilai sejarahnya dibandingkan Taman Suropati yang terletak di kawasan hunian para pejabat dan lebih homogen. Agar warisan taman kota bertahan, perlindungan harus ditingkatkan melampaui Undang-Undang Cagar Budaya, memasukkan mekanisme perlindungan nilai intangible dan spirit tempat tersebut ke dalam peraturan zonasi RTH, memastikan nilai non-fisik tidak mudah dihilangkan hanya berdasarkan keputusan fungsional sesaat.
Kontribusi Nilai Sejarah: Perbandingan Kasus Menteng vs. Suropati
| Kriteria Perbandingan | Taman Menteng, Jakarta | Taman Suropati, Jakarta |
| Kontribusi Nilai Sejarah | Nilai sejarah kecil, nyaris tidak dapat ditelusuri. Dibentuk oleh elemen fisik kontemporer. | Kontribusi unsur sejarah signifikan (9 kriteria terpenuhi). Dibentuk secara signifikan oleh elemen non-fisik. |
| Perubahan Fungsi/Desain | Berubah total (dari Stadion Menteng); Prioritas parkir bawah tanah dan multi-fungsi. | Perubahan fungsi tapak minim; Nilai sejarah berhasil dipertahankan. |
| Jejak Sejarah yang Tersisa | Hanya menyisakan sebuah sculpture pemain bola. | Jejak sejarah masih ada (misalnya Pohon Mahoni). |
| Lokasi Kritis | Daerah Mixed Use Area (lebih rentan tekanan komersial/fungsional). | Kawasan homogen, Ring 1 DKI (kurang rentan perubahan). |
Perbandingan Global: Studi Kasus Desain Ikonik dan Visi Kota
Perbandingan studi kasus global menunjukkan bahwa taman kota ikonik adalah hasil dari visi perencanaan jangka panjang dan investasi strategis, yang mampu mendefinisikan identitas kota.
Central Park, New York City: Desain Klasik dan Skala Monumental
Central Park terletak di jantung Manhattan, meliputi area seluas 843 acres (sekitar 341 hektare), menjadikannya salah satu taman perkotaan terbesar di dunia. Taman ini dirancang pada pertengahan abad ke-19 oleh Frederick Law Olmsted dan Calvert Vaux. Desainnya adalah mahakarya lanskap terencana yang menawarkan danau, taman, fasilitas rekreasi, dan bahkan kebun binatang, memberikan ruang alami yang luas bagi kota berdensitas tinggi.
Hyde Park, London: Warisan Kerajaan dan Evolusi Historis
Hyde Park, yang terletak di pusat London, membentang seluas 350 acres (sekitar 142 hektare). Taman ini memiliki sejarah yang panjang, didirikan pada abad ke-16 oleh Henry VIII. Hyde Park merupakan taman kerajaan yang telah mengalami beberapa perubahan selama bertahun-tahun, berevolusi menjadi campuran elemen formal dan informal. Taman ini menonjolkan beberapa taman spesifik (seperti Rose Garden dan Italian Garden) dan monumen (termasuk Diana Fountain). Meskipun Central Park berbentuk persegi panjang, Hyde Park memiliki bentuk yang lebih tidak beraturan. Kedua taman ikonik ini sama-sama strategis dan mudah diakses oleh transportasi publik, melayani turis dan penduduk lokal.
Gardens by the Bay (GBTB), Singapura: Visi Futuristik City in a Garden
Gardens by the Bay (GBTB) mewakili model taman kota strategis dan futuristik abad ke-21. Dibangun di atas lahan reklamasi, GBTB mencakup total area seluas 101 hektare (1.010.000 m²) di Marina Bay, terdiri dari Bay South, Bay East, dan Bay Central. GBTB dikonsepkan pada tahun 2005 sebagai komponen utama dari visi pemerintah “City in a Garden,” yang merupakan evolusi dari reputasi Singapura sebagai Garden City.
Alih-alih hanya memenuhi kebutuhan rekreasi dasar, GBTB dirancang sebagai aset global yang ditujukan untuk menyaingi ruang hijau ikonik seperti Central Park dan Kew Gardens, serta menjadi fitur penentu aspirasi Singapura menjadi kota global. GBTB menampilkan konservatori berpendingin, dan Supertrees setinggi hingga 50 meter yang diselimuti tumbuhan. Visi ini membutuhkan pendanaan publik dan penggunaan lahan premium, didukung oleh argumen bahwa ruang hijau ikonik akan meningkatkan nilai komersial pengembangan di sekitarnya serta meningkatkan daya tarik ekonomi dan pariwisata Singapura. GBTB fokus pada rekreasi hortikultura, melengkapi peran konservasi dan riset dari Singapore Botanic Gardens.
Tiga model ini menegaskan bahwa pengembangan taman ikonik harus didorong oleh strategi city branding dan turisme. Hal ini menunjukkan bahwa kota-kota Indonesia perlu mengidentifikasi dan berinvestasi pada magnet wisata hijau skala besar sebagai upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing kota.
Perbandingan Model Ikonik Taman Kota Global
| Taman Ikonik | Lokasi & Skala (Area) | Konsep Desain Kunci | Fokus Strategis |
| Central Park, NYC | Amerika Serikat (341 ha) | Klasik Olmstedian, Landscape Terencana, Rekreasi Tradisional | Manajemen profesional, daya tarik turis, pelestarian desain historis |
| Hyde Park, London | Inggris (142 ha) | Evolusi dari Lahan Kerajaan, Campuran Formal dan Informal | Warisan budaya dan sejarah, ruang publik di pusat kota |
| Gardens by the Bay | Singapura (101 ha) | Futuristik, Konservatori Berpendingin, Supertrees | Daya saing global, ekonomi turisme, dan city branding |
Model Pengelolaan dan Kemitraan Publik-Swasta (KPS)
Central Park Conservancy (CPC): Tolok Ukur KPS Global
Central Park Conservancy (CPC) di New York City adalah contoh tolok ukur Kemitraan Publik-Swasta (KPS) institusional yang sukses dalam manajemen taman kota. CPC didirikan pada tahun 1980 dan sejak 1998, telah mengelola Central Park melalui perjanjian tertulis dengan Kota New York. Di bawah perjanjian ini, Kota New York mempertahankan kepemilikan dan tanggung jawab kebijakan, sementara CPC bertanggung jawab atas pemeliharaan dan operasi harian.
Keberhasilan CPC didasarkan pada profesionalisme dan spesialisasi. CPC mengadopsi Sistem Manajemen Zona yang membagi Central Park menjadi 49 zona. Setiap zona diurus oleh tim terpilih yang terdiri dari tukang kebun, arborist, dan teknisi. Sistem ini memastikan keakraban individu terhadap lanskap masing-masing zona dan menjamin akuntabilitas. Tugas pemeliharaan meliputi perawatan lanskap dan rumput, pembersihan area publik, perawatan pohon, dan perbaikan monumen. CPC juga mengandalkan penggalangan dana jangka panjang yang masif (seperti kampanye Forever Green) untuk restorasi dan pemeliharaan, menunjukkan model pendanaan swasta yang stabil.
Implementasi KPS di Indonesia: Kebutuhan Pendanaan vs. Komersialisasi
Di Indonesia, KPS muncul sebagai respons terhadap kendala finansial, di mana pemeliharaan taman seringkali diabaikan karena dianggap tidak bernilai finansial tinggi. Keterlibatan swasta dipandang sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah dan merupakan bentuk kontribusi swasta.
Studi kasus Kota Bogor menunjukkan aplikasi KPS yang berfokus pada pembiayaan transaksional. Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan PT. Pilar Hijau Madani dalam penataan dan pemeliharaan dua taman melalui model kontrak sewa (lease contract). Sebagai kompensasi atas biaya yang ditanggung swasta, PT. Pilar Hijau Madani diberikan hak untuk menerapkan papan reklame di area taman.
Analisis Komparatif Model KPS
Terdapat kontras filosofis yang signifikan antara model global dan lokal. Model CPC fokus pada konservasi, profesionalisme ahli, dan didanai melalui filantropi non-komersial, yang bertujuan untuk melestarikan visi historis Olmsted/Vaux. Sebaliknya, model Indonesia (contoh Bogor) seringkali fokus pada penyelesaian masalah pembiayaan dasar, didanai melalui komersialisasi ruang publik (reklame).
Ketergantungan pada kompensasi reklame berisiko mengkompromikan nilai estetika dan fungsi rekreasi pasif taman. Hal ini dapat bertentangan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan bebas dari gangguan, yang merupakan kunci untuk mendorong keinginan masyarakat untuk berkunjung kembali. Oleh karena itu, agar manajemen taman kota di Indonesia mencapai kualitas internasional, pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan badan pengelola independen yang berorientasi pada keahlian teknis (mengadopsi sistem manajemen zona) dan mampu menarik pendanaan non-komersial yang berkelanjutan (donasi), alih-alih hanya mengandalkan pendapatan dari iklan.
Masa Depan Taman Kota: Adaptasi, Teknologi, dan Resiliensi
Strategi Adaptasi Iklim dan Desain Lanskap Resilien
Taman kota masa depan harus dirancang sebagai High-Performance Landscape yang resilien terhadap perubahan iklim. Tujuannya adalah tercapainya zona nyaman termal yang dibutuhkan masyarakat. Desain harus mampu mengurangi emisi panas dan meningkatkan kenyamanan termal melalui strategi peneduh, evapotranspirasi, dan pelindung angin.
Lebih jauh, elemen lanskap harus dipertimbangkan sebagai sumber energi terbarukan yang mampu mereduksi tingginya kadar CO2 akibat emisi gas rumah kaca. Implementasi strategi ini memerlukan pengukuran dan evaluasi yang cermat terhadap aspek desain pohon, kinerja iklim mikro, dan kontribusi terhadap indikator kelestarian lingkungan seperti kualitas tanah dan keanekaragaman hayati.
Integrasi Teknologi Pintar (Smart Park): IoT dan Efisiensi Operasional
Integrasi teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna taman kota. IoT melibatkan objek fisik yang ditanamkan sensor, perangkat lunak, dan kemampuan pemrosesan untuk bertukar data melalui jaringan. Bidang ini telah berkembang pesat berkat konvergensi komputasi ubiquitous, sensor komoditas, dan sistem tertanam.
Contoh penerapan paling nyata adalah sistem Smart Parking. Sensor parkir real-time (seperti infrared atau RFID), dikombinasikan dengan mikrokontroler (ESP32 atau Node MCU), dapat mendeteksi keberadaan kendaraan dan mengirimkan informasi ketersediaan ruang ke server. Data ini kemudian dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi seluler, memungkinkan mereka menemukan tempat parkir yang tersedia dengan cepat. Dalam pengujian, sistem sensor mampu mendeteksi kendaraan dengan akurasi hingga 95.04%, secara signifikan menghemat waktu pencarian. Meskipun teknologi ini menjanjikan efisiensi tinggi, perlu diperhatikan adanya kekhawatiran yang melekat terkait privasi dan keamanan data yang dihasilkan oleh perangkat IoT.
Manajemen Risiko Sosial-Digital
Tantangan di masa depan adalah mengelola taman secara cerdas sekaligus melindungi aset tersebut dari risiko sosial dan digital yang cepat berubah. Fenomena kerusakan taman akibat perburuan koin di Surabaya menjadi studi kasus penting. Hal ini menuntut adanya Protokol Digital Governance yang proaktif.
Pemerintah kota dan lembaga terkait harus mengoordinasikan respons cepat untuk mengatasi ancaman baru dari aktivitas game berbasis lokasi yang merusak fasilitas. Penetapan protokol dan zonasi yang jelas untuk mengatur interaksi antara teknologi (misalnya, Augmented Reality atau Location-Based Services) dan ruang publik sangat diperlukan untuk memastikan taman tetap menjadi ruang yang aman dan nyaman, serta melindungi aset fisik dari kerusakan yang tidak disengaja.
Kesimpulan
Analisis komprehensif terhadap taman kota di berbagai negara, termasuk studi kasus mendalam di Indonesia, menunjukkan bahwa taman kota harus dipandang sebagai infrastruktur multi-fungsi yang kritis bagi resiliensi ekologis, sosial, dan ekonomi perkotaan. Tantangan terbesar di Indonesia adalah mengalihkan fokus dari sekadar pemenuhan kuota luasan RTH menjadi optimalisasi kinerja dan manajemen berkualitas tinggi.
Sinkronisasi Kebijakan RTH Indonesia dengan Best Practices Global
- Optimalisasi Kinerja RTH: Kebijakan RTH perlu didorong untuk bergeser dari pendekatan kuantitatif (pemenuhan kuota 20%) menjadi fokus pada optimalisasi kinerja ekologis dan sosial. Hal ini memerlukan pengembangan metrik terukur untuk mengevaluasi dampak riil, seperti pengukuran suhu mikro, kualitas udara, tingkat kunjungan, dan persepsi keamanan pengguna.
- Perlindungan Nilai Tak Berwujud: Pemerintah daerah harus memperkuat regulasi untuk melindungi Nilai Tak Berwujud (Intangible Values) taman kota bersejarah. Kasus Taman Menteng dan Taman Suropati menunjukkan bahwa kebutuhan fungsional modern (seperti fasilitas parkir atau komersial) rentan menghilangkan warisan budaya dan sejarah yang tersemat dalam lanskap. Perlindungan ini harus diintegrasikan ke dalam peraturan zonasi.
Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pendanaan
- Institusionalisasi KPS Berbasis Keahlian: Kemitraan Publik-Swasta (KPS) harus diarahkan untuk membentuk badan konservasi yang independen dan profesional, fokus pada keahlian teknis (hortikultura, arborist), dan mengadopsi model Manajemen Zona yang terperinci, mencontoh keberhasilan Central Park Conservancy.
- Diversifikasi Pendanaan Filantropis: Perlu adanya skema pendanaan berkelanjutan (seperti endowment atau filantropi korporasi) untuk mengurangi ketergantungan pada kompensasi komersial (reklame) yang bersifat transaksional. Pendanaan non-komersial akan memastikan bahwa taman dikelola dengan prioritas pada estetika, kenyamanan, dan konservasi, bukan hanya kepentingan komersial.
Peta Jalan Taman Kota yang Responsif (2025–2035)
- Investasi Lanskap Berkinerja Tinggi (High-Performance Landscape): Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk riset dan pengembangan desain taman yang adaptif iklim. Standar desain baru harus memasukkan integrasi IoT dan sensor untuk monitoring iklim mikro dan manajemen fasilitas yang efisien, guna meningkatkan zona kenyamanan termal dan resiliensi lingkungan.
- Protokol Digital Governance: Mendesak pembentukan protokol dan zonasi yang mengatur penggunaan teknologi digital, khususnya Location-Based Games dan Augmented Reality, di ruang publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan fasilitas dan potensi konflik sosial, berdasarkan pelajaran yang didapat dari kasus di Surabaya.
- Pembangunan Aset Ikonik Regional: Mengidentifikasi lokasi strategis untuk pengembangan taman ikonik skala besar yang didorong oleh strategi city branding dan daya tarik turisme, mengikuti model Gardens by the Bay Singapura. Taman tersebut harus dilihat sebagai magnet wisata hijau yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing kota secara substansial.