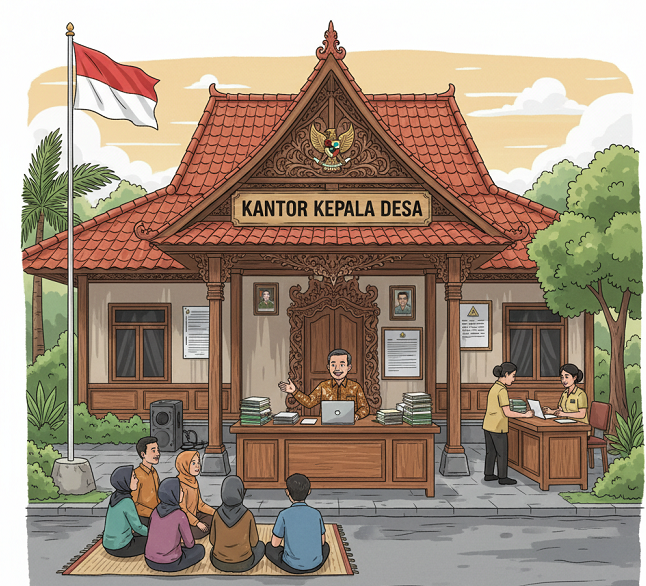Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai pergeseran paradigma yang mendasar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Secara historis, Desa sering diposisikan sebagai objek pembangunan yang menerima arahan dan intervensi dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, UU 6/2014 bertransformasi dengan menetapkan Desa sebagai subjek pembangunan (development subject), membalikkan logika sentralistik sebelumnya. Fondasi reformasi ini adalah pengakuan hukum bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pengakuan ini bukan sekadar pendelegasian wewenang administratif, melainkan sebuah restorasi kedaulatan lokal yang diakui dan dihormati secara eksplisit dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Paradigma baru ini menuntut pelaksanaan pemerintahan Desa berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola modern. Prinsip-prinsip tersebut meliputi demokrasi, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Prinsip musyawarah, khususnya, menjadi inti dalam proses pengambilan keputusan, menjamin bahwa perencanaan dan alokasi sumber daya dilakukan atas dasar kesepakatan kolektif. Kepala Desa juga diwajibkan untuk menjamin transparansi, termasuk memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
Kuatnya mandat otonomi hukum (de jure autonomy) yang terkandung dalam UU Desa ini secara inheren menempatkan beban tata kelola dan akuntabilitas yang sangat besar pada Aparat Desa. Sementara reformasi ini berhasil dalam aspek politik-hukum, reformasi kapasitas kelembagaan seringkali tertinggal. Pemberian otonomi yang luas, yang didukung oleh sumber daya fiskal masif melalui Dana Desa, akan menghadapi risiko kegagalan implementasi jika kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Desa belum memadai. Analisis ini menunjukkan bahwa reformasi UU Desa adalah langkah politik-hukum yang mendahului kesiapan kelembagaan di banyak daerah, menciptakan kesenjangan struktural yang harus diatasi.
Mekanisme Fiskal Dana Desa (DD): Skala dan Distribusi
Definisi dan Posisi Dana Desa dalam Struktur APBN
Dana Desa (DD) merupakan pilar utama desentralisasi fiskal pasca-2014. Secara definitif, DD adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Tujuan utama dari alokasi DD adalah membiayai empat fungsi utama di tingkat Desa: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Prioritas penggunaan DD tidak sepenuhnya otonom. Penggunaan dana ini tunduk pada peraturan prioritas yang ditetapkan secara terpusat, yakni oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT). Meskipun Desa memiliki ruang untuk menentukan kebutuhan lokal, pelaksanaan kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas wajib harus mendapat persetujuan dari bupati/walikota. Persetujuan ini hanya diberikan setelah dipastikan bahwa alokasi Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas wajib pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Tren Alokasi Dana Desa Sejak Inisiasi (2015–2024)
Skala fiskal program Dana Desa sangat masif dan menunjukkan komitmen finansial yang berkelanjutan dari Pemerintah Pusat. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, total alokasi anggaran Dana Desa yang telah disalurkan mencapai Rp 608,9 triliun hingga tahun 2024. Tren penyaluran menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimulai dengan alokasi sebesar Rp 20,8 triliun pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga mencapai anggaran sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2024.
Skala transfer ini menempatkan DD sebagai salah satu instrumen utama pemerintah dalam menstimulasi pembangunan di wilayah perdesaan.
Analisis Mekanisme Penyaluran dan Pengendalian Keuangan Desa
Mekanisme pengendalian dan akuntabilitas Dana Desa diatur secara ketat. Kepala Desa memiliki kewajiban ganda terkait transparansi: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memberikan/menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
Kegagalan Kepala Desa dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan akuntabilitas ini dapat berujung pada sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Jika sanksi administratif tersebut tidak diindahkan, tindakan yang lebih tegas seperti pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian penuh dapat diberlakukan.
Evaluasi Kinerja dan Dampak Sosio-Ekonomi Dana Desa
Capaian Kuantitatif Pembangunan Infrastruktur Desa
Setelah hampir satu dekade implementasi (2015–2024), Dana Desa telah menghasilkan capaian kuantitatif yang mengesankan, terutama di bidang pembangunan infrastruktur fisik. Hingga tahun 2023, Dana Desa tercatat telah membiayai pembangunan fisik secara masif.
Tabel 1: Akumulasi Dana Desa dan Dampak Kuantitatif Pembangunan (2015-2023)
| Indikator Kinerja Utama | Periode Data | Data Kuantitatif | Signifikansi |
| Total Alokasi Dana Desa | 2015 – 2024 | Rp 608,9 Triliun | Skala desentralisasi fiskal yang masif. |
| Capaian Pembangunan Jalan Desa | 2015 – 2023 | 357.666 km | Indikasi kuat fokus alokasi pada infrastruktur fisik. |
| Pembangunan Jembatan | 2015 – 2023 | 1.915 km | Peningkatan konektivitas antar wilayah. |
| Unit Air Bersih | 2015 – 2023 | 1.753.791 unit | Peningkatan akses layanan dasar. |
| Fasilitas Kesehatan (Polindes/Posyandu) | 2015 – 2023 | 26.565 Polindes dan 46.094 Posyandu | Penguatan layanan kesehatan primer. |
| Fasilitas Pendidikan (PAUD) | 2015 – 2023 | 70.776 kegiatan | Peningkatan akses pendidikan anak usia dini. |
Kontribusi DD terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan
Secara makro, implementasi Dana Desa telah berkorelasi positif dengan indikator kesejahteraan perdesaan. Tingkat kemiskinan perdesaan secara nasional menunjukkan tren penurunan. Apabila dibandingkan dengan September 2014, yang sebesar 13,76%, tingkat kemiskinan turun menjadi 12,6% pada September 2019, yang merupakan titik terendah dalam periode tersebut.
Selain itu, DD menunjukkan efektivitas dalam penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Desa turun dari 4,48% pada tahun 2014 menjadi 3,43% pada tahun 2022. Seiring dengan penurunan pengangguran, terjadi peningkatan signifikan pada pendapatan per kapita Desa, naik dari Rp 572.586 per kapita per bulan menjadi Rp 1.028.896 per kapita per bulan. Data juga menunjukkan bahwa indeks ketimpangan ekonomi (Indeks Gini) di Desa tetap rendah dan bahkan sedikit menurun, dari 0,319 menjadi 0,314, menandakan bahwa pertumbuhan yang terjadi relatif merata.
Kritik Keberlanjutan: Tantangan Transformasi ke Sektor Produktif
Meskipun DD sukses dalam mencapai target fisik dan mitigasi kemiskinan jangka pendek, terdapat kritik mendalam mengenai keberlanjutan dampak ekonominya. Dana Desa terperangkap dalam apa yang disebut sebagai Infrastructure Trap, di mana alokasi cenderung didominasi oleh pembangunan infrastruktur fisik yang sifatnya sementara (seperti jalan atau irigasi). Meskipun pembangunan infrastruktur penting, kritik menyatakan bahwa penggunaan dana belum optimal dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat berkelanjutan.
Analisis ini menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil sebagai instrumen mitigasi kemiskinan yang didorong oleh sisi penawaran (supply-side), terutama melalui penciptaan lapangan kerja sementara melalui proyek Padat Karya Tunai (PKT). Namun, DD menghadapi hambatan dalam bertransformasi menjadi instrumen perubahan struktural ekonomi berbasis sisi permintaan (demand-side), yaitu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Hal ini dikonfirmasi oleh studi empiris yang menemukan bahwa meskipun Dana Desa berdampak signifikan secara statistik terhadap perkembangan status desa (berdasarkan Indeks Pembangunan Desa/IPD), besaran koefisien regresi menunjukkan dampak ekonomi yang secara keseluruhan masih kecil.
Kegagalan untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi perdesaan. Tanpa fokus yang lebih besar pada investasi produktif dan penguatan kelembagaan BUMDes, dampak DD akan terbatas pada output fisik tanpa mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang.
Kebijakan Prioritas dan Transformasi Fokus (2025)
Petunjuk Operasional Terbaru: Sinkronisasi Prioritas Nasional dan SDGs Desa
Untuk mengatasi tantangan tata kelola dan keberlanjutan di masa lalu, Pemerintah Pusat telah memperkuat intervensi melalui penentuan prioritas yang lebih terperinci. Fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023.
Prioritas ini disinkronkan secara eksplisit dengan sasaran pembangunan nasional dan global, terutama Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Penggunaan Dana Desa diwajibkan untuk mendukung pencapaian 8 tipologi dan 17 tujuan SDGs Desa, yang mencakup aspek Desa tanpa kemiskinan/kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, Desa ramah lingkungan, hingga Desa responsif budaya dan berjejaring.
Fokus DD 2025 diprioritaskan untuk delapan bidang utama, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Desa adaptif Perubahan Iklim, peningkatan layanan kesehatan dasar, dukungan Ketahanan Pangan, serta pengembangan potensi lokal berbasis teknologi dan informasi.
Mandat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem: Implementasi BLT Desa
Penanganan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama melalui alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Dana Desa diwajibkan mengalokasikan maksimum 15% dari pagu dana untuk BLT Desa.
Penargetan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan secara terstruktur. Calon KPM diprioritaskan dari keluarga miskin yang berada di Desa yang bersangkutan, menggunakan data resmi pemerintah sebagai rujukan, khususnya data keluarga desil 1 untuk percepatan eliminasi kemiskinan ekstrem. Apabila data desil 1 tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data desil 2 hingga 4. Jika data kemiskinan ekstrem tidak ada, Kepala Desa dapat menetapkan KPM berdasarkan kriteria alternatif, seperti kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga rentan sakit kronis/disabilitas, lansia tunggal, atau kepala keluarga perempuan miskin. BLT Desa diberikan sebesar Rp300.000,00 setiap bulan selama 12 bulan per KPM.
Strategi Peningkatan Kesejahteraan melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) menjadi strategi kunci untuk memastikan Dana Desa berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal. PKTD didefinisikan sebagai kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif, memprioritaskan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi yang signifikan, kebijakan mewajibkan alokasi dana untuk PKTD setidaknya 50% dari dana kegiatan untuk membayar upah pekerja. Penekanan pada upah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat lokal dan memastikan manfaat DD dirasakan secara merata. Selain itu, pelaksanaan kegiatan prioritas DD diwajibkan dilakukan secara swakelola dan diprioritaskan menggunakan model PKTD, menjamin partisipasi aktif masyarakat setempat dalam proses pembangunan.
Integrasi Program Kesehatan Dasar, Ketahanan Pangan, dan Adaptasi Iklim
Kebijakan 2025 juga mendorong pergeseran fokus pembangunan menuju sektor-sektor non-fisik yang krusial untuk kualitas hidup dan keberlanjutan. Dana Desa diamanatkan untuk fokus pada peningkatan promosi dan penyediaan layanan kesehatan dasar, termasuk upaya pencegahan dan pengurangan stunting. Prioritas juga diberikan untuk program Ketahanan Pangan di Desa.
Salah satu mandat baru yang mencerminkan tantangan global adalah penguatan Desa agar adaptif terhadap Perubahan Iklim. Fokus ini mencakup kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, Mitigasi Perubahan Iklim, serta pengembangan Desa ramah lingkungan.
Penentuan fokus yang terperinci ini—termasuk penetapan batas maksimal (ceiling) 15% untuk BLT dan batas minimal (floor) 50% untuk upah PKTD—mengindikasikan peningkatan sentralisasi mandat pembangunan. Meskipun UU 6/2014 menekankan prinsip kemandirian , intervensi terpusat ini merupakan respons kebijakan terhadap kelemahan dalam penyelarasan prioritas lokal dengan sasaran nasional (seperti stunting dan kemiskinan ekstrem) yang terjadi di masa lalu. Kebijakan ini merupakan tradeoff strategis: mengorbankan sebagian otonomi desa demi efektivitas pencapaian target pembangunan nasional yang terukur, namun harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM Desa agar mandat ini tidak hanya menjadi beban administratif semata.
Tabel 2: Prioritas Utama Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Permen No. 2/2024)
| Fokus Prioritas (Pasal 2, Permen 2/2024) | Mekanisme Mandatori (Ceiling/Floor) | Tujuan Strategis |
| Penanganan Kemiskinan Ekstrem (BLT Desa) | Maksimum 15% dari pagu DD | Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. |
| Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai Desa (PKTD) | Minimal 50% dana kegiatan untuk upah | Peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja lokal. |
| Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar (termasuk Stunting) | Alokasi Wajib | Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan anak serta masyarakat. |
| Ketahanan Pangan | Alokasi Wajib | Memastikan ketersediaan dan akses pangan di tingkat Desa. |
| Penguatan Desa Adaptif Perubahan Iklim | Alokasi Wajib | Mengatasi risiko lingkungan dan mendorong keberlanjutan. |
Tantangan Kelembagaan dan Risiko Tata Kelola
Analisis Kapasitas SDM Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Meskipun aliran dana fiskal telah meningkat drastis, tantangan terbesar dalam implementasi DD adalah defisit tata kelola yang bersumber dari keterbatasan kapasitas SDM Aparat Desa. Keterbatasan ini mencakup aspek fundamental seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel.
Rendahnya pemahaman teknis dalam pengelolaan keuangan digital dan sistem informasi akuntansi Desa berpotensi menyebabkan penyimpangan administratif dan kesulitan dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Hal ini pada akhirnya menciptakan kerentanan Dana Desa terhadap penyalahgunaan, terutama jika minimnya pengawasan melekat.
Permasalahan Aktor Pendukung: Keterbatasan Peran Pendamping Desa (PD)
Peran Pendamping Desa (PD) sangat vital sebagai jembatan antara kebijakan pusat/daerah dengan realitas implementasi di lapangan. PD bertugas memberikan pendampingan intensif kepada individu masyarakat Desa maupun kelembagaan Desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan. Fungsi utamanya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.
Namun, studi kasus menunjukkan bahwa peran Pendamping Desa dalam pengelolaan anggaran seringkali belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, PD seringkali hanya berfungsi sebatas pemberi arahan tanpa memberikan pendampingan teknis yang memadai dan intensif. Kegagalan dalam pendampingan teknis, misalnya dalam perumusan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan, dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran dan kebutuhan riil.
Salah satu penyebab utama kurang maksimalnya pemantauan realisasi program fisik adalah masalah operasional dan geografis, di mana domisili atau tempat tinggal Pendamping Desa berada cukup jauh dari lokasi pendampingan. Ini menghambat pemantauan yang teratur dan periodik, mengakibatkan penggunaan anggaran yang belum merata dan tidak tepat sasaran, serta kegagalan dalam mendorong sektor pemberdayaan masyarakat seperti nelayan dan petani.
Penguatan Ekonomi Desa: Status Badan Hukum dan Tantangan BUMDes
Untuk mengatasi kelemahan dalam sektor produktif, reformasi hukum telah dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (diatur lebih lanjut dalam PP 11 Tahun 2021), BUMDes telah diberikan status sebagai Badan Hukum. Pemberian status badan hukum ini sangat krusial karena secara hukum memisahkan harta kekayaan BUMDes dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Pemisahan aset ini penting untuk meningkatkan profesionalisme, menjamin perlindungan hukum, dan menarik investasi dari pihak luar.
Meskipun legalitasnya telah diperkuat, tantangan operasional BUMDes masih signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi BUMDes meliputi struktur organisasi yang belum jelas dan pengurus yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta fungsinya (Tupoksi). Tantangan ini semakin diperumit dengan munculnya entitas ekonomi baru seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan BUMDes yang sudah ada. Oleh karena itu, sinergi diperlukan, di mana BUMDes didorong untuk berperan sebagai mitra, pemasok, atau pengelola unit bisnis yang beroperasi di bawah payung kelembagaan koperasi.
Pengawasan dan Akuntabilitas: Peran Multi-Lembaga dalam Pencegahan Penyalahgunaan
Risiko penyalahgunaan Dana Desa adalah konsekuensi langsung dari besarnya alokasi fiskal di tengah keterbatasan kapasitas SDM dan lemahnya pengawasan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperingatkan bahwa Dana Desa rawan penyalahgunaan jika pengawasan minimal.
Pengawasan dilakukan melalui sistem multi-lembaga yang kompleks. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di tingkat Kabupaten/Kota (Inspektorat) memegang peran kunci dalam pengawasan ex-post melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, sementara APIP Provinsi melakukan evaluasi dan pemantauan. Pemerintah juga menjalankan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan auditor negara, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan pengawasan terintegrasi dan pengendalian.
Secara paralel, mekanisme pengawasan oleh masyarakat juga diperkuat. Masyarakat Desa memiliki hak dan peran wajib untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan berhak meminta informasi dari Pemerintah Desa.
Mekanisme akuntabilitas yang ketat ini menciptakan sebuah trilema tata kelola. Di satu sisi, UU Desa memberikan otonomi dan mandat swakelola. Di sisi lain, Pemerintah Pusat menerapkan mandat prioritas terpusat (Permen 2/2024) , dan memberlakukan pengawasan supra-desa yang kompleks (APIP, KPK, BPKP). Tuntutan akuntabilitas yang tinggi dari lembaga pengawas adalah reaksi alami terhadap risiko penyalahgunaan yang muncul dari defisit kapasitas SDM. Namun, jika pengawasan yang ketat ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas yang memadai, fokus Aparat Desa dapat bergeser dari implementasi program pembangunan menjadi sekadar pemenuhan administrasi pelaporan. Hal ini mengubah Desa dari subjek pembangunan menjadi objek audit, yang pada akhirnya menghambat efektivitas DD di lapangan. Oleh karena itu, penguatan fungsi preventif dan peningkatan kompetensi adalah solusi yang lebih mendesak daripada fokus hanya pada penindakan.
Tabel 3: Tantangan Kelembagaan Utama Dana Desa
| Komponen Tata Kelola | Tantangan Utama | Dampak/Risiko |
| Kapasitas SDM Aparat Desa | Keterbatasan pengetahuan teknis (perencanaan, IT, keuangan). | Kerentanan penyalahgunaan; kesulitan pertanggungjawaban. |
| Pendamping Profesional Desa (PD) | Peran belum maksimal; kurangnya keahlian teknis dan isu domisili yang jauh. | Kegagalan monitoring fisik (RAB); penggunaan anggaran tidak tepat sasaran. |
| Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Struktur organisasi dan pemahaman Tupoksi pengurus yang belum jelas. | Kontribusi ekonomi kecil; risiko tumpang tindih dengan entitas baru. |
| Pengawasan dan Audit | Dana rawan penyalahgunaan jika pengawasan minimal. | Kehilangan kepercayaan publik; risiko korupsi. |
Kesimpulan
Program Dana Desa yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan eksperimen desentralisasi fiskal terbesar di Indonesia, menunjukkan keberhasilan yang tak terbantahkan dalam skala kuantitatif, mencapai total alokasi lebih dari Rp 600 triliun hingga 2024. DD berhasil sebagai instrumen mitigasi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja jangka pendek , sebagian besar didorong oleh fokus pada pembangunan infrastruktur fisik.
Namun, keberhasilan ini dibayangi oleh dua tantangan struktural: (1) The Productivity Bottleneck, di mana Dana Desa belum sepenuhnya mampu bertransformasi dari pembangunan infrastruktur generik menuju penciptaan nilai tambah ekonomi berkelanjutan melalui sektor produktif ; dan (2) The Governance Deficit, ditandai oleh rendahnya kapasitas SDM Aparat Desa dan kegagalan sistem pendampingan yang intensif.
Kebijakan tahun 2025, yang diperkuat melalui Permen No. 2/2024, merupakan respons yang terkalibrasi terhadap defisit tata kelola ini, dengan meningkatkan sentralisasi mandat prioritas (BLT Desa, PKTD, Stunting, Adaptasi Iklim). Meskipun intervensi ini bertujuan menjamin pencapaian target nasional, hal ini secara inheren menantang prinsip kemandirian Desa, sekaligus meningkatkan kompleksitas administrasi.
Rekomendasi Politik Fiskal
- Penguatan Investasi Produktif BUMDes Berbadan Hukum: Pemerintah perlu menggeser secara bertahap alokasi DD dari pembangunan infrastruktur generik ke investasi modal yang lebih agresif (capital injection) kepada BUMDes yang telah memiliki status Badan Hukum. Status badan hukum ini memberikan perlindungan aset dan kredibilitas yang diperlukan untuk menarik pendanaan dan investasi lebih lanjut, memaksimalkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal.
- Harmonisasi Anggaran untuk Program Prioritas: Wajib dilakukan sinkronisasi perencanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan dana sektoral lain (seperti dana kesehatan, pertanian, atau dana desa digital). Integrasi ini penting untuk menghindari duplikasi pendanaan dan memastikan bahwa mandat program prioritas nasional (seperti stunting dan adaptasi iklim) didukung secara maksimal dan terukur.
- Mempertahankan Mandat PKTD: Mandat minimal 50% dana kegiatan untuk upah PKTD harus dipertahankan, bahkan dipertimbangkan untuk ditingkatkan untuk menjamin Dana Desa terus berfungsi sebagai bantalan sosial dan penyerapan tenaga kerja lokal. Mekanisme PKTD harus diperluas dari proyek fisik sederhana ke proyek yang mendukung sektor produktif (misalnya, pemeliharaan BUMDes atau pengelolaan sumber daya alam lokal).
Rekomendasi Kapasitas Kelembagaan dan Pengawasan
- Revitalisasi Total Peran Pendamping Desa: Perlu adanya evaluasi kinerja menyeluruh dan rekonfigurasi tugas Pendamping Desa (PD). PD harus ditingkatkan kualifikasinya dan diubah dari sekadar “pemberi arahan” menjadi auditor teknis lapangan dan konsultan bisnis BUMDes. Kebijakan penempatan harus mengatasi masalah jarak domisili agar PD dapat melakukan pemantauan intensif, memverifikasi kesesuaian Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan memastikan pelaksanaan program tepat sasaran.
- Peningkatan Kompetensi Digital Aparat Desa: Pelatihan teknis intensif harus difokuskan pada penguasaan pengelolaan keuangan digital, sistem informasi Desa, dan akuntabilitas berbasis TI untuk menjembatani kesenjangan kapasitas SDM yang signifikan.
- Penguatan Pengawasan APIP yang Preventif: Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus digeser secara strategis dari audit post-factum (penindakan setelah penyimpangan) menjadi pengawasan preventif dan pre-audit. APIP Kabupaten/Kota harus diberdayakan untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan di awal tahun anggaran (misalnya, pada bulan Januari) untuk mendeteksi ketidaksesuaian perencanaan dan penggunaan dana sebelum alokasi disalurkan secara masif. Pendekatan ini akan memperkuat fungsi pembinaan dan mengurangi risiko bahwa Aparat Desa menjadi objek audit semata.