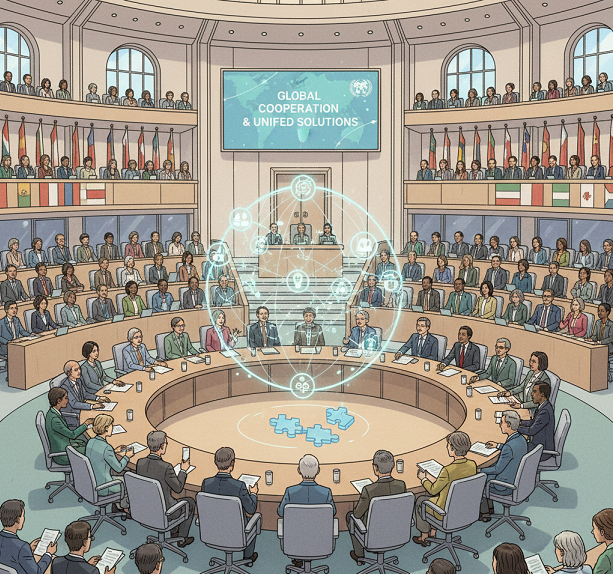Masa depan organisasi multilateral global, seperti World Trade Organization (WTO) dan World Health Organization (WHO), berada di persimpangan jalan yang kritis, di tengah pergeseran tatanan dunia dari unipolaritas menuju era multipolaritas dan fragmentasi geopolitik. Laporan ini mendiagnosis bahwa organisasi-organisasi universal menghadapi krisis legitimasi dan efektivitas yang disebabkan oleh kombinasi rivalitas kekuatan besar, kebangkitan nasionalisme, dan kegagalan struktural dalam mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang.
Secara sektoral, kelemahan sistematis terlihat jelas: WTO mengalami kelumpuhan mekanisme penyelesaian sengketa (Badan Banding) akibat blokade politik, sementara negosiasi tata kelola kesehatan global di WHO (Instrumen Pandemi) menemui jalan buntu karena isu fundamental mengenai ekuitas dan transfer teknologi (Pathogen Access and Benefit Sharing/PABS). Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap terperangkap dalam kebuntuan historis reformasi Dewan Keamanan (DK PBB) akibat hak veto, yang menghambat kemampuan sistem keamanan kolektif untuk merespons krisis kontemporer.
Ancaman eksistensial bagi tata kelola global semakin diperburuk oleh isu-isu non-tradisional yang kompleks, di antaranya perubahan iklim yang bertindak sebagai threat multiplier, memicu migrasi massal dan konflik sumber daya. Selain itu, transisi energi telah membuka medan perang geoeconomic baru, di mana persaingan atas mineral kritis antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menciptakan kebijakan proteksionis dan memfragmentasi rantai pasok hijau.
Meskipun lanskapnya mengarah pada skenario Fragmentation atau Multilateralisme Polisentris (Networks) , terdapat peluang bagi negara-negara berkembang dan kekuatan menengah, seperti Indonesia, untuk mendorong skenario Renewal. Hal ini menuntut diplomasi yang proaktif dan terkoordinasi melalui forum-forum alternatif seperti G20 dan BRICS , guna menuntut sistem multilateral yang lebih representatif, adil, dan inklusif.
Pengantar Dan Kerangka Konseptual: Krisis Multilateralisme Universal
Multilateralisme di Persimpangan Jalan: Dari Tatanan Pasca Perang Dingin ke Era Multipolaritas
Multilateralisme, sebagai prinsip dasar yang mengatur hubungan internasional pasca-Perang Dunia II, didirikan di bawah tatanan yang diwarnai oleh hegemon unipolar—Amerika Serikat—yang secara aktif mempromosikan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui institusi internasional. Namun, tatanan ini kini menghadapi ujian besar di era multipolar.
Gejolak kontemporer ini dipicu oleh dua faktor utama: rivalitas geopolitik yang meningkat dan ketidaksetaraan global yang semakin melebar. Kebijakan luar negeri AS pada masa awal pasca-Perang Dingin, meskipun mengedepankan multilateralisme, sempat diwarnai oleh aksi unilateralistik, seperti invasi ke Irak atau pelanggaran HAM dalam investigasi tahanan, yang secara signifikan merusak kredibilitas nilai-nilai multilateralisme yang diusung oleh AS sendiri.
Dalam tatanan dunia yang terpolarisasi, kemampuan kerjasama global untuk mengatasi tantangan transnasional terhambat. Masa depan tatanan dunia saat ini bergantung pada kemampuan kolektif untuk mengatasi perbedaan kepentingan dan mengedepankan kepentingan bersama demi stabilitas global.
Diagnosis Historis Krisis: Pilar Kepercayaan dan Legitimas yang Tergerus
Krisis multilateralisme tidak hanya bersifat siklus, melainkan berakar pada pelemahan pilar kepercayaan dan legitimasi institusional.
Kebangkitan Nasionalisme dan Rivalitas Kekuatan Besar
Menguatnya nasionalisme dan populisme global telah memicu “arus balik” terhadap multilateralisme, di mana kepentingan nasional cenderung diutamakan di atas upaya kolektif. Hal ini menghambat penanganan isu-isu global yang memerlukan komitmen lintas batas. Selain itu, rivalitas antara kekuatan besar, terutama AS dan Tiongkok, memperparah polarisasi global, menciptakan dinamika kompetisi strategis yang membagi aliansi dan memecah upaya kerjasama.
Keterbatasan Institusional dan Ketidaksetaraan Struktural
Kritik paling mendalam terhadap sistem multilateral datang dari negara-negara berkembang (Global South) yang merasa bahwa institusi yang ada gagal mengatasi ketidaksetaraan struktural. Negara-negara berkembang kesulitan mengakses teknologi hijau, vaksin, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan, sementara negara maju mempertahankan kontrol atas sumber daya dan inovasi. Ketika ketidaksetaraan struktural ini tidak ditangani, legitimasi tata kelola global tergerus, yang pada gilirannya mendorong munculnya blok-blok regional baru dan fragmentasi.
Transformasi ke Multilateralisme Multi-Kecepatan
Kegagalan institusi universal untuk mencapai konsensus, sering kali karena adanya hak veto atau keberatan mengenai kewajiban Perlakuan Khusus dan Berbeda (Special & Differential Treatment atau S&DT) bagi negara berkembang, mendorong negara-negara kuat untuk mencari mekanisme kerjasama yang lebih fleksibel. Analisis tatanan global menunjukkan kecenderungan menuju skenario sistem dunia Networks atau Multilateralisme Polisentris.
Multilateralisme Polisentris dicirikan oleh potensi kuatnya kerjasama, namun dalam kerangka yang lebih tersebar dan sering kali tumpang tindih. Hal ini diwujudkan melalui minilateralisme, yaitu kerjasama antara sejumlah kecil negara yang memiliki kepentingan serupa (like-minded countries) di luar struktur formal WTO atau PBB. Meskipun minilateralisme menawarkan kecepatan dan fleksibilitas (misalnya, Quad di Indo-Pasifik dalam isu keamanan maritim atau pembangunan infrastruktur) , risiko utamanya adalah pengabaian isu-isu sulit dan negara-negara yang kurang memiliki daya tawar, yang dapat memicu skenario Fragmentation.
Transformasi Tata Kelola Global: Peran Aktor Alternatif
Di tengah fragmentasi ini, aliansi baru dan forum ad-hoc mengambil peran yang semakin penting dalam membentuk tata kelola global.
Kelompok G20, misalnya, terbukti krusial sebagai jembatan untuk menghadapi tantangan global, termasuk isu perubahan iklim, krisis multisektor, dan perpecahan geopolitik. G20, yang anggotanya bertanggung jawab atas sekitar 80 persen emisi global, memiliki peran penting dalam mendorong pakta kolaborasi baru antara negara maju dan berkembang untuk menahan kenaikan suhu global di batas 1.5∘C.
Di sisi lain, kelompok seperti BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) menyediakan forum alternatif yang bertujuan untuk mendorong reformasi tata kelola ekonomi global, menciptakan sistem yang lebih adil dan tidak diskriminatif bagi negara-negara berkembang. Indonesia, yang secara aktif mempertimbangkan aksesi ke dalam BRICS, juga terlibat dalam mendorong peningkatan representasi negara-negara besar baru di dunia internasional, sebuah agenda reformasi yang disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam sistem PBB.
Ancaman Eksistensial Organisasi Sektoral Utama
World Trade Organization (WTO): Dari Arbitrator ke Arena Negosiasi Ulang
WTO, sebagai pilar tata kelola perdagangan global, menghadapi ancaman yang langsung mempengaruhi fungsi intinya.
Kelumpuhan Badan Banding (Appellate Body)
Krisis terparah menimpa mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Badan Banding, yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi perdagangan, telah lumpuh total sejak 2019. Kelumpuhan ini disebabkan oleh blokade Amerika Serikat terhadap penunjukan hakim baru. Akibatnya, WTO kehilangan kemampuan untuk menegakkan aturan perdagangan secara mengikat, yang berpotensi membuka opsi bagi negara anggota untuk menggunakan hak retaliasi (tindakan pembalasan) sebagai alat penegakan hukum dalam sengketa internasional.
Kasus sengketa hilirisasi nikel Indonesia dengan Uni Eropa menjadi simbol ketegangan ini. Indonesia dinyatakan kalah karena WTO menilai industri hilir domestik (besi) belum ‘matang’. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengajukan banding, prosesnya terhambat oleh blokade AS terhadap Badan Banding. Kasus ini menyoroti konflik mendasar antara hak negara berkembang untuk mengembangkan industrialisasi dan aturan perdagangan global yang dianggap bias atau tidak mendukung upaya pembangunan nasional.
Perang Agenda: Inklusivitas vs. Plurilateralisme
Di tengah kebuntuan institusional, terdapat pertentangan tajam mengenai agenda reformasi WTO. Negara-negara maju terus mendorong isu-isu baru seperti perdagangan digital (e-commerce), fasilitasi investasi, dan lingkungan melalui perjanjian plurilateral. Perjanjian plurilateral ini, yang hanya melibatkan negara-negara yang memiliki kepentingan sama (like-minded countries), merupakan manifestasi dari kecenderungan multilateralisme multi-kecepatan yang disoroti sebelumnya.
Sebaliknya, negara-negara berkembang menuntut reformasi yang berfokus pada pembangunan dan inklusivitas, termasuk: (1) penguatan ketentuan Perlakuan Khusus dan Berbeda (S&DT) yang merupakan kewajiban perjanjian WTO; dan (2) pengambilan keputusan mendesak mengenai usulan pengabaian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam rangka penanganan pandemi. Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah menekankan pentingnya multilateralisme yang adil dan inklusif dalam menghadapi Direktur Jenderal WTO.
Konstelasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa WTO berisiko menjadi forum yang hanya efektif untuk isu-isu yang disepakati oleh negara-negara kuat, sementara isu-isu pembangunan (S&DT) ditinggalkan, sehingga memperburuk ketidakadilan struktural yang dikritik oleh negara berkembang. Negara-negara besar melumpuhkan mekanisme penegakan yang tidak menguntungkan mereka (Badan Banding), namun pada saat yang sama, mereka secara agresif mendorong standar baru melalui plurilateralisme.
World Health Organization (WHO): Perjuangan untuk Ekuitas Kesehatan Global
Pandemi COVID-19 secara brutal mengungkap kelemahan mendasar dalam tata kelola kesehatan global. Alih-alih koordinasi erat, sistem kesehatan global menunjukkan kerentanan dan ketidakmampuan untuk bertindak solid. Hal ini memicu upaya reformasi besar-besaran di WHO, berpusat pada Amandemen Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan negosiasi Instrumen Pandemi (WHO CA+ on PPPR).
Kebuntuan dalam Instrumen Pandemi dan Isu Ekuitas
Meskipun Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-77 telah menyepakati paket amandemen IHR, negosiasi Instrumen Pandemi menemui jalan buntu dan diperpanjang hingga WHA 2025. Titik konflik utama adalah tuntutan negara-negara berkembang, yang tergabung dalam Kelompok Ekuitas dan Kelompok Afrika, mengenai akses yang adil pada produk kesehatan—sebuah isu yang sering disebut sebagai Red Line dalam negosiasi.
Negara-negara maju, seperti Uni Eropa, terus memblokade usulan tersebut. Tuntutan paling krusial adalah mekanisme Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS). Negara berkembang menuntut agar pembagian informasi mengenai patogen (yang seringkali berasal dari biodiversitas mereka) harus diimbangi dengan pembagian manfaat, termasuk produk langsung, pengurangan harga, dan dukungan teknologi serta keuangan. Sebaliknya, negara-negara maju cenderung hanya menginginkan surveilans dan pembagian informasi yang ekstensif, tanpa kewajiban timbal balik untuk transfer manfaat yang sepadan.
Kesehatan Global sebagai Isu Keamanan Geopolitik
Kekhawatiran negara-negara Afrika menunjukkan bahwa tata kelola kesehatan global telah bergeser menjadi dimensi keamanan strategis (Human Security framework). Kekhawatiran ini adalah bahwa jika Amandemen IHR yang berfokus pada surveilans disahkan tanpa Instrumen Pandemi yang mengikat isu ekuitas, negara-negara kuat akan kehilangan motivasi untuk menegosiasikan pembagian manfaat yang adil.
Dalam konteks ini, tata kelola yang muncul bersifat transaksional: negara maju memprioritaskan keamanan (surveilans ekstensif untuk mendeteksi ancaman), sementara negara berkembang memprioritaskan ekuitas (akses dan teknologi untuk melindungi populasi mereka). Kegagalan untuk mencapai kesepakatan yang mengikat mengenai ekuitas kesehatan akan sangat merusak legitimasi WHO dalam krisis kesehatan global di masa depan dan memperburuk ketidakseimbangan kekuasaan. Parlemen, seperti yang disarankan dalam penelitian, memiliki peran untuk memastikan kebijakan penanganan pandemi berlangsung inklusif dengan membangun kapasitas kesehatan domestik di masing-masing negara.
Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Keterbatasan Mandat dan Reformasi Dewan Keamanan (DK PBB)
Sebagai institusi multilateral universal terpenting, PBB menghadapi krisis eksistensial, terutama di Dewan Keamanan (DK PBB).
Krisis Legitimasi dan Hak Veto
DK PBB dikritik karena dianggap tidak representatif, dengan kurangnya perwakilan dari kawasan Asia, Afrika, dan Karibia dalam keanggotaan tetap. Selain itu, efektivitasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan kolektif terus terancam oleh penggunaan hak veto oleh anggota tetap (P5), seperti yang terlihat dalam kasus Perang Irak tahun 2003, konflik Israel-Lebanon tahun 2006, dan konflik-konflik kontemporer seperti di Ukraina. Sekjen PBB Antonio Guterres bahkan mengakui bahwa sistem keamanan kolektif PBB terancam oleh perpecahan geopolitik.
Hambatan Reformasi dan Isu Pendanaan
Upaya reformasi DK PBB yang paling signifikan, seperti yang didorong oleh Panel Tingkat Tinggi pada 2004, telah gagal karena pertentangan kepentingan yang kuat antar kelompok negara. Kelompok G4 (Jepang, Jerman, India, Brasil) menuntut perluasan anggota tetap dengan hak veto, namun ditentang oleh kelompok Uniting For Consensus (UFC) yang dipimpin oleh Italia dan Pakistan. African Union juga mengajukan tuntutan perluasan anggota tetap dan hak veto.
Kegagalan reformasi ini berakar pada kontradiksi antara prinsip keamanan kolektif dan kedaulatan negara besar. Negara-negara P5 menolak melepaskan kedaulatan yang diwujudkan melalui hak veto, sementara negara-negara lain menuntut representasi yang lebih adil. Isu pendanaan juga memperumit masalah. Masalah keuangan PBB, yang ditandai oleh tumpukan utang dan tunggakan pembayaran dari negara-negara maju (termasuk AS dan Rusia), dikaitkan dengan kelayakan keanggotaan dalam usulan reformasi DK PBB.
Guterres telah merilis laporan kemajuan reformasi struktural (Inisiatif UN80) dan mengadopsi “Pakta bagi Masa Depan” yang mencakup reformasi DK PBB, yang bertujuan untuk memperkuat tiga pilar PBB: perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, serta hak asasi manusia. Namun, selama kepentingan kedaulatan kekuatan besar terus mengalahkan prinsip representasi global, sistem PBB akan menghadapi risiko ketidakefektifan yang berkelanjutan.
Geopolitik Baru Dan Multilateralisme Kontemporer (The Nexus)
Multilateralisme masa depan akan ditentukan oleh kemampuan institusi global untuk mengatasi isu-isu non-tradisional yang mengancam human security.
Perubahan Iklim sebagai Threat Multiplier dan Krisis Kedaulatan
Perubahan iklim telah berkembang dari isu lingkungan menjadi ancaman strategis yang memengaruhi stabilitas global. Perubahan iklim bertindak sebagai threat multiplier, yang secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kemungkinan konflik dengan memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi di kawasan yang rentan.
Nexus Iklim, Sumber Daya, dan Konflik
Kelangkaan sumber daya, terutama air dan pangan, akibat perubahan iklim (kekeringan, banjir, cuaca ekstrem) memicu persaingan sumber daya. Di Timur Tengah dan Afrika, krisis air merupakan masalah mendesak yang diperburuk oleh perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan pengelolaan air yang buruk. Negara-negara hulu sering menunjukkan kecenderungan egosentris dengan mendominasi sumber daya air, memaksa negara-negara hilir menanggung utang signifikan untuk mengamankan akses.
Di Afrika Timur, siklus kekeringan dan banjir yang berulang telah memperparah kelangkaan air, meningkatkan kerentanan terhadap kerawanan pangan dan kemiskinan. Di tingkat domestik, meskipun data spesifik terbatas, konflik agraria di Indonesia menunjukkan potensi menjadi rawan pelanggaran HAM dan diperparah oleh kebijakan yang tidak tuntas dan bencana hidrologi.
Krisis Migrasi Iklim dan Kekosongan Hukum
Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan bencana alam, telah memicu perpindahan manusia (displacement) dalam skala besar, yang disorot oleh Sekjen PBB sebagai ‘mass exodus of entire populations on a biblical scale’. Di Afrika, diperkirakan kondisi ekstrem dapat memaksa migrasi, dengan 1,2 juta orang mengungsi karena badai dan banjir pada tahun 2020—jumlah yang hampir dua setengah kali lipat dari pengungsi konflik di tahun yang sama.
Secara geopolitik, kenaikan permukaan laut mengancam kedaulatan fisik pulau-pulau kecil, termasuk di Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau.
Isu mendasar yang harus diatasi multilateralisme adalah kekosongan kerangka hukum internasional untuk pengungsi iklim (environmental refugee). Konvensi Jenewa masih berpatokan pada definisi pengungsi tradisional, meninggalkan jutaan orang yang kehilangan hak dasar (hak hidup, air bersih, pangan) akibat kerusakan lingkungan tanpa perlindungan hukum yang komprehensif.
Kegagalan Keadilan Struktural Iklim
Krisis ini merupakan kegagalan keadilan struktural dalam tata kelola multilateral. Perubahan iklim didorong oleh emisi gas rumah kaca yang secara historis didominasi oleh negara maju (G20 bertanggung jawab atas 80% emisi global). Namun, dampaknya paling parah dirasakan oleh negara-negara miskin dan rentan. Multilateralisme telah gagal mengikat prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dalam bentuk kewajiban pendanaan adaptasi yang memadai. Jika negara-negara maju yang bertanggung jawab tidak memenuhi kewajiban mereka, tekanan geopolitik yang diakibatkan oleh migrasi dan kelangkaan sumber daya akan terus meningkat, menciptakan ketidakstabilan di tingkat regional dan global.
Geopolitik Mineral Kritis dan Tata Kelola Rantai Pasok Hijau
Transisi energi merupakan salah satu agenda multilateral terbesar untuk mengatasi perubahan iklim, namun hal ini telah memicu persaingan geopolitik baru, memindahkan fokus dari kontrol bahan bakar fosil ke mineral kritis.
Persaingan Mineral Kritis dan Proteksionisme Baru
Mineral kritis (seperti neodymium dan dysprosium) sangat penting untuk teknologi hijau, seperti motor kendaraan listrik dan turbin angin. Mineral ini kini dipandang sebagai ‘minyak baru’ strategis.
Persaingan strategis antara AS dan Tiongkok berfokus pada penguasaan sumber daya ini. Tiongkok saat ini mendominasi seluruh supply chain mineral kritis, mulai dari proses penambangan (mining), pengolahan (processing), hingga teknologi komponen baterai lithium. Amerika Serikat merespons dominasi ini dengan kebijakan proteksionis seperti Inflation Reduction Act (IRA), yang menerapkan batasan terhadap produk yang berasal dari entitas Tiongkok (foreign entity of concern / FEOC) dan menaikkan tarif impor untuk barang-barang strategis seperti EV dan baterai.
Rantai Pasok Hijau sebagai Alat Kontrol Geoeconomic
Konsep Green Supply Chain Management (GSCM), yang bertujuan untuk mengurangi limbah, mengonservasi sumber daya, dan mendorong teknologi ramah lingkungan , kini telah berkembang menjadi alat strategis. Negara-negara berupaya mengontrol rantai pasok hijau tidak hanya untuk keberlanjutan tetapi juga untuk ketahanan energi nasional dan keuntungan ekonomi.
Upaya global untuk mengatasi perubahan iklim melalui transisi energi secara ironis telah menciptakan medan perang geoeconomic baru. Sengketa WTO mengenai hilirisasi mineral (kasus Nikel) adalah manifestasi langsung dari upaya negara sumber daya (seperti Indonesia) untuk mendapatkan nilai tambah, yang bertabrakan dengan kepentingan rantai pasok global yang didominasi oleh negara-negara industri. Kegagalan multilateralisme perdagangan untuk mengatur mineral kritis secara adil akan memperparah fragmentasi dan mendorong proteksionisme baru.
Skenario Masa Depan Multilateralisme (2025-2035)
Masa depan tata kelola global tidak akan kembali ke tatanan homogen pasca-Perang Dingin. Berdasarkan diagnosis krisis dan dinamika geopolitik saat ini, tatanan dunia cenderung bergerak ke salah satu dari tiga skenario utama, yang oleh beberapa akademisi disebut sebagai skenario sistem dunia Kappen.
Skenario Networks (Multilateralisme Polisentris)
Skenario Networks dicirikan oleh potensi kerja sama yang kuat, namun dalam kerangka yang tersebar, tumpang tindih, dan non-hierarkis (polisentrisme).
Mekanisme dalam skenario ini didominasi oleh peningkatan peran aliansi spesifik (minilateralisme, G20, BRICS) yang menawarkan fleksibilitas dan kecepatan dalam menyelesaikan isu spesifik. PBB dan WTO akan terus eksis, namun perannya lebih kepada forum koordinasi dan legitimasi norma, daripada sebagai pengambil keputusan yang mengikat semua aktor. Keuntungan dari skenario ini adalah memungkinkan solusi yang cepat dan sesuai kepentingan kelompok yang terlibat, tetapi kelemahan utamanya adalah bahwa isu-isu universal (seperti krisis iklim, migrasi, dan ekuitas kesehatan) akan sulit ditangani secara komprehensif karena kurangnya mekanisme penegakan hukum yang mengikat seluruh aktor, terutama yang berada di luar jaringan utama.
Skenario Fragmentation (Erosi Total)
Skenario Fragmentation menunjukkan bahwa sistem global didominasi oleh kepentingan nasional yang ekstrem, unilateralisme, dan penarikan diri dari kewajiban perjanjian.
Dalam skenario ini, kegagalan reformasi di DK PBB dan WTO menjadi total. Negara-negara besar secara terbuka menarik diri dari inisiatif internasional (seperti penarikan partisipasi AS dari sejumlah inisiatif iklim internasional) atau menggunakan lembaga multilateral hanya untuk kepentingan sepihak, bukan kepentingan bersama. Dampaknya adalah peningkatan risiko konflik geopolitik, perang dagang yang meluas (tarif dan sengketa mineral kritis menjadi norma), dan kegagalan kolektif yang fatal dalam menghadapi ancaman eksistensial, seperti krisis pangan dan iklim global yang tidak terkelola. Analisis menunjukkan bahwa konstelasi tata kelola global saat ini memiliki kecenderungan mendekati skenario Networks dan Fragmentation.
Skenario Renewal (Pembaruan yang Dipimpin oleh Kekuatan Menengah)
Skenario Renewal (Pembaruan) adalah skenario yang paling ambisius, di mana reformasi institusional berhasil diwujudkan, didorong oleh koalisi negara-negara berkembang dan kekuatan menengah yang menuntut inklusivitas dan keadilan.
Mekanisme kuncinya adalah kemampuan Global South untuk menyatukan suara melalui forum-forum seperti BRICS, G20, dan Gerakan Non-Blok. Mereka memaksa PBB dan WTO untuk mengadopsi struktur yang lebih representatif (reformasi DK PBB) dan mekanisme yang adil (penguatan S&DT di WTO, pengesahan PABS di WHO). Skenario ini akan memberikan legitimasi baru pada sistem universal, memitigasi fragmentasi, dan memungkinkan penanganan tantangan transnasional secara efektif, serta mendukung upaya global untuk memenuhi agenda 2030 (SDGs).
Kunci untuk mendorong tatanan global ke arah Renewal terletak pada kemampuan kekuatan menengah, seperti Indonesia, untuk meningkatkan daya tawar melalui semua platform yang tersedia (multilateral, plurilateral, dan aliansi alternatif).
Rekomendasi Dan Posisi Strategis
Untuk menavigasi masa depan multilateralisme yang penuh gejolak dan memastikan kepentingan nasional Indonesia terakomodasi di tengah persaingan kekuatan besar, langkah-langkah strategis berikut direkomendasikan:
Mendesak Multilateralisme yang Adil dan Berbasis Prinsip
- Penegasan Prinsip Keadilan Iklim (CBDR-RC): Pemerintah harus terus mendesak negara-negara maju, terutama anggota G20, untuk memenuhi tanggung jawab historis mereka terkait emisi dan menyediakan pendanaan yang memadai untuk adaptasi dan mitigasi iklim. Diplomasi harus berfokus pada pengarusutamaan keadilan struktural dalam negosiasi iklim, khususnya pendanaan kerugian dan kerusakan.
- Kedaulatan Kesehatan Global: Dalam negosiasi WHO (WHO CA+), Indonesia harus memperkuat posisi bersama dengan Kelompok Ekuitas dan Kelompok Afrika untuk mempertahankan tuntutan Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS) dan transfer teknologi. Hal ini penting untuk memastikan kedaulatan kesehatan domestik dan mencegah eksploitasi informasi patogen tanpa manfaat yang sepadan.
- Memperkuat S&DT di WTO: Indonesia harus menjadikan penguatan Perlakuan Khusus dan Berbeda (S&DT) sebagai inti agenda reformasi WTO. Indonesia perlu membangun argumen yang solid dan meyakinkan dalam sidang banding nikel, yang menekankan hak negara berkembang untuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi untuk mencapai kematangan industri, tanpa dibatasi oleh aturan perdagangan yang bias.
Diplomasi Ekonomi Proaktif di Tengah Perang Mineral Kritis
- Mengamankan Rantai Pasok Hijau: Indonesia harus memperkuat value chains mineral kritis di dalam negeri, memanfaatkan posisi strategisnya, sambil menjaga keseimbangan antara tekanan geopolitik dari AS (IRA) dan dominasi Tiongkok. Strategi ini harus fokus pada pembangunan kapasitas domestik dan penetapan visi strategis jangka panjang atas sumber daya kritis.
- Memanfaatkan Forum Multilateral Baru: Aksesi ke OECD dan potensi keanggotaan dalam BRICS harus dimanfaatkan sebagai jalur diplomasi ekonomi untuk meningkatkan daya tawar Indonesia. Tujuan strategisnya adalah mendorong reformasi tata kelola ekonomi global yang tidak diskriminatif, termasuk dalam bidang pendanaan infrastruktur, energi terbarukan, dan peningkatan teknologi manufaktur.
Peningkatan Kapasitas dan Diplomasi Lintas Sektor
- Penguatan Diplomasi Parlemen: DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) harus memaksimalkan peranannya dalam forum internasional (AIPA, IPU) untuk mengatasi tantangan transnasional non-tradisional, seperti keamanan lingkungan dan perubahan iklim. Diplomasi parlemen menawarkan inklusivitas dan fleksibilitas yang sering kali sulit dicapai oleh diplomasi eksekutif.
- Ketahanan Domestik: Peningkatan posisi tawar di forum multilateral harus didukung oleh reformasi struktural domestik. Ini mencakup peningkatan ketahanan pangan (mengatasi keterbatasan adopsi varietas unggul tahan iklim dan ketergantungan pada impor pupuk) , pembangunan berkelanjutan energi terbarukan (seperti potensi energi laut di negara maritim) , dan investasi kesehatan domestik untuk ketahanan medis. Langkah ini memastikan Indonesia tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga siap menghadapi tantangan transnasional secara mandiri.