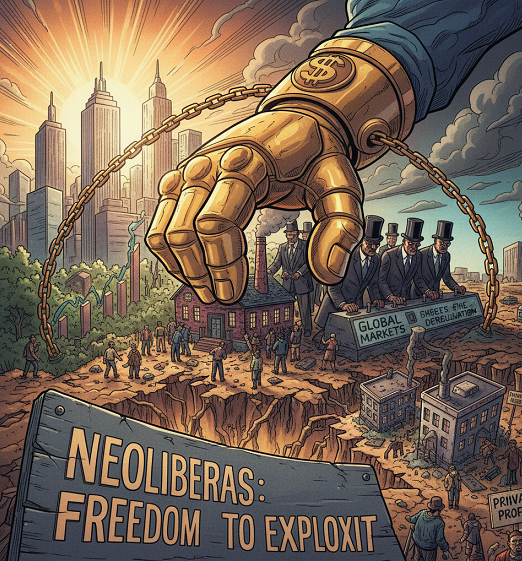Genealogi Intelektual: Dari F.A. Hayek dan Milton Friedman hingga Mazhab Chicago
Neoliberalisme merupakan penyempurnaan dan restorasi dari paham ekonomi liberal klasik yang mendapatkan hegemoni global pada paruh kedua abad ke-20. Secara historis, paham ini muncul sebagai reaksi keras terhadap konsensus ekonomi pasca-Perang Dunia II, khususnya model Keynesian yang mendukung intervensi pemerintah yang aktif, regulasi pasar, dan negara kesejahteraan. Tokoh-tokoh intelektual kunci di balik kebangkitan Neoliberalisme mencakup Friedrich August Hayek dan Milton Friedman, yang memimpin Mazhab Chicago.
Landasan filosofis Neoliberalisme sangat terkait erat dengan warisan Abad Pencerahan, yang menempatkan rasionalitas sebagai identitas utama modernitas dan mempromosikan konsep kebebasan individual. Abad Pencerahan memperkenalkan nilai-nilai dan institusi demokrasi liberal modern serta penekanan pada hak-hak individu. Namun, dalam konteks Neoliberalisme, rasionalitas ini bermetamorfosis menjadi rasionalitas instrumental yang sempit, di mana efisiensi dan supremasi pasar menjadi tujuan utama. Konsekuensi dari penekanan rasionalitas yang terlepas dari kerangka etis-sosial ini adalah terlepasnya landasan moral yang kuat, yang dikritik oleh beberapa pihak sebagai kegagalan sekularisme dalam memberikan pondasi intelektual etis-sosial bagi masyarakat. Pada dasarnya, klaim kebebasan yang diusung oleh Neoliberalisme justru menyebabkan destruksi solidaritas sosial karena menempatkan keuntungan pasar di atas norma moral dan sosial yang kohesif.
Kredo Utama: Supremasi Pasar dan Pengurangan Peran Negara
Doktrin utama Neoliberalisme adalah keyakinan mutlak pada kemampuan pasar untuk mengatur dirinya sendiri dan menciptakan kemakmuran, dengan meminimalkan intervensi negara. Kredo ini termanifestasi dalam beberapa pilar kebijakan struktural yang memiliki dampak sistemik terhadap kesejahteraan rakyat:
Pertama, Supremasi Pasar yang Mutlak. Kebijakan ini membebaskan kegiatan swasta dari segala bentuk peraturan dan kebijakan pemerintah, bahkan ketika aktivitas tersebut terbukti membawa dampak buruk bagi masyarakat luas atau lingkungan. Pandangan ini meyakini bahwa aturan-aturan ekonomi harus menguasai sektor-sektor lain, dan segala peraturan yang dianggap menghambat akumulasi keuntungan ekonomi harus dihilangkan atau dicabut.
Kedua, Austerity (Kebijakan Penghematan). Neoliberalisme secara sistematis menganjurkan pengurangan biaya untuk fasilitas dan pembangunan umum, seperti dana untuk pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih. Implikasi kebijakan penghematan ini adalah pemotongan anggaran tersebut secara proporsional paling besar dampaknya dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin. Mereka dipaksa untuk mengatasi sendiri masalah kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya tanpa bantuan sosial yang memadai dari negara.
Ketiga, Privatisasi/Swastanisasi. Neoliberalisme mendorong penjualan aset-aset milik negara (BUMN), termasuk di sektor-sektor strategis seperti air, listrik, perbankan, hingga rumah sakit dan sekolah. Meskipun argumennya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari korupsi , dalam praktiknya, penjualan perusahaan negara kepada pihak swasta seringkali berakhir dengan kenaikan biaya dan ongkos yang harus ditanggung oleh rakyat, sementara keuntungan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil elit.
Analisis kritis terhadap doktrin ini menemukan bahwa Neoliberalisme bukan hanya sebuah teori ekonomi yang gagal secara utopis, melainkan sebuah strategi politik yang disengaja. Ini merupakan ‘topeng’ untuk menutupi proyek restorasi kepentingan kelas yang berkuasa. Kebijakan seperti pelemahan serikat buruh, tekanan untuk menurunkan upah riil, dan upaya membebaskan swasta dari regulasi kepemilikan tanah petani secara luas, semuanya dirancang secara eksplisit untuk melayani kepentingan elit kapitalis dan mengkonsolidasikan kekayaan di puncak piramida sosial.
Washington Consensus: Blue Print Globalisasi Neoliberal di Negara Berkembang
Washington Consensus adalah manifestasi instrumental dari Neoliberalisme di tingkat kebijakan global, yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga yang berbasis di Washington D.C., seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Konsensus ini adalah serangkaian sepuluh kebijakan yang diwajibkan kepada negara-negara berkembang yang mengalami krisis ekonomi atau yang mengajukan pinjaman, sebagai bagian dari Structural Adjustment Programs.
Prinsip-prinsip yang dipaksakan ini meliputi disiplin fiskal, reformasi pajak, penetapan suku bunga oleh pasar, liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan pembukaan ekonomi terhadap Investasi Asing Langsung (FDI). Kebijakan ini menekankan bahwa kinerja ekonomi yang baik menuntut perdagangan bebas, stabilitas makro, dan kebijakan harga yang tepat. Penerapan Washington Consensus secara efektif mengimplementasikan hegemoni Neoliberal di seluruh dunia, memaksa negara-negara berkembang untuk mengadopsi model pasar bebas secara terburu-buru.
Mekanisme Implementasi Dan Kerentanan Pasar Di Indonesia
Liberalisasi Finansial dan Arus Modal Asing (FDI)
Di Indonesia, penerapan Neoliberalisme diwujudkan melalui dorongan kebijakan yang pro-Investasi Asing Langsung (FDI), yang dianggap sebagai salah satu indikator penting pertumbuhan makroekonomi. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investasi asing.
Namun, liberalisasi pasar keuangan dan modal di Asia, termasuk Indonesia, seringkali terjadi bukan karena kebutuhan ekonomi domestik yang murni, melainkan di bawah tekanan internasional yang masif, khususnya dari Washington Consensus. Ketergantungan pada FDI dan rantai produksi/distribusi global yang terliberalisasi ini justru menciptakan kerentanan struktural yang tinggi, membuat ekonomi lokal rentan terhadap guncangan eksternal dan pemutusan rantai pasok sepihak oleh negara-negara besar.
Deregulasi Pasca-Krisis dan Hegemoni Washington Consensus
Titik balik implementasi Neoliberalisme di Indonesia adalah Krisis Finansial Asia 1997, atau yang dikenal sebagai Krismon. Deregulasi finansial yang diterapkan sebelumnya terbukti menciptakan kerentanan yang parah. Dalam situasi terpuruk, Indonesia dipaksa menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF, yang mewajibkan penerapan paket kebijakan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi secara agresif, mengubah total arah kebijakan ekonomi negara.
Mekanisme reformasi ekonomi struktural seringkali terhambat atau gagal karena adanya kekuatan lama dan kelompok kepentingan (oportunis politik) yang posisinya terancam oleh perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Neoliberal, meskipun didasarkan pada logika efisiensi pasar, beroperasi dalam konteks politik domestik yang kompleks yang dapat menghambat hasil ideal yang dijanjikan.
Neoliberalisme dan Eksploitasi Sumber Daya Lokal
Doktrin Neoliberalisme secara struktural memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas pertimbangan sosial, kedaulatan nasional, dan pelestarian lingkungan hidup. Konsekuensi dari doktrin ini sangat terasa di sektor pertanian dan pangan. Tekanan untuk mencabut peraturan yang menghalangi keuntungan swasta mencakup kebebasan bagi swasta untuk mengakuisisi tanah petani seluas-luasnya.
Dampak dari kebijakan ini sangat mendalam, karena sektor pertanian di Indonesia secara kultural dan fungsional adalah pelindung sah bagi lingkungan hidup, sejarah, dan kebudayaan. Penghancuran kehidupan petani melalui deregulasi dan liberalisasi tanah adalah sama dengan menghancurkan ekosistem dan peradaban lokal. Lebih jauh lagi, keterbukaan perdagangan yang didorong Neoliberalisme melalui kesepakatan seperti WTO/SPS menimbulkan tekanan bagi negara berkembang untuk tidak melarang impor produk makanan yang mengandung GMO, mengorbankan perlindungan konsumen demi keuntungan pasar bebas. Hal ini mengikis kedaulatan negara dalam melindungi basis produksi pangan dan kesehatan masyarakat domestik.
Perbedaan tajam antara klaim keberhasilan makroekonomi dan realitas kesejahteraan mikroekonomi adalah ciri khas kebijakan struktural ini. Argumen pemerintah mengenai “fundamental ekonomi yang kuat” (seperti yang diyakini Bank Indonesia pada 1997) dapat secara berbahaya mengabaikan akumulasi ketidakadilan sosial dan kerentanan sistemik yang mendasari, sampai akhirnya krisis meletus. Hal ini menggarisbawahi perlunya metrik yang lebih sensitif terhadap kondisi riil masyarakat.
Dampak Ekonomi Makro: Pertumbuhan Dengan Imbalan Ketimpangan
Kualitas Pertumbuhan dan Upah Riil
Meskipun pasca-krisis 1997-1998, Indonesia menunjukkan perbaikan indikator makroekonomi, seperti penguatan kurs dan inflasi yang terkendali, masyarakat secara luas merasakan adanya perbedaan kualitas pertumbuhan ekonomi. Para ekonom kritis menyebut fenomena ini sebagai kondisi di mana makroekonomi membaik, tetapi banyak aspek mikroekonomi yang memburuk.
Indikator makro yang tetap stagnan dan amat buruk di tengah optimisme pertumbuhan adalah tingkat pengangguran, setengah pengangguran, dan khususnya, upah riil para pekerja. Stagnasi upah riil menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagian besar tidak didistribusikan secara merata kepada kelas pekerja. Kondisi ini berkorelasi kuat dengan tingginya tingkat kemiskinan, menunjukkan bahwa pertumbuhan yang dicapai di bawah paradigma Neoliberal adalah pertumbuhan yang tidak inklusif dan tidak berkualitas.
Bukti Empiris Peningkatan Ketimpangan Struktural
Implementasi kebijakan Neoliberal di Indonesia telah secara sistematis menciptakan dan memperdalam kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Data menunjukkan peningkatan ketimpangan yang tajam, yang membuktikan kegagalan struktural dari teori trickle-down effect yang dijanjikan oleh pasar bebas.
Table 1. Indikator Ketimpangan di Indonesia pada Masa Implementasi Neoliberal
| Indikator Kesejahteraan | Data Kunci | Periode/Tahun Referensi | Keterangan Analisis |
| Koefisien Gini | Naik dari 0,33 menjadi 0,41 | 2005 – 2011 | Peningkatan ketimpangan pendapatan yang tajam di tengah klaim pertumbuhan. |
| Konsentrasi Kekayaan | Kekayaan 40 orang terkaya setara dengan 60% populasi (140 juta orang) | Sekitar 2012 | Konsentrasi modal yang ekstrem, menunjukkan kegagalan trickle-down effect. |
| Stagnasi Pekerja | Tingkat pengangguran dan upah riil para pekerja tetap buruk | Pasca 1997-1998 | Pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh kelas pekerja dan rentan. |
Kenaikan Koefisien Gini dan konsentrasi kekayaan yang ekstrem (di mana kekayaan 40 orang terkaya setara dengan kekayaan 140 juta penduduk) menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung dinikmati oleh kelompok elit. Paradigma Neoliberal, yang fokus pada mekanisme pasar bebas, secara struktural gagal mencapai distribusi kekayaan yang adil, dan sebaliknya, justru memfasilitasi akumulasi kekayaan pada kelompok atas.
Ancaman Ekonomi Digital dan Kesenjangan Baru
Transformasi ekonomi digital yang pesat membawa sumber kekuatan baru bagi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, Revolusi Digital, yang berkembang dalam kerangka Neoliberal, juga menimbulkan tantangan serius terhadap kesejahteraan rakyat.
Fenomena ini melahirkan kesenjangan digital yang dapat memperburuk ketidaksetaraan upah dan kekayaan. Lebih lanjut, munculnya Gig Economy—model pekerjaan sementara, mandiri, dan fleksibel melalui platform digital —memberikan fleksibilitas bagi pekerja , tetapi juga menimbulkan kerangka kerja di mana hak-hak pekerja seringkali tidak terlindungi secara memadai. Dalam ekonomi gig, pekerja sering diperlakukan sebagai “mitra,” bukan karyawan, sehingga jaminan perlindungan hukum dan sosial (seperti asuransi dan pensiun) menjadi kabur atau hilang.
Kondisi ini merupakan konvergensi yang berbahaya antara filosofi Neoliberal yang mendamba pasar tenaga kerja yang fleksibel (deregulasi tenaga kerja) dan inovasi digital. Neoliberalisme mempercepat prekariat kerja dan mempersulit perlindungan hukum, sebuah ironi di mana “kebebasan pasar” justru mengikis jaminan ekonomi individu, menambah ketidakamanan dalam kehidupan masyarakat.
Erosi Kesejahteraan Sosial: Komodifikasi Layanan Publik
Dampak Austerity pada Layanan Publik Esensial
Prinsip austerity (pengurangan biaya) yang merupakan kredo utama Neoliberalisme secara langsung menargetkan sektor-sektor publik esensial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin:
- Sektor Kesehatan: Agenda reformasi Neoliberal menuntut pemotongan biaya untuk efisiensi, desentralisasi, dan penetapan layanan kesehatan sebagai barang swasta yang dijual (bukan barang publik yang dibayar pajak). Di negara-negara yang menerapkan privatisasi, hal ini meningkatkan biaya bagi individu dan keluarga serta menciptakan ketidaksetaraan kualitas layanan antara kelompok kaya dan miskin. Lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia mensyaratkan reformasi ideologis Neoliberal, termasuk pemotongan pengeluaran sosial, khususnya di sektor kesehatan, sebagai imbalan pinjaman di negara-negara berkembang.
- Sektor Pendidikan: Kebijakan ini mendorong komersialisasi pendidikan tinggi (sering disebut McDonaldization) yang berorientasi semata-mata pada pengerukan keuntungan. Akibatnya, perguruan tinggi didorong untuk mencari dana masyarakat, bahkan dengan membuka jalur khusus yang meningkatkan biaya operasional, sehingga akses ke pendidikan berkualitas menjadi semakin sulit bagi masyarakat kurang mampu.
Studi Kasus Privatisasi Air Bersih: Beban Biaya pada Masyarakat Miskin
Sektor air bersih menjadi ilustrasi nyata bagaimana Neoliberalisme menggunakan layanan publik sebagai mekanisme untuk mengekstrak nilai dari kelompok termiskin, seringkali disebut sebagai redistribusi terbalik.
Di Indonesia, cakupan layanan air bersih bagi masyarakat masih sangat rendah (40% di perkotaan dan hanya 8% di pedesaan). Analisis empiris menunjukkan ketidakadilan harga yang mencolok. Studi kasus di Kota Semarang mengungkapkan bahwa masyarakat miskin harus membayar air bersih hingga 10 kali lipat dari tarif yang dikenakan kepada rumah tangga kelas mewah. Bahkan, penelitian Bank Dunia di beberapa kawasan miskin Indonesia menemukan bahwa masyarakat miskin dapat membayar hingga 30 kali lipat lebih mahal daripada masyarakat kaya untuk mendapatkan layanan air bersih.
Kondisi ini diperparah oleh kerangka hukum pasca-Neoliberal. Undang-undang mengenai Sumber Daya Air (seperti UU No 7/2004) dikritik karena tidak memberikan jaminan yang memadai kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan air bersih, tidak adanya mekanisme kontrol harga yang jelas, dan cenderung membiarkan penguasaan sumber daya air oleh swasta yang mengikuti logika keuntungan, bukan kepentingan sosial.
Erosi Solidaritas Sosial dan Keberlanjutan Budaya
Dampak Neoliberalisme melampaui metrik ekonomi; ia merusak modal sosial dan struktur budaya. Globalisasi yang didorong oleh Neoliberalisme secara sistematis telah melemahkan norma-norma berbagi, menghancurkan ikatan sosial, dan mengikis sistem bantuan sosial tradisional.
Hal ini kontras dengan nilai-nilai kolektif yang mendalam dalam masyarakat Indonesia, seperti gotong royong. Dalam banyak komunitas, ritual kolektif seperti memasak bersama (rewangan di Jawa, mebat di Bali, bakureh atau makan bajamba di Minangkabau) adalah fondasi untuk membangun kebersamaan, solidaritas, dan bahkan resolusi konflik.
Namun, dorongan efisiensi pasar, seperti hadirnya jasa catering dalam pesta pernikahan (baralek), secara bertahap menggantikan tradisi memasak komunal. Meskipun terjadi peningkatan efisiensi, hal ini mengubah jenis solidaritas masyarakat dari solidaritas mekanik (berbasis kekeluargaan dan keakraban) menjadi solidaritas organik (berbasis saling ketergantungan fungsional). Konsekuensinya, terjadi penurunan interaksi dan keakraban yang erat antar-anggota masyarakat, menggerus fungsi antropologis dari ritual-ritual kolektif tersebut.
Krisis Dan Kegagalan Sistemik Akibat Deregulasi
Deregulasi Finansial dan Krisis Asia 1997
Krisis Finansial Asia 1997 (Krismon) adalah bukti nyata batas-batas Neoliberalisme. Krisis yang menimbulkan kepanikan ekonomi dunia ini disebabkan oleh deregulasi pasar modal dan keuangan yang diterapkan di kawasan tersebut, seringkali di bawah paksaan Washington Consensus. Krisis ini menelanjangi kerentanan yang diciptakan oleh liberalisasi finansial yang tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat. Meskipun solusi jangka pendek (rekapitalisasi perbankan) diterapkan, perubahan struktural yang fundamental untuk mengendalikan perilaku pengambilan risiko berlebih tetap sulit diwujudkan.
Krisis Finansial Global 2008: Manifestasi Neoliberalisme di Negara Maju
Krisis Keuangan Global (GFC) 2008 di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa krisis bukan kegagalan eksternal, melainkan produk internal dari Neoliberalisme itu sendiri. Deregulasi finansial memungkinkan lembaga keuangan menyalurkan kekayaan ke investasi spekulatif yang tidak diatur, seperti pasar hipotek subprime, yang memicu keruntuhan Lehman Brothers dan pasar global.
Analisis menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan yang ekstrem—sebagai hasil langsung dari kebijakan Neoliberal—memainkan peran kunci. Untuk mengimbangi stagnasi upah riil dan mempertahankan permintaan konsumen, sistem didorong oleh peningkatan kredit dan utang rumah tangga. Dengan demikian, Neoliberalisme menciptakan tatanan ekonomi yang secara inheren tidak stabil; deregulasi mendorong risiko berlebih, sementara ketimpangan menciptakan kebutuhan akan utang spekulatif, menjamin bahwa krisis adalah fenomena siklus yang menghancurkan kesejahteraan.
Dampak terhadap Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan Iklim
Neoliberalisme juga menciptakan ketidakadilan struktural dalam isu lingkungan global. Krisis iklim menuntut upaya adaptasi dan mitigasi yang masif, terutama dari negara-negara berkembang (Non-Annex I) yang paling rentan terhadap dampaknya.
Secara internasional, tanggung jawab ini diatur oleh prinsip Common But Differentiated Responsibilities (CBDR). Prinsip ini mewajibkan negara-negara maju (Annex II), yang memiliki kontribusi historis dan kemampuan finansial lebih besar, untuk memimpin upaya mitigasi dan menyediakan dukungan finansial serta teknologi kepada negara berkembang.
Table 2. Kontradiksi Kewajiban Iklim (CBDR) dan Realisasi Pendanaan Neoliberal
| Kategori Negara UNFCCC | Tanggung Jawab (Prinsip CBDR) | Realisasi Pendanaan Iklim (Praktik Neoliberal) | Implikasi Keadilan |
| Annex II (Negara Maju) | Menyediakan sumber daya finansial/teknologi untuk adaptasi dan mitigasi. | Pemenuhan janji $100 M terlambat (tercapai 2022). Sekitar 69% dana publik disalurkan sebagai pinjaman, bukan hibah. | Mentransfer beban utang dan risiko finansial kepada negara penerima, melanggar prinsip ekuitas. |
| Non-Annex I (Negara Berkembang) | Menerima dukungan untuk mitigasi/adaptasi, memprioritaskan pembangunan berkelanjutan. | Harus mengatasi masalah transfer teknologi hijau yang terhambat oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). | Dipaksa mengambil utang untuk mengatasi kerusakan yang bukan merupakan tanggung jawab emisi historis mereka. |
Analisis menunjukkan bahwa negara maju gagal memenuhi janji pendanaan iklim sebesar $100 miliar tepat waktu. Lebih buruk lagi, mayoritas pendanaan (69% pada 2022) disalurkan dalam bentuk pinjaman, bukan hibah, yang justru menambah beban utang negara berkembang.
Ini adalah perwujudan dari ketidakadilan iklim yang diwariskan oleh Neoliberalisme. Kebijakan ini, yang memprioritaskan pertumbuhan tanpa batas dan mengabaikan regulasi lingkungan , memaksa negara-negara miskin untuk mengambil utang guna mengatasi kerugian dan kerusakan (Loss and Damage) yang secara historis disebabkan oleh emisi negara-negara industri maju. Sementara pembentukan Loss and Damage Fund di COP28 merupakan langkah maju, dana ini dikritik karena sifat kontribusinya yang sukarela dan tidak mengaitkan dengan liabilitas atau kompensasi wajib, memungkinkan negara-negara kaya mengklaim telah mengatasi isu tersebut tanpa komitmen finansial yang mengikat.
Sintesis Dan Penutup: Dari Kritik Menuju Jalan Kesejahteraan Sejati
Kegagalan Pasar dalam Membangun Solidaritas Sosial dan Keadilan Distributif
Laporan ini menyimpulkan bahwa Neoliberalisme, meskipun dianut sebagai ideologi modern yang rasional, secara struktural dan sistematis telah menciptakan ketidaksetaraan yang ekstrem dan kerentanan ekonomi di Indonesia dan secara global. Dengan menempatkan supremasi pasar di atas moralitas sosial, Neoliberalisme berfungsi sebagai mekanisme restorasi kepentingan kelas yang berkuasa, alih-alih sebagai retorika utopis egalitarian yang dijanjikan.
Kegagalan ini tidak hanya tercermin pada melonjaknya Koefisien Gini dan stagnasi upah riil , tetapi juga dalam komodifikasi layanan publik esensial (seperti air bersih), yang menghasilkan mekanisme redistribusi terbalik di mana kelompok termiskin membayar biaya termahal untuk keuntungan swasta. Lebih jauh, Neoliberalisme mengikis modal sosial dan fungsi antropologis tradisi kolektif (seperti gotong royong dan ritual komunal) yang merupakan benteng pertahanan masyarakat terhadap fragmentasi sosial.
Ketika kegagalan sistemik ini semakin jelas, semakin kuat pula basis bagi munculnya gerakan-gerakan massa yang menuntut egalitarianisme politik dan jaminan ekonomi yang lebih besar. Jalan keluar dari hegemoni ini memerlukan pergeseran paradigma dari model pasar bebas absolut menuju peran negara yang lebih protektif dan intervensif (sebagaimana dianjurkan oleh pendekatan Heterodox Interventionist Liberals atau HIL) untuk memperbaiki kegagalan pasar.
Mendesain Ulang Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Inklusif
Untuk membangun kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, diperlukan perubahan fokus kebijakan secara mendasar:
- Prioritas Kualitas Pertumbuhan: Kebijakan ekonomi harus melampaui metrik Produk Domestik Bruto (PDB) murni dan beralih ke pengukuran kualitas pertumbuhan, yang sensitif terhadap upah riil, tingkat pengangguran, dan distribusi pendapatan.
- Jaminan Layanan Esensial: Negara harus menolak privatisasi dan austerity pada sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Layanan-layanan ini harus diperkuat sebagai barang publik untuk menjamin akses yang adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
- Memperkuat Modal Sosial: Mengembangkan kebijakan yang mengakui dan mendukung fungsi ekonomi dan sosial dari institusi adat dan kearifan lokal (seperti gotong royong dan sistem pangan tradisional), memandang mereka sebagai bagian penting dari ketahanan sosial, bukan sebagai hambatan bagi efisiensi pasar.
Alternatif Paradigma: Menuju Keadilan Distributif
Solusi terhadap destruksi kesejahteraan yang diakibatkan Neoliberalisme harus bersifat multidisiplin.
Secara ekonomi, perspektif Ekonomi Islam, dengan mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat, wakaf, dan infak, menawarkan alternatif yang kuat dalam mengatasi ketimpangan distributif. Sistem ini secara tegas melarang eksploitasi (riba) dan dapat mengurangi beban utang masyarakat miskin. Pengelolaan zakat yang terorganisir memiliki potensi untuk menyumbang hingga 3% dari PDB, sebuah potensi fiskal yang signifikan untuk mengatasi ketimpangan.
Secara politik dan sosial, kritik terhadap Neoliberalisme harus diangkat melalui lensa Ilmu Sosial Humaniora (ISH), menuntut kembali kedaulatan moral dan sosial yang telah didesak oleh supremasi ekonomi. Upaya kolektif dan pembentukan kembali institusi yang berpihak pada keadilan distributif harus diperkuat, mengambil pelajaran dari model-model kearifan lokal yang sukses dalam mengelola konflik komunal dan membangun perdamaian melalui solidaritas, seperti praktik Muakhi di Lampung. Peningkatan literasi digital dan penguatan perlindungan hukum bagi pekerja gig economy juga krusial untuk mencegah revolusi digital semakin mempercepat prekariat kerja.
Upaya untuk mencapai kesejahteraan sejati menuntut perlawanan kolektif, bukan hanya terhadap kebijakan, tetapi terhadap fondasi filosofis Neoliberalisme yang merasionalisasi ketidakadilan.