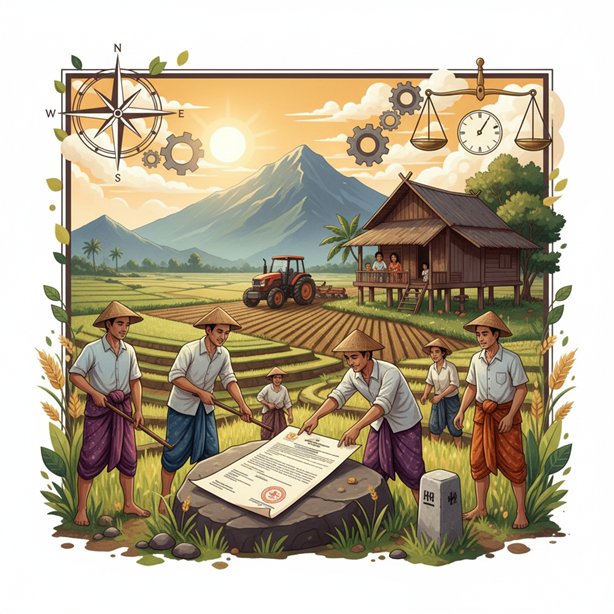Pengelolaan pertanahan merupakan isu krusial bagi negara berkembang di Asia Tenggara. Tanah adalah modal dasar kehidupan manusia, yang memiliki fungsi ganda: fungsi produktif (misalnya untuk pertanian atau pembangunan) dan fungsi non-produktif (seperti tempat tinggal atau konservasi). Keterbatasan luas tanah yang dihadapi oleh populasi yang terus bertumbuh pesat menjadi sumber konflik kepentingan yang tak terhindarkan, terutama dalam konteks pembangunan nasional yang membutuhkan alokasi lahan yang besar. Tulisan ini menyajikan analisis komparatif mendalam mengenai sistem pengelolaan pertanahan di dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada kerangka hukum dasar, rezim kepemilikan, administrasi, dan isu-isu konflik agraria kontemporer.
Latar Belakang dan Konteks Historis
Baik Indonesia maupun Malaysia mewarisi kompleksitas hukum agraria dari masa kolonial. Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, sementara Malaysia (khususnya Semenanjung) di bawah pengaruh Inggris. Pengaruh Barat ini menciptakan dualisme hukum tanah yang kontradiktif antara hukum barat (tertulis) dan hukum tradisional (hukum adat).
Indonesia mengambil langkah tegas untuk mengakhiri dualisme ini pada tahun 1960 melalui unifikasi hukum pertanahan. Sementara itu, Malaysia mengintegrasikan sistem tenure Inggris, yang kemudian disistematisasi dalam kerangka hukum nasionalnya, NLC 1965.
Pilar Hukum Dasar: UUPA 1960 vs. NLC 1965
Indonesia: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960
UUPA 1960 menandai berakhirnya pemberlakuan undang-undang tanah kolonial Belanda dan merupakan landasan bagi pengembangan hukum tanah nasional yang tunggal dan didasarkan pada hukum adat Indonesia.
Filosofi inti UUPA didasarkan pada prinsip Hak Menguasai Negara (HMN), yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. HMN memberikan otoritas tertinggi kepada negara untuk menguasai tanah, air, dan ruang udara, namun penguasaan ini bukan dalam bentuk kepemilikan mutlak, melainkan sebagai mandat untuk mengatur dan mengelola demi kemakmuran rakyat. UUPA juga mengakui adanya hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial, serta hak masyarakat hukum adat.
Malaysia: National Land Code (NLC) 1965
NLC 1965 diperkenalkan dengan tujuan utama untuk menstandardisasi undang-undang tanah yang berbeda-beda yang digunakan di berbagai negara bagian di Semenanjung Malaysia (sebelumnya terdapat Land Code Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, dan Ordinance Penang/Malaka). NLC mencakup konsolidasi hukum yang berkaitan dengan tanah dan tenure tanah, pendaftaran hak atas tanah, transaksi terkait, dan pemungutan pendapatan.
NLC menguraikan hak dan kekuasaan State Authority (Pihak Berkuasa Negeri) terkait administrasi dan disposisi tanah. Kode ini mendefinisikan dan mengklasifikasikan tanah menjadi tanah dialienasi, tanah tambang, tanah cadangan, dan tanah negara. NLC berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengimplementasikan sistem pendaftaran hak milik, yang dikenal sebagai Sistem Torrens.
Perbedaan Fondasi Filosofis dan Implikasinya terhadap Kontrol Negara
Terdapat perbedaan mendasar dalam fondasi filosofis kedua sistem yang memiliki implikasi signifikan terhadap kontrol negara dan kepastian hukum. UUPA 1960 Indonesia berakar pada konsep HMN dan Hukum Adat, memungkinkan negara untuk terus-menerus mendefinisikan ulang dan mengintervensi hak atas tanah demi kepentingan publik yang lebih luas. Otoritas penguasaan negara ini diejawantahkan melalui penetapan jangka waktu bagi hak-hak tertentu seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), serta melalui mekanisme penertiban tanah terlantar. Hal ini menjadikan sistem Indonesia secara inheren lebih fleksibel untuk kebijakan reforma agraria dan kontrol pemanfaatan lahan.
Sebaliknya, NLC 1965 Malaysia berakar pada sistem tenure Torrens. Meskipun NLC memberikan kekuasaan besar kepada State Authority untuk disposisi awal tanah negara, setelah hak itu didaftarkan (melalui Sistem Torrens), prinsip indefeasibility of title memberikan kepastian hukum yang sangat tinggi kepada pemegang hak, membatasi intervensi negara pasca-pendaftaran. Oleh karena itu, sistem Malaysia cenderung menawarkan stabilitas hukum yang lebih tinggi bagi pemegang sertifikat, sementara sistem Indonesia, yang didorong oleh prinsip HMN, lebih berfokus pada fungsi sosial tanah, sehingga kepastiannya lebih dinamis dan bersyarat.
Rezim Hak Atas Tanah (Land Tenure System)
Sistem kepemilikan tanah di kedua negara menunjukkan struktur yang mirip dalam membedakan antara kepemilikan penuh dan hak guna jangka waktu, namun perinciannya berbeda, terutama terkait akses bagi entitas asing.
Jenis Hak Atas Tanah di Indonesia
Berdasarkan UUPA, Indonesia mengenal beberapa jenis hak atas tanah utama yang menentukan durasi, transferabilitas, dan kegiatan yang diizinkan.
- Hak Milik (HM): Merupakan bentuk kepemilikan penuh (freehold) yang paling aman. Hak ini hanya dapat dipegang oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau entitas Indonesia yang secara spesifik diizinkan.
- Hak Guna Usaha (HGU): Hak untuk melaksanakan kegiatan pertanian, perkebunan, atau konsesi berskala besar. Hak ini biasanya dipegang oleh badan hukum (seperti PT PMA untuk partisipasi asing). Jangka waktu awal adalah hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang, dengan total durasi hingga 60 tahun (tergantung regulasi).
- Hak Guna Bangunan (HGB): Hak untuk membangun dan memiliki struktur atau bangunan di atas tanah negara atau di atas Hak Milik orang lain. HGB adalah struktur standar untuk menjalankan usaha komersial skala besar, seperti resort, hotel, atau pabrik. Jangka waktu awal 30 tahun, dan dapat diperpanjang hingga total 80 tahun.
- Hak Pakai (HP): Hak untuk menggunakan properti untuk tujuan yang ditentukan. Hak ini sering tersedia untuk orang asing dengan jangka waktu tertentu (awal 25 tahun, diperpanjang total hingga 50 tahun).
- Hak Sewa (Leasehold Kontraktual): Ini adalah sewa murni berbasis kontrak untuk jangka waktu tetap, umumnya 20 hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang. Hak Sewa merupakan cara yang paling fleksibel dan cepat bagi investor asing untuk mengakses properti untuk proyek jangka pendek atau proyek percontohan, karena menghindari penundaan dalam pembentukan perusahaan (PT PMA), meskipun menawarkan permanensi yang lebih rendah dibandingkan HGB atau HGU.
Jenis Hak Atas Tanah di Malaysia (National Land Code)
Di Malaysia, hak atas tanah dibagi berdasarkan klasifikasi tanah (tanah dialienasi, tanah negara, dsb.) yang ditentukan oleh NLC.
- Freehold Title (Hakmilik): Kepemilikan penuh yang tidak terbatas (perpetuity), analog dengan Hak Milik di Indonesia, tunduk pada syarat dan ketentuan penahanan tanah yang ditetapkan oleh State Authority saat pengasingan awal.
- Leasehold Title: Hak sewa jangka panjang, yang umum digunakan untuk pengembangan komersial dan residensial, biasanya diberikan untuk jangka waktu 99 tahun.
- Temporary Occupation License (TOL): Izin pendudukan sementara yang dikeluarkan untuk penggunaan tanah negara yang bersifat tidak permanen, biasanya diperbarui setiap tahun.
Perbandingan Hak Komersial dan Investasi
Sistem Indonesia menggunakan Hak Guna Waktu (HGU dan HGB) sebagai instrumen utama untuk investasi skala besar. Durasi hak ini telah ditetapkan dan tunduk pada persyaratan kinerja dan pemanfaatan yang ketat. Apabila tanah HGU atau HGB tidak dimanfaatkan sesuai tujuannya, tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar dan ditertibkan kembali oleh negara. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memiliki mekanisme kebijakan yang kuat untuk mencegah spekulasi lahan dan memastikan pemanfaatan tanah sesuai tujuan ekonomi nasional.
Sebaliknya, Malaysia, meskipun juga menggunakan Leasehold jangka panjang, kontrol negara pasca-alienasi lebih terfokus pada kepatuhan terhadap kondisi penahanan yang ditetapkan dalam Akta Hakmilik, sesuai dengan prinsip Sistem Torrens.
| Kategori Hak | Indonesia (UUPA) | Malaysia (NLC) | Durasi Maksimum (Umum) | Kepastian Hukum | Akses Asing |
| Kepemilikan Penuh | Hak Milik (Freehold) | Freehold Title (Hakmilik) | Tidak terbatas/Perpetuity | Sangat Tinggi | Hanya WNI/Entitas Malaysia |
| Hak Membangun Skala Besar | Hak Guna Bangunan (HGB) | Leasehold (Long-Term Alienation) | Hingga 80 tahun total | Tinggi (berbasis sertifikat) | Tidak Langsung (melalui PT PMA) |
| Hak Pertanian Skala Besar | Hak Guna Usaha (HGU) | Leasehold (Agricultural/Plantation) | Hingga 60 tahun total | Tinggi (berbasis sertifikat) | Tidak Langsung (melalui PT PMA) |
| Hak Sewa Murni | Hak Sewa (Leasehold Kontraktual) | Leasehold (Contractual) | Umumnya 25–30 tahun | Berbasis Kontrak | Langsung |
Administrasi dan Jaminan Kepastian Hukum (Pendaftaran Tanah)
Kepastian hukum atas tanah bergantung pada sistem pendaftaran yang dianut suatu negara. Indonesia dan Malaysia menggunakan sistem yang berbeda secara fundamental.
Perbandingan Sistem Registrasi Inti
Malaysia: Sistem Torrens (Title Registration)
Malaysia telah mengadopsi dan menerapkan Sistem Torrens, yang merupakan sistem pendaftaran hak milik (title registration). Sistem ini beroperasi atas dasar NLC 1965. Keunggulan Torrens terletak pada prinsip indefeasibility of title, di mana sertifikat atau Hak milik yang didaftarkan dianggap hampir absolut dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi bagi pemegang hak. Dengan sistem ini, pembeli dapat mengandalkan keakuratan catatan yang terdaftar, tanpa perlu menelusuri riwayat kepemilikan sebelumnya.
Indonesia: Sistem Akta (Deeds Registration) dan Reformasi
Indonesia, sebaliknya, secara tradisional menerapkan sistem pendaftaran akta (deeds registration) yang diatur oleh UUPA 1960. Mandat Pasal 19 UUPA mewajibkan negara untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia secara berkelanjutan. Secara inheren, sistem pendaftaran akta bergantung pada keabsahan dokumen historis, yang secara historis kurang memberikan jaminan kepastian hukum absolut dibandingkan Torrens.
Meskipun kepastian hukum telah diperkuat melalui sertifikasi, di Indonesia masih dimungkinkan adanya klaim terhadap sertifikat dalam jangka waktu tertentu, yaitu maksimum lima tahun setelah pendaftaran.
Reformasi dan Tantangan Pendaftaran Tanah
Untuk memenuhi mandat UUPA, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program percepatan, yang terbaru dan paling masif adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL adalah kelanjutan dari program-program administrasi pertanahan sebelumnya (seperti PRONA dan ILAP) yang bertujuan mendaftarkan bidang tanah secara lengkap dan sistematis. Tujuan logis dari PTSL adalah menciptakan iklim investasi yang baik dengan menyediakan jaminan kepastian hukum, lokasi, dan batas bidang tanah yang akurat.
Namun, implementasi PTSL menghadapi tantangan, termasuk masalah sinkronisasi regulasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.
Perbandingan antara sistem Torrens Malaysia dan PTSL Indonesia memperlihatkan adanya pertukaran yang mendasar antara kecepatan dan kualitas jaminan hukum. Malaysia memilih rigiditas Torrens untuk memastikan jaminan kepemilikan yang hampir absolut. Sementara itu, Indonesia melalui PTSL, memprioritaskan kecepatan dan cakupan luas pendaftaran (untuk memenuhi mandat UUPA). Kecepatan ini, sayangnya, sering kali mengorbankan ketelitian dalam verifikasi hak-hak tenurial, terutama hak komunal, sehingga menciptakan risiko sengketa hukum pasca-sertifikasi yang lebih tinggi.
Selain itu, Indonesia juga sedang bergerak menuju modernisasi melalui digitalisasi administrasi pertanahan, ditandai dengan peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data.
Tata Kelola, Desentralisasi, dan Pengadaan Tanah
Struktur tata kelola dan distribusi kewenangan dalam urusan pertanahan merupakan pembeda signifikan antara kedua negara.
Struktur Kewenangan Pertanahan dan Desentralisasi
Malaysia (Model Desentralisasi Asimetris Kuat)
Sistem Malaysia menunjukkan distribusi kedaulatan yang khas di mana otoritas substansial dalam pengelolaan dan disposisi tanah diberikan dari pemerintah federal kepada negara-negara bagian (State Authority). Meskipun NLC 1965 merupakan undang-undang federal yang seragam di Semenanjung, implementasi operasional, penentuan kondisi penahanan, tarif, dan izin tanah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah negara bagian. Oleh karena itu, pengelolaan tanah di Malaysia dapat diklasifikasikan sebagai model desentralisasi asimetris yang kuat, di mana negara bagian memiliki otonomi yang signifikan dalam urusan agraria.
Indonesia (Sentralistik Terkoordinasi)
Indonesia mengelola kewenangan pertanahan secara terpusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Indonesia menerapkan model desentralisasi simetris (umum) dan asimetris (untuk wilayah otonomi khusus). Perbedaan krusial dengan Malaysia terletak pada sifat otoritas. Malaysia mendistribusikan kedaulatan kepada negara bagian dalam urusan tanah, sedangkan Indonesia cenderung hanya mendelegasikan otoritas dari pemerintah pusat (BPN) kepada pemerintah daerah, menjaga kontrol kebijakan utama secara nasional.
Implikasi dari perbedaan struktur ini sangat penting bagi investasi dan kebijakan. Di Malaysia, keputusan strategis terkait disposisi dan pengadaan tanah sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat negara bagian. Sementara di Indonesia, meskipun ada administrasi daerah, kebijakan besar (seperti PTSL atau penetapan HGU/HGB) dikendalikan secara sentral, sehingga tantangan birokrasi lebih terpusat di antara BPN dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Eminent Domain)
Kedua negara, dalam rangka melaksanakan pembangunan, selalu berkaitan dan memerlukan tanah. Seringkali, program pembangunan berbenturan dengan tanah yang sudah ada alas haknya atau dikuasai oleh orang atau badan hukum. Kedua negara memiliki kerangka legislasi yang mengatur pengambilalihan tanah pribadi untuk kepentingan umum (eminent domain).
Namun, penelitian komparatif menunjukkan adanya penyimpangan dalam penafsiran dan penggunaan istilah kepentingan umum di kedua negara. Istilah ini terkadang digunakan oleh pemerintah sebagai dalih untuk mendapatkan tanah, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi dan konflik berbeda di masyarakat terkait penyediaan lahan.
Penertiban Tanah Terlantar (Idle Land)
Kedua sistem hukum mengatur penertiban tanah terlantar, meskipun regulasinya berbeda. Di Indonesia, pengaturan tanah terlantar didasarkan pada konsep HMN yang mewajibkan pemegang hak untuk menggunakan tanah sesuai fungsi sosialnya. Hukum positif Indonesia yang mengaturnya mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Di Malaysia, tanah terlantar diatur dalam National Land Code 1965.
Perbedaan mendasar dalam konsepsi hukum tanah (HMN vs. Torrens) menciptakan perbedaan substansial dalam: (1) definisi dan kriteria tanah terlantar; (2) pihak yang berwenang melakukan penertiban; dan (3) tahapan penetapan dan pendayagunaan kembali tanah terlantar. Kontrol negara atas tanah terlantar di Indonesia cenderung lebih ketat karena prinsip HMN yang menuntut pemanfaatan optimal.
Isu Kritis dan Konflik Agraria Kontemporer
Meskipun memiliki kerangka hukum yang berbeda, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan berat terkait konflik agraria, terutama yang melibatkan hak-hak masyarakat hukum adat.
Konflik Hak Masyarakat Adat (Customary Rights)
Indonesia (Hak Ulayat)
Hukum tanah Indonesia secara filosofis menganut hukum adat, di mana tanah yang tidak dikuasai oleh negara pada hakikatnya adalah tanah masyarakat hukum adat (Hak Ulayat). Pengakuan Hak Ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA dan diperkuat oleh UUD 1945, sepanjang hak tersebut benar-benar ada dan tidak bertentangan dengan hukum negara yang lebih tinggi.
Namun, dalam praktiknya, hakikat tanah masyarakat hukum adat sering mengalami reduksi. Regulasi pemerintah cenderung menonjolkan aspek legalitas formal, mengharuskan status tanah adat disahkan melalui peraturan daerah. Proses ini sangat rentan terhadap kepentingan politik kepala daerah, yang dapat merugikan masyarakat adat dan menyebabkan kemiskinan karena kehilangan akses ke lahan kelolaan.
Konflik agraria sering memuncak di daerah Hak Guna Usaha (HGU), khususnya perkebunan kelapa sawit, di mana masyarakat adat merasa sebagai pemilik sah atas tanah tersebut. Selain itu, program PTSL yang masif, meskipun bertujuan memberikan kepastian hukum, secara tidak langsung mengabaikan hak-hak tenurial komunal. Implementasi PTSL berimplikasi pada penghancuran hak adat yang melekat dan mengubahnya menjadi hak individu formal, sehingga meningkatkan potensi sengketa.
Malaysia (Native Customary Rights – NCR)
Di Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah), hak adat dikenal sebagai Native Customary Rights (NCR). NCR dilindungi di bawah Konstitusi Federal Malaysia, yang menjamin posisi khusus penduduk asli Sabah dan Sarawak.
Meskipun dilindungi, konflik terjadi akibat sengketa definisi dan penentuan batas. Secara historis, NCR di Sarawak diakui jika tanah tersebut telah dibuka atau diolah sebelum 1 Januari 1958. Namun, masyarakat adat berpandangan bahwa NCR mencakup wilayah komunal yang lebih luas, seperti teritori komunal (pemakai menua) dan hutan desa (pulau). Pemerintah negara bagian, sementara itu, cenderung mengklasifikasikan tanah yang belum diolah atau hutan perawan sebagai State Land (tanah negara).
Sengketa ini memicu krisis, karena banyak konsesi logging dan perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan kepada investor oleh pemerintah negara bagian melanggar wilayah NCR yang belum dipetakan dan disertifikasi. Diperkirakan 20% tanah negara di Sarawak diklasifikasikan sebagai NCR, tetapi hanya 2% yang telah disurvei dan memiliki hakmilik resmi.
Konvergensi Konflik Agraria
Meskipun menggunakan kerangka hukum yang berlawanan (HMN/Adat di Indonesia vs. Torrens/NLC di Malaysia), kedua negara menghadapi intensitas konflik agraria yang tinggi.
Perbedaan sistem hukum hanya mengubah mekanisme konflik. Di Indonesia, konflik utamanya bersifat legal-administratif, di mana program sertifikasi cepat (PTSL) dan penekanan pada legalitas formal mereduksi sifat komunal hak adat. Sebaliknya, konflik di Malaysia berpusat pada penentuan batas dan definisi teritorial, di mana otoritas negara bagian (State Authority) gagal memetakan klaim komunal yang luas, memungkinkan tanah tersebut dialokasikan sebagai konsesi.
Berikut adalah sintesis perbandingan isu kritis:
| Aspek Kritis | Indonesia (UUPA/PTSL) | Malaysia (NLC/Torrens) | Tantangan Utama |
| Sistem Registrasi | Deeds Registration, diakselerasi PTSL. | Torrens System (Title Registration). | Indonesia: Sinkronisasi regulasi, risiko sengketa pasca-sertifikasi. |
| Kepastian Hukum Formal | Kuat, tetapi terbuka untuk klaim dalam 5 tahun pasca-sertifikat. | Prinsip Indefeasibility of Title (Hampir Absolut). | Malaysia: Mengatasi klaim historis/komunal yang tidak terdaftar. |
| Pengakuan Hak Adat | Hak Ulayat (sering tereduksi legalitas formal). | Native Customary Rights (NCR) (dilindungi Konstitusi). | Konflik definisi (pemakai menua vs. State Land) dan pemetaan yang lambat. |
| Dampak Program Percepatan | Risiko penghancuran hak tenurial adat (individualisasi hak) melalui PTSL. | Pemanfaatan State Land untuk konsesi di atas klaim NCR yang belum disurvei. | Kesenjangan antara hukum modern dan realitas tenurial komunal di kedua negara. |
Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Ringkasan Temuan Kunci
Analisis komparatif menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pertanahan di Indonesia dan Malaysia dikendalikan oleh filosofi yang berbeda secara fundamental. Indonesia, yang berlandaskan UUPA 1960 dan prinsip Hak Menguasai Negara (HMN), membangun sistem yang secara intrinsik fleksibel dan berorientasi pada fungsi sosial, tetapi menghadapi tantangan besar dalam mencapai kepastian hukum yang absolut, terutama melalui sistem Deeds Registration yang dipercepat oleh PTSL. Sebaliknya, Malaysia, yang mengadopsi NLC 1965 dan Sistem Torrens, menawarkan kepastian hak milik yang tinggi setelah pendaftaran (indefeasibility), namun harus menavigasi kompleksitas pembagian kewenangan yang kuat kepada negara bagian dan tantangan dalam pengakuan hak adat yang tidak terdaftar (NCR).
Kekuatan kontrol negara di Indonesia diwujudkan melalui pemberian hak-hak jangka waktu (HGU/HGB) yang bersyarat, memungkinkannya mengontrol pemanfaatan tanah dan mencegah lahan terlantar. Di Malaysia, sistem Torrens memprioritaskan keamanan kepemilikan formal, menjadikan intervensi negara pasca-pendaftaran lebih sulit.
Implikasi dan Pelajaran Komparatif
- Keseimbangan Stabilitas dan Fleksibilitas: Model Malaysia menunjukkan bahwa sistem Torrens dapat menjadi tolok ukur untuk mencapai kepastian hukum formal yang tinggi. Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat kualitas sertifikat dan membatasi periode klaim pasca-sertifikasi (saat ini 5 tahun), meskipun harus berhati-hati agar rigiditas Torrens tidak menghambat agenda reforma agraria berbasis HMN.
- Konflik Tata Kelola Desentralisasi: Peran dominan State Authority di Malaysia dalam urusan tanah menghasilkan variasi regional dalam implementasi hukum, khususnya pengakuan NCR. Hal ini menyajikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola desentralisasi asimetrisnya agar tidak menciptakan kebijakan agraria yang inkonsisten di tingkat nasional.
- Tantangan Universal Pembangunan: Kedua negara menunjukkan bahwa dorongan pembangunan ekonomi berbasis lahan (seperti proyek-proyek besar dan konsesi sawit/logging) seringkali mengarah pada penyimpangan dalam penggunaan istilah “kepentingan umum”, serta konflik yang intens dengan masyarakat adat. Kegagalan terletak pada ketidakmampuan kerangka hukum modern untuk mengintegrasikan sistem tenure komunal secara adil di tengah tekanan kapitalisasi lahan.
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan analisis komparatif ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk meningkatkan tata kelola pertanahan di kedua negara:
- Untuk Indonesia: Reformasi Kualitas Sertifikasi dan Hak Adat. Diperlukan upaya mendesak untuk menyelesaikan isu sinkronisasi regulasi terkait pendaftaran tanah. Yang lebih penting, program percepatan seperti PTSL harus didesain ulang untuk memastikan bahwa proses sertifikasi tidak mereduksi hak tenurial komunal menjadi hak individu semata, melainkan memberikan pengakuan formal terhadap Hak Ulayat dalam bentuk komunal.
- Untuk Malaysia: Percepatan Resolusi Konflik NCR. Pemerintah Negeri, khususnya di Sarawak dan Sabah, harus memprioritaskan percepatan survei dan penetapan batas wilayah Native Customary Rights (NCR) dan pemakai menua. Tindakan ini harus mendahului pemberian konsesi komersial besar-besaran untuk mengurangi konflik lahan.
- Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Tanah. Kedua negara harus memperkuat pengawasan independen untuk memastikan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan secara transparan, sesuai dengan definisi hukum, dan memberikan kompensasi yang adil dan tepat waktu kepada semua pihak yang dirugikan.
- Investasi pada Modernisasi Digital. Kedua negara harus melanjutkan dan mengintensifkan inisiatif digitalisasi administrasi pertanahan, seperti program Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia, guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan mengurangi peluang praktik korupsi.