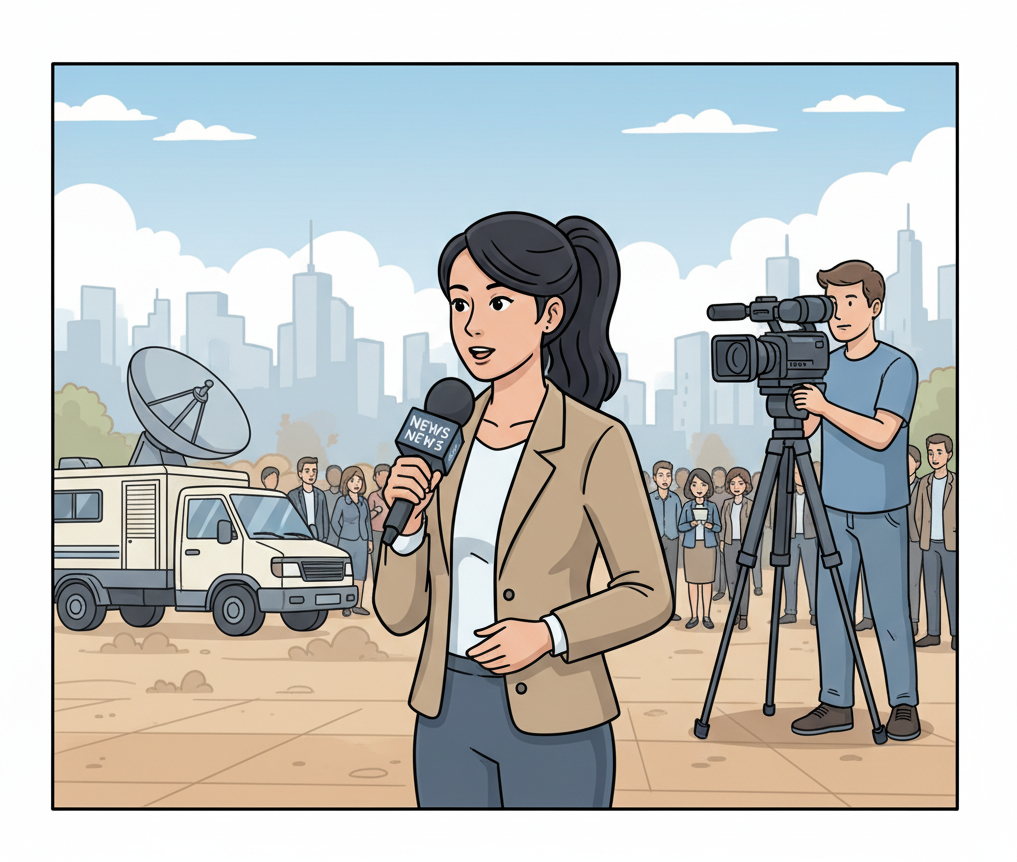Konflik bersenjata kontemporer menunjukkan pergeseran karakteristik yang signifikan, ditandai oleh pertikaian bersenjata non-internasional (NIAC) dan operasi asimetris, yang secara langsung meningkatkan risiko penargetan terhadap personel yang seharusnya dilindungi. Lingkungan operasional yang kompleks ini menimbulkan tantangan mendalam mengenai kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya implementasi prinsip pembedaan (distinction). Tujuan fundamental Hukum Humaniter Internasional adalah untuk membuat suatu perlindungan kepada para korban perang yang tergolong sebagai non-kombatan, yang tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan
Meskipun perlindungan hukum bagi personel kemanusiaan ditetapkan secara tegas, seringkali terlihat bahwa perlindungan hukum di atas kertas gagal diterjemahkan menjadi keselamatan operasional. Berbagai insiden pelanggaran yang terjadi secara berulang menunjukkan bahwa pihak yang bertikai, dalam beberapa kasus, secara strategis menganggap netralitas medis atau kehadiran jurnalis sebagai penghalang operasional. Hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya menjamin bahwa personel tersebut dilindungi, bukan malah menjadi target serangan. Kegagalan penegakan ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap efektivitas Hukum Humaniter Internasional di tengah pihak militer tertentu, yang merasa hukum ini mempersulit operasi mereka di lapangan.
Definisi Kunci dan Status Hukum di bawah Hukum Humaniter Internasional
Hukum Humaniter Internasional menetapkan kategorisasi ketat untuk membedakan antara mereka yang berhak berpartisipasi dalam permusuhan (kombatan) dan mereka yang harus dilindungi (non-kombatan). Pembedaan ini sangat krusial dalam menentukan status perlindungan bagi relawan medis, jurnalis, dan pekerja kemanusiaan lainnya.
Status Warga Sipil dan Non-Kombatan
Warga Sipil (Civilians): Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (Customary IHL), warga sipil didefinisikan sebagai orang-orang yang bukan anggota angkatan bersenjata. Populasi sipil terdiri dari semua orang yang tergolong sebagai warga sipil. Jurnalis dan pekerja kemanusiaan non-medis umumnya masuk dalam kategori ini, dan mereka harus dilindungi dari serangan, selama mereka tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Aturan perlindungan ini juga berlaku dalam konflik non-internasional.
Pembedaan (Distinction): Hukum Humaniter Internasional menekankan pembedaan tegas antara kombatan (yang mempunyai hak untuk melakukan permusuhan) dan non-kombatan (penduduk sipil). Kegagalan untuk mematuhi prinsip pembedaan ini (misalnya, dengan menargetkan objek sipil atau personel yang dilindungi) adalah inti dari sebagian besar pelanggaran terhadap pekerja kemanusiaan.
Status Relawan Medis dan Penggunaan Lambang
Relawan Medis (Medical Personnel): Personel ini memiliki perlindungan khusus dan dilarang menjadi target, sesuai dengan Konvensi Jenewa I 1949 Bab IV Pasal 24. Mereka yang dilindungi adalah personel yang secara eksklusif terlibat dalam pencarian, pengumpulan, pengangkutan, atau perawatan korban luka atau sakit. Status mereka dijamin oleh Hukum Humaniter Internasional dan dibuktikan dengan keberadaan lambang yang menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan bagian dari gerakan kemanusiaan.
Penggunaan lambang kemanusiaan (seperti Palang Merah atau Bulan Sabit Merah) memiliki dualitas fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai alat pertahanan (protective use), dan yang kedua adalah sebagai alat pengenal (indicative use). Namun, ketika lambang ini secara rutin diabaikan atau bahkan dijadikan target serangan yang disengaja, fungsi perlindungannya menjadi tumpul. Hal ini memaksa organisasi kemanusiaan menghadapi dilema etis dan operasional untuk memilih antara meningkatkan visibilitas (sebagai pengenal) atau mengurangi visibilitas (demi keamanan) untuk menghindari penargetan.
Landasan Hukum Perlindungan Khusus (Fokus Yuridis Normatif)
Kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI)
Kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang berakar dari Konvensi Den Haag (1899 dan 1907) dan mencapai puncaknya dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977, berfungsi sebagai regulasi utama bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata. Inti dari Hukum Humaniter Internasional adalah memastikan bahwa apabila konflik bersenjata harus dilakukan, pihak-pihak yang bertikai wajib melakukannya sesuai dengan standar kemanusiaan, menjamin perlindungan personel dan fasilitas yang netral.
Perlindungan Khusus Personel Medis dan Fasilitas (Non-Kombatan Absolut)
Perlindungan yang diberikan kepada personel medis bersifat tegas dan hampir absolut. Tenaga medis yang bertugas di zona konflik harus mendapat perlindungan dan penghormatan, serta tidak boleh menjadi target dalam konflik. Serangan terhadap mereka merupakan pelanggaran berat (grave breach) dan kejahatan perang yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.
Perlindungan Fasilitas Medis
Rumah sakit sipil secara tegas dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memainkan peran krusial dalam perumusan konvensi ini dan terus memberikan perlindungan serta bantuan. Perlindungan ini hanya dapat dicabut jika fasilitas tersebut digunakan untuk melakukan “tindakan yang merugikan musuh” (Acts Harmful to the Enemy). Namun, analisis hukum menunjukkan bahwa klaim pencabutan perlindungan ini seringkali dijadikan celah hukum yang dieksploitasi untuk melegitimasi serangan ilegal. Suatu negara yang menyerang harus membuktikan bahwa klaim ini benar-benar memenuhi standar Hukum Humaniter Internasional, termasuk prinsip proporsionalitas, dan harus didahului dengan peringatan yang wajar kepada pihak yang bertanggung jawab.
Status Jurnalis dan Pekerja Kemanusiaan Lainnya (Warga Sipil Berbahaya)
Jurnalis yang meliput di zona konflik, terutama mereka yang menjalankan misi profesional yang berbahaya, dilindungi sebagai warga sipil, selama mereka tidak terlibat langsung dalam permusuhan.
Perlindungan terhadap jurnalis diperkuat oleh Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (Pasal 79) dan Deklarasi Internasional tentang Perlindungan Jurnalis. Kerangka hukum ini melarang serangan fisik, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghinaan terhadap martabat, intimidasi, dan penghalangan pekerjaan jurnalis. Serangan terhadap jurnalis secara fundamental merupakan serangan terhadap hak atas informasi dan akuntabilitas.
Dalam konteks konflik bersenjata modern, perlindungan jurnalis tidak hanya mencakup ancaman fisik. Peralatan mereka sering disita atau dirusak, dan mereka juga menghadapi ancaman keamanan digital seperti peretasan dan penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika konflik kontemporer memerlukan interpretasi Hukum Humaniter Internasional yang diperluas untuk mencakup perlindungan keamanan siber dan data, yang kini merupakan bagian integral dari ancaman terhadap kebebasan pers dan peliputan di medan perang.
Tabel I: Ringkasan Status Hukum dan Perlindungan Kelompok Profesional di Zona Konflik
| Kelompok Profesional | Status HHI Primer | Perlindungan Khusus (Ya/Tidak) | Dasar Hukum Utama | Keterangan Penting |
| Personel Medis | Non-Kombatan | Ya (Absolut, Dilindungi dan Dihormati) | Konvensi Jenewa I, Pasal 24, Protokol Tambahan I, II | Dapat kehilangan perlindungan hanya jika digunakan untuk tindakan merugikan musuh (Harus didahului peringatan). |
| Pekerja Kemanusiaan (Non-Medis) | Sipil | Tidak (Namun dilindungi sebagai sipil) | Konvensi Jenewa IV, Protokol Tambahan I (Pasal 71) | Serangan disengaja terhadap mereka adalah Kejahatan Perang. |
| Jurnalis | Sipil (Misi Berbahaya) | Tidak (Namun dilindungi sebagai sipil) | Protokol Tambahan I (Pasal 79), HHI Kebiasaan | Penargetan, intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang dilarang. |
Pola Pelanggaran Berat: Studi Kasus dan Analisis Risiko
Penargetan Sistem Kesehatan: Kejahatan Perang yang Sistematis
Serangan terhadap fasilitas medis, personel, dan ambulans di zona konflik telah menjadi pola yang sistematis, menunjuk pada pelanggaran berat (grave breach) terhadap Konvensi Jenewa. Ketika serangan ini terjadi secara terus-menerus, hal itu bukan hanya pelanggaran taktis terisolasi, melainkan merupakan strategi yang disengaja untuk melumpuhkan kapasitas medis musuh dan secara efektif menghukum penduduk sipil yang sakit.
Kasus Gaza dan Rumah Sakit Indonesia
Dalam konflik Israel-Palestina, serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk fasilitas medis, menimbulkan kekhawatiran serius. Studi kasus spesifik mengenai serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi syarat pencabutan perlindungan yang ketat sebagaimana diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan kejahatan perang di bawah Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Keengganan beberapa pihak yang bertikai untuk menghormati aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat dalam kasus serangan terhadap tenaga medis, menyoroti tantangan mendasar dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional.
Kolapsnya Sistem Kesehatan di Suriah
Penargetan fasilitas medis juga terlihat sistemik di Suriah. Serangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, yang didukung Rusia, terhadap berbagai rumah sakit di Aleppo telah menghancurkan sistem layanan kesehatan kota tersebut. Konsekuensinya sangat parah: dilaporkan 95% dokter di Aleppo telah mengungsi, ditahan, atau dibunuh.
Secara keseluruhan, pelayanan kesehatan di Suriah telah hancur oleh pengeboman dalam konflik yang berkepanjangan. Lebih dari separuh rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat di negara itu ditutup atau hanya berfungsi sebagian. Eksodus hampir dua pertiga tenaga profesional kesehatan dan penurunan dua pertiga produksi obat-obatan dalam negeri memiliki implikasi jangka panjang. Hasilnya, banyak warga Suriah yang sekarat akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, bukan hanya karena luka perang. Penghancuran sistemik ini merupakan bentuk kejahatan perang yang disengaja yang bertujuan untuk membuat wilayah tertentu tidak dapat dihuni, melumpuhkan upaya rekonstruksi sosial dan medis selama bertahun-tahun.
Risiko Kritis Jurnalis: Impunitas dan Pembungkaman
Jurnalis yang meliput di zona konflik sering menghadapi risiko yang jauh lebih besar daripada warga sipil pada umumnya. Risiko ini tidak hanya terbatas pada cedera yang tidak disengaja akibat konflik, tetapi juga penargetan langsung. Data menunjukkan tingkat kematian yang mengkhawatirkan: 68 jurnalis terbunuh pada tahun 2024 secara global. Dalam konflik Israel-Hamas, tercatat bahwa lebih dari 122 jurnalis tewas , dengan laporan spesifik menunjukkan 108 jurnalis terbunuh di Gaza antara 7 Oktober 2023 hingga 19 Juli 2024.
Mekanisme Intimidasi dan Kontrol Informasi
Zona konflik seperti Gaza menjadi sangat berbahaya bagi wartawan. Tindakan kekerasan tidak hanya bersifat fisik. Jurnalis juga menghadapi intimidasi, penganiayaan, penyiksaan, dan penangkapan tanpa proses hukum yang jelas. Militer sering menganggap media sebagai bagian dari ancaman militan, yang menciptakan efek menakutkan (chilling effect). Rasa takut ini menghalangi jurnalis untuk mengaktifkan kamera atau melakukan peliputan secara terbuka karena mereka tahu mereka berisiko menjadi sasaran. Strategi ini memungkinkan pihak militer engontrol arus informasi dan membatasi kritik terhadap operasinya.
Masalah Impunitas sebagai Kejahatan Perang
Jurnalis bertindak sebagai saksi kunci dan pengumpul bukti kejahatan perang. Penargetan mereka merupakan serangan langsung terhadap akuntabilitas internasional. Semakin banyak jurnalis yang dibunuh atau diintimidasi, semakin sedikit bukti yang tersedia untuk penuntutan.
Meskipun banyaknya korban jiwa, laporan UNESCO mencatat bahwa tingkat impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis masih tinggi. Contoh kasus penembakan jurnalis Shireen Abu Akleh, yang diklaim sebagai kejahatan perang, menyoroti kurangnya akuntabilitas dan keengganan negara terkait untuk berpartisipasi dalam penyelidikan internasional yang independen Impunitas ini secara fundamental melemahkan kemampuan komunitas internasional untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional dan menciptakan lingkaran setan kekerasan berkelanjutan.
Tabel II: Pola Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terhadap Personel dan Fasilitas Kritis (Studi Kasus Selektif)
| Zona Konflik (Tahun) | Target Pelanggaran | Jenis Pelanggaran HHI Kunci | Dampak Kuantitatif/Kualitatif |
| Gaza (2023-2024) | Fasilitas Medis (RS Indonesia) | Pelanggaran Prinsip Distingsi, Kejahatan Perang | Fasilitas hancur, diklasifikasikan sebagai grave breach menurut Statuta Roma |
| Suriah (Aleppo) | Sistem Layanan Kesehatan | Penargetan Dokter/Fasilitas, Kejahatan Kemanusiaan | 95% dokter mengungsi/dibunuh, sistem kesehatan kolaps, peningkatan kematian akibat penyakit non-perang |
| Global (2024) | Jurnalis | Pembunuhan, Impunitas Tinggi | 68 Jurnalis terbunuh secara global. 108 jurnalis terbunuh di Gaza (Okt 2023-Juli 2024) |
| Gaza (2023-2025) | Pekerja Kemanusiaan (MSF) | Pembunuhan Staf, Penarikan Akses | 11 staf terbunuh, dipaksa mundur dari 20 fasilitas, blokade dan politisasi bantuan |
Hambatan Akses Kemanusiaan (Denial of Access)
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pekerja kemanusiaan adalah hambatan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap akses bantuan. Blokade wilayah dan pembatasan pergerakan sering kali menghambat distribusi bantuan yang optimal bagi warga terdampak. Hal ini diperburuk oleh keamanan lapangan yang berisiko tinggi bagi tenaga bantuan dan proses birokrasi internasional yang seringkali memakan waktu lama.
Peran gencatan senjata menjadi sangat vital dalam konteks ini, karena kesepakatan tersebut sering memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk mengakses daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau. Peningkatan akses ini krusial untuk distribusi makanan, obat-obatan, dan bantuan darurat lainnya kepada populasi yang paling membutuhkan
Eksploitasi Bantuan sebagai Senjata Perang (Weaponization of Aid)
Ketika akses kemanusiaan dibatasi, timbul risiko bahwa bantuan itu sendiri digunakan sebagai alat atau senjata perang, sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Organisasi Doctors Without Borders (MSF) telah menyerukan diakhirinya blokade Gaza dan mendesak pihak yang bertikai untuk menghentikan penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai senjata.
MSF melaporkan telah menghadapi 50 insiden kekerasan di Gaza, termasuk pembunuhan sebelas anggota stafnya, dan terpaksa mundur dari setidaknya 20 fasilitas kesehatan sejak Oktober 2023. Laporan menunjukkan bahwa pasokan bantuan dialihkan, dipersyaratkan, atau diblokir untuk mendukung tujuan militer dan politik. Penggunaan blokade sebagai strategi perang telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dan mendorong penduduk ke jurang kelaparan ekstrem.
Politisasi bantuan semacam ini secara langsung merusak prinsip netralitas organisasi bantuan. Ketika bantuan dilihat tidak lagi didistribusikan dengan aman atau tanpa memihak, persepsi netralitas organisasi tersebut terkikis, yang pada gilirannya secara langsung meningkatkan risiko keamanan bagi staf di lapangan karena mereka tidak lagi dianggap sebagai entitas non-partisan. Menghadapi denial of access, respons diplomatik yang kompleks menjadi penting, seperti yang ditunjukkan oleh strategi Indonesia yang menggunakan pendekatan diplomasi politik, bantuan terukur melalui mitra terpercaya, dan penguatan kapasitas medis Palestina.
Dampak Psikososial dan Krisis Kesehatan Mental Staf
Biaya tersembunyi dari bekerja di zona konflik adalah dampak psikologis yang mendalam pada relawan medis, jurnalis, dan pekerja kemanusiaan. Personel ini berisiko tinggi mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).
Manifestasi Trauma: Trauma pasca-kejadian, seperti peperangan atau kekerasan, dapat menyebabkan luka dan trauma berkepanjangan. Gejala PTSD bervariasi dalam tingkat keparahan dan durasinya. Secara psikologis, penderita dapat merasa tidak berdaya, putus asa, dan kehilangan kendali. Keadaan ini juga memengaruhi tubuh dengan gejala fisik seperti gangguan pola tidur, mendadak hilang nafsu makan, kurang konsentrasi, keringat dingin, dan jantung berdetak kencang. Kondisi fisik dan kesehatan mental sangat berkaitan erat, dan PTSD yang tidak ditangani secara profesional dapat memengaruhi kesehatan fisik dan karir.
Pentingnya Intervensi: Penanganan profesional sangat krusial dan harus dilakukan dalam dua tahap: pada masa krisis dan pada masa trauma. Intervensi krisis bertujuan untuk menstabilkan korban segera dan mengurangi risiko dari trauma yang terjadi. Penanganan trauma jangka panjang berfokus pada pemulihan dan penyembuhan secara profesional. Organisasi kemanusiaan wajib menyediakan struktur dukungan profesional ini.
Tabel III: Manifestasi PTSD dan Kebutuhan Intervensi bagi Staf Kemanusiaan
| Kategori Dampak | Gejala Psikologis Kunci | Gejala Fisik Terkait | Tindakan Penanganan Primer |
| Akut (Masa Krisis) | Kecemasan, Kebingungan, Panik, Kehilangan Kontrol | Keringat dingin, Jantung berdetak kencang, Gangguan tidur | Intervensi Krisis (Stabilisasi segera, mengurangi risiko krisis/trauma) |
| Kronis (Pasca-Trauma) | Flashback, Hiper-kewaspadaan, Keputusasaan | Gangguan pola makan, Masalah kesehatan non-medis yang sulit dijelaskan | Penanganan Trauma Profesional (Pemulihan karir, terapi kognitif/psikofarmakologi) |
Mekanisme Akuntabilitas dan Tantangan Penegakan Hukum Internasional
Klasifikasi Kejahatan Perang dan Yurisdiksi ICC
Kejahatan perang dan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma 1998 membuka sejarah baru dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, kemanusiaan, dan perang. Serangan terhadap personel medis, jurnalis, dan pekerja kemanusiaan yang dilindungi, serta fasilitas mereka, merupakan kejahatan perang yang secara eksplisit berada di bawah yurisdiksi ICC.
Yurisdiksi ICC dapat berlaku jika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma, atau jika pelakunya adalah warga negara pihak. Dalam konteks Gaza, Palestina secara resmi menjadi anggota ICC pada tahun 2015. Keanggotaan ini memungkinkan ICC untuk menjalankan yurisdiksi teritorial atas kejahatan perang yang terjadi di Jalur Gaza.
Hambatan Yurisdiksi dan Prinsip Komplementaritas
Meskipun ICC memiliki mandat luas, penegakan hukumnya sering terhalang oleh kendala politik dan hukum.
Prinsip Komplementaritas dan Kendala Politik
ICC beroperasi di bawah prinsip komplementaritas, yang berarti ICC hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan terhadap para pelaku kejahatan. Namun, dalam situasi di mana negara tidak ingin atau tidak mampu mengadili kejahatan perang (seperti dalam kasus penargetan jurnalis yang dilakukan oleh militer), prinsip komplementaritas secara efektif menjadi hambatan, menciptakan kekosongan akuntabilitas.
Selain itu, ICC menghadapi kendala yurisdiksi terhadap pelaku dari negara yang bukan pihak Statuta Roma. Upaya penangkapan terhadap pemimpin seperti Vladimir Putin, misalnya, menghadapi tantangan hukum karena Rusia bukan negara pihak. ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksi jika negara non-pihak tersebut secara eksplisit menyatakan menerima yurisdiksi ICC.
Hambatan politik dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) juga sangat signifikan. Keberadaan hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap (AS, Inggris, Prancis, Tiongkok, Rusia) memungkinkan mereka memblokir rujukan kasus ke ICC, terutama jika kasus tersebut melibatkan kepentingan mereka atau sekutu mereka. Adanya hak veto ini memastikan bahwa kelima negara tersebut secara praktis tidak akan pernah terkena resolusi DK PBB yang merugikan diri sendiri, melemahkan fungsi ICC sebagai penegak hukum yang imparsial.
Pentingnya Bukti dan Dokumentasi
Kualitas akuntabilitas secara langsung bergantung pada kualitas bukti yang dikumpulkan. Jurnalis dan personel medis seringkali merupakan saksi mata utama, bahkan korban, dari Hukum Humaniter Internasional. Penargetan mereka menghancurkan mata rantai bukti yang krusial. Kematian atau intimidasi terhadap jurnalis secara langsung berkorelasi dengan tingginya impunitas, yang memungkinkan pelaku kejahatan perang lolos dari hukuman.
Tantangan Teknologi Baru (Otonomi Senjata)
Munculnya Sistem Senjata Otonom (Autonomous Weapon Systems – AWS) yang didukung machine learning menimbulkan kekhawatiran baru dalam perlindungan personel kemanusiaan. Penggunaan AWS berisiko tinggi menyebabkan jatuhnya korban sipil karena algoritma mungkin melanggar prinsip pembedaan (distinction) dalam Hukum Humaniter Internasional. Komandan militer mungkin berargumen bahwa kesalahan teknis yang menewaskan pekerja kemanusiaan tidak dapat diprediksi. Namun, Hukum Humaniter Internasional (Pasal 36 Protokol Tambahan I) mewajibkan negara memastikan semua persenjataan yang digunakan mematuhi hukum yang berlaku. Perlindungan di masa depan sangat bergantung pada regulasi yang efektif terhadap teknologi perang baru ini untuk memastikan bahwa keputusan penargetan masih berada di bawah kendali dan akuntabilitas manusia.
Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis
Ringkasan Temuan Kunci
Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Hukum Humaniter Internasional memberikan kerangka perlindungan yang jelas dan tegas bagi relawan medis, jurnalis, dan pekerja kemanusiaan, pola penargetan sistematis terhadap kelompok-kelompok ini di zona konflik menunjukkan krisis penegakan hukum yang akut.
- Pelanggaran Berat yang Sistematis: Penargetan fasilitas medis dan personel kesehatan (contoh Suriah dan Gaza) bukanlah insiden acak, melainkan pelanggaran berat Konvensi Jenewa yang bertujuan melumpuhkan kapasitas sipil, yang berpotensi menjadi kejahatan perang.
- Krisis Jurnalis dan Impunitas: Jurnalis menghadapi risiko yang jauh lebih tinggi sebagai warga sipil, dan penargetan mereka (baik fisik maupun digital) merupakan upaya untuk mengontrol informasi dan menciptakan impunitas.
- Hambatan Operasional dan Politisasi: Akses kemanusiaan sering terhalang oleh blokade (denial of access), dan bantuan telah digunakan sebagai senjata perang untuk tujuan militer atau politik, yang merusak prinsip netralitas.
- Biaya Tersembunyi: Staf kemanusiaan menanggung beban psikologis yang parah, berisiko tinggi menderita PTSD, yang menuntut intervensi krisis dan dukungan profesional jangka panjang.
- Akuntabilitas yang Terhambat: Mekanisme penegakan hukum internasional, khususnya ICC, terhambat oleh prinsip komplementaritas yang rapuh dan hambatan politik (hak veto DK PBB), yang memungkinkan impunitas terus berlangsung.
- Tantangan Baru: Teknologi perang baru, seperti AWS, menimbulkan risiko serius terhadap prinsip pembedaan, menuntut interpretasi dan regulasi Hukum Humaniter Internasional yang diperbarui.
Rekomendasi untuk Penguatan Perlindungan Hukum dan Operasional
Untuk mengatasi kesenjangan antara perlindungan hukum dan realitas operasional, direkomendasikan langkah-langkah strategis berikut:
- Peninjauan dan Adopsi Doktrin Militer yang Ketat: Mendesak negara-negara pihak untuk merevisi doktrin operasional militer mereka agar secara eksplisit melarang penargetan fasilitas medis dan memastikan bahwa klaim pencabutan perlindungan medis hanya dapat diajukan dengan bukti yang tidak ambigu dan setelah peringatan yang jelas diberikan.
- Peningkatan Keamanan Jurnalis Melalui Mandat Internasional: Mengimplementasikan mandat internasional yang lebih kuat untuk melindungi jurnalis dari intimidasi fisik dan digital, serta mewajibkan penyelidikan independen atas setiap pembunuhan jurnalis di zona konflik.
- Pengamanan Akses Kemanusiaan: Komunitas internasional harus secara tegas menerapkan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap pihak-pihak yang secara sistematis menggunakan blokade atau penolakan akses sebagai strategi perang, menegaskan bahwa denial of access adalah pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional I.
- Dukungan Psikologis dan Kesehatan Mental Wajib: Organisasi kemanusiaan harus menyediakan struktur dukungan profesional yang wajib, termasuk intervensi krisis segera dan penanganan PTSD jangka panjang, untuk menjamin keberlanjutan karir dan kesehatan staf mereka.
Rekomendasi untuk Mekanisme Akuntabilitas yang Lebih Efektif
- Pemanfaatan Yurisdiksi Universal: Negara-negara pihak Konvensi Jenewa didorong untuk secara aktif menerapkan yurisdiksi universal untuk menuntut individu yang dicurigai melakukan kejahatan perang terhadap personel yang dilindungi, terutama ketika ICC terhalang oleh kendala politik atau yurisdiksi.
- Reformasi DK PBB terkait ICC: Negara-negara anggota harus mendesak reformasi dalam Dewan Keamanan PBB terkait penggunaan hak veto dalam rujukan kasus pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional, untuk mengurangi politisasi akuntabilitas.
- Penguatan Kapasitas Bukti: Meningkatkan pendanaan dan dukungan teknis untuk organisasi yang bertugas mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti kejahatan perang di zona konflik, yang sangat penting mengingat penargetan saksi (jurnalis dan medis).