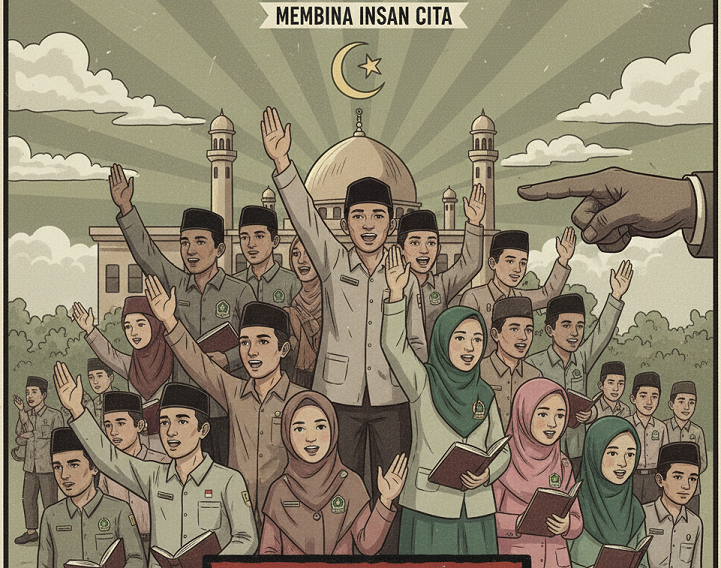Latar Belakang Kebijakan Asas Tunggal (UU No. 8 Tahun 1985)
Rezim Orde Baru (OB), di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, menjalankan proyek politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas absolut dan menyingkirkan semua kekuatan politik yang berpotensi mengancam hegemoni kekuasaan negara. Setelah menumpas organisasi komunis pada pertengahan 1960-an, satu-satunya kekuatan yang dianggap mampu menandingi rezim Orde Baru adalah kekuatan Islam politik. Dalam konteks upaya gigih untuk menghalangi kemajuan gerakan Islam politik ini, rezim menggunakan perangkat hukum untuk mengontrol dan mendepolitisasi organisasi-organisasi massa (ormas).
Kebijakan kontrol ini dikristalisasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Undang-undang ini mewajibkan setiap partai politik dan organisasi massa, tanpa terkecuali, untuk menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau Asas Tunggal. Tujuan kebijakan ini melampaui homogenisasi ideologi; ini adalah mekanisme struktural untuk kooptasi dan penjinakan kekuatan Islam terpelajar. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia, berada di persimpangan jalan eksistensial, dipaksa memilih antara mempertahankan asas Islam atau mengadopsi Pancasila demi kelangsungan hidup institusional dan legal.
Tesis Utama: Konflik Asas sebagai Representasi Pergulatan Adaptasi Politik Islam terhadap Hegemoni Orde Baru
Perpecahan yang terjadi di tubuh HMI pada tahun 1986 akibat kebijakan Asas Tunggal merupakan demonstrasi paling jelas dari konflik strategis yang dihadapi kelompok Islam terpelajar di bawah rezim otoritarian. Konflik ini bukanlah semata-mata perselisihan administratif, melainkan representasi pergulatan mendalam antara survivalisme politik dan purifikasi ideologis.
Analisis ini menunjukkan bahwa Orde Baru berhasil memecah dan mengkooptasi kelompok Islam terpelajar melalui mekanisme struktural dan represi. Faksi yang memilih akomodasi (HMI Dipo) efektif menukarkan independensi ideologis dengan akses politik dan perlindungan dari represi negara, sementara faksi yang menolak (HMI MPO) memilih perlawanan ideologis dengan risiko ilegalitas dan penekanan negara. Perpecahan ini, oleh karena itu, mencerminkan dua strategi respons yang berbeda terhadap ancaman hegemoni negara.
Anatomi Represi Orde Baru dan Latar Belakang Intelektual HMI Pra-1985
Strategi Depolitisasi dan Pengendalian Kekuatan Non-Militer
Orde Baru secara sistematis menerapkan strategi depolitisasi terhadap kelompok masyarakat sipil, terutama ormas yang memiliki basis massa kuat dan tradisi perlawanan ideologis. Ancaman pembubaran secara legal (non-pengakuan) merupakan senjata utama rezim untuk memaksa ormas mematuhi Asas Tunggal. Tekanan ini tidak hanya dialami HMI; organisasi Islam besar lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU) juga menghadapi dilema serupa, mendorong munculnya generasi-generasi baru yang berupaya mendefinisikan kembali paradigma gerakan Islam mereka agar tetap relevan di tengah kebuntuan politik.
Dalam konteks HMI, dilema ini sangat tajam karena HMI telah lama menjadi reservoir utama bagi elit politik dan intelektual Muslim. Dengan memaksa HMI menerima Asas Tunggal, rezim memastikan bahwa bahkan kelompok mahasiswa yang memilih jalur adaptasi akan selalu berada di bawah pengawasan ketat negara. Ini berarti bahwa kekuatan intelektual yang berpotensi menjadi oposisi kritis di masa depan akan diarahkan untuk mendukung narasi dan kepentingan rezim, atau setidaknya tidak secara eksplisit menentangnya.
Pergulatan Intelektual Internal HMI Pra-1985
Perpecahan struktural HMI pada 1986 bukanlah ledakan tiba-tiba, melainkan kristalisasi konflik ideologis yang sudah berakar jauh sejak wacana pembaharuan pemikiran Islam mulai menguat. Pergolakan pemikiran dalam tubuh HMI mencapai puncaknya pada tahun 1970. Tokoh sentral dalam diskursus ini adalah Nurcholish Madjid (Cak Nur), mantan Ketua Umum PB HMI dua periode, yang menyampaikan ide pembaharuannya dengan topik “Keharusan Pembaharuan Pemikiran dalam Islam dan Masalah Integrasi Umat”.
Cak Nur melontarkan slogan yang sangat kontroversial, yaitu “Islam Yes, Partai Islam No!”. Slogan ini menciptakan preseden penting yang mendiskusikan pemisahan politik identitas Islam dari wadah organisasi politik formal. Diskursus ini secara tidak langsung membuka jalan bagi wacana penyesuaian dasar HMI dari Islam menjadi Pancasila. Para intelektual HMI sudah terbiasa dengan ide bahwa mempertahankan substansi keislaman secara ideologis dan kultural tidak harus diiringi dengan mempertahankan asas organisasi secara harfiah.
Ketika tekanan Asas Tunggal muncul pada 1985, faksi yang kemudian dikenal sebagai HMI Dipo menggunakan warisan intelektual Cak Nur sebagai pembenaran untuk adaptasi pragmatis. Mereka berargumen bahwa menerima Pancasila adalah cara untuk mengembalikan Islam ke ranah kultural, menghindari jebakan politik praktis Orde Baru yang represif, dan memastikan organisasi tetap bertahan. Sebaliknya, kelompok yang membentuk MPO melihat Astung sebagai serangan terhadap identitas fundamental HMI 1947 dan menolak kompromi ideologis tersebut. Dengan demikian, Asas Tunggal berfungsi sebagai katalisator eksternal yang memaksa faksi-faksi internal yang sudah berbeda pandangan filosofis untuk memilih sisi secara definitif.
Kronologi dan Pemicu Perpecahan Struktural (1985-1986)
Keputusan Kontroversial Pengurus Besar (PB) HMI, 10 April 1985
Fase perpecahan struktural HMI dimulai dengan keputusan Pengurus Besar (PB) HMI di bawah kepemimpinan Harry Azhar Azis (periode 1983–1986). Meskipun Azis dikenal sebagai salah satu kritikus aktif terhadap Orde Baru, kepemimpinannya mengambil langkah krusial yang pada akhirnya membelah organisasi.
Pada tanggal 10 April 1985 di Yogyakarta, PB HMI mengumumkan melalui jumpa pers tentang penerimaan asas Pancasila sebagai asas organisasi. Keputusan sepihak ini, yang diambil tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan tertinggi organisasi yaitu Kongres, dinilai oleh sebagian cabang HMI sebagai sebuah “kesalahan besar”. Cacat prosedural ini menjadi pemicu struktural perpecahan, memicu konflik berkepanjangan di internal HMI.
Konsolidasi Faksi Penolak (Majelis Penyelamat Organisasi – MPO)
Keprihatinan mendalam menyikapi penerimaan asas tunggal memicu perlawanan dari cabang-cabang utama yang memiliki basis massa dan intelektual terbesar. Cabang-cabang yang menolak keputusan PB termasuk Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Ujungpandang, dan Purwokerto. Cabang Yogyakarta, khususnya, dikenal sebagai salah satu yang terbesar, mengelola lebih dari 50 komisariat saat itu.
Sebagai bentuk perlawanan, cabang-cabang penolak membentuk forum yang bernama Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) pada 15 Maret 1986 di Jakarta. Tujuan MPO adalah untuk berdialog dan tetap kukuh mempertahankan asas Islam sebagai asas resmi HMI. MPO berhasil mengorganisir 9 cabang terbesar di HMI, termasuk Cabang Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.
Klimaks Konflik: Kongres XVI Padang (Maret 1986)
Ketegangan antara PB HMI (kubu pro-Astung) dan MPO meningkat menjelang Kongres XVI. Awalnya, MPO berencana melakukan demonstrasi di kantor PB HMI (Jl. Diponegoro 16, Jakarta) karena tanggapan PB HMI terhadap upaya dialog mereka terkesan meremehkan.
Dalam demonstrasi tersebut, PB HMI justru merespons dengan mengundang kekuatan militer untuk menghalau MPO. Beberapa anggota MPO ditangkap oleh aparat dengan tuduhan subversif. Penggunaan instrumen represi negara oleh faksi yang berkuasa di PB HMI ini membuktikan bahwa mereka menyelaraskan diri sepenuhnya dengan metode kekuasaan Orde Baru: menggunakan aparat negara untuk menyelesaikan konflik internal organisasi. Tindakan ini merupakan konsekuensi langsung dari memilih jalur akomodatif.
Situasi kekerasan dan penangkapan ini berlanjut sampai diselenggarakannya Kongres HMI XVI di Padang, Sumatera Barat (24–31 Maret 1986). Kongres ini dijadikan forum oleh PB HMI untuk secara resmi melegitimasi perubahan asas organisasi menjadi Pancasila. Kehadiran MPO yang mewakili basis dukungan ideologis mayoritas ditolak oleh panitia kongres. Kongres hanya diikuti oleh cabang-cabang pro-PB HMI dan cabang-cabang transitif (cabang bentukan PB HMI sebagai upaya pengalihan legitimasi), yang kehadirannya memicu kekacauan fisik dalam ruangan sidang.
Kongres XVI di Padang akhirnya menetapkan Pancasila sebagai asas HMI, dan secara efektif memecah HMI menjadi dua faksi: HMI Dipo (merujuk pada kantor PB di Jalan Diponegoro) yang diakui sah oleh pemerintah, dan HMI MPO. MPO, yang dipimpin oleh HMI Cabang Yogyakarta, merespons dengan menyelenggarakan kongres tandingan di Gunung Kidul. Kongres MPO ini segera dianggap sebagai ilegal, bentuk pembangkangan terhadap negara, dan anti-Pancasila oleh Orde Baru, disertai ancaman pembubaran dan penangkapan.
Tabel 1: Kronologi Kritis Pecahnya HMI Era Asas Tunggal (1985-1986)
| Tanggal/Periode | Peristiwa Kunci | Signifikansi |
| April 1985 (Sebelum 10 April) | Pengesahan UU Keormasan No. 8/1985 (Asas Tunggal). | Tekanan eksternal maksimal yang memaksa ormas menyesuaikan diri. |
| 10 April 1985 | PB HMI mengumumkan penerimaan Asas Pancasila melalui jumpa pers di Yogyakarta. | Keputusan sepihak yang melanggar prosedur organisasi (tanpa Kongres); pemicu struktural. |
| Pra-Kongres XVI | PB HMI mengundang militer untuk membubarkan MPO; penangkapan anggota. | Faksi Dipo menyelaraskan diri dengan metode represi negara untuk mengatasi konflik internal. |
| 15 Maret 1986 | Pembentukan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) di Jakarta. | Formalisasi faksi ideologis yang menolak Astung. |
| 24–31 Maret 1986 | Kongres XVI di Padang. | Legitimasi formal Pancasila sebagai asas (HMI Dipo) dan perpecahan struktural. |
| Maret 1986 | Kongres tandingan HMI MPO di Gunung Kidul. | Penegasan identitas HMI Islam (1947) dan status ilegal dari rezim. |
Analisis Komparatif: Dualisme Ideologis HMI Dipo dan HMI MPO
Perpecahan HMI melahirkan dua model gerakan mahasiswa Islam yang berbeda, masing-masing memiliki strategi bertahan hidup dan berinteraksi dengan kekuasaan yang kontras.
Asas dan Identitas: Pancasila vs. Islam
HMI Dipo (HMI Pancasila): Faksi ini secara resmi menyesuaikan diri dengan UU Ormas dan mengubah asas organisasi menjadi Pancasila. Meskipun demikian, mereka berpegang pada narasi bahwa Islam tetap menjadi “nafas” atau semangat gerakan, sementara Pancasila hanyalah asas formal yang diperlukan untuk mendapatkan pengakuan legal dari negara.
HMI MPO (HMI Islam/1947): Kelompok ini tetap kukuh mempertahankan Islam sebagai asas resmi organisasi. Penamaan MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) dan klaim sebagai “HMI 1947” bertujuan untuk menegaskan bahwa mereka adalah pewaris sah HMI pada tahun awal berdirinya, yaitu HMI yang independen dan berbasis Islam murni. Mereka memandang penolakan Asas Tunggal sebagai bentuk perjuangan untuk menjaga kemurnian ideologis HMI.
Strategi Organisasional: HMI Dipo (Akomodatif/Pragmatisme Politik)
HMI Dipo memilih jalur akomodasi, yang kemudian berbuah akses politik. Organisasi ini diakui secara resmi oleh pemerintah dan bersikap akomodatif terhadap rezim Orde Baru. Strategi ini memungkinkan kader Dipo untuk mengambil peran besar dalam berbagai aspek kehidupan nasional, terutama dalam birokrasi dan politik praktis.
Kader-kader HMI Dipo berhasil menguasai beberapa departemen dan lembaga negara, seperti Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Sekretariat Negara (Setneg). Mantan kader HMI juga banyak duduk di kabinet, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Narasi yang diusung oleh HMI Dipo adalah bahwa penerimaan Asas Tunggal merupakan strategi bertahan hidup untuk menghindari pembubaran, memungkinkan kaderisasi tetap berjalan di jalur yang legal, dan membuka peluang infiltrasi dari dalam sistem kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan negara.
Strategi Organisasional: HMI MPO (Perlawanan/Ideologis Militan)
Sebaliknya, HMI MPO memilih jalur perlawanan konfrontatif. Karena penolakan total terhadap Asas Tunggal, mereka dianggap ilegal, anti-Pancasila, dan mengalami penekanan berat oleh rezim Orde Baru. Akibatnya, aktivitas MPO sempat dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama beberapa tahun.
Kader HMI MPO dikenal memiliki karakter yang cenderung lebih radikal dan militan dibandingkan Dipo. Fokus kaderisasi MPO adalah pada penanaman ideologi Islam yang murni dan gerakan yang bersifat kritis serta konfrontatif terhadap otoritarianisme negara. Paradoksnya, represi yang dilakukan negara justru membuat HMI MPO menjadi lebih matang dan kuat dalam mempertahankan identitas ideologis dan semangat perjuangan mereka.
Dualisme HMI Dipo dan HMI MPO ini secara kolektif menghasilkan divisi tenaga kerja yang tidak disengaja dalam gerakan Islam Indonesia: Dipo menjadi oposisi birokratik yang bekerja dari dalam sistem, memperoleh sumber daya, dan memengaruhi kebijakan secara halus; sementara MPO menjadi oposisi ideologis yang menentang secara eksplisit dari luar, mempertahankan integritas moralitas gerakan dengan mengorbankan akses politik.
Tabel 2: Perbandingan Ideologis dan Struktural HMI Dipo vs. HMI MPO (Pasca 1986)
| Aspek Komparasi | HMI Dipo (Hasil Kongres XVI Padang) | HMI MPO (HMI Islam/1947) |
| Asas Organisasi | Pancasila | Islam |
| Sikap terhadap Orde Baru | Akomodatif/Pragmatis (Diakui) | Menolak/Konfrontatif (Ilegal) |
| Status Resmi Pemerintah | Diakui Secara Sah | Dianggap Ilegal, Mengalami Penekanan |
| Basis Dukungan Awal | PB HMI, Cabang Transitif, Cabang Kecil | Cabang-cabang Besar (Pusat Intelektual) |
| Fokus Strategi | Infiltrasi ke birokrasi negara (BULOG, Setneg) | Perjuangan ideologis dan gerakan militan |
Implikasi Jangka Panjang Dualisme HMI
Dampak terhadap Gerakan Mahasiswa dan Intelektual Muslim
Perpecahan HMI memiliki dampak signifikan pada peta pergerakan mahasiswa Islam. Fragmentasi ini melemahkan posisi tawar gerakan mahasiswa Islam secara keseluruhan dalam menghadapi rezim Orde Baru, karena energi organisasi terkuras dalam konflik internal dan klaim legitimasi.
Secara intelektual, dualisme ini menciptakan dua jalur karier dan filosofis yang berbeda. HMI Dipo cenderung menghasilkan intelektual yang fokus pada modernisasi dan integrasi Islam dalam struktur negara dan ekonomi. Sebaliknya, HMI MPO fokus pada pemurnian ideologi, kritik sosial-politik berbasis Islam murni, dan penentangan terhadap kompromi kekuasaan. Perpecahan HMI juga menambah kompleksitas pada peta pergerakan mahasiswa, yang saat itu juga diisi oleh organisasi seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang turut menghadapi dilema Astung.
Peran HMI Dipo dan MPO dalam Transisi Politik Pasca-1998 (Reformasi)
Jaringan HMI Dipo, berkat sikap akomodatif mereka terhadap Orde Baru, telah mengakar kuat dalam birokrasi dan politik nasional. Kekuatan jaringan alumni (KAHMI) dari kubu Dipo memungkinkan mereka memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses transisi politik pasca-1998 (Reformasi), baik sebagai elit yang mengisi jabatan penting maupun sebagai kritikus konstruktif terhadap pemerintahan Soeharto menjelang kejatuhannya.
Sementara itu, setelah Orde Baru tumbang, HMI MPO mendapatkan ruang untuk beraktivitas secara terbuka dan menegaskan kembali identitas ideologis mereka yang non-kompromistis. MPO menjadi representasi bagi kelompok mahasiswa yang mencari alternatif gerakan di luar jalur politik akomodatif yang sebelumnya ditempuh oleh Dipo.
Isu Penyatuan dan Hambatan Struktural-Ideologis
Meskipun konteks politik yang memicu perpecahan—kebijakan Asas Tunggal Orde Baru—telah lama berakhir, upaya penyatuan kembali HMI Dipo dan HMI MPO yang rutin diwacanakan menjelang setiap kongres selalu gagal terwujud. Kegagalan penyatuan ini menunjukkan bahwa perpecahan yang dipicu oleh otoritarianisme eksternal telah berevolusi menjadi perpecahan internal permanen yang didorong oleh perbedaan filosofis dan kepentingan struktural yang terinstitusionalisasi.
Hambatan utama penyatuan terletak pada perbedaan konstitusi (asas) dan klaim legitimasi historis. Kedua kubu sama-sama merasa sebagai pewaris sah HMI 1947. Lebih jauh lagi, hambatan pragmatis menjadi penghalang besar. Faksi Dipo telah memiliki akses finansial, jaringan politik, dan modal sosial yang mapan di tingkat nasional, sementara MPO mempertahankan klaim moralitas ideologis dan kemurnian perjuangan. Penyatuan mengharuskan salah satu mazhab organisasi ini menyerahkan identitasnya, sebuah pilihan yang tidak dapat diambil secara sukarela setelah puluhan tahun beroperasi sebagai entitas independen. Krisis 1985–1986, dengan demikian, melahirkan dua model aktivisme Islam yang mandiri: satu yang memilih jalur kekuasaan, dan satu lagi yang memilih jalur ideologi murni.
Kesimpulan
Pecahnya HMI di era Asas Tunggal merupakan salah satu babak paling dramatis dalam sejarah gerakan mahasiswa Islam di Indonesia. Perpecahan ini adalah demonstrasi nyata dari tekanan politik eksistensial yang memaksa organisasi Islam memilih antara kehancuran legal (jika menolak Asas Tunggal) dan kompromi ideologis (jika menerima).
Temuan kunci menunjukkan bahwa perpecahan ini merupakan hasil dari intervensi negara yang berhasil membiakkan faksi yang patuh (Dipo) dengan memberikan imbalan akses politik, sekaligus secara represif menekan faksi yang menolak (MPO) melalui mekanisme militer dan tuduhan subversif. Perpecahan ini melampaui konflik administratif, menjadi sebuah pilihan fundamental antara pragmatisme politik yang didukung oleh warisan intelektual modernis (Cak Nur) dan purifikasi ideologis yang memilih perjuangan militan. Dualisme yang bertahan hingga saat ini membuktikan bahwa perpecahan tersebut telah menginstitusionalisasi perbedaan filosofis yang mendalam tentang peran HMI bagi bangsa, terlepas dari runtuhnya rezim Orde Baru.
Prospek Studi Lanjutan
Untuk memahami sepenuhnya konsekuensi jangka panjang dari dualisme ini, penelitian lebih lanjut disarankan. Fokus studi dapat mencakup:
- Analisis mendalam mengenai dampak kebijakan Asas Tunggal terhadap keragaman pemikiran teologis di kalangan kader HMI MPO yang dipaksa bergerak secara semi-ilegal, dan bagaimana pengalaman represi tersebut membentuk ideologi perlawanan pasca-Reformasi.
- Studi perbandingan jejaring alumni (KAHMI) antara HMI Dipo dan HMI MPO, menganalisis perbedaan struktur kekuasaan, sumber daya finansial, dan pengaruh politik mereka terhadap kebijakan nasional kontemporer, untuk memahami mengapa upaya penyatuan terus mengalami kebuntuan struktural.