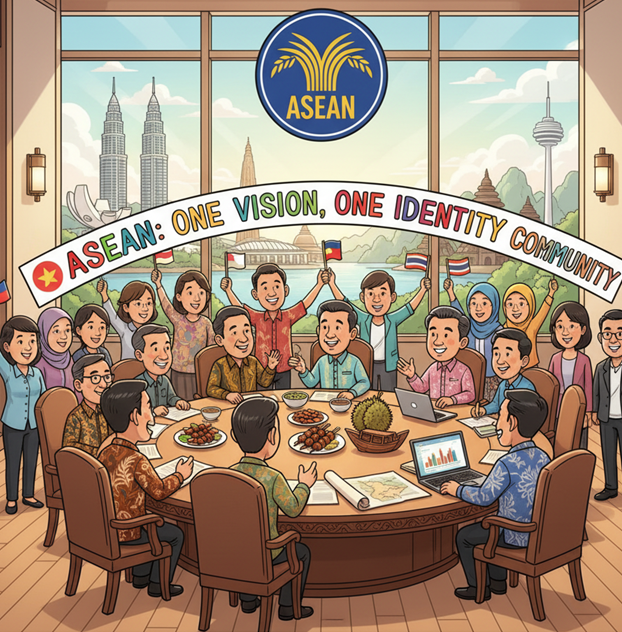Tulisan ini menganalisis secara mendalam bagaimana dinamika politik domestik yang heterogen di negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara fundamental membentuk, dan sering kali menghambat, kohesi regional serta peran organisasi di kancah geopolitik global. Analisis ini dibangun di atas hipotesis bahwa kohesi ASEAN yang fluktuatif, yang sebagian besar ditentukan oleh stabilitas dan kepentingan domestik anggotanya, secara langsung berkorelasi dengan kemampuan ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya dan memengaruhi dinamika kawasan Indo-Pasifik.
Kerangka Analisis dan Paradoks Normatif ASEAN
Bagian awal ini menetapkan kerangka teoretis yang mengikat politik domestik dengan kinerja kelembagaan ASEAN, menyoroti dilema inti yang diabadikan dalam filosofi pendiriannya, yang dikenal sebagai The ASEAN Way.
Definisi Konseptual: Politik Domestik, Kohesi, dan Sentralitas
Dalam konteks ini, Politik Domestik mencakup spektrum luas mulai dari sistem pemerintahan (demokrasi, monarki, junta), tingkat legitimasi rezim, prioritas pembangunan ekonomi nasional, hingga penanganan konflik internal dan etnis. Variabel-variabel domestik ini adalah penentu utama Kohesi Regional, yaitu kemampuan negara anggota untuk mencapai posisi kolektif (common position) dan melaksanakan keputusan bersama tanpa dibatalkan oleh perhitungan kepentingan bilateral atau nasional. Ketika kohesi institusional meningkat, organisasi menunjukkan ketahanan yang lebih besar.
Kohesi ini secara langsung memengaruhi Sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality), yang merupakan posisi organisasi sebagai pendorong utama dan pemimpin arsitektur regional dalam forum keamanan dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.
Analisis Kritis Terhadap Prinsip “The ASEAN Way”
Prinsip dasar yang memandu ASEAN adalah The ASEAN Way, yang berakar pada konsensus dan non-intervensi. Prinsip ini adalah produk langsung dari pengalaman historis negara-negara Asia Tenggara yang menjunjung tinggi kedaulatan negara sebagai reaksi terhadap pengalaman kolonial dan intervensi eksternal selama Perang Dingin. Deklarasi Bangkok yang mendirikan ASEAN secara eksplisit menekankan perlunya negara-negara untuk mengamankan stabilitas dan keamanan mereka dari intervensi eksternal.
Mekanisme pengambilan keputusan didasarkan pada informality, musyawarah, dan konsensus mufakat. Pendekatan ini terbukti berhasil dalam mengelola konflik intra-mural dan mempromosikan perdamaian regional selama 55 tahun terakhir.
Namun, model ini menghadapi dilema kelembagaan yang signifikan. Prinsip non-intervensi, yang merupakan fondasi pemelihara perdamaian, kini dipandang oleh para kritikus sebagai hambatan utama untuk perubahan institusional, terutama ketika menghadapi isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kekerasan internal di negara anggota.
Organisasi regional ini menghadapi konflik antara tujuan menjaga identitas normatifnya (The ASEAN Way) dan perlunya fungsionalitas dalam menghadapi ancaman keamanan abad ke-21. ASEAN dibentuk untuk memastikan stabilitas regional , dan stabilitas ini dicapai melalui penghormatan kedaulatan absolut. Namun, interpretasi sempit terhadap prinsip non-intervensi mengakibatkan ASEAN tidak mampu menangani krisis domestik internal yang mengancam keamanan manusia dan regional, seperti yang terjadi di Myanmar. Dalam keadaan ini, upaya untuk mempertahankan norma inti organisasi justru menghambat efektivitasnya dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan dan keamanan regional.
Heterogenitas Politik Domestik sebagai Sumber Fragilitas Kohesi
Keragaman besar di antara negara-negara anggota ASEAN—yang meliputi perbedaan sistem politik, pandangan strategis, dan tingkat perkembangan ekonomi—menjadi tantangan fundamental bagi kekompakan dan solidaritas kolektif.
Variasi Sistem Pemerintahan dan Komitmen Normatif
Spektrum politik di ASEAN, yang mencakup negara-negara dengan sistem demokratis hingga junta militer, secara inheren mempersulit upaya kolektif untuk menegakkan norma-norma Komunitas Politik-Keamanan ASEAN yang mencakup demokrasi, HAM, dan tata kelola yang baik.
Hal ini terlihat jelas dalam penanganan pelanggaran HAM dan konflik etnis, seperti krisis Rohingya di Myanmar. Dewan HAM ASEAN kesulitan bertindak karena kurangnya persatuan. Sikap tidak tegas dari delapan negara anggota lainnya muncul dari ketakutan bahwa ketegasan tersebut akan mengganggu kerja sama bilateral yang telah ada dengan Myanmar. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan domestik dan kehati-hatian diplomatik bilateral seringkali lebih diutamakan daripada kohesi regional dan komitmen normatif kolektif. Konsekuensi dari isu-isu yang tidak terselesaikan ini adalah bahwa krisis domestik tersebut, seperti yang terjadi pada Rohingya, dapat mengganggu dan menelantarkan agenda kerja sama ASEAN yang lain—baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik-keamanan.
Kepentingan Ekonomi Nasional dan Dampaknya pada Integrasi
Kebijakan luar negeri negara anggota ASEAN sebagian besar didorong oleh prioritas domestik, terutama melalui diplomasi ekonomi. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Singapura secara aktif mengintegrasikan strategi diplomasi ekonomi untuk menarik Investasi Asing Langsung (FDI) demi pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan visi ekonomi yang mandiri (berdikari).
Meskipun Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) bertujuan menciptakan kawasan yang terintegrasi, prioritas domestik ini terkadang tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan integrasi yang lebih luas. Misalnya, optimalisasi sumber energi dalam negeri atau pengembangan UMKM adalah fokus domestik yang mengarahkan kebijakan luar negeri.
Yang lebih krusial adalah ketergantungan ekonomi eksternal. Peningkatan dominasi ekonomi Cina di kawasan, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekspor ASEAN ke Cina (sekitar 11 persen pada 2024) , telah menyebabkan beberapa negara anggota menjadi bergantung secara ekonomi pada Beijing. Perhitungan domestik ini membuat mereka rentan terhadap tekanan politik dari Cina, yang pada gilirannya secara kolektif merusak otonomi strategis ASEAN.
Kondisi ini menciptakan dekopling antara kemajuan integrasi ekonomi regional dan kohesi politik-keamanan. Negara anggota dapat berhasil dalam aspek ekonomi, memanfaatkan AEC, tetapi ketergantungan ekonomi domestik pada aktor non-ASEAN menciptakan kerentanan politik yang signifikan. Artinya, integrasi ekonomi parsial dapat terus berjalan, tetapi Sentralitas ASEAN dalam isu keamanan kritis tetap terfragmentasi karena kepentingan ekonomi dan politik domestik saling bertabrakan.
Studi Kasus Kohesi yang Terdestabilisasi: Myanmar dan Krisis Legitimasi
Krisis politik di Myanmar pasca-kudeta militer pada Februari 2021 menjadi studi kasus empiris yang paling jelas mengenai kegagalan prinsip non-intervensi dan krisis kohesi di ASEAN.
Kegagalan Implementasi Five-Point Consensus (5PC)
Solusi bagi krisis politik domestik di Myanmar belum menemukan titik terang, bahkan setelah empat tahun upaya diplomasi. Mekanisme penyelesaian melalui Konsensus Lima Poin (5PC) telah mandek, dan keadaan di Myanmar malah memburuk. Kegagalan ini membuktikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis konsensus dan pendekatan antar-pemerintah (government-to-government atau G-to-G) menjadi tidak efektif ketika salah satu pihak, yaitu rezim penguasa Myanmar, telah kehilangan legitimasi.
Dalam krisis kemanusiaan, interpretasi sempit terhadap prinsip non-intervensi menghambat fungsi ASEAN sebagai organisasi regional, bahkan ketika berhadapan dengan kejahatan internasional. Ketika konsensus kolektif gagal tercapai, penyelesaian sengketa seringkali diserahkan kembali kepada KTT ASEAN, yang hanya menghasilkan retorika diplomatik dari masing-masing negara anggota.
Kegagalan ASEAN dalam mengambil peran kepemimpinan untuk menyelesaikan krisis telah menciptakan ruang bagi kekuatan eksternal. Cina dilaporkan bergerak agresif di Myanmar, bahkan mendesak junta untuk menyelenggarakan pemilu pada Oktober 2025 , yang menunjukkan erosi pengaruh ASEAN.
Keterbatasan Pendekatan Diplomasi Tradisional
Efektivitas diplomasi ASEAN tampak volatil, tergantung pada jenis konflik yang dihadapi. Analisis terhadap upaya mediasi yang dipimpin oleh Malaysia, misalnya, menunjukkan potensi dan keterbatasan pendekatan tradisional.
Malaysia berhasil dalam mediasi ad hoc seperti perjanjian damai Bangsamoro di Filipina, yang mengakhiri konflik 40 tahun dan membentuk wilayah otonomi. Demikian pula, intervensi personal Perdana Menteri Malaysia berhasil memfasilitasi gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Meskipun langkah ini dianggap sebagai “titik balik dalam diplomasi ASEAN” karena beralih dari ceremonial hosting ke operational problem-solving, gencatan senjata tersebut hanya mengatasi gejala, bukan perselisihan mendasar.
Sebaliknya, kasus Myanmar menggambarkan kegagalan total mekanisme G-to-G. Konflik di Myanmar melibatkan aktor non-negara, seperti Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), kelompok etnis bersenjata, dan jaringan masyarakat sipil. Pendekatan antar-pemerintah tidak dapat mengatasi konflik yang sangat kompleks dan melibatkan krisis legitimasi negara. Krisis Myanmar menunjukkan bahwa pendekatan tradisional meremehkan pentingnya keterlibatan multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholder engagement) untuk mencapai hasil yang tahan lama.
Kegagalan institusional ini menggeser keberhasilan ASEAN menjadi sangat bergantung pada kapasitas dan stabilitas negara anggota kunci. Indonesia, misalnya, dengan reputasinya sebagai middle power yang berpengaruh dan rekam jejaknya dalam diplomasi perdamaian (termasuk mediasi konflik Thailand-Kamboja 2011 dan keterlibatan di Afganistan) , menjadi pendorong utama penyelesaian krisis, termasuk dalam kasus Myanmar. Hal ini menyiratkan bahwa efektivitas ASEAN tidak ditentukan oleh kekuatan kelembagaannya sendiri, melainkan oleh stabilitas politik domestik dan kemauan para pemimpin dalam rotasi kepemimpinan. Kohesi ASEAN menjadi adhocratic dan rentan terhadap transisi politik di negara-negara kuncinya.
Table 1: Perbandingan Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN dalam Krisis Domestik dan Bilateral
| Studi Kasus | Sifat Konflik | Mekanisme yang Digunakan | Tingkat Kohesi Regional yang Tercapai | Hasil/Efektivitas dan Keterbatasan |
|
| Krisis Politik Myanmar (Pasca-Kudeta) | Domestik, Pelanggaran HAM/Kejahatan Internasional | Five-Point Consensus (5PC), Diplomasi G-to-G | Sangat Rendah (Fragmentasi) | Mandek; Kegagalan institusional dalam konflik multi-stakeholder; Cina mengisi kekosongan. | |
| Perjanjian Damai Bangsamoro (Filipina) | Internal, Gerakan Separatis | Mediasi oleh Malaysia (G-to-G) | Tinggi (Dukungan penuh) | Berhasil mengakhiri konflik 40 tahun dan membentuk wilayah otonomi. | |
| Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja | Bilateral, Teritorial | Mediasi Personal P.M. Malaysia; Pembentukan Tim Pengamat ASEAN | Sedang (Kohesi fungsional) | Berhasil mengatasi gejala (gencatan senjata), tetapi tidak menyelesaikan perselisihan mendasar. |
Sengketa Laut Cina Selatan: Ujian Sentralitas dalam Persaingan Kekuatan Besar
Isu Laut Cina Selatan (SCS) adalah medan geopolitik utama di mana kepentingan domestik yang saling bertentangan secara langsung mengurangi kemampuan kolektif ASEAN untuk bertindak sebagai blok yang bersatu.
Kepentingan Domestik vs. Posisi Kolektif
Sengketa SCS melibatkan klaim teritorial yang tumpang tindih antara Cina dan beberapa anggota ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei). Bagi negara-negara klaiman, prioritas utama adalah kedaulatan nasional dan keamanan maritim mereka sendiri. Indonesia, meskipun bukan negara klaiman, merespons ketegangan dengan meningkatkan patroli TNI AL dan Bakamla di Natuna, yang menunjukkan penyesuaian keamanan domestik terhadap dinamika regional.
Fragmentasi klaim di antara anggota ASEAN menghambat organisasi untuk membentuk posisi kolektif yang tunggal dan kuat terhadap klaim Cina, terutama setelah Beijing mendeklarasikan SCS sebagai salah satu “core interest” negaranya.
Korelasi Kohesi dan Kerentanan terhadap Pengaruh Cina
Penelitian menunjukkan adanya korelasi timbal balik yang jelas: Kohesi ASEAN yang rendah secara empiris membuat organisasi semakin sulit mencapai posisi bersama yang kuat dan akibatnya, sulit memengaruhi sikap yang diambil oleh Cina terkait sengketa wilayah.
Dalam kondisi kohesi yang tidak efektif, ASEAN rentan terhadap pengaruh pihak ketiga, terutama Cina. Beijing dapat memanfaatkan perpecahan internal ini dengan berinteraksi secara bilateral, menargetkan anggota yang secara ekonomi bergantung. Sebaliknya, kohesi yang tinggi meningkatkan ketahanan institusional ASEAN, membuatnya lebih sulit dipengaruhi oleh pihak ketiga. Kohesi yang kuat bahkan memungkinkan ASEAN untuk mengajak Cina terlibat lebih aktif dalam mekanisme manajemen sengketa wilayah yang diinisiasikan oleh ASEAN. Sayangnya, tren kohesi ASEAN sejak tahun 1992 hingga 2017 umumnya tergolong sebagai caucus, menunjukkan bahwa kemampuan untuk bertindak sebagai blok yang solid seringkali terbatas.
Dinamika Geopolitik dan Ancaman terhadap Netralitas
Kompetisi geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina di Indo-Pasifik dianggap merongrong kohesi internal ASEAN, membuat upaya lama organisasi untuk menyeimbangkan kekuatan besar menjadi semakin sulit dipertahankan.
Contoh konkret dari perpecahan internal adalah tanggapan yang beragam terhadap aliansi keamanan AUKUS. Filipina menyatakan dukungan terhadap blok pertahanan tersebut, sementara Malaysia menyatakan keprihatinan bahwa aliansi tersebut dapat memicu perlombaan senjata. Perbedaan ini mencerminkan minimnya kesamaan persepsi di antara negara anggota mengenai cara menjaga netralitas dan Sentralitas ASEAN. Respons yang berbeda-beda ini muncul dari perbedaan domestik dalam persepsi ancaman dari Cina dan inkonsistensi narasi identitas nasional.
Kegagalan mengambil sikap bersama dalam menghadapi inisiatif geopolitik besar ini melanggar prinsip netralitas, yang berimplikasi pada perpecahan anggota dan mengancam Sentralitas ASEAN.
Faktor eksternal seperti persaingan kekuatan besar hanya berhasil memecah ASEAN karena adanya perbedaan mendasar dalam kepentingan domestik, pandangan strategis, dan ketergantungan ekonomi. Dengan kata lain, dinamika domestik bertindak sebagai filter yang menginternalisasi tekanan geopolitik, mengubah tantangan eksternal menjadi fragmentasi internal. ASEAN tidak dipecah dari luar, melainkan menjadi rentan terhadap perpecahan karena kondisi politik dan ekonomi di dalamnya.
Dampak Global: Sentralitas ASEAN yang Terkikis dan Peran Middle Power
Sentralitas ASEAN sebagai penggerak utama arsitektur regional di Indo-Pasifik diakui secara global. Namun, kohesi internal yang menurun akibat dinamika domestik secara langsung melemahkan peran dan daya tawar ASEAN di forum-forum global.
Evaluasi Sentralitas ASEAN
Meskipun ASEAN telah sukses dalam membangun institusi regional dengan modalitas informality The ASEAN Way , krisis domestik yang parah mengurangi kapasitas negara anggota untuk memusatkan perhatian dan sumber daya pada isu-isu regional.
Peningkatan dominasi Cina dan kebijakan luar negerinya yang tegas menantang otonomi strategis ASEAN. Negara anggota yang sangat tergantung secara ekonomi pada Cina cenderung lebih rentan terhadap tekanan politik untuk tidak bertindak melawan kepentingan Cina, khususnya dalam isu SCS.
Persepsi Pihak Eksternal tentang Kohesi ASEAN
Kawasan Asia Tenggara dianggap “sangat penting” secara geografis dan ekonomi bagi banyak kekuatan besar dunia. Cina, misalnya, telah menunjukkan dominasi ekonomi dengan secara aktif mempererat hubungan dagang dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat akibat kebijakan proteksionis.
Uni Eropa (UE) menyadari pentingnya Indo-Pasifik sebagai pusat perekonomian dunia. Dalam strategi Indo-Pasifiknya, UE berupaya hadir secara konstruktif—melalui kerja sama ekonomi dan pembangunan—dan secara eksplisit mengedepankan ASEAN, dengan tujuan menghindari terlibat dalam rivalitas kekuatan besar. Namun, kemitraan konstruktif ini hanya dapat dimaksimalkan jika ASEAN memiliki kohesi yang memadai untuk bertindak sebagai mitra yang solid.
Peran Indonesia sebagai Penjaga Stabilitas dan Pendorong Kohesi
Stabilitas politik domestik di negara-negara anggota kunci sangat penting bagi integrasi regional. Indonesia, sebagai negara penggagas ASEAN dan kekuatan menengah (middle power) yang berpengaruh , memiliki komitmen kuat untuk memperkuat integrasi. Stabilitas politik domestik dan reputasi Indonesia dalam diplomasi memungkinkannya menjadi advokat kebijakan luar negeri ASEAN yang kohesif.
Kepemimpinan Indonesia (misalnya pada 2023) diarahkan untuk memperkuat integrasi ekonomi regional, mencapai tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025, dan mengarahkan blok tersebut di tengah tantangan global. Ini adalah contoh bagaimana stabilitas domestik diterjemahkan menjadi dorongan integrasi.
Karena kohesi kolektif ASEAN rentan terhadap tekanan domestik dan eksternal , stabilitas domestik Indonesia berfungsi sebagai public good regional, atau sebagai penyeimbang internal yang menjaga Konsensus dan Sentralitas ASEAN agar tidak sepenuhnya runtuh. Kehadiran aktor internal yang stabil dengan kapasitas diplomatik yang tinggi sangat krusial untuk mencegah fragmentasi total organisasi.
Table 2: Dampak Dinamika Politik Domestik pada Kohesi dan Sentralitas ASEAN
| Variabel Politik Domestik (Endogen) | Dampak pada Kohesi ASEAN | Dampak pada Sentralitas Global | Mekanisme Transmisi Causal |
| Instabilitas Rejim / Kudeta Militer (Myanmar) | Fragmentasi, Sulit mencapai Konsensus Fungsional | Legitimasi dipertanyakan; Mengundang intervensi eksternal (Cina); Fokus organisasi teralihkan. | Non-Intervensi Strict (Penghambat Aksi) -> Krisis Kemanusiaan -> Krisis Institusional. |
| Ketergantungan Ekonomi Tinggi pada Cina (Kamboja/Laos) | Sulit mengambil posisi kolektif yang kuat (SCS); Mengorbankan kepentingan regional demi bilateral. | Menurunkan otonomi strategis; Dianggap rentan terhadap tekanan pihak ketiga. | Prioritas Domestik Ekonomi -> Keterbatasan Strategi Politik Regional. |
| Stabilitas Domestik dan Kapasitas Middle Power (Indonesia/Malaysia) | Berfungsi sebagai mediator dan pendorong norma; Peningkatan kepercayaan dan kerja sama operasional. | Memperkuat daya tawar ASEAN; Mampu memimpin arsitektur regional (misal, Indo-Pasifik). | Stabilitas Politik Domestik -> Ketersediaan Kapasitas Diplomatik untuk Regional. |
| Perbedaan Persepsi Ancaman (AUKUS) | Erosi Netralitas; Anggota dipaksa memilih pihak; Melanggar prinsip penyelesaian damai. | Sentralitas terkikis; ASEAN dipandang tidak kompak dan tidak relevan dalam isu keamanan keras. | Heterogenitas Strategis Domestik -> Kegagalan Konsensus Keamanan Kolektif. |
Rekomendasi Strategis untuk Peningkatan Kohesi dan Peran Global
Dinamika politik domestik adalah penentu utama kinerja kelembagaan ASEAN di tingkat regional dan global. Untuk mengatasi fragilitas kohesi yang diakibatkan oleh heterogenitas domestik dan tekanan eksternal, ASEAN perlu mengambil langkah-langkah reformasi strategis.
Reformasi Normatif dan Interpretasi Prinsip Non-Intervensi
ASEAN harus melakukan refleksi normatif terhadap prinsip non-intervensi. Interpretasi yang terlalu sempit harus diubah, memungkinkan organisasi untuk melakukan intervensi atau tindakan kolektif dalam kasus-kasus luar biasa yang melibatkan kejahatan internasional, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Penerapan pengecualian kemanusiaan ini penting untuk memulihkan kredibilitas normatif ASEAN dan memenuhi fungsinya sebagai organisasi keamanan regional. Selain itu, konsolidasi demokrasi dan tata kelola yang baik harus didorong di tingkat domestik sebagai prasyarat fundamental bagi komitmen regional, sebagaimana diamanatkan oleh Piagam ASEAN.
Penguatan Kapasitas Resolusi Konflik Regional
Berdasarkan kegagalan 5PC di Myanmar, ASEAN harus mengembangkan mekanisme resolusi konflik yang melampaui pendekatan government-to-government yang kaku. Mekanisme baru harus memiliki kapasitas untuk melibatkan aktor multi-pemangku kepentingan, termasuk kelompok etnis bersenjata, organisasi masyarakat sipil, dan oposisi politik (seperti NUG), untuk mencapai solusi yang lebih holistik dan tahan lama.
Organisasi harus berupaya menginstitusionalisasikan keberhasilan ad hoc dalam mediasi yang telah dicapai oleh negara-negara anggota (misalnya, Malaysia dan Indonesia). Tujuannya adalah bertransisi dari sekadar ceremonial hosting (tuan rumah seremonial) menjadi operational problem-solving (penyelesaian masalah operasional) dalam struktur ASEAN.
Strategi Kolektif dalam Mengelola Persaingan Kekuatan Besar
Mengingat kohesi yang tinggi meningkatkan ketahanan institusional terhadap pengaruh eksternal, investasi dalam pembangunan kohesi sangat penting. ASEAN harus membangun kesamaan persepsi strategis yang solid di antara negara anggota mengenai ancaman dan peluang di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini mencakup upaya untuk mitigasi ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada satu kekuatan besar, seperti Cina, melalui diversifikasi pasar dan investasi.
Dengan memanfaatkan posisi strategisnya sebagai titik temu kekuatan global , ASEAN harus memperkuat otonomi strategisnya. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong kemitraan konstruktif (seperti dengan Uni Eropa yang menawarkan fokus ekonomi dan pembangunan) , sambil secara tegas mempertahankan netralitas aktif dan Sentralitas ASEAN. Sentralitas dapat dipertahankan hanya jika negara anggota mampu memprioritaskan kepentingan kolektif regional di atas perhitungan politik dan ekonomi domestik sesaat.