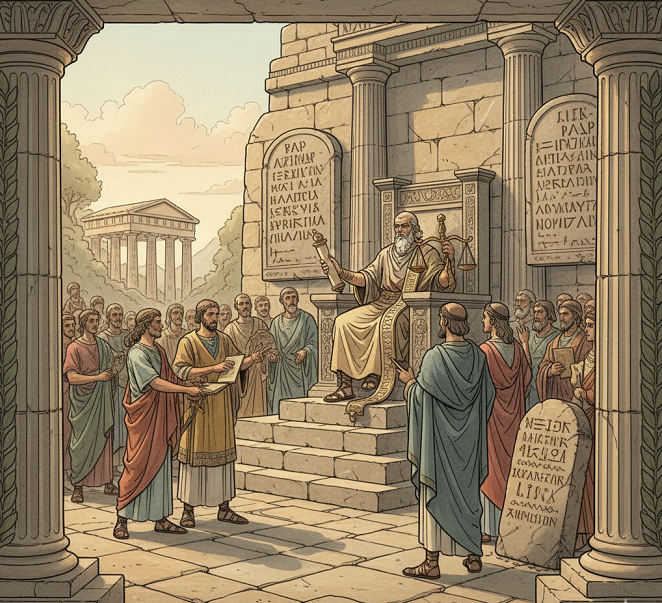Latar Belakang dan Kontekstualisasi Sejarah Hukum
Tulisan ini menyajikan analisis komparatif mendalam mengenai kesinambungan struktural (kontinuitas) dan pemutusan filosofis radikal (diskontinuitas) antara sistem hukum perintis kuno dan struktur yudisial kontemporer. Tujuan utamanya adalah melacak bagaimana warisan yurisprudensi Babilonia dan Romawi, yang dibentuk ribuan tahun yang lalu, terus memengaruhi cara pengadilan modern mengonsep keadilan, sanksi, dan hak-hak warga negara.
Pentingnya studi komparatif hukum dalam konteks ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Memahami sejarah hukum adalah prasyarat fundamental untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif di masa depan. Hukum harus dilihat sebagai sebuah fenomena yang hidup dan terus berkembang, di mana aturan formal tertulis sering kali tertinggal di belakang fakta dan perkembangan sosial. Pandangan ini terangkum dalam pepatah “Het recht hink achter de feiten ann”—hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya. Oleh karena itu, yurisprudensi modern harus secara proaktif menjembatani kesenjangan ini dengan merujuk pada prinsip-prinsip abadi sambil secara tegas menolak praktik-praktik yang tidak sesuai dengan moralitas kontemporer.
Ruang Lingkup Fokus dan Tesis Sentral
Kajian ini berfokus pada dua sistem hukum kuno yang memiliki dampak global yang tak terhapuskan: Kode Hammurabi (Mesopotamia), yang menjadi model retribusi kaku dan kodifikasi berbasis status sosial; dan Hukum Romawi, yang melalui Ius Civile dan Ius Gentium meletakkan fondasi bagi universalitas hukum dan sistem Civil Law modern.
Tesis sentral yang diusung adalah bahwa hukum kuno memberikan warisan struktural yang fundamental, yang terwujud dalam tradisi kodifikasi dan spesifikasi kejahatan serta hukuman. Namun, pengadilan modern secara radikal menolak fondasi filosofis dari sistem kuno tersebut, terutama praktik diskriminasi berbasis status sosial dan konsep pemidanaan absolut yang kini secara universal diakui melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Fondasi Legitimasi Kuno sebagai Perintis Rule of Law
Meskipun terlihat primitif jika dilihat dari lensa modern, sistem hukum kuno memecahkan masalah legitimasi dan aksesibilitas hukum. Kode Hammurabi, misalnya, tidak hanya sekadar kumpulan peraturan, tetapi merupakan sebuah monumen yang berisi hukum-hukum. Hukum tersebut dituliskan di atas tugu batu setinggi lebih dari 2 meter dan ditempatkan di tengah ibukota, diklaim sebagai pemberian dari Dewa Marduk atau Shamash. Klaim legitimasi ilahi dan visibilitas fisik ini merupakan langkah awal yang krusial menuju konsep Rule of Law.
Dengan adanya hukum tertulis yang dapat dibaca oleh publik, kekuasaan arbiter raja dibatasi, karena ia harus merujuk pada teks yang dilegitimasi secara transenden. Epilog pada Kode Hammurabi bahkan mengundang siapa saja yang mencari kebenaran untuk datang membaca stel hukum tersebut, menekankan fungsi publiknya sebagai pedoman keadilan. Tradisi kodifikasi yang dimulai di Babilonia dan kemudian disempurnakan oleh Kekaisaran Romawi (melalui Corpus Juris Civilis ) adalah nenek moyang langsung dari sistem Civil Law modern. Dalam sistem Civil Law saat ini, undang-undang tertulis yang dikodifikasi dianggap sebagai sumber hukum utama, yang menunjukkan kesinambungan struktural yang berakar kuat pada tradisi kuno tersebut.
Pondasi Hukum Kuno: Paradigma Mesopotamia dan Romawi
Kode Hammurabi (Mesopotamia): Kodifikasi Status dan Kepastian Hukum Casuistic
Kode Hammurabi, yang disusun sekitar 1755–1750 SM, diakui sebagai teks hukum tertulis terpanjang, terorganisir, dan terpelihara terbaik dari Timur Dekat kuno. Raja Hammurabi mempromulgasikan hukum ini dengan tujuan utamanya “mencegah yang kuat menindas yang lemah”. Hukum tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari hukum pidana (pencurian, perampokan, perzinahan), hukum perdata (kontrak, kompensasi), hukum keluarga (perkawinan, warisan), hingga hukum properti dan ekonomi.
Struktur hukum dalam kode ini bersifat casuistic, di mana aturan diekspresikan dalam kalimat bersyarat “jika… maka…”. Pendekatan ini menunjukkan upaya dini untuk menciptakan kepastian hukum dengan mencakup situasi hukum spesifik, sebuah karakteristik yang dihargai dalam masyarakat modern.
Meskipun demikian, hukum acara dalam Kode Hammurabi mengandung praktik yang sangat bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip due process modern. Salah satu contoh paling ekstrem adalah “uji coba sungai” (trial by ordeal). Jika seseorang dituduh melakukan kejahatan dan ia melompat ke sungai, jika ia tenggelam, ia dianggap bersalah dan penuduhnya mengambil alih rumahnya. Namun, jika ia selamat, penuduhnya akan dihukum. Prosedur ini tidak hanya melanggar keras asas praduga tak bersalah, tetapi juga menunjukkan nilai yang sangat tinggi pada penyelesaian cepat dan stabilitas sosial daripada hak individu.
Lebih lanjut, kode ini memberlakukan hukuman mati yang sangat ketat. Hukuman mati tidak hanya dikenakan pada pelaku kejahatan modal, tetapi juga pada penuduh yang gagal membuktikan tuduhan kejahatan modalnya. Bahkan, saksi yang tidak dapat mengidentifikasi barang yang hilang dalam waktu enam bulan dapat dianggap sebagai “pelaku kejahatan” dan dijatuhi hukuman. Ancaman serius terhadap tuduhan palsu ini menunjukkan penekanan ekstrem pada pembuktian. Prosedur ini, meskipun bertujuan menjamin kepastian hukum, menciptakan risiko yang sangat tinggi bagi pelapor dan tertuduh, suatu kontras tajam dengan perlindungan prosedural yang ditekankan dalam hukum modern.
Hukum Romawi: Evolusi dari Ius Civile menuju Universalitas Ius Gentium
Hukum Romawi menawarkan lintasan sejarah yang berbeda, terutama dalam hal perluasan ruang lingkup subjek hukum. Pada masa awal Republik Romawi, Ius Civile (hukum sipil) dikembangkan berdasarkan kebiasaan atau legislasi dan diterapkan secara eksklusif kepada warga negara Romawi. Sistem ini, meskipun canggih, membatasi akses keadilan penuh berdasarkan kewarganegaraan.
Titik balik filosofis terjadi pada pertengahan abad ke-3 SM dengan pengembangan Ius Gentium (hukum bangsa-bangsa). Ius Gentium adalah sistem hukum yang dirancang untuk diterapkan pada warga Romawi dan non-Romawi yang berinteraksi dalam kekaisaran. Konsep ini secara historis lebih maju dalam hal universalitas dibandingkan hukum Babilonia yang berbasis status kelas kaku.
Ius Gentium dianggap sebagai bentuk dari Ius Naturale (hukum alam), karena aturannya dipercaya dapat diturunkan dari akal alami (natural reason) yang melekat pada seluruh umat manusia. Pelepasan hukum dari ikatan kasta atau kewarganegaraan tertentu ini menciptakan cetak biru filosofis yang krusial. Konsep ini menjadi fondasi bagi hukum kanon Eropa dan, yang paling penting, merupakan cikal bakal Hukum Internasional modern. Dengan demikian, warisan Romawi, melalui ius gentium, meletakkan dasar bagi kesetaraan universal yang menjadi esensi Hak Asasi Manusia modern, menempatkannya sebagai jembatan penting dari hukum kuno yang stratifikasi ke universalitas kontemporer.
Perbandingan Tema Kunci (Fokus 1): Dari Lex Talionis ke Keadilan Proporsional dan Restoratif
Pemahaman Mendalam Lex Talionis
Prinsip lex talionis (“mata ganti mata, gigi ganti gigi”) adalah inti yang paling sering diidentifikasi dari hukum retributif kuno, khususnya Kode Hammurabi. Meskipun interpretasi populer mengaitkannya dengan “balas dendam liar,” fungsi historis lex talionis jauh lebih bernuansa. Dalam konteks yudisial, prinsip ini dimaksudkan sebagai kebijakan peradilan yang berfungsi sebagai batasan proporsionalitas awal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau pengadilan tidak melebihi kerugian yang ditimbulkan, sehingga membatasi siklus vendetta pribadi yang tidak terkontrol. Dengan kata lain, ia menetapkan batas atas pembalasan.
Namun, penerapan lex talionis dalam Kode Hammurabi didominasi oleh diskriminasi yang berbasis status sosial. Prinsip ini ditegakkan, tetapi pelaksanaannya dibedakan menurut status sosial korban dan pelaku. Jika orang bebas melukai bangsawan, pembalasan fisik mungkin berlaku. Sebaliknya, jika orang bebas melukai budak atau individu dari status yang lebih rendah, kompensasi berupa gandum, uang, atau barang sering menggantikan pembalasan fisik yang setara. Diskriminasi ini menunjukkan bahwa meskipun Kode Hammurabi memperkenalkan konsep proporsionalitas, ia gagal mencapai prinsip kesetaraan fundamental modern.
Transformasi Menuju Proporsionalitas dan Konvergensi Hukuman Modern
Hukum modern telah berevolusi melewati kerangka retribusi kaku. Evolusi teori pemidanaan kontemporer berfokus pada tujuan multi-dimensi, termasuk pencegahan (deterrence), rehabilitasi (untuk reintegrasi pelaku ke masyarakat), dan keadilan restoratif.
Prinsip lex talionis telah berevolusi menjadi konsep retribusi modern, di mana sanksi harus setara dengan kesalahan, tetapi harus disalurkan melalui mekanisme negara, bukan pembalasan pribadi. Evolusi ini kemudian diperkuat dengan konvergensi antara konsep retributif dan rehabilitatif dalam filosofi hukum pidana kontemporer. Meskipun fokus utamanya bergeser ke pemulihan , aspek retribusi (rasa keadilan dan kepantasan hukuman) tetap penting untuk melegitimasi penghukuman di mata publik dan mencegah anggapan bahwa hukum terlalu lunak.
Pentingnya Proporsionalitas telah meningkat secara signifikan, melampaui sekadar penentuan sanksi pidana. Proporsionalitas modern kini menjadi alat pengujian konstitusional (proportionality test atau the ultimate rule of law) yang digunakan oleh berbagai peradilan konstitusi. Uji ini memastikan bahwa pembatasan terhadap hak-hak warga negara adalah sah, perlu, dan setimpal. Sebagai contoh, penerapan Pasal 21 UU Tipikor di Indonesia, yang memberikan ancaman hukuman tegas (3-12 tahun penjara), harus proporsional dengan tujuan menjaga integritas dan kelancaran proses hukum, menunjukkan proporsionalitas yang canggih dan multidimensi. Ini jauh melampaui proporsionalitas kuantitatif lex talionis.
Keadilan Restoratif: Menantang Retribusi Kaku
Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice – RJ) semakin menantang pendekatan retributif kuno. RJ berfokus pada pemulihan korban dan komunitas. RJ menganjurkan pemulihan “community bond” dan menentang isolasi pelaku, khususnya pada remaja, yang dianggap justru memicu kejahatan lebih lanjut.
Meskipun RJ mungkin tampak sebagai konsep baru, fokusnya pada pemulihan dan penyelesaian damai melalui mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik secara ironis mungkin memiliki resonansi dengan sistem penyelesaian konflik komunal kuno. Namun, RJ modern harus berhati-hati dalam penerapannya. Ada risiko instrumentalisasi tradisi yang dapat mengarah pada relativisme kultural atau memperkuat struktur hierarkis sosial lama, yang bertentangan dengan prinsip HAM universal.
Tabel 1: Pergeseran Filosofi Pemidanaan
| Dimensi | Kode Hammurabi (Lex Talionis) | Hukum Pidana Modern (Kontemporer) |
| Filosofi Utama | Retribusi Kaku (Pembalasan Setimpal) | Rehabilitasi, Keadilan Restoratif, Pencegahan |
| Prinsip Proporsionalitas | Kuantitatif, Kaku (Fisik atau Setara Barang/Uang) | Kualitatif, Multi-Faktor (Uji Proporsionalitas Konstitusional) |
| Status Sosial | Diskriminasi Tegas Berdasarkan Kelas | Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (Non-Diskriminasi) |
Perbandingan Tema Kunci (Fokus 2): Evolusi Hak-Hak Individu dan Universalitas
Diskriminasi Kuno dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Modern
Salah satu aspek hukum kuno yang paling keras mengguncang kesadaran moral pengadilan modern adalah legalisasi stratifikasi sosial dan diskriminasi dalam pelaksanaan keadilan. Sistem seperti Kode Hammurabi secara eksplisit mendefinisikan hukuman yang berbeda berdasarkan status sosial (bangsawan, orang bebas, atau budak). Hukum kuno memandang individu melalui lensa hierarki sosial, bukan kesetaraan intrinsik.
Prinsip ini bertentangan secara frontal dengan fondasi Hak Asasi Manusia (HAM) modern. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR 1948) yang diadopsi oleh PBB menegaskan prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi, Hak untuk Hidup, dan Hak untuk Mengakses Keadilan. Pelanggaran hak asasi yang paling mendasar dalam hukum kuno tidak hanya terletak pada diskriminasi status, tetapi juga pada prosedur hukumnya. Metode pembuktian seperti trial by ordeal—yang mengancam nyawa tertuduh jika gagal dalam ujian—secara radikal menantang asas praduga tak bersalah dan hak atas proses hukum yang adil (due process). Penolakan modern terhadap praktik-praktik ini menandai pematangan peradaban dalam menjamin perlindungan individu di hadapan negara.
Warisan Romawi dan Fondasi Universalitas Hukum Modern
Perkembangan ius gentium dalam Hukum Romawi merupakan tonggak penting yang menyediakan landasan filosofis bagi universalitas hukum modern. Ius gentium melepaskan hukum dari ikatan teritorial atau kewarganegaraan, berkat dasarnya pada akal alami (natural reason) yang diyakini melekat pada seluruh umat manusia.
Meskipun konsep ius gentium mulai terfragmentasi seiring dengan bangkitnya negara-negara individual dan penurunan otoritas Paus pada abad ke-16 , warisan filosofisnya tentang hukum yang transenden (melampaui batas negara) tetap kuat. Prinsip universal yang dibangun Romawi menjadi dasar bagi pengembangan Hukum Internasional modern, termasuk konsep jus cogens (norma imperatif).
Tantangan Universalitas Hukum di Era Modern
Meskipun ius gentium adalah fondasi universalitas, hukum modern menghadapi dilema dalam penerapannya. Konsep HAM modern mewarisi prinsip universal ini , tetapi sering kali berhadapan dengan relativisme kultural atau upaya untuk menginstrumentalisasi tradisi kuno dalam konteks modern. Studi perbandingan hukum saat ini harus menganalisis bagaimana hukum nasional bernegosiasi dengan hukum internasional, terutama dalam menjamin ketaatan perjanjian internasional yang non-diskriminasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik hukum yang diklaim ‘tradisional’ atau ‘komunal’, seperti beberapa bentuk Keadilan Restoratif, tidak secara tidak sengaja menegakkan kembali struktur hierarkis sosial yang dilarang oleh prinsip universalitas Romawi yang telah berevolusi menjadi HAM modern.
Perbandingan Tema Kunci (Fokus 3): Sistem Pemerintahan dan Peran Yudisial
Struktur Kodifikasi dan Legitimasi Hukum (Dari Raja ke Konstitusi)
Struktur sistem hukum modern, terutama dalam tradisi Civil Law, berutang besar pada inisiatif kodifikasi kuno. Legitimasi hukum kuno sangat berakar pada kekuasaan sentral dan, seringkali, legitimasi ilahi. Raja Hammurabi adalah contoh klasik seorang penguasa yang mengklaim kekuasaan hukumnya sebagai pemberian dewa.
Setelah keruntuhan Romawi, kodifikasi tersebut menjadi dasar bagi sistem Civil Law yang mendominasi Eropa Kontinental dan menyebar ke banyak negara di dunia. Dalam sistem ini, kodifikasi memastikan kepastian dan stabilitas hukum, menjadikan undang-undang tertulis yang komprehensif sebagai sumber hukum utama. Sistem ini kontras dengan sistem kuno, di mana legitimasi tertinggi kini bergeser dari kekuasaan monarki/teokratis ke kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui Konstitusi dan nilai-nilai HAM.
Peran Hakim: Konflik antara Penafsir Teks dan Pencipta Hukum
Tradisi Romawi memengaruhi peran hakim secara mendalam dalam sistem Civil Law. Secara tradisional, tugas utama hakim adalah menafsirkan hukum secara tekstual dan sistematis (judicial restraint), menggunakan metode interpretasi gramatikal untuk memahami arti kata-kata dalam undang-undang. Dalam pandangan klasik ini, hakim tidak memiliki kebebasan untuk menciptakan preseden baru seperti dalam sistem Common Law.
Namun, kompleksitas masyarakat modern telah menciptakan krisis peran bagi hakim. Sebagaimana disinggung sebelumnya, hukum tertulis sering tertinggal di belakang perkembangan masyarakat. Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara, meskipun mereka menjumpai “kekosongan hukum”.
Dalam menghadapi kekosongan ini, hakim modern dituntut melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum tidak hanya melibatkan interpretasi, tetapi juga melengkapi atau mengisi peraturan hukum. Pendekatan ini sesuai dengan aliran “sistem terbuka” hukum, yang menyatakan bahwa setiap penafsiran dan putusan mengandung unsur penciptaan. Fenomena ini, yang dikenal sebagai Judicial Activism (keaktifan yudisial), menimbulkan dilema yurisprudensial yang signifikan dalam sistem Civil Law modern. Hakim harus menyeimbangkan antara menghormati teks undang-undang warisan Romawi (judicial restraint) dan tuntutan keadilan substantif kontemporer, bergerak menuju Judicial Prudence. Dengan demikian, warisan positivisme kaku Romawi telah dimodifikasi oleh kebutuhan substantif keadilan kontemporer.
Independensi Peradilan: Syarat Mutlak Keadilan Modern
Dalam sistem teokratis atau monarkis kuno, meskipun terdapat proklamasi keadilan oleh penguasa, pengadilan dan proses hukum sangat terikat pada kehendak raja. Raja Hammurabi sendiri menegaskan dirinya sebagai pembawa keadilan dalam epilognya , yang menunjukkan bahwa legitimasi keadilan terpusat pada otoritas eksekutif.
Sebaliknya, independensi dan imparsialitas hakim adalah syarat fundamental yang tidak dapat diganggu gugat dalam negara hukum modern. Syarat ini krusial untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan tanpa intervensi politik atau kekuasaan eksekutif. Meskipun demikian, tantangan terhadap independensi tetap ada, terutama dalam sistem Civil Law di mana fungsi penegakan hukum (seperti kepolisian dan kejaksaan) dapat berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif, yang secara fungsional dapat memengaruhi independensi yudisial dalam tahapan proses hukum.
Tabel 2: Perbandingan Peran Hakim dalam Sistem Hukum
| Aspek Yudisial | Hukum Kuno (Hammurabi) | Civil Law Tradisional (Warisan Romawi) | Pengadilan Modern (Civil Law Kontemporer) |
| Legitimasi | Teokratis/Monarkis | Positivisme Legislatif | Konstitusi dan Nilai HAM/Keadilan |
| Fungsi Utama | Penerapan Kaku Teks Casuistic | Interpretasi Teks Gramatikal/Sistematis | Penemuan Hukum (Judicial Activism) dan Pengisian Kekosongan |
| Diskriminasi | Eksplisit Berdasarkan Status Sosial | Non-Diskriminasi (Prinsip Formal) | Non-Diskriminasi dan Perlindungan HAM Universal |
Kesimpulan dan Implikasi Yurisprudensial Modern
Jejak Kuno yang Masih Beresonansi di Pengadilan Modern
Analisis komparatif menunjukkan bahwa sistem hukum kuno, terutama Kode Hammurabi dan Hukum Romawi, adalah fondasi tak terhindarkan bagi sistem peradilan modern. Kontinuitas utama terletak pada fondasi struktural: inisiatif kodifikasi Babilonia memberikan kepastian hukum dan stabilitas, sementara Hukum Romawi memberikan metode sistematis untuk pengembangan hukum.
Warisan filosofis paling berharga dari masa lalu adalah konsep Ius Gentium Romawi. Prinsip ini, yang didasarkan pada akal alami yang universal , merupakan titik awal pergeseran fundamental menuju kesetaraan manusia, yang kemudian menjadi inti dari Hukum Internasional dan prinsip jus cogens saat ini.
Bagaimana Konsep Kuno Mengguncang Pengadilan Modern: Peringatan Kritis
Guncangan paling signifikan yang ditimbulkan oleh hukum kuno terhadap pengadilan modern adalah melalui perannya sebagai cermin kritis. Hukum kuno berfungsi sebagai peringatan keras terhadap bahaya stratifikasi sosial dan hukuman berbasis status. Penolakan radikal terhadap lex talionis berbasis kelas dan praktik prosedural yang melanggar hak asasi, seperti trial by ordeal , menandai kemenangan hak individu universal.
Evolusi yurisprudensial dari retribusi kaku menuju konvergensi rehabilitasi dan keadilan restoratif menunjukkan pematangan moral peradaban. Hukum modern harus secara konstan menyeimbangkan kebutuhan akan kepastian hukum (warisan kuno) dengan tuntutan keadilan substantif yang berpusat pada pemulihan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, hukum kuno mengingatkan para praktisi modern tentang pentingnya Prinsip Proporsionalitas sebagai alat untuk mengendalikan kekuasaan, sebuah prinsip yang kini berevolusi dari batasan pembalasan fisik menjadi uji konstitusional yang kompleks terhadap pembatasan hak.
Rekomendasi untuk Kajian Lanjutan dalam Hukum Perbandingan
Berdasarkan analisis ini, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang berfokus pada:
- Implementasi Keadilan Restoratif:Menganalisis bagaimana implementasi praktis Keadilan Restoratif dalam yurisdiksi seperti Indonesia dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip HAM universal, sambil secara proaktif mengatasi risiko relativisme kultural atau instrumentalisasi tradisi yang dapat secara tidak sengaja menegakkan kembali struktur hierarkis sosial kuno.
- Dinamika Yudisial:Mengkaji lebih lanjut sejauh mana Judicial Activism dalam sistem Civil Law kontemporer telah berhasil menjembatani kesenjangan antara warisan kaku Judicial Restraint Romawi dan tuntutan mendesak keadilan substantif dan penemuan hukum di era kontemporer.