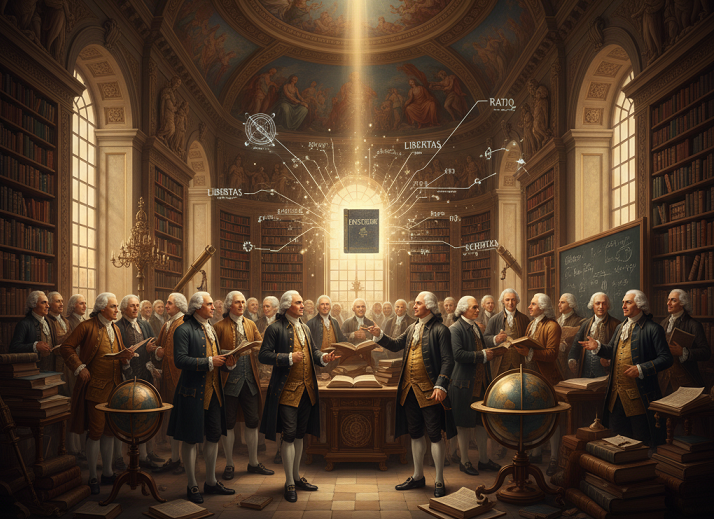Kritik atas Narasi Eurosentris Pencerahan (The Great European Enlightenment Myth)
Pencerahan Eropa, yang lazim didefinisikan sebagai proyek intelektual abad ke-18 yang berpusat pada rasionalitas instrumental, humanisme, dan otonomi moral, secara historis telah diposisikan sebagai sumber tunggal modernitas global. Narasi ini, yang seringkali bersifat Eurosentris, mengklaim universalitas prinsip-prinsipnya, seperti hak asasi manusia dan pemerintahan berdasarkan nalar. Namun, di saat klaim-klaim ini diartikulasikan di pusat-pusat Eropa, kekuatan-kekuatan yang sama menggunakan rasionalitas instrumental untuk melegitimasi dan mengoperasionalisasikan penindasan kolonial yang brutal di Global Selatan. Inilah kontradiksi mendasar dari Pencerahan Eropa: klaim universalitas yang digunakan untuk membenarkan penindasan partikularistik.
Oleh karena itu, kajian Pencerahan harus didekati melalui kerangka teori poskolonial untuk menelusuri warisan kolonial dalam identitas dan budaya. Pendekatan ini secara mendasar menantang hegemoni epistemik, yaitu pandangan bahwa ide-ide modernitas adalah produk transmisi satu arah dari Eropa ke dunia jajahan. Pencerahan yang diperjuangkan oleh para pemikir di pinggiran (Afrika, Asia, Timur Tengah) secara inheren berbeda. Meskipun mereka mengadopsi prinsip rasionalitas, mereka melakukannya bukan sebagai penerima pasif ide-ide Barat, tetapi sebagai agen aktif yang menggunakan alat ini untuk mengkritik sistem yang menindas mereka. Jika Pencerahan diidentikkan dengan peningkatan kesadaran dan wawasan yang mengarah pada perubahan lingkungan sosial budaya yang rasional dan lebih manusiawi , maka pemikir di pinggiran harus merebut kembali dan mendefinisikan ulang rasionalitas tersebut sebagai alat untuk melawan hegemoni kekuasaan dan ideologi kolonial, bukan sekadar menirunya. Ini adalah Pencerahan yang bersifat dekolonial.
Teori Pinggiran (The Periphery) dan Dinamika Pusat-Pinggiran
Untuk memahami produksi pengetahuan di luar kanon Barat, sangat penting untuk menggunakan kerangka teori poskolonial. Kerangka ini menyoroti politik oposisi dan perjuangan yang muncul dari dinamika antara pusat dan pinggiran, bertujuan untuk memproblematisasi dan “mengacaukan penghalang” di sekitar kanon sastra dan filosofis Barat yang secara historis melindungi keutamaan standar dan bukti diri mereka. Teori sosial poskolonial menegaskan bahwa dalam klasifikasi ilmiah, pemahaman, dan penelitian, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kepentingan, kekuasaan, dan ideologi.
Para arsitek Pencerahan yang dibahas dalam laporan ini, seperti Raja Ram Mohan Roy dan Jose Rizal, seringkali berasal dari kelas elit yang terdidik (misalnya, Ilustrado di Filipina). Posisi sosial ini, yang lahir dari perubahan politik dan ekonomi abad ke-19 , memberi mereka akses vital untuk artikulasi ide-ide Pencerahan. Namun, keberhasilan dan relevansi mereka terletak pada kemampuan mereka untuk mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip universal ini—seperti humanisme dan rasionalitas—untuk mengatasi isu-isu lokal dan memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan (subaltern). Penting untuk menekankan bahwa diskusi tentang individu kolonial atau poskolonial harus ditempatkan dalam konteks spesifik mereka—gender, sosial, geografis, dan historis—untuk memahami berbagai pengalaman kolonial dan poskolonial. Meskipun mereka adalah elit, kritik mereka terhadap penindasan klerikal atau praktik sosial regresif (seperti Sati) menunjukkan dedikasi mereka pada pembebasan subaltern.
Sinkronisitas Intelektual: Paralelisme dan Konvergensi Ide
Penempatan pemikir dari pinggiran dalam garis waktu historis yang sama dengan rekan-rekan mereka di Eropa menunjukkan bahwa modernitas intelektual bukanlah hasil transmisi yang terlambat, melainkan hasil dari dialog dan produksi pengetahuan yang sinkron secara global. Para tokoh ini tidak hanya “mengimpor” Pencerahan; mereka terlibat dalam konvergensi ide, seringkali berjuang dengan dilema yang sama mengenai otonomi moral dan hubungan antara individu dan negara, meskipun dalam konteks opresi kolonial.
Tabel berikut menunjukkan perbandingan kronologis untuk menegaskan bahwa para arsitek pinggiran ini adalah kontemporer sejati dari filsuf-filsuf Eropa, yang ide-ide mereka berkembang secara paralel dan independen, namun secara cerdik disintesis untuk tujuan kritis lokal:
Tabel 1: Perbandingan Kronologis Pencerahan: Pusat vs. Pinggiran
| Tokoh (Pusat) | Masa Hidup | Fokus Filosofis Utama | Tokoh (Pinggiran) | Masa Hidup | Fokus Kritis Lokal | Teks Kunci |
| Immanuel Kant | 1724–1804 | Otonomi Moral, Sapere Aude | Raja Ram Mohan Roy | 1772–1833 | Reformasi Sosial, Monoteisme | Tuhfat-ul-Muwahhidin |
| John Stuart Mill | 1806–1873 | Utilitarianisme, Kebebasan Individu | Rifa’a al-Tahtawi | 1801–1873 | Modernisasi Hukum, Pendidikan Patriotik | Takhlis al-Ibriz |
| Friedrich Nietzsche | 1844–1900 | Kritik Moralitas, Kehendak Berkuasa | Jose Rizal | 1861–1896 | Kritik Klerikal, Nasionalisme Revolusioner | Noli Me Tángere |
Dinamika Intelektual Abad ke-19: Inkubasi Pencerahan Pinggiran
Pendidikan Elit Lokal dan Munculnya Kritik Internal
Abad ke-19 adalah periode transformasi besar di mana struktur kolonial—didukung oleh perubahan politik dan ekonomi—secara tidak sengaja menciptakan kelas intelektual yang akhirnya menjadi algojo mereka sendiri. Di Filipina, kelompok ini disebut Ilustrado (yang tercerahkan); di Mesir, muncul Effendiyyah. Jose Rizal adalah contoh utama dari Ilustrado yang konteks kemunculannya dipicu oleh perubahan struktur elit kolonial. Akses ke pendidikan Eropa memberikan mereka kerangka berpikir rasionalis dan liberal, yang ironisnya menjadi alat untuk menganalisis dan membongkar sistem kolonial yang membesarkan mereka.
Kontradiksi yang dihadapi oleh elit yang terdidik ini adalah inti dari Pencerahan di pinggiran. Kolonialisme menjanjikan rasionalitas universal dan kemajuan melalui pendidikannya, namun secara konsisten menolak penerapan universal prinsip-prinsip tersebut kepada penduduk koloni. Ketika prinsip Pencerahan (seperti kesetaraan dan kebebasan) diterapkan pada realitas kolonial, hasilnya adalah kritik paling tajam. Para intelektual ini menyadari bahwa diskrepansi antara klaim kolonial dan kenyataan penindasan memerlukan dekonstruksi sistem, bukan reformasi sederhana.
Jaringan Global dan Diaspora Intelektual
Peran diaspora intelektual dan mobilitas geografis sangat vital. Perjalanan ke pusat-pusat kolonial, seperti Spanyol atau Prancis, berfungsi sebagai laboratorium penting bagi kritik anti-kolonial. Di Eropa, para pemikir ini memiliki kesempatan untuk membandingkan idealisme Pencerahan dengan praktik sosial politik di Eropa dan, yang lebih penting, memperkuat argumen mereka terhadap opresi yang diderita tanah air mereka. Rizal dan Rifa’a al-Tahtawi, misalnya, menggunakan pengalaman mereka di Eropa untuk mengasah visi mereka tentang modernitas lokal.
Selain mobilitas fisik, media cetak berperan sebagai wahana utama penyebaran ide-ide Pencerahan. Raja Ram Mohan Roy, yang dikenal karena pengaruhnya dalam politik, administrasi publik, pendidikan, dan agama , memanfaatkan jurnalisme dan publikasi untuk membentuk opini publik. Ia mendirikan dan menulis untuk surat kabar yang menyebarkan gagasan reformasi sosial dan rasionalisme. Penggunaan media ini memungkinkan ide-ide Pencerahan untuk menembus batas-batas elit dan mencapai khalayak yang lebih luas, menumbuhkan kesadaran kolektif yang esensial untuk gerakan kemerdekaan.
Rasionalitas Ganda: Reformasi Sosial dan Perlawanan Politik
Para arsitek Pencerahan di pinggiran harus menghadapi dua front secara bersamaan: opresi kolonial eksternal dan kebutuhan mendesak akan reformasi sosial internal yang rasional. Penerapan logika Pencerahan oleh tokoh seperti Raja Ram Mohan Roy untuk mengatasi stagnasi dan praktik regresif internal merupakan strategi perlawanan yang cerdik.
Kolonis seringkali membenarkan kekuasaan mereka dengan mengklaim bahwa masyarakat yang dijajah tidak rasional atau barbar, merujuk pada praktik-praktik tertentu. Dengan secara agresif menargetkan dan menghilangkan praktik “barbar” seperti Sati , Roy secara efektif menghilangkan pembenaran moral yang paling kuat bagi kekuasaan Inggris. Perjuangan Roy untuk mempromosikan martabat, kesetaraan, dan keadilan bagi semua adalah aplikasi langsung dari humanisme Pencerahan. Dengan menunjukkan bahwa masyarakat India mampu melakukan reformasi internal berdasarkan nalar dan etika, ia memperkuat klaim martabat India dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri secara beradab, sehingga menjadikan reformasi sosial sebagai tindakan anti-kolonial yang mendalam.
Studi Kasus I: Raja Ram Mohan Roy (1772–1833) dan Fajar Rasionalisme Bengal
Brahmo Samaj dan Fondasi Monoteisme Rasional
Raja Ram Mohan Roy, yang dihormati sebagai “Bapak India Modern” dan “Bapak Renaisans India” , merupakan arsitek utama Renaisans Bengal. Ia adalah figur kunci yang mengintegrasikan pengetahuan Barat dengan kearifan tradisional India, meletakkan dasar bagi Vedantisme modern.
Pada tahun 1828, Roy mendirikan Brahmo Samaj (pendahulu Brahmo Sabha), sebuah gerakan reformasi sosio-religius. Sebelumnya, ia mendirikan Atmiya Sabha pada tahun 1814 sebagai lingkaran diskusi filosofis di Kolkata untuk mengatasi masalah pemujaan berhala (idolatry), struktur kasta yang kaku, dan ritual yang dianggap tidak berarti. Melalui Brahmo Samaj, Roy memformalkan Monoteisme etis, yang berfokus pada penyembahan entitas ilahi tunggal, menekankan etika di atas ritual. Secara filosofis, pendekatan ini merupakan sintesis rasionalis Pencerahan dan Upanishad. Dengan mempromosikan monoteisme murni yang rasional (mirip dengan Deisme Pencerahan), Roy memberikan landasan spiritual India yang setara atau bahkan unggul secara moral dibandingkan dengan agama-agama Barat, secara cerdas memutus kebutuhan untuk membuang tradisi demi menjadi modern.
Proyek Kemanusiaan dan Reformasi Sosial
Kontribusi Roy yang paling ikonik adalah kampanye kerasnya melawan praktik Sati, di mana para janda dipaksa membakar diri. Ini adalah demonstrasi paling kuat dari aplikasinya terhadap humanisme Pencerahan, berjuang untuk nilai-nilai yang menjamin martabat dan kehidupan. Kampanye ini berhasil, dan praktik Sati dilarang pada tahun 1829.
Selain Sati, Raja Ram Mohan Roy juga secara tegas menentang pernikahan anak dan poligami yang tersebar luas. Ia berjuang untuk menghapus berbagai kejahatan sosial, mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan martabat bagi semua orang, termasuk advokasi hak-hak perempuan. Komitmennya terhadap reformasi sosial bersifat transformatif, meletakkan dasar bagi masyarakat yang lebih tercerahkan.
Pendidikan dan Kontribusi Linguistik
Dalam domain pendidikan, Roy adalah seorang visioner. Ia mengadvokasi pendidikan modern yang memadukan pengetahuan tradisional India dengan sains Barat, menekankan pentingnya pendidikan bahasa Inggris untuk pemberdayaan intelektual India. Baginya, mengakses sains Barat bukanlah penyerahan diri, melainkan akuisisi alat untuk emansipasi.
Ia juga berkontribusi pada pengembangan bahasa lokal. Roy menulis Gaudiya Vyakaran, tata bahasa Bangla lengkap pertama. Upaya ini menunjukkan kesadaran bahwa untuk menginternalisasi dan menyebarluaskan ide-ide Pencerahan, bahasa lokal harus dimodernisasi, memastikan bahwa diskursus modernitas dapat berakar kuat dalam konteks Bengal.
Studi Kasus II: Jose Rizal (1861–1896): Pencerahan, Kritik Kolonial, dan Identitas Filipina
Rizal dan Munculnya Elit Kolonial yang Kritis
Jose Rizal adalah figur yang sangat penting bagi sejarah intelektual Filipina, muncul dari kelas Ilustrado, elit kolonial yang terdidik di abad ke-19. Perkembangannya sebagai kritikus radikal adalah hasil dari konteks politik dan ekonomi abad ke-19 di Kepulauan Filipina. Rizal menggunakan pendidikan yang ia peroleh untuk mengubah dirinya dari anggota elit menjadi suara yang menantang hegemoni Spanyol.
Berbeda dengan beberapa kontemporer di Asia yang fokus pada reformasi agama internal, Rizal mengarahkan kritik Pencerahan secara langsung dan frontal pada struktur opresif eksternal, yaitu rezim kolonial Spanyol dan, yang terpenting, dominasi klerikal (kekuatan para biarawan). Sasaran kritiknya adalah kemunafikan sistem yang mengklaim membawa iman dan peradaban, padahal hanya menjalankan tirani.
Noli Me Tángere sebagai Traktat Politik Pencerahan
Novel-novel Rizal, terutama Noli Me Tángere, berfungsi sebagai analisis sosiologis dan traktat Pencerahan. Novel ini bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi studi kasus rasional yang mengungkap penyakit masyarakat dan opresi kolonial Spanyol. Melalui sastra, Rizal secara ilmiah menganalisis korupsi, kesewenang-wenangan, dan kekejaman yang dilegitimasi oleh aliansi antara Negara dan Gereja.
Rizal secara implisit dan eksplisit menuntut prinsip-prinsip Pencerahan: sekularisme, kebebasan individu, dan tuntutan agar otoritas tunduk pada akal sehat dan hukum. Noli Me Tángere secara efektif menggunakan rasionalitas sebagai senjata untuk mendiagnosis kelemahan dan penyakit masyarakat, menunjukkan bahwa Filipina tidak sakit secara inheren, tetapi sakit karena ulah kolonialisme Spanyol.
Ide Sekularisme dan Nasionalisme Revolusioner
Rizal menerapkan hak-hak universal Pencerahan untuk menuntut otonomi dan kesetaraan bagi orang Filipina. Pemikirannya mengarah pada penciptaan ide “Nasionalisme Bawaan.” Mengadopsi konsep Pencerahan tentang kedaulatan rakyat dan negara-bangsa, Rizal berpendapat bahwa orang Filipina memiliki hak kodrati untuk mendefinisikan identitas mereka sendiri, terlepas dari narasi kolonial Spanyol.
Ia menuntut agar hak-hak universal harus diterapkan secara setara, menantang penguasa yang mengklaim diri sebagai pembawa peradaban tetapi menolak hak-hak dasar warganya sendiri. Meskipun Rizal sendiri menganjurkan reformasi damai, diagnosis rasionalnya melalui Noli Me Tángere memberikan landasan filosofis yang kuat bagi Revolusi Filipina yang meletus kemudian. Pemikirannya mengubah perjuangan melawan Spanyol dari pemberontakan sporadis menjadi perang kemerdekaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip politik Pencerahan.
Kasus III: Rifa’a al-Tahtawi (1801–1873): Reformasi Pendidikan dan Patriotisme Mesir
Misi Paris dan Pengalaman Transfer Epistemik
Rifa’a al-Tahtawi adalah tokoh sentral dalam proyek nahda (kebangkitan) Mesir di bawah Muhammad Ali Pasha. Sebagai imam yang dikirim untuk mendampingi misi pendidikan di Paris pada tahun 1826, Tahtawi memiliki kesempatan unik untuk mengamati masyarakat, sains, dan institusi politik Eropa secara langsung.
Pengalamannya menghasilkan Takhlis al-Ibriz fi Talkhis Bariz. Karya ini berfungsi sebagai teks Pencerahan Arab yang sistematis, menawarkan analisis kritis tentang modernitas Eropa dan mengadvokasi penerapan prinsip-prinsipnya (terutama hukum, sains, dan ketertiban sipil) di Mesir. Tahtawi bertindak sebagai jembatan intelektual, menginterpretasikan dan menyaring modernitas Eropa, menunjukkan bahwa kemajuan tidak perlu menunggu izin dari Barat, tetapi dapat diimpor dan diolah secara mandiri.
Penerjemahan, Pendidikan, dan Ilmu Pengetahuan
Peran Tahtawi dalam mendirikan dan memimpin Sekolah Bahasa (kemudian Al-Alsun) di Mesir sangatlah transformatif. Ia mengawasi proyek penerjemahan besar-besaran, yang mencakup teks-teks hukum, filosofis, dan ilmiah ke dalam bahasa Arab. Kontrol atas mekanisme intelektual ini adalah kunci dekolonisasi pengetahuan.
Melalui proyek penerjemahan, Tahtawi melakukan indigenisasi Pencerahan. Ia memastikan bahwa bahasa Arab dapat berfungsi sebagai bahasa modernitas yang fungsional, memutus ketergantungan epistemik pada bahasa kolonial seperti Prancis. Tindakan ini memungkinkan Mesir untuk mengimpor ilmu pengetahuan dan rasionalitas hukum tanpa mengimpor ideologi ketergantungan yang menyertainya. Tahtawi menunjukkan bahwa kemajuan institusional hanya mungkin terjadi jika fondasi pengetahuan dapat diakses dan diinternalisasi dalam bahasa ibu.
Sintesis Watan (Tanah Air) dan Visi Modernitas Islam
Tahtawi memperkenalkan konsep watan (tanah air) dan patriotisme sipil yang didasarkan pada kesetiaan kepada negara, hukum, dan institusi modern—suatu gagasan yang sangat kental dengan konsep negara-bangsa Pencerahan. Konsep patriotisme konstitusional ini merupakan pergeseran dari kesetiaan yang didominasi oleh faktor agama atau dinasti.
Lebih lanjut, Tahtawi berargumen bahwa prinsip-prinsip kemajuan Eropa—seperti hukum kodifikasi, sistem pendidikan modern, dan penekanan pada nalar—sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran fundamental Islam yang rasional. Ia mendorong reformasi internal dan menolak pandangan bahwa Islam secara inheren anti-modern. Visi ini memungkinkan Mesir untuk merangkul modernitas dengan mempertahankan identitas Islamnya, menunjukkan bahwa Pencerahan dapat disintesis dengan tradisi keagamaan untuk menghasilkan jalan menuju kemajuan yang otonom.
Warisan Intelektual dan Relevansi Kontemporer (Kesimpulan Sintetik)
Para arsitek Pencerahan yang terlupakan ini berhasil karena otonomi intelektual mereka: kemampuan untuk membedakan antara prinsip-prinsip universal Pencerahan (rasionalitas, humanisme) dan manifestasi institusionalnya yang korup (imperialisme dan praktik regresif internal). Mereka secara strategis menyaring dan mengawinkan ide-ide Pencerahan dengan isu-isu lokal untuk mencapai tujuan emansipasi.
Sintesis akhir ini merangkum strategi adaptasi Pencerahan di pinggiran melalui tiga mekanisme yang berbeda namun saling melengkapi:
- Reformasi Sosio-Religius (Roy):Menggunakan rasionalitas untuk membersihkan dan memperkuat tradisi , menghilangkan pembenaran moral kolonial.
- Kritik Politik-Klerikal (Rizal):Menggunakan rasionalitas untuk menelanjangi opresi kolonial dan tirani klerikal , memicu kesadaran nasional yang revolusioner.
- Transfer Epistemik-Institusional (Tahtawi):Menggunakan rasionalitas untuk membangun kapasitas negara modern melalui penerjemahan dan pendidikan, menjamin modernitas yang mandiri.
Strategi-strategi ini secara kolektif membuktikan bahwa modernitas intelektual bukanlah hasil dari kepatuhan pasif terhadap Eropa, tetapi hasil dialektika kritis yang diarahkan oleh kebutuhan lokal akan pembebasan.
Pemikiran yang dihasilkan oleh para arsitek ini merupakan kontra-narasi global yang kuat. Mereka memberikan bukti historis yang meyakinkan bahwa modernitas intelektual tidak dimonopoli oleh geografi tertentu. Sebagai pemikir universal yang bergulat dengan isu-isu hak asasi, nalar, dan kebebasan, mereka menantang kanon sejarah intelektual yang cenderung mereduksi kontribusi non-Barat menjadi sekadar imitasi atau reaksi.
Dari perspektif teoritis, karya mereka secara de facto memvalidasi kerangka poskolonial, yang menyoroti perlunya memprioritaskan suara-suara dari pinggiran untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengetahuan. Dengan mengacaukan hubungan pusat-pinggiran , mereka menunjukkan bahwa perjuangan politik oposisi dan perjuangan epistemik adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pemikiran mereka adalah pengingat bahwa pencerahan sejati adalah proses kritis yang digunakan untuk kebebasan, terlepas dari sumber geografisnya.
Warisan Pencerahan di pinggiran memiliki implikasi kritis bagi studi kontemporer dan kurikulum akademis.
Implikasi dan Rekomendasi:
- Integrasi ke dalam Kurikulum Inti:Tokoh-tokoh seperti Roy, Rizal, dan Tahtawi harus diintegrasikan ke dalam studi filsafat global dan ilmu politik tidak sebagai figur periferal, melainkan sebagai pemikir inti yang secara aktif membentuk sejarah intelektual modern. Kisah mereka memperkaya pemahaman tentang bagaimana universalisme dikontekstualisasikan.
- Model Rasionalitas yang Beragam:Studi tentang para arsitek ini menawarkan model-model rasionalitas yang melampaui paradigma Barat, menunjukkan bahwa reformasi (Roy), revolusi (Rizal), dan transfer ilmu pengetahuan (Tahtawi) adalah jalur rasional yang valid menuju modernitas, yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan politik dan sosial yang spesifik.
- Memahami Konflik Kontemporer:Perjuangan mereka mengenai sekularisme, identitas nasional, dan hubungan antara tradisi dan nalar tetap menjadi sumber utama konflik dan perdebatan politik di Global Selatan hingga hari ini. Memahami landasan filosofis yang mereka letakkan sangat penting untuk menganalisis dinamika politik kontemporer di India, Filipina, dan Mesir.
Pencerahan yang diperjuangkan oleh para arsitek ini bersifat inklusif, humanis, dan, yang paling penting, otonom. Mereka membuktikan bahwa cahaya nalar tidak hanya bersinar dari satu pusat, tetapi terlahir kembali dalam setiap perjuangan melawan ketidakadilan di seluruh dunia.