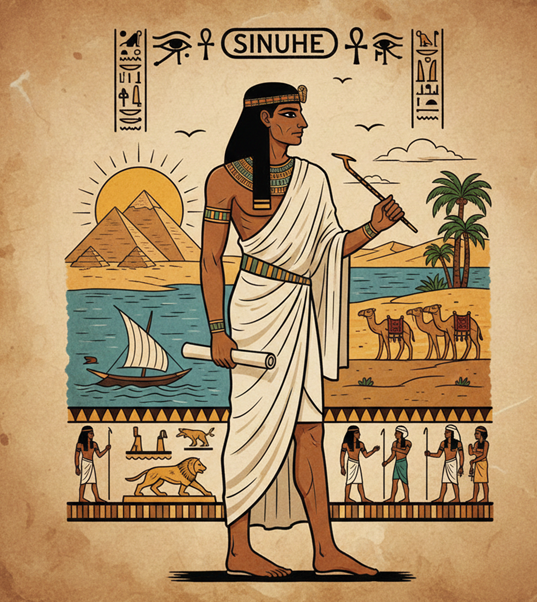Masyarakat Ainu, yang secara etimologis berarti “manusia” dalam bahasa mereka sendiri, merupakan kelompok pribumi yang secara historis menghuni wilayah luas di utara kepulauan Jepang dan daratan Rusia, mencakup Hokkaido, Sakhalin, Kepulauan Kuril, hingga Semenanjung Kamchatka. Keberadaan mereka sering kali terabaikan dalam narasi sejarah arus utama Jepang, meskipun bukti genetik dan arkeologis menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan langsung dari masyarakat Jomon yang telah mendiami wilayah tersebut sejak 12.000 tahun yang lalu. Salah satu ciri budaya yang paling mencolok dan mendalam secara filosofis adalah tradisi sinuye, yakni praktik tato wajah yang dilakukan secara eksklusif oleh kaum wanita, di mana pola hitam kebiruan diukir di sekitar mulut hingga membentuk kesan seringai yang lebar. Praktik ini bukan sekadar upaya estetika dekoratif, melainkan sebuah ontologi kehidupan yang menghubungkan dunia manusia dengan alam roh (kamuy), berfungsi sebagai jimat perlindungan dari entitas jahat, serta menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai kedamaian di alam baka.
Evolusi kebudayaan Ainu mencerminkan transisi yang kompleks dari periode prasejarah hingga era modern. Sejarah mereka terbagi dalam beberapa fase kebudayaan yang berbeda, mulai dari tradisi berburu-meramu Jomon yang bertahan selama sepuluh milenium, berlanjut ke kebudayaan Epi-Jomon dan Satsumon yang mulai mengadopsi pengaruh dari wilayah utara melalui kontak dengan kebudayaan Okhotsk, hingga akhirnya membentuk identitas Ainu yang distingtif sekitar abad ke-12 atau ke-13. Namun, sejak Restorasi Meiji pada abad ke-19, masyarakat Ainu menghadapi krisis eksistensial akibat kebijakan asimilasi paksa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Mantan Penduduk Asli Hokkaido tahun 1899, tradisi sinuye dilarang keras, bahasa mereka ditekan, dan tanah leluhur mereka disita untuk kepentingan pembangunan negara-bangsa Jepang yang homogen. Penindasan sistematis ini membawa tradisi tato mulut ke ambang kepunahan, dengan kematian pemegang tato tradisional terakhir yang tercatat pada tahun 1998. Meskipun demikian, di era kontemporer, muncul gerakan revitalisasi yang digerakkan oleh generasi baru seniman dan aktivis Ainu yang berupaya merebut kembali martabat mereka melalui penelitian sejarah, seni pertunjukan, dan advokasi hak-hak masyarakat adat.
Genealogi dan Arkeologi Kebudayaan Ainu
Akar sejarah masyarakat Ainu tertanam kuat dalam lapisan prasejarah kepulauan Jepang. Penelitian DNA menunjukkan bahwa mereka memiliki keterkaitan genetik yang unik dengan masyarakat Jomon, yang berbeda secara signifikan dari populasi Yamato (etnis Jepang mayoritas) yang bermigrasi kemudian dari daratan Asia. Kebudayaan Ainu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari sintesis panjang antara tradisi lokal dan pengaruh eksternal di sepanjang pesisir Laut Okhotsk.
| Fase Kebudayaan | Rentang Waktu | Karakteristik Utama dan Transisi |
| Jomon | 14.000 – 300 SM | Ekonomi berburu, meramu, dan menangkap ikan; awal penggunaan tembikar; bukti awal dekorasi tubuh melalui patung dogu. |
| Epi-Jomon | 300 SM – 700 M | Kelanjutan tradisi Jomon di Hokkaido saat Honshu beralih ke periode Yayoi; penguatan adaptasi lingkungan utara. |
| Satsumon | 700 M – 1200 M | Pengenalan alat besi; pola pemukiman di sepanjang sungai; pengaruh dari daratan Asia melalui kontak dengan kebudayaan Okhotsk. |
| Ainu Klasik | 1200 M – 1868 M | Formasi identitas etnis yang kuat; sistem ritual kamuy; perdagangan aktif bulu binatang, salmon, dan kelp dengan Jepang dan Tiongkok. |
| Era Kolonial | 1869 M – 1997 M | Aneksasi oleh pemerintah Meiji; asimilasi paksa; pelarangan sinuye; pemisahan paksa dari gaya hidup tradisional. |
Transisi dari kebudayaan Satsumon ke Ainu ditandai dengan perubahan pola ekonomi dan spiritual. Orang Ainu mulai mengandalkan perdagangan transit antara Honshu dan Asia Timur Laut, di mana mereka bertindak sebagai produsen dan pedagang produk kelautan dan hasil hutan yang sangat dicari. Pada periode ini, elemen-elemen kunci seperti ritual beruang (iyomante), penggunaan alat musik tonkori, dan praktik sinuye menjadi mapan sebagai pilar identitas mereka. Keberadaan mereka diakui dalam teks-teks sejarah Tiongkok Dinasti Qing yang menyebut mereka sebagai Kuye atau Kuwei, menggambarkan komunitas yang tangguh di wilayah Amur dan Sakhalin.
Struktur Sosial dan Kosmologi Kotan
Masyarakat Ainu secara tradisional tinggal dalam desa-desa yang disebut kotan, yang biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki ikatan kekerabatan atau kepentingan ekonomi yang sama. Lokasi kotan dipilih secara strategis di dekat sumber air atau pesisir pantai untuk memudahkan akses terhadap ikan salmon, yang merupakan sumber pangan utama. Rumah tradisional mereka, yang disebut cise, dibangun dengan struktur kayu dan atap jerami yang sangat efisien dalam menahan suhu dingin ekstrem di Hokkaido.
Struktur sosial Ainu sangat menekankan pada keseimbangan gender dan peran spiritual. Sementara pria bertanggung jawab atas perburuan dan ritual publik, wanita memegang peranan sentral dalam pelestarian tradisi lisan, kerajinan tangan seperti tenun attus, dan praktik sinuye yang bersifat matrilineal. Dalam kotan, peradilan dilakukan secara kolektif oleh anggota komunitas melalui diskusi panjang hingga mencapai konsensus, di mana hukuman fisik seperti pemotongan tendon atau daun telinga hanya diberikan pada kasus pembunuhan yang sangat berat, sementara hukuman lainnya lebih bersifat restoratif atau beatifikasi.
Kosmologi Ainu berpusat pada konsep kamuy, yaitu dewa-dewa atau roh yang bersemayam dalam setiap elemen alam, mulai dari hewan, tumbuhan, fenomena cuaca, hingga benda buatan manusia. Kehidupan adalah sebuah pertukaran antara dunia manusia (Ainu Mosir) dan dunia roh (Kamuy Mosir). Ritual seperti iyomante dilakukan untuk mengembalikan roh beruang ke dunia asal mereka setelah mereka memberikan daging dan bulunya kepada manusia. Dalam kerangka berpikir inilah tato mulut wanita Ainu menemukan makna terdalamnya; tubuh manusia bukan sekadar fisik, melainkan sebuah wadah yang harus disucikan dan dilindungi agar selaras dengan kehendak para kamuy.
Sinuye: Ontologi Tato Mulut dan Estetika Rasa Sakit
Praktik sinuye, yang secara harfiah berarti “mengukir diri” atau “menulis di tubuh”, merupakan ritual inisiasi yang mendefinisikan transisi seorang gadis menjadi wanita dewasa dalam masyarakat Ainu. Tato ini dilakukan secara eksklusif oleh spesialis wanita yang dikenal sebagai “Bibi Tato” (Tattoo Aunts) yang biasanya merupakan anggota keluarga senior dari garis keturunan ibu. Hal ini menegaskan bahwa tradisi ini adalah warisan perempuan yang diturunkan antar-generasi sebagai bentuk perlindungan dan kebanggaan kelompok.
Proses Teknik dan Materialitas Tradisional
Proses pentatoan adalah sebuah upaya fisik yang sangat menyakitkan dan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Dimulai sejak seorang gadis berusia sekitar enam atau tujuh tahun dengan sebuah titik kecil di bibir atas, tato tersebut diperluas secara bertahap seiring bertambahnya usia hingga mencapai bentuk sempurnanya menjelang pernikahan.
| Komponen Ritual | Deskripsi Material dan Fungsi | Makna Simbolis / Spiritual |
| Alat Pemotong | Awalnya menggunakan obsidian (anchi), kemudian beralih ke pisau logam (makiri) atau silet. | Ketajaman dan ketegasan dalam menghadapi transisi kehidupan. |
| Pigmen | Jelaga (pas) yang diambil dari bagian bawah kuali masak yang menghadap api. | Hubungan langsung dengan Dewi Api (Fuchi) yang menjaga perapian. |
| Antiseptik | Larutan rebusan kulit kayu birch atau kulit kayu nire (spindlewood). | Pembersihan luka dan pencegahan infeksi melalui kekuatan alam. |
| Larutan Pembersih | Campuran abu kayu dan air panas untuk menghapus darah sebelum pengolesan jelaga. | Ritual pemurnian tubuh dari sisa-sisa fisik menuju tanda spiritual. |
Teknik pengerjaannya melibatkan pembuatan sayatan-sayatan kecil pada kulit menggunakan pisau. Setelah darah dibersihkan dengan kain yang direndam antiseptik, jelaga digosokkan ke dalam luka terbuka tersebut menggunakan jari. Selama proses ini, sang Bibi Tato akan melantunkan yukar atau mantra sihir seperti “pas ci-yay, roski, roski, pas ren-ren” (jelaga terkurunglah, tetaplah di sana, jelaga meresaplah, meresaplah) untuk memastikan warna tato menjadi gelap dan permanen. Setelah sesi tato, bibir gadis tersebut akan mengalami pembengkakan hebat yang terasa seperti bara api, sehingga ia sering kali mengalami demam dan hanya bisa minum melalui bantuan serat kapas basah yang diperas ke mulutnya.
Makna Spiritual: Pelindung dari Roh Jahat dan Prasyarat Akhirat
Tujuan utama dari tato di sekitar mulut dan hidung adalah untuk mencegah roh jahat atau demon penyakit (pah-kamuy) masuk ke dalam tubuh manusia. Masyarakat Ainu percaya bahwa lubang-lubang pada tubuh adalah gerbang rentan yang harus dijaga. Karena para istri dewa surgawi diyakini memiliki tato serupa, demon-demon yang melihat wanita Ainu bertato akan mengira mereka adalah dewi dan merasa takut untuk mendekat.6
Lebih jauh lagi, tato ini dianggap sebagai identitas abadi yang akan dibawa hingga kematian. Legenda Ainu memperingatkan bahwa wanita yang tidak memiliki tato akan menghadapi siksaan di pintu masuk dunia roh, di mana para demon akan mengukir tato di wajah mereka secara paksa menggunakan pisau besar. Oleh karena itu, memiliki tato yang lengkap adalah bentuk kesalehan dan kepatuhan terhadap tradisi leluhur yang menjamin kebahagiaan di alam baka bersama anggota keluarga yang telah mendahului. Selain di mulut, tato juga diberikan pada lengan dan tangan wanita, yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi kesehatan, memperkuat penglihatan di masa tua, dan sebagai tanda bahwa mereka telah siap untuk melayani suami mereka melalui kerja keras.
Sejarah Penindasan: Dari Otonomi ke Asimilasi Paksa
Hubungan antara Ainu dan Jepang (Wajin) telah mengalami fluktuasi dari perdagangan yang saling menguntungkan hingga penaklukan militer yang brutal. Sejak abad ke-15, pengaruh klan Matsumae di Hokkaido selatan mulai menekan kedaulatan Ainu. Konflik besar seperti Perang Koshamain (1456) dan Perang Shakushain (1669) menjadi titik balik di mana otonomi politik Ainu mulai runtuh di bawah kekuatan militer dan ekonomi Jepang.
Kebijakan Pelarangan pada Era Edo dan Meiji
Upaya untuk menghapus identitas visual Ainu telah dimulai sejak akhir abad ke-18. Shogun Ezo pada tahun 1799 mengeluarkan larangan pertama terhadap tato, dengan argumen bahwa praktik tersebut tidak perlu dilakukan oleh generasi baru. Namun, larangan yang paling sistematis dan menghancurkan terjadi selama era Meiji (1868–1912). Pemerintah Meiji, yang terobsesi dengan modernisasi dan citra “peradaban” di mata Barat, menganggap tato Ainu sebagai praktik yang barbar dan memalukan.
Pada tahun 1871, Komisi Pengembangan Hokkaido mengeluarkan perintah keras yang melarang tato bagi anak perempuan yang lahir setelah hari itu. Mereka yang melanggar akan dikenakan hukuman berat, dan para Bibi Tato dipaksa untuk menghentikan praktik mereka. Meskipun ada perlawanan dari masyarakat Ainu—di mana para ibu sering kali mentato anak-anak mereka secara rahasia demi keselamatan spiritual anak tersebut—tekanan sosial dan hukum membuat tradisi ini perlahan-lahan meredup.
Undang-Undang Perlindungan Mantan Penduduk Asli 1899
Puncak dari asimilasi kolonial ini adalah pemberlakuan Hokkaido Former Aborigines Protection Act pada 2 Maret 1899. Meskipun judulnya menyiratkan “perlindungan”, substansi undang-undang ini justru bertujuan untuk melenyapkan identitas Ainu secara total:
- Transformasi Ekonomi Paksa: Masyarakat Ainu dilarang berburu rusa dan memancing salmon, yang merupakan fondasi kehidupan mereka. Mereka dipaksa menjadi petani di lahan-lahan marjinal yang tidak subur.
- Penyitaan Kedaulatan Tanah: Wilayah yang secara tradisional dianggap sebagai milik bersama komunitas Ainu dinyatakan sebagai tanah milik negara (terra nullius) dan dibagikan kepada pemukim Jepang.
- Eradikasi Bahasa dan Nama: Penggunaan bahasa Ainu di sekolah-sekolah dilarang. Keluarga Ainu dipaksa mendaftar dalam sistem sensus Jepang (koseki) dan mengadopsi nama keluarga bergaya Jepang, yang sering kali diberikan secara sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah.
- Stigmatisasi Sosial: Istilah “Mantan Penduduk Asli” (kyudojin) menjadi label diskriminatif yang menempel pada identitas mereka selama lebih dari seabad, menciptakan rasa malu kolektif yang membuat banyak orang Ainu menyembunyikan asal-usul mereka.
| Dimensi Penindasan | Kebijakan Meiji (1868-1912) | Dampak Jangka Panjang terhadap Tradisi Sinuye |
| Hukum | Larangan tato tahun 1871. | Penghentian transmisi pengetahuan teknis pentatoan. |
| Sosial | Stigma “barbar” dan “primitif”. | Perubahan standar kecantikan menjadi standar Jepang. |
| Agama | Pelarangan ritual pengorbanan hewan. | Pelemahan hubungan antara tato dan fungsi spiritual. |
| Pendidikan | Sekolah khusus dengan kurikulum asimilasi | Generasi muda merasa malu terhadap penampilan leluhur mereka. |
Kepunahan Fisik dan Kesaksian Generasi Terakhir
Akibat dari kebijakan penindasan yang berlangsung selama puluhan tahun, jumlah wanita Ainu yang memiliki tato tradisional menurun secara drastis. Pada awal abad ke-20, masih terdapat komunitas kecil wanita lanjut usia di daerah pedalaman Hokkaido yang mempertahankan tato mereka sebagai bentuk kesetiaan terakhir pada adat. Namun, tekanan untuk berasimilasi demi kelangsungan hidup ekonomi membuat praktik ini benar-benar terhenti pada pertengahan abad ke-20.
Kematian wanita Ainu terakhir yang memiliki tato mulut tradisional pada tahun 1998 merupakan sebuah momen yang sangat melankolis dalam sejarah antropologi Jepang. Peristiwa ini menandai berakhirnya sebuah rantai sejarah yang telah ada sejak zaman purba. Meskipun identitas fisik tersebut hilang, memori kolektif tentang sinuye tetap hidup melalui dokumentasi foto-foto lama dan catatan-catatan para misionaris serta peneliti seperti John Batchelor yang, meskipun memiliki bias kolonial, sempat mencatat alasan-alasan religius di balik praktik tersebut pada tahun 1901.
Kesenjangan informasi antara data resmi pemerintah dan realitas lapangan sangat mencolok. Meskipun secara resmi jumlah orang yang mengaku sebagai Ainu hanya sekitar 25.000 orang, para ahli memperkirakan bahwa ada sekitar 200.000 orang Jepang yang memiliki darah Ainu namun memilih untuk tetap anonim guna menghindari diskriminasi sistemik yang masih ada dalam masyarakat modern. Hilangnya tato wajah secara permanen dianggap sebagai “genosida tanpa darah” yang berhasil menghapus perbedaan visual antara penjajah dan yang dijajah.
Dialektika Revitalisasi di Era Modern
Bangkitnya kesadaran global terhadap hak-hak masyarakat adat memberikan dorongan baru bagi komunitas Ainu untuk memulihkan martabat mereka. Setelah bertahun-tahun melakukan advokasi, pada tahun 2008, Diet Jepang akhirnya mengeluarkan resolusi yang mengakui Ainu sebagai penduduk asli Jepang. Langkah ini diikuti dengan pencabutan Undang-Undang tahun 1899 dan penggantiannya dengan Undang-Undang Promosi Kebudayaan Ainu (CPA) pada tahun 1997, yang kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Promosi Kebijakan Ainu (APPA) pada tahun 2019.
Upopoy: Ruang Simbolis dan Kritik Terhadapnya
Sebagai manifestasi fisik dari undang-undang tahun 2019, pemerintah Jepang mendirikan Upopoy (Ruang Simbolis untuk Harmoni Etnis) di Shiraoi, Hokkaido, yang mencakup Museum Nasional Ainu dan Taman Nasional Ainu. Fasilitas ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan tentang budaya Ainu kepada publik luas dan menyediakan tempat bagi transmisi tradisi yang hampir punah. Di Upopoy, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan tari kuno Ainu, mendengarkan musik mukkuri, dan melihat kerajinan tangan yang rumit.
Namun, keberadaan Upopoy tidak luput dari kritik dari kalangan aktivis Ainu. Beberapa pemimpin adat, seperti Yuji Shimizu, menyatakan kekhawatiran bahwa fasilitas tersebut lebih berfungsi sebagai objek wisata untuk kepentingan ekonomi pemerintah daripada sebagai sarana untuk mengembalikan hak-hak substantif Ainu atas tanah dan sumber daya alam. Definisi budaya dalam undang-undang tersebut dianggap terlalu sempit, hanya fokus pada manifestasi material seperti kerajinan dan tari, tanpa memberikan ruang bagi otonomi politik atau reparasi atas ketidakadilan sejarah. Sebagai contoh, hak untuk menangkap salmon di sungai, yang secara tradisional merupakan bagian integral dari budaya Ainu, masih sangat dibatasi oleh hukum perikanan Jepang, yang memicu gugatan hukum dari kelompok seperti Raporo Ainu Nation.
Seni Kontemporer Mayunkiki dan Reklamasi Sinuye
Dalam ranah ekspresi budaya, upaya yang paling signifikan untuk merevitalisasi sinuye dilakukan melalui jalur seni kontemporer. Mayunkiki, seorang seniman dan musisi Ainu, telah menjadi figur sentral dalam gerakan ini. Melalui karyanya, ia mengeksplorasi makna kecantikan tradisional dan bagaimana asimilasi telah mengubah persepsi diri wanita Ainu.
Mayunkiki tidak menggunakan tato permanen di wajahnya, melainkan menggunakan cat wajah atau makeup untuk mereplikasi pola tato mulut leluhurnya dalam penampilan publik dan pementasan musik bersama grupnya, Marewrew. Melalui penelitian sejarah yang mendalam, ia mewawancarai para tetua untuk mengumpulkan fragmen-fragmen ingatan tentang bentuk dan makna tato tersebut. Bagi Mayunkiki, tindakan melukis wajahnya adalah sebuah bentuk resistensi terhadap sejarah penghapusan budaya. Ia sengaja memilih untuk tidak menggunakan bahasa Inggris dalam pameran internasionalnya sebagai protes terhadap dominasi kolonialisme linguistik, dan sebaliknya menggunakan penerjemah untuk memastikan suaranya tetap otentik sebagai orang Ainu.
Revitalisasi ini juga merambah ke dunia tato profesional. Seniman tato seperti Taku Oshima mulai mengerjakan desain tradisional Ainu untuk klien yang ingin menunjukkan identitas mereka. Meskipun sebagian besar tato ini masih dilakukan di area tubuh yang tertutup atau di lengan, munculnya keberanian untuk menampilkan kembali motif sinuye merupakan indikator bahwa trauma sejarah mulai dihadapi secara aktif oleh generasi muda.
Analisis Mendalam: Tato sebagai Perlawanan dan Pemulihan Kolektif
Tato mulut Ainu merepresentasikan sebuah teka-teki yang mendalam mengenai bagaimana tubuh manusia berfungsi sebagai kanvas bagi ideologi politik dan ketahanan spiritual. Ada beberapa lapisan wawasan yang dapat ditarik dari fenomena ini.
- Tubuh sebagai Medan Pertempuran Kedaulatan
Penghapusan tato oleh pemerintah Meiji bukan sekadar masalah estetika, melainkan serangan terhadap otonomi individu dan komunitas. Dalam pandangan dunia Ainu, tubuh adalah milik individu dan roh leluhur. Dengan melarang tato, pemerintah Jepang mengklaim kedaulatan atas tubuh subjek Ainu, mengubah mereka menjadi “properti” negara yang harus menyesuaikan diri dengan citra nasional Jepang. Oleh karena itu, reklamasi tato saat ini—baik melalui cat wajah maupun tato permanen—adalah tindakan politik untuk merebut kembali kedaulatan atas tubuh tersebut.
- “Aroma Tato” sebagai Metafora Kesehatan Budaya
Konsep masyarakat Ainu tentang “aroma tato” (the scent of tattooing) sebagai obat untuk mengusir wabah penyakit memberikan wawasan unik tentang kaitan antara identitas dan kesejahteraan mental. Hilangnya tato dan bahasa secara paksa telah menciptakan “penyakit” sosial berupa trauma intergenerasi, kemiskinan, dan rendahnya rasa percaya diri etnis. Revitalisasi budaya saat ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menyebarkan kembali “aroma” identitas tersebut guna menyembuhkan luka psikologis kolektif masyarakat Ainu.
- Paradoks Komodifikasi vs. Otentisitas
Keberadaan fasilitas seperti Upopoy menciptakan paradoks. Di satu sisi, ia menyediakan dana dan panggung untuk pelestarian tradisi yang hampir punah. Di sisi lain, ada bahaya bahwa budaya Ainu akan “dibekukan” dalam bentuk pertunjukan yang steril untuk konsumsi turis, kehilangan esensi spiritual dan protes sosialnya. Kesaksian Mayunkiki menunjukkan bahwa otentisitas tidak ditemukan di dalam kotak kaca museum, melainkan dalam tindakan aktif untuk mempraktikkan kembali tradisi tersebut dalam konteks modern yang relevan.
- Kaitan Global dengan Masyarakat Adat Lainnya
Kisah penindasan Ainu memiliki paralel yang kuat dengan pengalaman suku asli Amerika (seperti yang tercermin dalam perbandingan antara UU 1899 dengan Dawes Act di Amerika Serikat) dan suku-suku asli di Australia. Penggunaan tato wajah sebagai penanda identitas yang menantang standar kecantikan Barat juga ditemukan dalam tradisi Moko suku Maori di Selandia Baru atau Hajichi di Okinawa. Ini menempatkan narasi Ainu bukan sebagai kasus isolasi, melainkan sebagai bagian dari gerakan global dekolonisasi di mana masyarakat adat di seluruh dunia berupaya memulihkan kedaulatan budaya mereka.
Kesimpulan: Menatap Masa Depan Ainu Mosir
Perjalanan panjang masyarakat Ainu dari penguasa tanah Ainu Mosir hingga menjadi minoritas yang terpinggirkan di tanah air mereka sendiri merupakan sebuah tragedi sejarah yang masih mencari jalan menuju rekonsiliasi. Tato mulut “seringai” yang dahulu dianggap sebagai pelindung sakral, kini berdiri sebagai simbol ketahanan yang tak tergoyahkan. Meskipun tato permanen terakhir telah menghilang bersama pemiliknya pada tahun 1998, esensi dari sinuye telah bermigrasi dari kulit ke dalam kesadaran politik dan seni generasi baru.
Masa depan identitas Ainu sangat bergantung pada kemampuan negara Jepang untuk tidak hanya merayakan budaya Ainu secara dangkal, tetapi juga memberikan hak-hak substantif yang memungkinkan masyarakat ini untuk berkembang secara mandiri. Revitalisasi bahasa, pengakuan hak atas tanah dan sungai, serta penghapusan stigma sosial adalah langkah-langkah krusial yang harus diambil. Melalui keberanian seniman seperti Mayunkiki dan advokasi para tetua, masyarakat Ainu terus membuktikan bahwa “manusia” sejati adalah mereka yang mampu mempertahankan martabatnya meskipun di bawah tekanan asimilasi yang paling berat sekalipun. Tato mulut itu mungkin tidak lagi terukir secara permanen di wajah setiap wanita Ainu, namun keberanian untuk tersenyum menghadapi sejarah adalah bentuk “sinuye” baru yang akan terus menghiasi narasi masyarakat pribumi Jepang utara ini hingga masa yang akan datang.