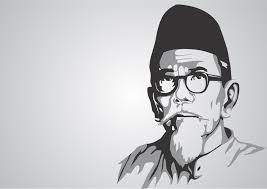Mengurai Sosok The Grand Old Man
Haji Agus Salim, yang terlahir dengan nama Masjhoedoelhaq Salim, merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dikenal secara informal dengan julukan kehormatan “The Grand Old Man” atau Kamitua yang Mulia , sosoknya melampaui deskripsi sederhana sebagai politisi atau pejuang. Beliau adalah arsitek diplomasi Indonesia, seorang jurnalis yang piawai, pemimpin pergerakan yang karismatik, sekaligus intelektual Muslim yang progresif. Julukan tersebut secara khusus diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan prestasinya yang luar biasa, khususnya di bidang diplomasi, sebuah ranah yang menjadi medan perjuangan utamanya. Tulisan ini akan menyajikan sebuah tinjauan mendalam, menguraikan riwayat hidup, pemikiran, pencapaian, dan warisan abadi dari sosok yang dikenal fasih dalam setidaknya sembilan bahasa ini.
Riwayat Hidup dan Formasi Intelektual (1884-1915)
Masa Kecil, Pendidikan, dan Jalan yang Tidak Terpilih
Lahir pada tanggal 8 Oktober 1884, di desa Koto Gadang, Bukittinggi, Sumatra Barat, Agus Salim berasal dari keluarga Minangkabau yang terpandang. Ayahnya, Sutan Mohammad Salim, adalah seorang jaksa dan hakim kolonial yang mencapai jabatan tinggi sebagai jaksa kepala untuk pengadilan pribumi di Tanjung Pinang. Posisi terhormat ayahnya memungkinkan Agus Salim dan kakaknya, Jacob, untuk mendapatkan status yang setara dengan orang Eropa, sebuah hak istimewa yang sangat langka bagi penduduk pribumi saat itu.
Salim memulai pendidikan dasarnya di Europeesche Lagere School (ELS), sebuah sekolah khusus anak-anak elite, di mana kecerdasannya telah menarik perhatian guru-gurunya. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Hogere Burgerschool (HBS) di Batavia dan berhasil lulus pada tahun 1903 dengan skor tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Dengan prestasi akademis yang gemilang ini, Salim mengajukan permohonan beasiswa dari pemerintah kolonial untuk melanjutkan studi kedokteran di Belanda, namun permohonan tersebut ditolak. Bahkan tawaran dari Kartini, seorang mahasiswa terdidik Eropa lainnya, untuk menangguhkan beasiswanya demi Salim juga tidak diterima.
Kegagalan untuk menempuh pendidikan di Belanda ini merupakan sebuah peristiwa penting yang secara kausal mengubah jalur hidup Agus Salim. Alih-alih menjadi seorang dokter seperti yang dicita-citakan, jalan yang tidak terpilih ini justru membawanya menuju takdir yang lain. Peristiwa penolakan tersebut menjadi katalisator yang mengarahkannya pada sebuah pengembaraan intelektual yang lebih besar, membentuknya sebagai seorang intelektual yang mendalam dan pemimpin yang visioner di masa depan.
Pengembaraan Intelektual di Jazirah Arab
Pasca penolakan beasiswa, C.S. Hurgronje, seorang administrator kolonial terkemuka yang dikenal karena studinya tentang urusan pribumi, mengambil Agus Salim di bawah naungannya. Pada tahun 1905, Hurgronje mengatur kepergian Salim ke Jeddah untuk bekerja sebagai penerjemah dan sekretaris di konsulat Belanda, di mana tugasnya adalah menangani urusan haji.
Masa-masa di Jeddah ini memiliki arti yang sangat mendalam bagi formasi pemikiran Agus Salim. Walaupun bekerja untuk pemerintah kolonial, kesempatan tersebut digunakannya untuk memperdalam pengetahuan agama dan berinteraksi dengan pemikiran para pembaharu Islam transnasional. Ia mengenal gagasan-gagasan reformis seperti Jamaluddin al-Afgani dan muridnya, Muhammad Abduh, yang menganjurkan Islam yang modern dan progresif. Wawasan tentang Islam modern yang ia peroleh di Jazirah Arab ini tidak akan pernah ia dapatkan di Belanda, dan inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pemikiran nasionalisme Islamnya di kemudian hari. Pengembaraan ini menghasilkan sintesis yang unik, di mana ia adalah produk pendidikan elit kolonial Barat (HBS) , namun juga seorang ulama yang mendalam dengan wawasan global dari Timur. Dualisme ini menjadi pondasi bagi ideologinya yang menolak fanatisme dan mempertahankan akal sehat.
Awal Karier dan Jurnalisme yang Kritis
Salim kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1911 dan memutuskan untuk menekuni karier di dunia jurnalisme. Profesi ini pada saat itu tidaklah populer di kalangan elit pribumi, namun bagi Salim, jurnalisme adalah arena perjuangan ideologi dan penyebaran pemikiran. Ia berkontribusi dalam berbagai publikasi, seperti Hindia Baroe, Fadjar Asia, dan Moestika. Puncaknya, ia menjabat sebagai redaktur di harian Neratja, sebuah surat kabar yang berafiliasi dengan organisasi Sarekat Islam, di mana ia juga menjadi anggota aktif.
Kiprahnya sebagai jurnalis dikenal sangat kritis dan berani. Sebagai pemimpin redaksi di harian Hindia Baroe yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang Belanda, ia tetap memposisikan dirinya sebagai wartawan yang tegas. Ia bahkan pernah mengkritik praktik eksploitasi perburuhan di perkebunan-perkebunan Belanda di Sumatra. Ketika sikapnya yang kritis ini tidak disetujui oleh para pemilik koran, Agus Salim memilih untuk mengundurkan diri. Pengalaman sebagai wartawan yang kritis ini adalah “sekolah” politik baginya, mengasah kemampuan retorika, analisis, dan keberaniannya dalam menghadapi kekuasaan. Keterampilan ini, yang diasah melalui dunia jurnalisme, kelak menjadi modal utama yang menjadikannya seorang diplomat ulung di panggung internasional.
Sang Pejuang di Medan Pergerakan Nasional (1915-1945)
Peran Sentral di Sarekat Islam
Pada tahun 1915, Agus Salim secara resmi bergabung dengan Sarekat Islam (SI), sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dengan cepat, ia menjadi figur sentral dan dipercaya sebagai tangan kanan pemimpin SI, H.O.S. Tjokroaminoto. Peran utamanya adalah memengaruhi arah gerakan Syarikat Islam dan menjaganya dari perpecahan internal.
Beliau memainkan peran vital dalam menahan infiltrasi dan perpecahan yang disebabkan oleh elemen-elemen komunis yang masuk ke dalam tubuh Sarekat Islam. Pemikirannya yang moderat namun tegas memungkinkan ia untuk memimpin diskusi yang mengarah pada penarikan diri kelompok komunis dari organisasi tersebut pada awal tahun 1920-an. Setelah perpecahan ini, ia mengarahkan Sarekat Islam menjauh dari aktivitas politik konfrontatif dan memfokuskannya pada gerakan Pan-Islamisme, yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan Islam di Indonesia dan membangun hubungan dengan gerakan-gerakan Islam di luar negeri. Peran strategisnya dalam konflik internal Sarekat Islam ini menunjukkan kapasitas kepemimpinannya yang moderat namun tegas, menjadikannya figur yang menjaga pergerakan nasional dari fragmentasi ideologis.
“Singa Podium”: Kemahiran Retorika dan Kecerdasan Linguistik
Kepiawaian Agus Salim dalam berpidato dan menguasai berbagai bahasa asing membuatnya mendapatkan julukan “Singa Podium”. Julukan ini bukan sekadar deskripsi, melainkan pengakuan atas kekuatan retorika sebagai senjata non-militer dalam perjuangan kemerdekaan. Kecerdasannya dalam berbahasa menjadi salah satu keunggulan utamanya sebagai diplomat di kemudian hari.
Agus Salim dilaporkan fasih dalam setidaknya sembilan bahasa, termasuk bahasa aslinya yaitu Minangkabau dan Melayu, serta bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Jepang, Jerman, Latin, dan Turki. Kemampuannya ini membuatnya diangkat menjadi delegasi Belanda untuk Konferensi Buruh Internasional di Jenewa pada tahun 1929. Di forum tersebut, ia berbicara dalam bahasa Prancis, dan penampilannya berhasil membuat banyak orang kagum, mengangkat nama Indonesia di panggung internasional.
Berbagai anekdot historis juga menggambarkan kecerdasan dan humornya yang tajam. Salah satu cerita terkenal adalah ketika beberapa anggota Sarekat Islam mencoba mengejeknya dengan suara kambing saat ia sedang berpidato, mengacu pada janggut putihnya. Dengan tenang, Agus Salim bertanya kepada ketua sidang apakah Sarekat Islam telah mengundang sekawanan kambing ke dalam pertemuan. Ia melanjutkan, jika ya, sebagai seorang poliglot, ia akan menghormati hak mereka untuk mendengarkan pidatonya dalam “bahasa kambing”. Ada pula cerita saat ia membungkam anggota Volksraad Belanda yang mengejeknya karena menggunakan kata ‘ekonomi’ yang dianggap bukan bahasa Melayu asli. Anagram ini menunjukkan bahwa kemampuan verbal dan kecerdasan intelektual Agus Salim bukanlah sekadar hobi, tetapi modal perjuangan yang digunakan untuk membela martabat bangsanya.
Peran dalam Persiapan Kemerdekaan
Meskipun aktivitas utamanya berada di Sarekat Islam, Agus Salim juga memainkan peran penting dalam persiapan kemerdekaan. Ia tercatat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk merancang dasar negara. Keterlibatannya juga mencakup keanggotaannya dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD) yang diketuai oleh Soekarno. Peran-peran ini menegaskan posisinya sebagai salah satu pendiri bangsa yang memberikan kontribusi fundamental terhadap dasar-dasar negara. Transisi dari seorang jurnalis yang pandai mengolah kata menjadi seorang orator ulung dan negosiator ulung yang menggunakan kata-kata untuk perdebatan ideologis dan politik, adalah bukti nyata bagaimana kemampuan intelektual dan komunikasi menjadi modal utama dalam perjuangan.
Diplomat Ulung dan Arsitek Hubungan Internasional (1945-1954)
Visi dan Peran Sentral dalam Diplomasi
Setelah proklamasi kemerdekaan, peran Agus Salim berubah dari pemimpin pergerakan menjadi seorang diplomat dan negarawan. Ia tidak langsung menduduki posisi di kabinet pertama, namun diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kepandaiannya dalam berdiplomasi dengan cepat diakui, sehingga ia dipercaya menjadi penasihat Menteri Luar Negeri Sutan Syahrir. Seiring berjalannya waktu, ia menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir II dan III, kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II, serta Kabinet Hatta I dan II.
Agus Salim merupakan seorang tokoh yang sangat dihormati di kalangan diplomatik, dan julukan “The Grand Old Man” merupakan bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang ini. Julukan ini diberikan tidak hanya karena usianya yang tua, tetapi lebih pada pengakuan terhadap kontribusinya yang sangat besar dalam perjuangan diplomasi Indonesia.
Misi Diplomasi Menggalang Pengakuan Dunia
Ketika pejuang lain berjuang di medan perang, Agus Salim bertempur di meja perundingan. Ia menggunakan kata-kata, logika, dan kecerdasan sebagai senjata untuk memenangkan perang politik. Salah satu prestasi terbesarnya adalah ketika ia ditunjuk sebagai ketua delegasi untuk misi diplomatik ke negara-negara Timur Tengah pada 4 April 1947. Berkat kepiawaiannya, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure pada 10 Juni 1947. Pengakuan ini menjadi pintu gerbang yang membuka jalan bagi pengakuan dari negara-negara Arab lainnya, sekaligus menutup semua kemungkinan bagi Belanda untuk mengklaim kembali Indonesia di mata dunia. Prestasi ini merupakan puncak dari karier diplomasinya dan merupakan contoh nyata bagaimana kejeniusan seorang diplomat dapat secara langsung memengaruhi nasib suatu bangsa.
Selain itu, ia juga mewakili Indonesia di Sidang Dewan Keamanan PBB di New York pada 12 Agustus 1947. Dalam sidang tersebut, ia berhasil menggalang simpati dan dukungan internasional, yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN), sebuah langkah strategis untuk menginternasionalisasi masalah Indonesia-Belanda.
Kepiawaian Berunding: Perjanjian Linggarjati dan Renville
Keterlibatan Agus Salim dalam perundingan-perundingan penting membuktikan kemahirannya sebagai negosiator ulung. Dalam Perundingan Linggarjati, ia tidak secara langsung menjadi ketua delegasi, namun ia berperan sebagai penasihat dan orang kedua setelah Sutan Syahrir. Meskipun perannya tidak terlihat secara langsung, ia adalah seorang lobbyist yang memainkan peran penting dalam hubungan dengan delegasi Belanda dan Inggris.
Dalam Perundingan Renville, ia menjadi salah satu anggota delegasi Indonesia. Perundingan ini berlangsung di atas kapal perang milik Amerika Serikat, USS Renville. Di atas kapal tersebut, dalam sebuah anekdot yang terkenal, Agus Salim berhasil membungkam utusan Belanda yang menuduh Republik Indonesia menyalahi kesepakatan Linggarjati. Dengan cerdiknya, ia melontarkan pertanyaan retoris: “Apakah aksi militer yang Tuan lancarkan terhadap kami sesuai dengan Perjanjian Linggarjati?”. Ia juga menambahkan, jika Belanda kembali melancarkan aksi militer, Indonesia akan mendapatkan pengakuan de jure di seluruh dunia. Peristiwa ini menunjukkan ketegasan, kecerdasan taktis, dan kepiawaiannya sebagai pendebat ulung, memanfaatkan celah moral dan hukum untuk keuntungan bangsanya.
Peran dalam Konferensi Meja Bundar
Agus Salim juga turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda. Dalam konferensi yang bertujuan untuk mempercepat proses pengakuan kedaulatan ini, ia mendampingi delegasi Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Keberadaannya dalam perundingan-perundingan krusial ini mengukuhkan posisinya sebagai arsitek utama dalam perjuangan diplomasi Indonesia.
Riwayat Jabatan dan Peran Diplomatik Pasca-Kemerdekaan
| Jabatan/Peran | Periode | Kabinet Terkait |
| Anggota Dewan Pertimbangan Agung | Pasca-Proklamasi | Kabinet Presidentil |
| Penasihat Menteri Luar Negeri | – | Kabinet Syahrir |
| Menteri Muda Luar Negeri | – | Kabinet Syahrir II & III |
| Menteri Luar Negeri | 1947–1949 | Kabinet Amir Sjarifuddin I & II, Kabinet Hatta I & II |
| Ketua Misi Diplomasi ke Timur Tengah | 1947 | – |
| Anggota Delegasi | 1947-1948 | Perundingan Renville |
| Anggota Delegasi | 1949 | Konferensi Meja Bundar |
Pemikiran dan Warisan Abadi
Nasionalisme Islam Agus Salim
Pemikiran Haji Agus Salim adalah jembatan antara dua arus besar pergerakan nasional: nasionalisme dan Islam. Ideologi nasionalisme Islamnya dipengaruhi oleh pendidikan sekuler Belanda dan interaksinya dengan para reformis Islam di Jeddah. Ia berpandangan bahwa nasionalisme harus diperjuangkan dalam kerangka pengabdian yang lebih besar, yaitu kepada Tuhan. Dalam pandangannya, kecintaan terhadap tanah air dan bangsa seharusnya tidak bersifat fanatik. Ia secara tegas memperingatkan bahwa nasionalisme yang berlebihan dapat mengarah pada penyembahan negara (deifies the state), mengutip contoh Hitler di Jerman sebagai kasus yang harus dihindari.
Ideologi ini membedakannya dari nasionalisme sekuler Soekarno dan Hatta, karena bagi Salim, nasionalisme tidak dapat dipisahkan dari agama. Meskipun berbeda, ia tidak mengkritik pandangan Soekarno, melainkan hanya ingin menyoroti perbedaan prinsip antara pandangannya dan pandangan Sarekat Islam. Pemikirannya membuktikan bahwa idealisme kebangsaan dan keislaman dapat saling melengkapi untuk mencapai kemerdekaan yang bermakna, sebuah wawasan yang tetap relevan hingga saat ini. Peringatannya tentang bahaya “penyembahan negara” menjadi sebuah pedoman etika politik yang abadi, mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam perjuangan politik.
Warisan untuk Masa Depan
Agus Salim mengabdikan seluruh hidupnya untuk perjuangan bangsa hingga akhir hayatnya. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Menjelang akhir hidupnya, beliau berkeinginan untuk menuliskan semua pemikirannya dalam sebuah buku dan menyelesaikan karangan tafsir Al-Qur’an, namun niatnya tidak sempat terlaksana.
Meskipun demikian, warisan utamanya tidak hanya terwujud dalam dokumen-dokumen resmi, melainkan dalam keteladanan, sikap, dan pidatonya. Ia meninggalkan warisan tentang bagaimana menjadi seorang intelektual yang berprinsip, sederhana, dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk kebenaran dan kemerdekaan bangsanya. Sebagai bentuk penghormatan atas segala jasa dan perjuangannya, Presiden Soekarno secara anumerta menganugerahinya gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada tanggal 27 Desember 1961. Nama dan sosoknya diabadikan dalam nama jalan dan stadion di berbagai kota di Indonesia, sebagai bentuk pengakuan abadi atas kontribusi fundamentalnya bagi bangsa.
Ringkasan Julukan Haji Agus Salim
| Julukan | Makna dan Konteks |
| The Grand Old Man | Julukan kehormatan yang diberikan atas prestasi dan kontribusi besar di bidang diplomasi. |
| Singa Podium | Menggambarkan kemahirannya dalam berpidato dan kepiawaiannya dalam retorika. |
| Diplomat dari Negeri Kata-Kata | Menggambarkan kemampuannya menggunakan retorika sebagai instrumen perjuangan diplomasi. |
Kesimpulan
Berdasarkan analisis komprehensif terhadap riwayat hidup, pemikiran, dan pencapaiannya, dapat disimpulkan bahwa Haji Agus Salim adalah sosok multidimensional yang memainkan peran krusial dalam membentuk identitas dan arah perjuangan bangsa Indonesia. Posisinya yang unik sebagai seorang intelektual yang melampaui zamannya dan seorang pemimpin yang menggabungkan pemikiran kritis Barat dengan kearifan Islam menjadikannya salah satu bapak bangsa yang paling berpengaruh. Ia menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dimenangkan di medan perang fisik, tetapi juga melalui pertempuran ideologis, verbal, dan diplomatik.
Dari seorang jurnalis yang berani hingga seorang diplomat ulung yang cerdik, Haji Agus Salim menggunakan kekuatan kata-kata untuk memperjuangkan kedaulatan dan mendapatkan pengakuan dunia. Warisannya tidak hanya tercatat dalam sejarah diplomasi, tetapi juga dalam pemikirannya yang menyatukan nasionalisme dan Islam, serta keteladanannya sebagai seorang intelektual yang berprinsip. Kisah hidupnya mengukuhkan posisi beliau sebagai “The Grand Old Man,” yang warisannya terus menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk terus berjuang dengan kecerdasan, integritas, dan pengabdian yang tulus.