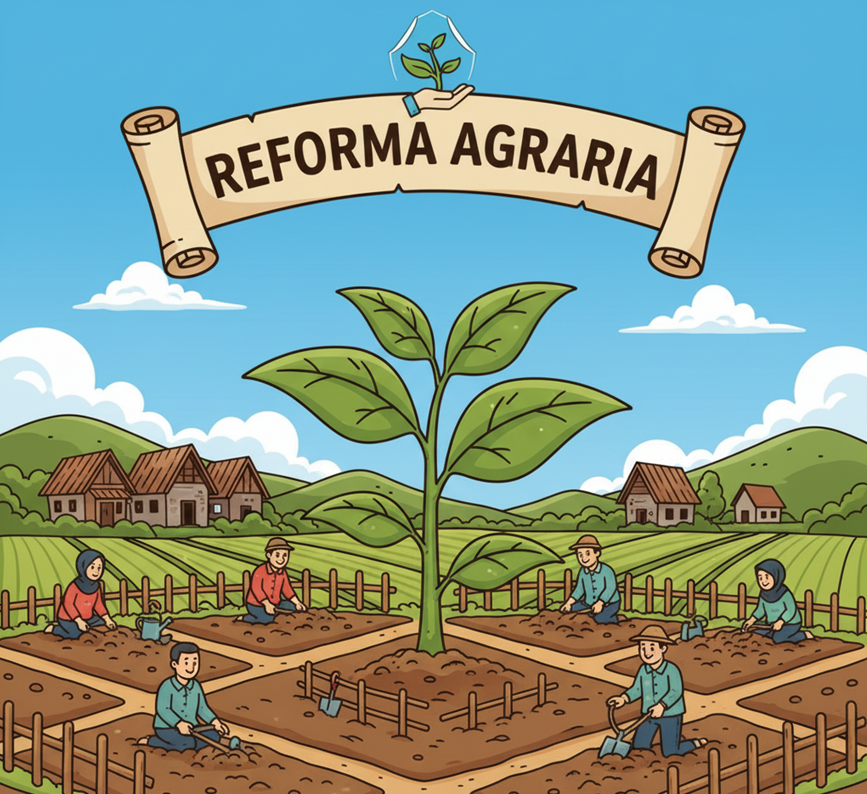Latar Belakang dan Urgensi Struktural Ketimpangan Agraria
Diagnosis ketimpangan agraria secara konsisten menunjukkan bahwa ketidakmerataan penguasaan lahan di Indonesia merupakan warisan struktural dari masa kolonial dan feodal. Kondisi ini diperburuk oleh strategi pembangunan yang cenderung bias terhadap investasi berskala besar. Ketimpangan penguasaan lahan dalam suatu wilayah merupakan salah satu alasan mendasar terhambatnya pelaksanaan reforma agraria yang efektif.
Saat ini, upaya perbaikan kesejahteraan petani tidak lagi cukup hanya melalui perbaikan teknologi dan kelembagaan produksi. Keberhasilan upaya perbaikan kehidupan masyarakat pedesaan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh perbaikan akses petani terhadap lahan. Namun, lahan pertanian cenderung semakin terbatas akibat kompetisi dengan penggunaan lahan lain, sementara regulasi yang diterbitkan seringkali memfasilitasi akses investor terhadap lahan, termasuk lahan pertanian dan lahan yang secara tradisional dikuasai masyarakat, alih-alih melindungi hak petani. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan menyediakan evaluasi kritis terhadap implementasi Reforma Agraria (RA) modern di Indonesia dan menyintesis pembelajaran dari praktik internasional untuk mengatasi hambatan struktural ini.
Definisi dan Landasan Filosofis Reforma Agraria Indonesia (UUPA 1960)
Reforma Agraria kontemporer di Indonesia didefinisikan sebagai upaya menghilangkan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan. Secara operasional, RA dilakukan melalui sinkronisasi Penataan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial
Landasan hukum dan filosofis utama RA adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA berfungsi sebagai peraturan dasar yang melahirkan instrumen pelaksanaan landreform Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, yang bertujuan menertibkan kepemilikan tanah. Secara filosofis, hukum tanah Indonesia menganut hukum adat, di mana tanah yang tidak dikuasai oleh negara pada hakikatnya adalah tanah masyarakat hukum adat. Negara diberikan otoritas dalam penguasaan tanah melalui doktrin Hak Menguasai Negara (HMN), yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun, penerapan HMN dalam praktik empiris menunjukkan risiko penyimpangan. Secara filosofis, HMN seharusnya menjamin kemakmuran rakyat, tetapi pelaksanaannya seringkali bias dalam pemberian hak kepada investor melalui berbagai peraturan sektoral. Penyalahgunaan HMN ini secara efektif mereduksi hakikat tanah masyarakat hukum adat demi legalitas formal dan kepentingan politik atau pribadi kepala daerah. Jika HMN dimanfaatkan untuk mengakumulasi dan memfasilitasi akses modal, maka upaya Reforma Agraria, yang secara ideologis bergantung pada negara untuk membagi lahan, menjadi sebuah kebijakan yang secara internal kontradiktif. Negara bertindak ganda sebagai regulator konflik dan sekaligus pelaku utama dalam pengakumulasian lahan.
Genealogi dan Evolusi Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia
Era Orde Lama (1960-1965): Ideologi Landreform dan Awal Redistribusi
Kebijakan agraria Indonesia dimulai secara signifikan pada Era Orde Lama, yang dilandasi semangat revolusioner untuk membongkar kapitalisme kolonial dan feodalisme. Tujuan utama saat itu adalah nasionalisasi perusahaan asing dan redistribusi tanah kepada petani. Kebijakan ini dikenal sebagai Landreform dan diimplementasikan sekitar tahun 1963 hingga 1965.
Instrumen kebijakan kunci yang mendefinisikan era ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dan UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
Era Orde Baru dan Stagnasi Kebijakan
Pada Era Orde Baru, fokus kebijakan agraria mengalami pergeseran drastis. Orientasi pembangunan beralih ke pertumbuhan ekonomi berbasis sektor dan industrialisasi, yang cenderung mengabaikan agenda pemerataan struktural UUPA 1960. Implementasi
landreform secara substansial terhenti. Regulasi yang muncul pada era ini, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform, lebih bersifat administratif. Selain itu, kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, menunjukkan penguatan peran negara dalam alokasi lahan skala besar, seringkali untuk kepentingan non-pertanian.
Era Reformasi dan Nawacita (2001-Sekarang): Kebangkitan RA Modern
Kebangkitan kembali agenda Reforma Agraria ditandai oleh Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. RA kemudian menjadi salah satu agenda utama Nawacita pada masa pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla. Kerangka regulasi modern diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Program prioritas RA mencakup lima pilar utama: penguatan regulasi, penataan penguasaan TORA, kepastian hukum TORA, pemberdayaan masyarakat (Penataan Akses), dan kelembagaan.
Pelaksanaan Reforma Agraria modern berlandaskan pada dua pilar utama: Penataan Aset (melalui Legalisasi dan Redistribusi) dan Penataan Akses (Pemberdayaan). Konsep RA saat ini telah bertransformasi dari ideologi redistribusi radikal Orde Lama menjadi program dualistik—yaitu, program legal-administratif (PTSL) dan program struktural-redistributif (TORA). Keberadaan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan menunjukkan bahwa sumber utama konflik dan TORA kini adalah kawasan hutan. Hal ini menyoroti adanya perseteruan kebijakan antara regulasi agraria dan regulasi kehutanan. Oleh karena itu, keberhasilan Reforma Agraria sangat ditentukan oleh kemampuan politik negara untuk mengatasi konflik kepentingan dan ego sektoral antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pilar Implementasi: Penataan Aset dan Penataan Akses Indonesia
Penataan Aset (Legalisasi dan Redistribusi)
Penataan Aset, yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan pemerataan penguasaan tanah, terdiri dari dua komponen utama. Pertama, Legalisasi Aset, yang dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai masyarakat.
Kedua, Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), yang memiliki target total sebesar 4.5 juta Ha. Sumber TORA terbagi menjadi 4.1 juta Ha yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan, dan 0.4 juta Ha dari tanah terlantar, eks Hak Guna Usaha (HGU), dan tanah negara lainnya. Mekanisme perolehan TORA dari kawasan hutan melibatkan proses kompleks, termasuk Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan.
Penataan Akses (Pemberdayaan Ekonomi)
Penataan Akses adalah pilar krusial yang dirancang untuk melengkapi Penataan Aset. Kegiatan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan taraf kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi ekonomi atas tanah yang telah diredistribusi atau dilegalisasi.
Fase implementasi Penataan Akses terbagi dalam dua tahap: Fase 1 berfokus pada Pemetaan Sosial, dan Fase 2 berfokus pada Fasilitasi Pendampingan Usaha. Proses bisnisnya di tahun 2025 meliputi Penetapan Lokasi, Penyuluhan, Pemetaan Sosial, Penyusunan Data, hingga Ekspose Data dan Perencanaan Kerja Sama. Strategi pemberdayaan kunci mencakup pemanfaatan program pemberdayaan yang sudah ada, serta menjamin adanya off-taker (penjamin pembeli hasil). Kehadiran off-taker menjadi jaminan agar hasil pertanian petani tidak jatuh ke tangan tengkulak, sehingga memperkuat keberlanjutan ekonomi lahan yang diterima.
Evaluasi Kinerja dan Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)
Kinerja Penataan Aset: Kontras Ekstrem antara Legalitas dan Redistribusi
Data realisasi menunjukkan kinerja yang sangat berbeda antara dua komponen utama Penataan Aset, menandakan adanya prioritas kebijakan yang timpang.
Tabel 1: Capaian dan Kesenjangan Target Penataan Aset Reforma Agraria (Periode RPJMN)
| Komponen Penataan Aset | Target (Juta Ha) | Realisasi (Ha) (s.d. Nov 2023) | Persentase Realisasi (%) | Implikasi Kinerja |
| Legalisasi Aset (PTSL) | 3.9 | 9,173,953 | 235.23% | Sangat melampaui target, fokus pada kepastian hukum. |
| Redistribusi TORA (Kawasan Hutan) | 4.1 | 357,094.76 | 8.71% | Kesenjangan masif, menunjukkan hambatan struktural/kelembagaan. |
| Legalisasi Aset (Transmigrasi) | 0.6 | 140,590.72 | 23.43% | Capaian rendah akibat masalah data dan tumpang tindih kawasan. |
Data di atas menunjukkan bahwa program Legalisasi Aset, terutama melalui PTSL, berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi mencapai 235.23% dari 3.9 juta Ha.11 Keberhasilan ini mengindikasikan efisiensi birokrasi dalam memberikan kepastian hukum dan sertifikasi.
Sebaliknya, Redistribusi TORA dari kawasan hutan hanya mencapai 8.71% dari target 4.1 juta Ha. Capaian yang sangat rendah ini menandakan adanya hambatan struktural yang masif, terutama dalam penyediaan tanah dari sektor kehutanan. Sementara itu, penyelesaian tanah transmigrasi juga jauh dari optimal (23.43%), disebabkan oleh kendala teknis dan yuridis seperti ketidaksesuaian data antar instansi, objek yang tumpang tindih dengan izin HGU, dan objek yang masuk dalam kawasan hutan.
Kritik Terhadap Ketimpangan Capaian
Keberhasilan PTSL yang masif menunjukkan bahwa prioritas politik dalam RA saat ini adalah menghilangkan ketidakpastian hukum (yang disukai oleh pasar) alih-alih menghilangkan ketimpangan struktural (yang menantang kekuasaan). PTSL merupakan kemenangan administratif yang fokus pada penguatan kepastian hukum tanah yang sudah dikuasai.
Sebaliknya, kegagalan dalam Redistribusi TORA mengindikasikan bahwa inti dari Reforma Agraria—yaitu perubahan struktur penguasaan lahan—belum terealisasi. Ketersediaan fresh land TORA sangat terbatas. Lahan yang dilepaskan oleh KLHK seringkali belum siap ditindaklanjuti oleh ATR/BPN karena kondisi fisik yang belum terpetakan, titik koordinat yang simpang siur, dan belum adanya verifikasi bersama yang memadai. Kegagalan mencapai target redistribusi berarti ketimpangan penguasaan lahan terus menghambat perbaikan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Tantangan Struktural dan Kendala Implementasi Reforma Agraria
Isu Kelembagaan: Konflik Kewenangan dan Ego Sektoral
Kendala terbesar dalam pelaksanaan RA adalah isu kelembagaan, terutama perselisihan kewenangan dan ego sektoral. Hubungan kerja antara ATR/BPN dan KLHK, termasuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dinilai belum efektif dalam menjalankan koordinasi. Di lapangan, ketiadaan tim terpadu untuk verifikasi lahan TORA dari kawasan hutan, serta tidak adanya model kerja yang jelas, menyebabkan pelambatan dan saling lempar tanggung jawab antar lembaga. Ego sektoral secara eksplisit diidentifikasi sebagai alasan utama mengapa target realisasi RA belum tercapai secara optimal.
Isu Yuridis dan Data: Kekacauan Data dan Tumpang Tindih
Secara teknis, basis data pertanahan saat ini berada dalam kondisi chaotic (kacau), sebuah situasi yang diperburuk oleh multiplisitas institusi yang menangani status tanah. Kekacauan data ini menjadi hambatan utama yang bersifat sistemik.
Selain itu, strategi pembangunan yang cenderung tidak berpihak pada pertanian, ditambah dengan penerbitan berbagai undang-undang dan peraturan sektoral (termasuk UU Cipta Kerja) yang memudahkan investor mengakses lahan, secara inheren merintangi upaya redistribusi. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan komitmen politik mendesak untuk mereformasi UU dan peraturan yang secara struktural meningkatkan akses investor. Tanpa revisi regulasi fundamental, upaya teknis RA akan terus melawan arus kebijakan ekonomi makro negara.
Ancaman Pasca-Redistribusi: Kegagalan Penataan Akses
Meskipun Penataan Aset berhasil diredistribusi, terdapat ancaman nyata berupa proses eksklusi dan re-akumulasi lahan. Studi kasus di Indonesia (Jawa) maupun di Filipina, Vietnam, dan Laos, menunjukkan bahwa tanah yang diredistribusi rentan untuk diambil alih kembali oleh elite atau tuan tanah, baik melalui pembelian maupun penyewaan. Hal ini terjadi karena lahan yang diterima subjek redistribusi seringkali terlalu kecil dan disertai kurangnya dukungan ekonomi (Penataan Akses yang belum optimal). Akibatnya, petani kecil tidak dapat menggantungkan hidup sepenuhnya pada lahan tersebut, dan pada akhirnya terancam terusir. Ini membuktikan bahwa redistribusi aset harus didukung oleh penguatan kelembagaan dan jaminan keberlanjutan ekonomi untuk mencegah kegagalan struktural pasca-redis.
Analisis Komparatif Model Reforma Agraria Global
Model Vietnam: Dari Kekerasan Revolusioner ke Hak Guna Tanah (Land Use Rights)
Reforma Agraria di Vietnam menunjukkan evolusi dramatis. Fase awal di Vietnam Utara (1953–1956) bersifat radikal dan revolusioner, ditandai dengan konfiskasi tanah dari tuan tanah dan distribusi kepada petani miskin, yang juga melibatkan represi dan kekerasan.
Setelah era Doi Moi (renovasi) pada tahun 1980-an, meskipun kepemilikan tanah tetap pada seluruh rakyat (diwakili negara), Vietnam mengadopsi sistem pasar dengan memberikan Hak Guna Lahan (Land Use Rights atau LUR) yang diakui secara hukum melalui “buku merah”. Sistem LUR ini berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan mengubah Vietnam menjadi salah satu pengekspor pangan utama. LUR berfungsi sebagai dasar hukum yang aman bagi pengguna tanah untuk melakukan transfer dan transaksi di pasar sekunder. Namun, Vietnam kini menghadapi tantangan modernisasi, termasuk tekanan untuk melonggarkan kontrol guna menarik investasi asing, yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran mengenai kontrol lahan oleh pihak eksternal.
Model Filipina: Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)
Filipina mengimplementasikan Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) melalui Republic Act No. 6657 (1988), yang bertujuan meredistribusi lahan pertanian publik dan swasta. Prinsip utama CARP adalah mempromosikan keadilan sosial dan menetapkan kepemilikan oleh penggarap (owner cultivatorship), sembari memberikan jaminan hak bagi pemilik lahan atas kompensasi yang adil (just compensation). Program ini menetapkan batas retensi kepemilikan dan memprioritaskan distribusi kepada petani terorganisir. Setelah redistribusi, CARP menyediakan pelatihan dan dukungan teknis , meskipun Filipina secara umum masih menghadapi kendala manajerial dan akses terhadap kredit pasca-redistribusi.
Pembelajaran Kritis untuk Indonesia
Perbandingan internasional menunjukkan bahwa masalah struktural pasca-redistribusi adalah tantangan regional yang meluas.
Tabel 2: Perbandingan Model Reforma Agraria Kunci di Asia Tenggara
| Karakteristik | Indonesia (Era Reformasi) | Vietnam (Era Doi Moi) | Filipina (CARP 1988) |
| Landasan Kepemilikan | Hak Menguasai Negara (HMN) / Hak Milik Individu | Kepemilikan Seluruh Rakyat, dioperasionalisasi melalui Hak Guna Lahan (LUR) | Hak Milik Individu, diredistribusi dengan kompensasi |
| Mekanisme Redistribusi | TORA (Tanah Negara, Eks-HGU, Hutan) | Transfer Hak Guna Lahan | Pembelian Lahan Swasta (Kompensasi Wajib) |
| Capaian Redistribusi | Rendah (TORA Hutan: 8.71% dari target) | Cepat & Efektif (dalam LUR), mendorong produktivitas | Lahan Pertanian Swasta yang luas terdistribusi |
| Kendala Utama Regional | Ego Sektoral, Kekacauan Data, Re-akumulasi Lahan | Batasan LUR, Risiko Kontrol Asing | Masalah Manajerial, Exclusion Pasca-Redistribusi |
| Fokus Pasca-Redistribusi | Penataan Akses (Pemberdayaan Ekonomi) | Peningkatan Produktivitas Pertanian | Dukungan Teknis dan Kredit (Sering Terkendala) |
Indonesia berada di persimpangan antara model kompensasi yang mahal (Filipina) dan model LUR yang pro-pasar (Vietnam). Dengan mengandalkan mekanisme TORA yang “gratis” dari kawasan hutan, Indonesia menghadapi masalah kritis dalam ketersediaan lahan (supply-side failure) akibat kebuntuan kelembagaan. Pembelajaran utama adalah bahwa kegagalan regional dalam mencegah eksklusi lahan pasca-redistribusi membuktikan bahwa redistribusi aset saja tidak cukup. Indonesia harus menjadikan Penataan Akses, melalui dukungan kelembagaan dan fasilitasi pasar (termasuk off-taker), sebagai komponen utama untuk menstabilkan kepemilikan tanah oleh petani yang baru bersertifikat.
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan (Policy Recommendations)
Kesimpulan Utama: Diagnosis Kegagalan Struktural dan Kesenjangan Capaian
Reforma Agraria di Indonesia menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam aspek administratif dan legalitas (PTSL), yang mencapai 235.23% dari target. Namun, program ini mengalami kegagalan struktural yang mendalam dalam inti redistribusi TORA, dengan realisasi dari kawasan hutan hanya 8.71%. Hambatan utama bersifat kelembagaan (ego sektoral ATR/BPN vs. KLHK) dan yuridis (kekacauan basis data dan keberadaan regulasi yang memprioritaskan akses investor). Kontras ini menunjukkan bahwa komitmen politik untuk menghilangkan ketidakpastian hukum lebih kuat daripada komitmen untuk menghilangkan ketimpangan struktural. Tanpa adanya Penataan Akses yang optimal, lahan yang berhasil diredistribusi berisiko tinggi kembali diakumulasi oleh kelompok elite, mengulangi kegagalan yang diamati di berbagai negara Asia Tenggara.
Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Kelembagaan
- Integrasi Kelembagaan Total: Diperlukan intervensi politik tingkat tinggi untuk mengatasi ego sektoral. Harus dibentuk mekanisme kelembagaan yang mengikat, mungkin di bawah koordinasi Kantor Menko Perekonomian atau Presiden, untuk menyelesaikan sengketa TORA kawasan hutan, dengan mekanisme sanksi yang jelas bagi kementerian yang menghambat.
- Perbaikan Data dan Verifikasi Dini: Anggaran harus diprioritaskan untuk memperbaiki basis data pertanahan yang chaotic. Verifikasi TORA
fresh land harus dilakukan secara terpadu oleh ATR/BPN dan KLHK sebelum pelepasan diumumkan, untuk menjamin kesiapan spasial dan fisik lahan.
Rekomendasi Hukum: Reformasi Regulasi Sektoral
- Revisi Regulasi Pro-Investor: Reforma Agraria harus diawali dengan mereformasi undang-undang dan peraturan yang secara akumulatif meningkatkan akses lahan bagi investor.1 Hal ini untuk memastikan upaya redistribusi tidak terus menerus melawan arus kebijakan ekonomi makro.
- Penguatan Hak Masyarakat Adat: Status dan hak tanah masyarakat hukum adat harus dipertegas dan dilindungi secara hukum, mencegah reduksi hak mereka demi kepentingan legalitas formal atau kepentingan politik lokal.
Rekomendasi Programatik: Optimalisasi Penataan Akses
- Anggaran Penataan Akses yang Proporsional: Anggaran dan sumber daya untuk Penataan Akses harus ditingkatkan secara signifikan, setara dengan ambisi yang ditunjukkan dalam program PTSL. Penataan Akses tidak boleh hanya menjadi pelengkap, melainkan pilar pencegah kegagalan struktural.
- Jaminan Keberlanjutan Ekonomi: Penataan Akses Fase 2 (Pendampingan Usaha) harus diperkuat dengan fokus pada fasilitasi off-taker BUMN atau swasta. Jaminan pasar ini penting untuk memutus rantai tengkulak, menjamin hasil usaha petani, dan secara fundamental mencegah terjadinya land exclusion pasca-redistribusi.
Daftar Pustaka :
- Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia, accessed on October 1, 2025, https://www.researchgate.net/publication/320588085_Beberapa_Permasalahan_dalam_Pelaksanaan_Reformasi_Agraria_di_Indonesia
- PERALIHAN HAK ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN PRINSIP REFORMA AGRARIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN D – E-Journal UNSRAT, accessed on October 1, 2025, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52316/44540
- Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia – Neliti, accessed on October 1, 2025, https://www.neliti.com/publications/64253/beberapa-permasalahan-dalam-pelaksanaan-reformasi-agraria-di-indonesia
- KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (KAJIAN …, accessed on October 1, 2025, https://repository.stpn.ac.id/683/1/RAYYAN.pdf
- Reforma Agraria: Sinkronisasi TORA dan Perhutanan Sosial – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, accessed on October 1, 2025, https://ekon.go.id/publikasi/detail/2097/reforma-agraria-sinkronisasi-tora-dan-perhutanan-sosial
- BAB I PENDAHULUAN – DPR RI, accessed on October 1, 2025, https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20160916-102549-6280.pdf
- (PDF) Reformasi Hukum Tanah Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global – ResearchGate, accessed on October 1, 2025, https://www.researchgate.net/publication/365215930_Reformasi_Hukum_Tanah_Desa_Dalam_Kepungan_Kapitalisme_Global
- Reformasi Agraria dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia pada Era Orde Lama dan Orde Baru – DOAJ, accessed on October 1, 2025, https://doaj.org/article/dbedbcb2f50542c49f3036c9e212b57b
- Langkah Percepatan Reforma Agraria – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, accessed on October 1, 2025, https://ekon.go.id/publikasi/detail/2099/langkah-percepatan-reforma-agraria
- Implementasi Teori Hukum dalam Reformasi Hukum Agraria di Indonesia, accessed on October 1, 2025, https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/download/439/647/2601
- REVITALISASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA …, accessed on October 1, 2025, https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/236/112/
- REFORMA AGRARIA: TANAH OBYEK REMORMA AGRARIA DAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN, accessed on October 1, 2025, https://repository.stpn.ac.id/1748/1/16%20laporan%20RA_Sumsel_2019.pdf
- Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan – Repository …, accessed on October 1, 2025, https://repository.stpn.ac.id/60/1/Buku%20Ajar%20Reforma%20Agraria.pdf
- Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia – kantor pertanahan kab. pringsewu, accessed on October 1, 2025, https://kab-pringsewu.atrbpn.go.id/infografis/pelaksanaan-reforma-agraria-di-indonesia
- petunjuk teknis – penanganan akses reforma agraria, accessed on October 1, 2025, https://spse.inaproc.id/atrbpn/dl/e1298b89898ee34342b41073fb79a23a45c29aabd40476069422c40b8cc6f3bb63f0286cb5a84ff062d71cc769d7065db3e651f341d75dec5c8a959cbf5f8b79acb783e3cbaf53a9603ffc04044cc8e73f3801940867718db89c8f4856965684ec388d8e31cde1742249211759e585aa
- Buka Monev Penataan Agraria Semester I 2025, Wamen Ossy Tekankan Pentingnya Penataan Akses demi Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat – ATR/BPN, accessed on October 1, 2025, https://www.atrbpn.go.id/berita/buka-monev-penataan-agraria-semester-i-2025-wamen-ossy-tekankan-pentingnya-penataan-akses-demi-peningkatan-taraf-hidup-masyarakat
- Reforma Agraria Masih Jauh dari Ideal? Ini Data Target dan Capaian Nyata di Lapangan, accessed on October 1, 2025, https://blitarkawentar.jawapos.com/nasional/2276432546/reforma-agraria-masih-jauh-dari-ideal-ini-data-target-dan-capaian-nyata-di-lapangan
- Vietnam land law 2013 – Viet An Law Firm, accessed on October 1, 2025, https://vietanlaw.com/vietnam-land-law-2013/
- Legal Perspective on Land Use Rights in Vietnam – ASL LAW Firm, accessed on October 1, 2025, https://aslgate.com/legal-perspective-on-land-use-rights-in-vietnam/
- Vietnam and Philippine Agriculture Fall Prey to Globalization of Land Rights, accessed on October 1, 2025, https://www.iatp.org/sites/default/files/Vietnam_and_Philippine_Agriculture_Fall_Prey_t.htm
- Comprehensive Agrarian Reform Law (R.A. No. 6657) – DAR – LIS, accessed on October 1, 2025, http://www.lis.dar.gov.ph/documents/226
- Participation of stakeholders in developing agrarian reform communities in the Philippines – Food and Agriculture Organization of the United Nations, accessed on October 1, 2025, https://www.fao.org/4/y0434t/Y0434t02.htm
- Transformative Pathways of Agrarian Reform: Comparative Bibliometric Insights of Southeast Asia and Indonesia Cases, accessed on October 1, 2025, https://jurnal.pusbindiklatren.bappenas.go.id/lib/jisdep/article/view/534