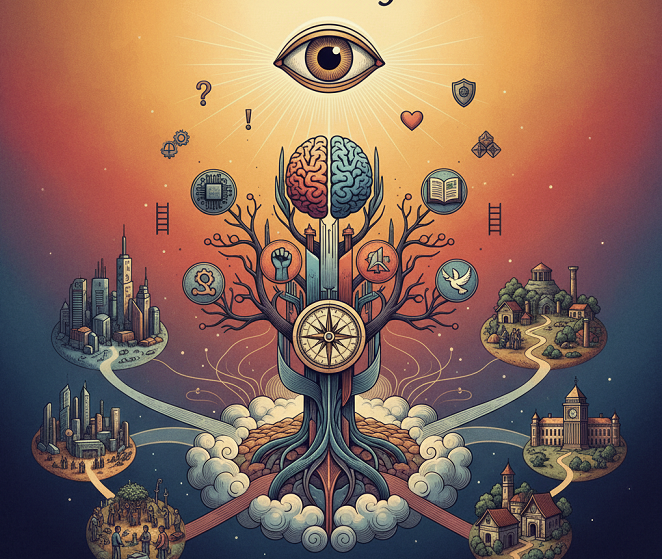Konteks Ideologi Politik Pasca-Otoritarianisme
Sistem kepartaian di Indonesia sejak era Reformasi menunjukkan spektrum ideologis yang kompleks, di mana warisan sejarah, kewajiban konstitusional, dan tuntutan pragmatisme kekuasaan saling berinteraksi. Untuk memahami posisi partai-partai saat ini, penting untuk menetapkan konteks teoretis dan historis mengenai bagaimana ideologi diartikulasikan di ruang politik Indonesia.
Latar Belakang Historis dan Transformasi Ideologi Partai
Dinamika ideologi partai politik di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Pada masa Orde Lama, politik didominasi oleh sistem Aliran dengan basis massa yang kaku. Namun, pada masa Orde Baru, terjadi penyederhanaan paksa dan depolitisasi. Partai keagamaan, misalnya, dipaksa melebur menjadi satu entitas. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan pada 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi dari empat partai keagamaan: Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Fusi ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian.
Setelah jatuhnya rezim otoriter pada 1998, Era Reformasi ditandai dengan ledakan jumlah partai, namun proses ini membawa tantangan baru: konsolidasi ideologis yang harus beradaptasi dengan sistem demokrasi elektoral yang menekankan fungsi pemilu.
Landasan Teoretis: Ideologi, Kekuasaan, dan Pragmatisme
Dalam konteks politik Indonesia, ideologi harus dipahami bukan hanya sebagai seperangkat nilai abstrak, tetapi sebagai paham tertentu yang digunakan untuk melingkupi semua usaha mencapai kondisi ideal tertentu, yang secara eksplisit dihubungkan dengan kekuasaan. Keterkaitan antara ideologi dan kekuasaan ini menjelaskan mengapa pragmatisme seringkali mendominasi.
Salah satu fenomena kunci yang muncul dalam sistem politik multipartai presidensial Indonesia adalah Ideological Blurring atau keburaman ideologi. Pembentukan koalisi partai politik dimungkinkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kesamaan platform dalam masalah agama, ekonomi, dan kebangsaan. Namun, keharusan membentuk koalisi—sebuah sistem yang tidak dapat dihindari dalam pemerintahan presidensial multipartai—menimbulkan implikasi yuridis dan politis. Untuk mencapai stabilitas pemerintahan atau sekadar untuk bertahan hidup dalam sistem ambang batas presiden (presidential threshold), partai seringkali dituntut untuk melonggarkan rincian ideologis mereka, membuktikan bahwa akses kekuasaan dan kelangsungan politik adalah fungsi utama yang seringkali mengesampingkan kekakuan ideologi murni.
Pancasila sebagai Supra-Ideologi: Batasan dan Legitimasi
Semua partai politik di Indonesia wajib berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ditempatkan sebagai supra-ideologi; ia berfungsi sebagai kontrak sosial, norma tertinggi yang memandu (litstern), dan kerangka bagi struktur hukum Indonesia.
Kewajiban struktural ini secara efektif membatasi spektrum politik. Ideologi partai, baik Marhaenisme, Islamisme, maupun Populisme, harus diartikulasikan sebagai interpretasi instrumental dari Pancasila, bukan sebagai entitas yang bertentangan atau menggantikannya. Konsekuensinya, partai-partai cenderung berkonvergensi pada tingkat kebijakan umum (misalnya, semua mengklaim menjunjung tinggi “keadilan sosial” atau “demokrasi kerakyatan”), namun mereka berbeda tajam dalam artikulasi ideologis mereka pada isu-isu sosial-kultural dan penafsiran spesifik terhadap sila-sila Pancasila.
Peta Spektrum Ideologi Politik Indonesia: Klasifikasi dan Pilar Utama
Partai politik utama di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga blok ideologis utama, meskipun mobilitas dan kebutuhan koalisi sering membuat batas-batas ini menjadi cair.
Blok Ideologis Kebangsaan (Nasionalis Sekuler / Kiri-Tengah)
Blok ini didominasi oleh partai-partai yang menempatkan nasionalisme sekuler dan prinsip kerakyatan sebagai inti ideologi mereka.
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): PDI-P adalah partai nasionalis sekuler yang menempatkan diri di posisi tengah hingga kiri-tengah. Ideologi intinya adalah Pancasila, Nasionalisme Indonesia, Sukarnoism, Marhaenism, Sosial Demokrasi, dan Sekularisme. Secara tegas, PDI-P menggunakan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Marhaenisme, yang menekankan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, menjadi prinsip politik yang diajarkan kepada seluruh kader. PDI-P juga fokus pada Ekonomi Kerakyatan, di mana partai secara aktif melakukan pemberdayaan konstituen, seperti melalui Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- Partai Nasional Demokrat (NasDem): Partai ini mengadopsi ideologi Pancasila, Nasionalisme Indonesia, Sekularisme, Sosial Demokrasi, Sosial Liberalisme, dan Progresivisme. Posisi politiknya diidentifikasi sebagai tengah hingga tengah-kiri, menunjukkan pergeseran dari tradisi Golkar (yang merupakan partai asal beberapa pendirinya) menuju nasionalisme yang lebih progresif.
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI): PSI menempati posisi kiri-tengah dan secara eksplisit berfokus pada progresivisme, sekularisme, pluralisme, dan hak-hak minoritas. PSI mengadopsi konsep Pancasila dan Trisakti Soekarno, yang mereka terjemahkan menjadi Trilogi PSI: Menebar kebajikan, Merawat keragaman, dan Meneguhkan solidaritas. Partai ini dikenal karena platform progresifnya dan dukungannya yang eksplisit terhadap Jokowism.
Blok Ideologis Islam (Partai Berbasis Agama dan Fusi)
Partai-partai berbasis Islam di Indonesia terbagi antara tradisi Islam Fusi/Tengah, Islam Tradisionalis, dan Islam Modernis/Konservatif. Pembagian ini bukan hanya tentang klaim agama, tetapi juga tentang perebutan otoritas tafsir Islam di ranah politik.
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): PKS umumnya diklasifikasikan sebagai partai Islam Modernis/Konservatif yang menonjolkan kaderisasi kuat dan penekanan ideologis pada Ketuhanan.
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): PKB secara historis terkait erat dengan Nahdlatul Ulama (NU), mewakili Islam Tradisionalis dan Islam Moderat Nusantara.
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP): PPP mewakili Islam Fusi/Tengah, yang merupakan kelanjutan dari sejarah penyederhanaan kepartaian Orde Baru.
Pertarungan ideologis antara NU (yang sangat memengaruhi PKB) dan PKS seringkali menjadi manifestasi persaingan politik yang mendalam. Misalnya, pada Pilpres 2024, tokoh-tokoh NU menggunakan narasi usang, menggambarkan koalisi yang didukung PKS sebagai kelompok Wahabi yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin. Pemanfaatan narasi transnasional ini adalah strategi delegitimasi yang memperjelas bahwa “Islam Politik” Indonesia tidaklah monolitik. Sebaliknya, ia terbagi tajam antara kelompok Tradisionalis yang cenderung akulturatif dan kelompok Modernis yang cenderung lebih puritan atau konservatif secara sosial.
Blok Ideologis Fungsionalis dan Populisme (Nasionalis Kanan / Catch-All)
Blok ini terdiri dari partai-partai yang fokus pada stabilitas fungsional, pembangunan, dan mobilisasi berbasis kepemimpinan karismatik atau populisme.
- Partai Golkar: Ideologi inti Golkar adalah Kekaryaan, yang menekankan pembangunan fungsional dan pluralisme majemuk. Golkar berfungsi sebagai catch-all party yang berupaya menampung kemajemukan bangsa dan memandang keberagaman sebagai anugerah yang terikat dalam Bhinneka Tunggal Ika.
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): Gerindra secara ideologis diklasifikasikan sebagai Populisme Sayap Kanan dan Nasionalis Keras. Meskipun berasaskan Pancasila dan UUD 1945, identitasnya berakar kuat pada nasionalisme, populisme, agama, dan keadilan sosial. Gerindra, yang didirikan pada 2008, berfungsi sebagai kendaraan politik bagi Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden. Partai ini sering digambarkan sebagai nasionalis-religius oleh anggotanya sendiri.
- Partai Demokrat: Partai ini umumnya mengambil posisi sentrisme pragmatis. Ketua Dewan Pembina Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah menekankan bahwa Globalisme dan Nasionalisme tidak perlu dipertentangkan , yang menunjukkan posisi yang fleksibel dan berorientasi teknokratik.
Tabel Esensial 1: Klasifikasi Partai Politik Mayor Berdasarkan Blok Ideologis (Periode Reformasi)
| Blok Ideologis | Partai Utama | Karakteristik Ideologi Inti | Posisi Politik Umum | Referensi |
| Nasionalis Sekuler / Kiri-Tengah | PDI-P, NasDem, PSI | Sukarnoism, Marhaenisme, Sosial-Demokrasi, Progresivisme, Sekularisme | Pusat hingga Kiri-Tengah | |
| Islam / Berbasis Agama | PKS, PPP, PKB | Islam Modernis (Konservatif Sosial), Islam Fusi/Tengah, Islam Tradisionalis (NU) | Pusat hingga Kanan (Sosial-Kultural) | |
| Nasionalis Fungsionalis / Populisme Kanan | Golkar, Gerindra, Demokrat | Kekaryaan, Nasionalisme Keras, Populisme Sayap Kanan, Sentrisme Pragmatis | Pusat hingga Kanan |
Analisis Mendalam Implementasi Ideologi Partai Mayor
Ideologi tidak hanya tercermin dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tetapi juga dalam bagaimana partai memilih isu kebijakan dan menafsirkan Pancasila.
Ideologi Ekonomi: Marhaenisme PDI-P vs. Fungsionalisme Golkar
Perbedaan ideologi ekonomi menunjukkan kontras dalam peran negara dan masyarakat. PDI-P, melalui Marhaenisme, fokus pada Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan. Partai ini mewujudkan komitmen ini dengan berperan sebagai wadah dan penghubung antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput. Contohnya adalah peran Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan PDI-P di desa-desa.
Sebaliknya, Golkar, dengan ideologi Kekaryaan, menekankan pembangunan yang stabil dan inklusif di bawah payung pluralisme. Gerindra, yang berideologi nasionalisme keras dan populisme, cenderung mengarah pada Nasionalisme Ekonomi yang proteksionis, meskipun retorika ini harus diseimbangkan dengan kebutuhan koalisi.
Ideologi Sosial-Kultural: Konservatisme vs. Progresivisme
Dalam lingkungan politik pasca-Reformasi, di mana mayoritas partai harus mengadopsi platform ekonomi yang serupa (berbasis Pancasila dan pasar terbuka), isu sosial-kultural menjadi medan pertempuran ideologis utama yang menentukan garis batas antarpartai.
PKS: Konservatisme Sosial sebagai Penanda Batas
PKS secara konsisten menggunakan isu sosial-moral untuk menegaskan identitas ideologisnya. Partai ini menyoroti kekosongan hukum terkait isu LGBT dan mendorong penguatan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). PKS juga terlibat dalam kontroversi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang memunculkan perdebatan mengenai legalitas moral dan potensi pro-LGBT. Taktik ini menunjukkan bahwa dalam konvergensi kebijakan nasionalis-ekonomi, PKS berpegang teguh pada garis konservatisme sosial yang ketat untuk mempertahankan konstituen dan membedakan diri secara ideologis dari partai Nasionalis Sekuler atau Islam Tradisionalis yang lebih akomodatif kultural.
PSI: Pluralisme dan Progresivisme Eksplisit
Di kutub yang berlawanan, PSI secara eksplisit mengusung Sekularisme, Progresivisme, Pluralisme, dan Hak Minoritas. Posisi ini adalah salah satu yang paling progresif-sosial dalam spektrum politik nasional. Penekanan PSI pada Merawat Keragaman sebagai bagian dari Trilogi mereka adalah respons langsung terhadap isu-isu sosial-kultural yang dihindari oleh banyak partai politik besar lainnya.
Perbandingan Tafsir Pancasila: Kerakyatan (PDI-P) versus Ketuhanan (PKS)
Walaupun semua partai berlandaskan Pancasila, tafsir terhadap sila-sila utamanya berbeda dan menjadi pembeda ideologis yang mendasar. PDI-P berpegang pada semangat Pancasila 1 Juni 1945, yang menekankan Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi (nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial) sebagai jati diri partai.
Sebaliknya, sementara PKS juga berasaskan Pancasila, praktik ideologis mereka menempatkan penekanan yang jauh lebih besar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diinterpretasikan secara konservatif untuk mendefinisikan moralitas publik dan hukum.
Tabel Esensial 2: Interpretasi Ideologis Kunci oleh Partai Pilihan terhadap Isu Sentral
| Partai | Pilar Ideologi Dasar (AD/ART) | Interpretasi Pancasila | Sikap Ekonomi Kunci | Sikap Sosial/HAM Kunci |
| PDI-P | Nasionalisme, Marhaenisme, Sosio-Demokrasi | Sosio-Nasionalisme & Sosio-Demokrasi (1 Juni 1945), Fokus Kerakyatan | Ekonomi Kerakyatan/Negara Kuat | Pluralis, Sekuler-Nasionalis |
| Gerindra | Nasionalisme, Populisme, Keadilan Sosial | Nasionalisme Keras, Keamanan Negara | Nasionalisme Ekonomi (Proteksionis) | Nasionalis-Religius (Fleksibel) |
| PSI | Pluralisme, Progresivisme, Jokowism | Trisakti Soekarno, Merawat Keragaman | Sosial-Demokrasi, Liberalisme | Progresif, Pluralis, Hak Minoritas |
| PKS | Islam | Ketuhanan Yang Maha Esa (Konservatif) | Konservatif (Welfare Islam) | Konservatif, Penekanan pada Moralitas Publik (RUU KUHP/P-KS) |
Dinamika Kontemporer: Pragmatisme dan Tantangan Institusionalisasi
Dinamika ideologi partai di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: personalisasi kekuasaan dan rendahnya pelembagaan partai.
Peran Personalisasi Politik dan De-Institusionalisasi Partai
Sebagian besar partai besar di Indonesia menunjukkan tingkat personalisasi yang ekstrem, di mana ideologi dan pengambilan keputusan terikat kuat pada sosok elit tunggal. Di PDI-P, Megawati Sukarnoputri dianggap sebagai pemimpin partai yang tak tergantikan, dan segala keputusan penting—mulai dari penentuan calon legislatif, calon presiden/wakil presiden, hingga kepala daerah—hanya dilakukan atas persetujuannya. Model kepemimpinan yang mengedepankan tokoh elit ini seringkali dianggap sebagai bentuk demokrasi terpimpin di internal partai.
Ketergantungan pada tokoh karismatik ini, meskipun menjamin soliditas jangka pendek, menimbulkan dampak negatif serius berupa de-institusionalisasi partai. Organisasi dan manajemen partai tidak berjalan optimal, dan pembuatan kebijakan cenderung dipengaruhi kuat oleh kepentingan elit tertentu, yang berarti mekanisme demokrasi internal tidak berjalan sesuai fungsinya. Ketika ideologi diwakilkan oleh karisma tokoh tunggal, penanaman nilai ideologis (value infusion) yang konsisten di kalangan kader menjadi rentan. Stabilitas partai menjadi sangat bergantung pada soliditas ekonomi dan keuangan yang menopang elit tersebut, bukan pada kekuatan kelembagaan partai itu sendiri.
Ideological Blurring sebagai Strategi Koalisi yang Tak Terhindarkan
Kebutuhan untuk berkoalisi dalam sistem multipartai presidensial memaksa partai untuk bersikap pragmatis, yang seringkali memburamkan garis ideologi mereka. Gerindra, misalnya, yang dibentuk dengan ideologi populisme sayap kanan dan nasionalis , memposisikan diri sebagai partai oposisi murni dari 2008 hingga 2019. Namun, setelah Pemilu 2019, Gerindra memilih bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo, meskipun Prabowo Subianto sebelumnya adalah lawan utama Jokowi dalam dua pemilihan presiden.
Pergeseran ini menunjukkan bahwa meskipun ideologi berfungsi sebagai platform untuk mobilisasi massa dan diferensiasi elektoral, fleksibilitas ideologis (ideological blurring) adalah harga yang harus dibayar untuk mengakses kekuasaan eksekutif dan memastikan stabilitas politik dalam sistem presidensial Indonesia.
Ideologi dan Konsolidasi Demokrasi: Krisis Kelembagaan
Partai politik adalah pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional; mereka berfungsi sebagai kendaraan utama perwakilan politik, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, dan saluran utama untuk memelihara akuntabilitas. Namun, fungsi-fungsi ini terganggu oleh tantangan struktural.
Penelitian menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia menempati urutan terbawah sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Rendahnya kepercayaan publik ini merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan partai untuk melembagakan organisasinya dengan baik. Tingkat pelembagaan partai masih jauh dari ideal, terutama pada derajat kesisteman (systemness) dan penanaman nilai ideologis (value infusion).
Ketika ideologi dikorbankan demi pragmatisme koalisi dan keputusan dikendalikan secara sepihak oleh elit (personalisasi), publik memandang partai sebagai oportunistik. Situasi ini menghambat fungsi partai dalam menyerap aspirasi masyarakat dan berkontribusi pada tantangan kualitas demokrasi. Penguatan peran partai dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui legislasi hanya dapat dioptimalkan jika partai memiliki hubungan yang lebih terstruktur dan kokoh dengan masyarakat, yang hanya mungkin tercapai melalui agenda partai yang hadir secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu.
Kesimpulan
Ideologi partai politik di Indonesia beroperasi dalam suatu paradoks fundamental. Secara formal, semua ideologi terikat pada Pancasila sebagai ideologi negara, membatasi adopsi paham-paham radikal dan mendorong konvergensi pada isu-isu kebangsaan dan ekonomi. Namun, secara praktik, implementasi ideologi didorong oleh pragmatisme kekuasaan, kebutuhan koalisi, dan personalisasi ekstrem.
Ideologi masih mempertahankan fungsi pentingnya sebagai alat mobilisasi massa dan penanda batas sosial-kultural (sebagaimana terlihat jelas pada PKS dan PSI). Namun, ia sering menjadi faktor sekunder dibandingkan dengan kepentingan elit dan kebutuhan untuk membentuk koalisi yang stabil. De-institusionalisasi yang disebabkan oleh personalisasi politik merusak penanaman nilai ideologis jangka panjang dan melemahkan kepercayaan publik terhadap fungsi partai dalam demokrasi.
Untuk memperkuat peran ideologi dalam konsolidasi demokrasi dan stabilitas politik, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi personalisasi dan de-institusionalisasi:
- Revitalisasi Kaderisasi Ideologis: Partai harus memperkuat sistem kaderisasi yang fokus pada penanaman nilai ideologis (value infusion) yang konsisten, yang tidak tergantung pada karisma tokoh tunggal. Hal ini akan meningkatkan kesisteman partai dan menjamin keberlanjutan ideologi di luar masa jabatan elit pendiri.
- Reformasi Demokrasi Internal: Mendorong reformasi internal yang secara struktural mengurangi personalisasi ekstrem, mengembalikan otoritas pengambilan keputusan kepada mekanisme kelembagaan yang demokratis, dan mengatasi kerugian yang disebabkan oleh model kepemimpinan elit.
- Penguatan Fungsi Pemberdayaan Konstituen: Partai politik harus meningkatkan aktivitas pemberdayaan konstituen dan masyarakat umum secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu. Kerja politik harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk membangun hubungan yang kokoh antara ideologi, program partai, dan masyarakat yang diwakilinya.