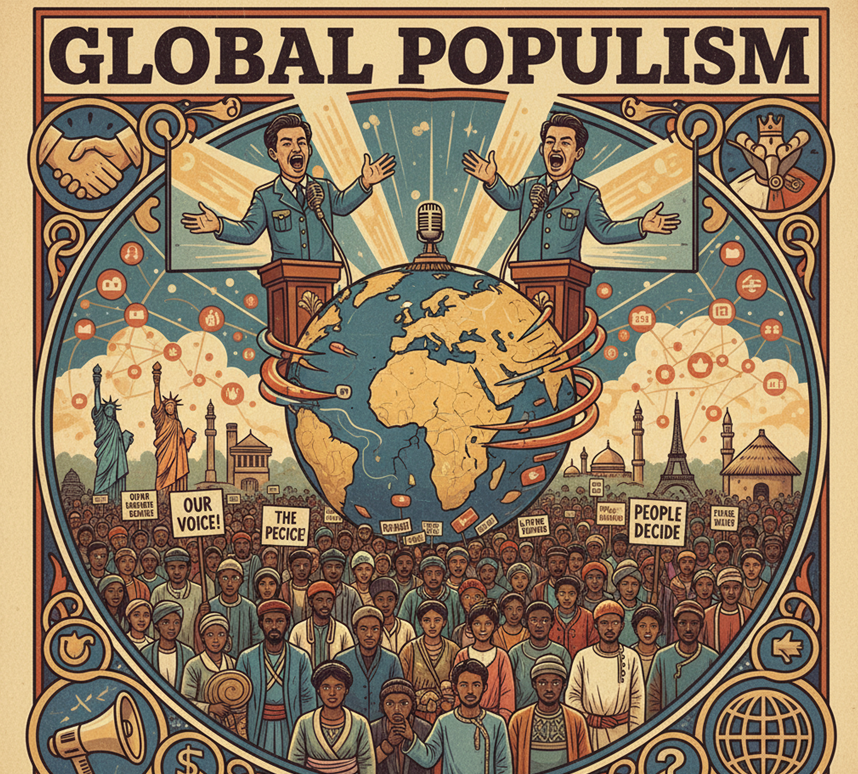Kerangka Konseptual Populisme Kontemporer
Kebangkitan populisme merupakan salah satu fenomena politik paling signifikan di era kontemporer. Gerakan ini telah meluas secara global, dan titik baliknya seringkali diasosiasikan dengan peristiwa politik besar seperti kemenangan Donald J. Trump dalam pemilihan presiden AS pada tahun 2016 dan referendum Brexit di Britania Raya. Kebangkitan ini dipahami sebagai reaksi mendalam terhadap serangkaian krisis sosial-ekonomi dan politik yang terjadi, khususnya setelah dampak Krisis Keuangan Global 2008, yang memunculkan ketidakpuasan terhadap sistem yang sudah mapan di negara-negara demokrasi maju.
Secara akademis, populisme paling efektif didefinisikan bukan sebagai ideologi yang lengkap (full ideology), melainkan sebagai ideologi berpusat tipis (thin-centered ideology). Populisme membutuhkan ideologi “tuan rumah” (seperti nativisme sayap kanan atau sosialisme sayap kiri) untuk memberikan substansi politiknya. Inti dari populisme terletak pada konstruksi wacana dikotomi Manichean, yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok homogen dan antagonistik: Rakyat Murni (The People) yang baik, dan Elit Korup (The Elite) yang tidak bermoral dan mengkhianati kepentingan rakyat.
Gerakan populis memiliki ciri khas berupa penolakan tegas terhadap status quo dan institusi yang dianggap mapan, termasuk partai politik tradisional, media mainstream, dan lembaga-lembaga internasional. Pemimpin populis seringkali memiliki karisma yang kuat, memposisikan diri mereka sebagai satu-satunya perwakilan sah dari kehendak rakyat.
Pola pikir ini menjelaskan bagaimana populisme berinteraksi dengan demokrasi. Karena populisme secara fundamental menekankan pada kedaulatan mayoritas rakyat, ia cenderung memandang institusi demokrasi liberal—seperti supremasi hukum, perlindungan hak minoritas, dan pembagian kekuasaan—sebagai penghalang yang membatasi kehendak mayoritas. Konsekuensinya, terdapat kecenderungan kuat dalam gerakan populis untuk mengikis mekanisme checks and balances, meyakini bahwa institusi tersebut hanya menjadi alat elit lama.
Meskipun demikian, peran populisme dalam demokrasi bersifat ambigu. Di satu sisi, ia menjanjikan pembaruan demokratis dengan memperkenalkan aktor dan kebijakan baru ke dalam sistem politik. Namun, di sisi lain, populisme seringkali menimbulkan masalah dalam tata kelola. Kurangnya minat atau kemampuan para aktor populis untuk terlibat dalam proses legislatif yang terperinci dapat mengalihkan pembuatan kebijakan ke aktor di luar partai yang berkuasa. Hal ini justru merusak akuntabilitas dan konsistensi kebijakan, yang memicu munculnya reformasi yang heterodox, cepat, dan seringkali tidak terduga.
Akar Kebangkitan Global: Kesenjangan, Identitas, dan Digitalisasi
Kebangkitan global populisme didorong oleh konvergensi antara faktor sosial-ekonomi, kultural, dan teknologi komunikasi.
Akar Sosio-Ekonomi: Kecemasan Globalisasi
Ketidakpuasan yang memicu populisme berakar pada dampak globalisasi. Studi menunjukkan adanya kecemasan mendalam akibat dampak sosial dan ekonomi ini, yang melanda tidak hanya di kalangan kelas pekerja yang terdeindustrialisasi, tetapi juga di kalangan kelas menengah di banyak masyarakat.
Masyarakat di daerah-daerah deindustrialisasi dan dekarbonisasi di negara-negara demokrasi maju merasakan bahwa mereka telah dilupakan, menjadi korban tatanan politik tradisional, dan menumbuhkan kebencian terhadap elit. Populisme datang sebagai respons, menjanjikan kembalinya era kejayaan masa lalu dan menyalahkan elit petahana serta aktor-aktor internasional atas pelemahan kedaulatan negara dan kemerosotan ekonomi.
Akar Kultural: Nativisme dan Politik Identitas
Dalam konteks kultural, gelombang populisme sayap kanan radikal dimobilisasi secara efektif melalui nativisme, sebuah paham yang menekankan pembedaan antara “pribumi” dan “non-pribumi” melalui narasi us versus them.
Isu imigrasi telah menjadi medan pertempuran utama. Krisis pengungsi dan imigrasi besar-besaran, khususnya di Eropa setelah tahun 2015, dieksploitasi untuk memperkuat narasi bahwa nilai-nilai kebangsaan, etnisitas, dan identitas kultural terancam oleh unsur sosio-kultural dari luar. Strategi ini terbukti sangat efektif dalam mempengaruhi dukungan suara pemilih terhadap kandidat populis.
Faktor Katalis: Media Digital dan Kamar Gema
Perkembangan teknologi komunikasi digital bertindak sebagai katalis yang kuat dalam menyebarkan dan memperkuat populisme. Media sosial telah menjadi platform utama yang memungkinkan penyebaran pesan populis, termasuk politik identitas berbasis agama, dengan sangat cepat, memberikan akses tanpa mediasi kepada audiens yang luas.
Platform digital turut memfasilitasi pembentukan kamar gema (echo chambers), yaitu lingkungan online di mana pengguna hanya bertemu informasi yang memperkuat keyakinan mereka yang sudah ada. Lingkungan tertutup ini membatasi paparan terhadap perspektif yang beragam, sehingga memperkuat polarisasi sosial dan politik. Populisme modern dipandang sebagai produk dari ketidakpuasan yang dikemas dan diperkuat secara algoritmik. Kecenderungan alami manusia untuk berinteraksi dengan kelompok sejenis (homophily) ** diperkuat oleh algoritma media sosial. Proses ini mengubah ketidakpuasan ekonomi menjadi bias kognitif yang terpolarisasi (sociocentric thinking), yang kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin populis untuk mobilisasi massa .
Meskipun retorika populis berfokus pada kepentingan ‘rakyat biasa’ melawan ‘elit’, analisis menunjukkan adanya aspek instrumentalitas yang menarik. Politik populis seringkali diinstrumentalisasikan sebagai wahana untuk kepentingan elit dan oligarki penyokong. Para elit ini menggunakan retorika anti-elit dan identitas primordial untuk mendapatkan kekuasaan, namun kebijakan yang diterapkan seringkali menguntungkan segmen elit yang baru atau yang mendukung mereka, terkadang melalui praktik ekonomi neopatrimonial.
Studi Kasus I: Populisme “America First” Donald Trump (Model Personalistik-Retoris)
Donald J. Trump dianggap sebagai simbol utama kebangkitan populisme kontemporer. Model populisme yang ia gunakan sangat bersifat personalistik dan berbasis pada karisma individu.
Retorika dan Gaya Kepemimpinan
Retorika Trump dicirikan oleh gaya yang sangat agresif, personalisasi kepemimpinan, dan fokus pada polarisasi dan demonisasi lawan politik. Ia secara konsisten menggunakan retorika anti-institusi, menantang legitimasi media mainstream, badan intelijen, dan lembaga peradilan, untuk membangun hubungan langsung dan emosional dengan basis pendukungnya. Kemenangan Trump pada tahun 2016 didorong oleh mobilisasi dari gerakan anti-kemapanan, seperti Tea Party, yang memberikan basis akar rumput yang mendukung narasi populisnya.
Nasionalisme Ekonomi dan Proteksionisme
Prinsip inti kebijakan luar negeri Trump adalah America First, yang menekankan kedaulatan nasional, nasionalisme ekonomi, dan secara eksplisit menganjurkan pengurangan komitmen global. Populisme gaya AS berfokus pada melindungi kepentingan Amerika di atas segalanya, menghindari perang yang mahal, dan mengurangi bantuan asing.
Secara ekonomi, Trump menerapkan tarif tinggi kepada produk impor dari mitra dagang utama seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa, dengan tujuan untuk melindungi industri domestik dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. Kebijakan proteksionis ini memicu perang dagang dan menciptakan ketidakpastian ekonomi global, yang menyebabkan investor menahan investasi karena khawatir akan kerugian.
Meskipun retorika Trump sangat agresif dan personalistik yang mengancam kohesi sosial, serangannya terhadap institusi cenderung bersifat eksternal (mencerca) dibandingkan sistematis (mengubah struktur). Institusi demokrasi AS yang mapan menunjukkan tingkat daya tahan (resiliensi) yang signifikan untuk bertahan dari serangan retoris yang intensif, yang mencerminkan batas-batas populisme personalistik dalam sistem yang memiliki lembaga-lembaga yang terlembaga kuat.
Tantangan terhadap Multilateralisme
Skeptisisme terhadap aliansi global adalah ciri khas populisme America First. Kebijakannya mempertanyakan aliansi tradisional, seperti menuntut pembayaran dari negara anggota NATO, dan menganjurkan bilateralisme daripada kerangka kerja internasional. Kebijakan ini menempatkan kepentingan AS di atas tatanan liberal internasional. Namun, prioritas ini secara paradoks mempersulit posisi AS sebagai pemimpin global, mendorong negara-negara sekutu untuk mencari strategi adaptif baru dan membuka ruang kosong yang berpotensi diisi oleh kekuatan global lainnya.
Studi Kasus II: Gerakan Illiberal di Eropa Timur (Model Institusional-Sistematis)
Di Eropa Tengah dan Timur (ETT), populisme mengambil bentuk yang lebih institusional dan sistematis, sering disebut sebagai tata kelola illiberal atau “demokrasi illiberal,” yang secara eksplisit dianut oleh pemimpin seperti Viktor Orbán di Hungaria.
Konsolidasi Kekuasaan dan Demokrasi Illiberal
Kebangkitan partai seperti Fidesz di Hungaria (sejak 2010) dan Law and Justice (PiS) di Polandia (sejak 2015) menandai pelemahan konsensus liberal pasca-Perang Dingin. Kedua partai ini secara sistematis mengikis checks and balances, yang tercermin dalam penurunan skor demokrasi negara-negara tersebut. Hungaria bahkan mencatatkan peringkat terendah sebagai rezim otoriter terkonsolidasi di Eropa Tengah dalam beberapa survei.
Strategi mereka adalah perubahan konstitusional yang terencana. Fidesz, yang memegang mayoritas dua pertiga, memanfaatkan posisi ini untuk merevisi undang-undang dasar, memungkinkan mereka memperkuat kekuasaan eksekutif dan mengamankan kontrol terhadap pengadilan dan lembaga independen lainnya.
Strategi Erosi Kelembagaan: Yudikatif dan Media
Model populisme ETT sangat bersifat proaktif dan sistematis. Tujuannya adalah melembagakan kekuasaan mayoritas secara permanen melalui kolonisasi institusi netral. Hal ini menandai pergeseran dari sekadar mengkritik elit menjadi menjadi elit baru yang menggunakan mekanisme negara untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan mereka.
Pengendalian Yudikatif (Judiciary Undermining)
Pelemahan independensi yudikatif adalah bahan utama dalam playbook otokrat modern seperti Orbán. Pengkolonisasian lembaga peninjauan yudisial memfasilitasi tindakan “membengkokkan dan melanggar hukum” karena langkah-langkah illiberal yang diambil oleh eksekutif dapat dilegitimasi secara konstitusional. Ini termasuk intervensi dalam penunjukan hakim dan perombakan struktur pengadilan.
Penangkapan Media (Media Capture)
Pengendalian dan manipulasi media adalah unsur krusial lain. Di Hungaria, sebagian besar media swasta telah dibeli oleh afiliasi Partai Fidesz, memberikan pemerintah kemampuan untuk mengarahkan debat publik dan secara signifikan membatasi kebebasan pers. Di Polandia, PiS mengambil alih media publik segera setelah berkuasa pada tahun 2015. Pemerintah populis ETT juga mengancam media independen dengan regulasi atau pajak pendapatan iklan, serta mengkriminalisasi “informasi palsu,” yang bertujuan mendorong self-censorship di kalangan jurnalis yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan populis ini dicirikan oleh reformasi heterodox, mengesampingkan veto-players, dan menggunakan bahasa Manichean yang emosional, seringkali dengan bingkai krisis. Hal ini memungkinkan pembenaran konsolidasi kekuasaan eksekutif: setiap kegagalan kebijakan dapat dituduhkan pada “musuh” (elit lama, Uni Eropa, atau migran), daripada menuntut akuntabilitas teknokratis.
Analisis Komparatif: Divergensi Model Populisme AS dan Eropa Timur
Perbedaan utama dalam manifestasi populisme antara AS dan ETT terletak pada tingkat konsolidasi demokrasi dan strategi yang digunakan untuk berinteraksi dengan institusi negara.
Perbandingan ini menggarisbawahi bagaimana faktor kelembagaan menentukan sifat dan dampak dari gerakan populis:
Perbedaan Populisme: AS vs. Eropa Timur
| Dimensi Kunci | Model AS (Donald Trump) | Model Eropa Timur (Orbán/PiS) |
| Sifat Populisme | Personalistik, berbasis personality, dan anti-kemapanan. Retorika konfrontatif. | Institusional/Partai, berbasis nativisme, bertujuan mengubah struktur negara. Sistematis. |
| Strategi terhadap Institusi | Mencerca, mengabaikan, meremehkan norma, dan menantang legitimasi (misalnya, FBI, Justice Dept.). | Mengambil alih (capture), merevisi konstitusi (mayoritas dua pertiga), dan mengisi jabatan yudikatif/regulasi dengan loyalitas partai. |
| Strategi Media | Mencap media arus utama sebagai ‘musuh rakyat’ (fake news). Memanfaatkan media sosial untuk akses tanpa mediasi. | Penangkapan media publik (media capture), akuisisi media swasta oleh oligarki sekutu, dan ancaman regulasi/pajak. |
| Fokus Utama Kebijakan | Nasionalisme Ekonomi (Proteksionisme, Tarif Tinggi) dan Isolasionisme/Retraint Militer. | Nativisme Kultural, Pertahanan Identitas Etnis/Agama, dan Pengendalian Migrasi. |
Perbedaan fundamental ini didasarkan pada kekuatan kelembagaan yang mendasarinya. Sistem AS, dengan lembaga-lembaga yang mapan dan berumur panjang, menunjukkan resiliensi (institusi menahan serangan retoris). Sebaliknya, Eropa Timur, yang memiliki lembaga pasca-komunis yang relatif lebih rapuh dan kendala eksekutif yang lebih lemah, menunjukkan vulnerabilitas tinggi terhadap penangkapan sistematis kekuasaan oleh partai populis. Populisme bertindak sebagai kekuatan yang mengungkap kelemahan struktural yang laten dalam sistem politik.
Lebih lanjut, meskipun nativisme adalah pendorong di kedua kawasan, fokusnya berbeda. Di AS, nativisme Trump terkait erat dengan nasionalisme ekonomi dan perlindungan pekerja domestik. Di Eropa Timur, nativisme lebih mengedepankan isu perlindungan identitas etnis dan agama (seringkali Kristianitas) serta penolakan imigran atas dasar moral dan budaya.
Implikasi Sistemik dan Tantangan Global
Kebangkitan populisme memiliki implikasi sistemik yang melampaui politik domestik, menantang tatanan liberal internasional yang berlaku.
Ancaman terhadap Tata Kelola Global
Populisme global, melalui seruan isolasionisme, proteksionisme, dan bilateralisme, merupakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap organ tata kelola global dan perjanjian multilateral yang telah dibangun sejak Perang Dunia II. Sentimen anti-globalisasi yang diusung oleh para populis secara aktif menyalahkan aktor-aktor internasional atas pelemahan kedaulatan negara dan rusaknya demokrasi . Hal ini menyebabkan fragmentasi dan kesulitan dalam kerja sama internasional yang efektif .
Erosi Supremasi Hukum dan Hak Minoritas
Pemerintahan populis secara konsisten cenderung mengikis prinsip-prinsip supremasi hukum. Dalam upaya mengklaim mewakili “kehendak mayoritas,” populisme sering menempatkan suara mayoritas di atas perlindungan hak individu dan minoritas, yang pada akhirnya memperlemah integritas sistem hukum. Konsolidasi kekuasaan eksekutif, terutama di Eropa Timur, dan kebijakan yang mengesampingkan veto-players telah mengurangi pluralisme yang muncul pasca-Perang Dingin.
Fenomena populisme seringkali menciptakan lingkaran umpan balik negatif yang mengarah pada otoritarianisme. Ketidakpuasan publik memicu pemilihan pemimpin populis. Pemimpin ini kemudian menerapkan kebijakan yang secara sistematis merusak institusi, menghilangkan mekanisme akuntabilitas. Meskipun kerusakan kelembagaan ini memperburuk masalah sosial dan ekonomi, kritik diredam karena media berada di bawah kendali. Mekanisme ini Menghasilkan kemunduran demokrasi yang terkunci (locked-in democratic backsliding), sebagaimana dibuktikan oleh penurunan peringkat demokrasi Hungaria.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa populisme kontemporer jarang menggunakan metode otoriter keras. Sebaliknya, mereka menggunakan mekanisme demokrasi—pemilu dan undang-undang yang sah secara prosedur—untuk mencapai tujuan anti-liberal mereka. Model illiberal di Eropa Timur menunjukkan bagaimana disrupsi tata kelola kini terjadi melalui cara-cara yang sah tetapi substansial tidak liberal, menjadikannya tantangan yang lebih sulit bagi komunitas internasional. Populisme di pemerintahan dapat mengikis kendala kelembagaan terhadap kekuasaan eksekutif, bahkan di negara demokrasi maju
Kesimpulan
Populisme global adalah reaksi kompleks dan multifaset yang didorong oleh kesenjangan yang diciptakan oleh globalisasi dan polarisasi yang diperburuk oleh teknologi digital. Analisis komparatif menunjukkan adanya dua jalur utama populisme: model personalistik-retoris yang didominasi oleh figur karismatik (seperti Donald Trump di AS) yang menantang institusi secara verbal; dan model institusional-sistematis yang terlihat di Eropa Timur (Fidesz/PiS), yang secara proaktif dan sistematis mengambil alih dan mengubah institusi negara untuk mengamankan kekuasaan abadi.
Model ETT, dengan fokusnya pada media capture dan kolonisasi yudikatif, menimbulkan risiko kemunduran demokrasi yang lebih struktural dan terkunci (locked-in) dibandingkan dengan model AS yang lebih bergantung pada retorika dan personality.
Prospek masa depan menunjukkan bahwa risiko fragmentasi global akan terus meningkat selama narasi populis yang didasarkan pada dikotomi antagonistik tetap dominan. Hal ini menuntut strategi adaptif dalam tata kelola global untuk memastikan pelestarian nilai-nilai demokrasi dan kolaborasi internasional yang efektif. Penguatan kerangka kelembagaan, supremasi hukum yang independen, dan media yang pluralis, harus menjadi benteng pertahanan utama melawan upaya capture sistematis yang dilakukan oleh populisme illiberal.