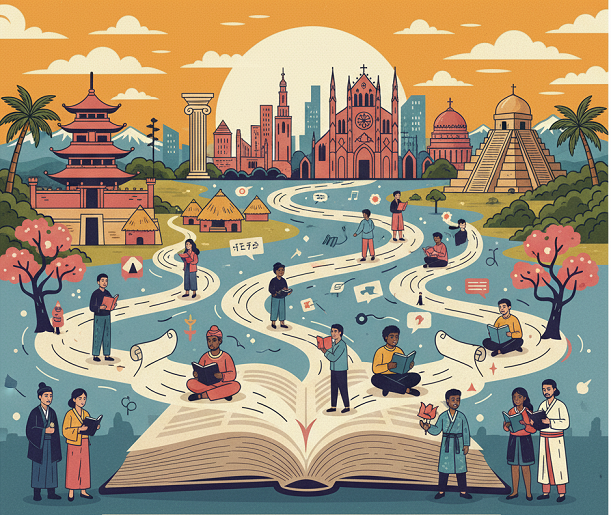Sastra Bandingan sebagai Disiplin Lintas Budaya
Kajian sastra bandingan (Comparative Literature) secara tradisional didefinisikan sebagai studi terhadap dua atau lebih karya sastra dalam perbandingan, melampaui batas-batas literatur nasional. Namun, dalam praktik akademis kontemporer, disiplin ini telah berkembang menjadi sebuah metodologi yang jauh lebih eksperimental, lintas budaya, dan kritis terhadap produksi pengetahuan itu sendiri. Sastra bandingan berfungsi sebagai alat diagnostik untuk menganalisis bagaimana trauma sejarah, struktur sosial, dan faktor filosofis membentuk interpretasi tema-tema yang bersifat universal.
Metodologi interdisipliner dalam sastra bandingan mengharuskan analisis komponen multidimensi, yang mencakup faktor historis, gender, ekonomi, kultural, sosial, filosofis, agama, dan linguistik dari budaya yang dianalisis. Laporan ini berpegangan pada model kajian yang mengintegrasikan sastra bandingan dengan representasi budaya , memungkinkan perbandingan mendalam yang melibatkan studi antardisiplin ilmu—yaitu perbandingan karya sastra dengan bidang-bidang non-sastra seperti politik, filsafat, dan agama—untuk memperjelas informasi sastra dan implikasi sosialnya. Pendekatan ini sangat relevan dalam menganalisis wacana global modern, yang diwarnai oleh dekonstruksi sastra dunia dan pertemuan antara narasi Barat dan Timur.
Dengan menggunakan kerangka kerja interdisipliner ini, perbandingan antara karya Gabriel Garcia Marquez dari Kolombia (mewakili Amerika Latin) dan Haruki Murakami dari Jepang (mewakili Asia Timur) menjadi lebih dari sekadar perbandingan plot; ini adalah analisis komparatif bagaimana dua proyek modernitas yang berbeda—yang satu dibebani oleh warisan kolonial dan politik yang siklus, yang lain dibingungkan oleh modernisasi pasca-perang yang dipaksakan—menafsirkan kondisi eksistensial manusia melalui lensa budaya masing-masing.
Definisi Kerja Tema “Kesendirian” (Solitude dan Loneliness) dalam Sastra
Untuk menghindari ambiguitas dalam analisis lintas budaya, penting untuk membedakan secara tegas antara solitude (kesendirian yang memberdayakan atau terpilih) dan loneliness (kesepian yang menyakitkan atau alienasi).
Solitude didefinisikan sebagai kualitas atau keadaan terpencil atau jauh dari masyarakat. Ketika dihadapi dengan kesadaran dan penerimaan, solitude dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan pribadi, kreativitas, dan pemahaman diri yang lebih dalam. Dalam sastra, periode menyepi ini sering diinterpretasikan sebagai kegiatan introspeksi diri.
Sebaliknya, loneliness adalah kondisi psikologis negatif yang timbul dari perasaan kekurangan koneksi sosial. Meskipun pengalaman loneliness bersifat universal, sastra berfungsi untuk menerjemahkan rasa sepi tersebut, menenangkan hati pembaca bahwa ia adalah rasa yang tak terhindarkan. Inti perbedaan antara dua kondisi ini terletak pada pilihan dan kualitas kehadiran diri yang ditumbuhkan: solitude adalah keadaan internal yang restoratif, sementara loneliness adalah kekurangan eksternal yang menyakitkan.
Bagian selanjutnya akan menunjukkan bahwa nilai budaya (apakah budaya itu kolektivistik atau individualistik) sangat menentukan apakah waktu sendirian dibingkai sebagai kesempatan untuk pertumbuhan (seperti dalam tradisi kontemplatif Timur) atau sebagai kekurangan sosial (seperti dalam ideal ekstrovert Barat).
Batasan dan Rerangka Komparasi
Laporan ini membatasi perbandingannya pada Gabriel Garcia Marquez, terutama melalui karyanya One Hundred Years of Solitude (Seratus Tahun Kesunyian), yang merupakan mahakarya Realisme Magis Amerika Latin , dan Haruki Murakami, melalui karya-karya utamanya seperti The Wind-Up Bird Chronicle dan Norwegian Wood, yang mewakili Surealisme Postmodern Jepang. Perbandingan ini menggunakan Realisme Magis Marquez dan Surealisme Murakami sebagai teknik non-realistis yang secara fundamental berbeda dalam fungsi kultural dan politik mereka dalam menafsirkan tema kesendirian.
Konstruksi Filosofis Kesendirian Lintas Budaya
Kajian tentang kesendirian memerlukan pemahaman mendalam tentang akar filosofis kulturalnya. Perbedaan antara latar belakang Amerika Latin (yang dipengaruhi oleh Katolisisme dan sejarah politik) dan Jepang (yang dipengaruhi oleh tradisi Zen/Taoisme dan modernitas pasca-perang) menghasilkan polaritas dalam interpretasi tema universal ini.
Solitude dalam Model Barat: Individualisme dan Kapitalisme
Dalam masyarakat yang sangat individualistik—seperti yang dominan di Barat—terdapat preferensi kultural yang kuat terhadap ekstroversi, di mana menjadi terbuka, ramah, dan terus terhubung dianggap ideal. Dalam kerangka ini, di mana pencapaian individu dan keterlibatan sosial diprioritaskan, solitude atau memilih untuk menyendiri dapat disalahpahami sebagai loneliness atau sebagai tanda kegagalan sosial.
Konflasi antara solitude dan loneliness ini menimbulkan kecurigaan bahwa tindakan memilih untuk menyendiri adalah gejala ketidakbahagiaan. Fenomena ini dapat ditelusuri ke pengaruh sosiologis kapitalisme konsumen. Keengganan modern Barat terhadap kesendirian secara fundamental terkait dengan sistem ekonomi yang menuntut populasi yang terus-menerus merasa tidak puas dan mencari pemenuhan melalui akuisisi. Seseorang yang merasa puas dalam kesendiriannya akan kurang rentan terhadap tekanan pemasaran dan budaya konsumen. Dengan demikian, narasi kultural yang menyamakan kesendirian dengan kesepian menjadi komponen yang diperlukan untuk mempertahankan ekonomi berbasis konsumsi.
Solitude dalam Model Timur: Kontemplasi dan Interkoneksi
Sebaliknya, tradisi kontemplatif Timur, seperti Buddhisme, Zen, dan Taoisme, melihat solitude bukan sekadar ketiadaan orang lain, melainkan sebagai kehadiran yang mendalam terhadap diri dan alam semesta.
Dalam filsafat ini, solitude adalah praktik vital yang dipandang sebagai alat untuk transformasi dan pertumbuhan spiritual. Tradisi Zen dan Taoisme secara historis menghargai retret soliter sebagai esensial untuk perkembangan spiritual dan wawasan. Tujuannya adalah untuk mengamati kerja pikiran, menumbuhkan kesadaran (mindfulness), dan mencapai pemahaman diri yang lebih dalam, terlepas dari keadaan eksternal.
Model Timur ini menopang pandangan non-dualistik: solitude bukanlah upaya untuk memisahkan diri dari dunia, melainkan metode untuk menyadari keterhubungan segala sesuatu (interconnectedness). Melalui isolasi terpilih, seseorang dapat melarutkan ilusi diri yang terpisah untuk mencapai rasa koneksi yang lebih mendalam dengan keberadaan secara keseluruhan. Jadi, meskipun masyarakat Jepang pasca-perang bergumul dengan alienasi postmodern, kerangka filosofis tradisional ini menyediakan jalan bagi karakter Murakami untuk mencari kejelasan batin melalui isolasi yang disengaja. Karakter-karakter ini sering kali mengalami kegagalan modernitas (menciptakan loneliness), tetapi metode penanganan mereka (introspeksi yang terisolasi, seperti turun ke sumur) mencerminkan praktik solitude Timur. Hal ini menciptakan ambivalensi tematik yang menjadi ciri khas karya Murakami.
Representasi Solitude dalam Sastra Amerika Latin: Kasus Gabriel Garcia Marquez
Dalam karya Gabriel Garcia Marquez, terutama One Hundred Years of Solitude (Cien Años de Soledad), kesendirian adalah tema yang memiliki resonansi makro, berfungsi sebagai kritik sosial dan politik terhadap kondisi kontinental Amerika Latin.
Konteks Sosio-Politik: Solitude sebagai Beban Sejarah
Kesendirian bagi Marquez bukanlah hanya kondisi pribadi, melainkan kondisi kolektif—sebuah kutukan yang ditimpakan oleh sejarah. Marquez sendiri menegaskan hal ini dalam pidato Nobelnya, yang secara eksplisit merujuk pada “The Solitude of Latin America”. Pandangan ini mencerminkan situasi tragis benua yang belum terbebas dari beban dominasi sejarah dan kekerasan.
Novel Seratus Tahun Kesunyian menyajikan Macondo, sebuah kota fiktif yang sejarahnya mereplikasi sejarah politik Amerika Latin dalam skala yang lebih kecil. Macondo didirikan di hutan terpencil , tetapi harmoni awal mereka terganggu oleh kedatangan representasi pemerintahan luar, seperti Don Apolinar Moscote. Gangguan ini membawa kekacauan, perang antara kaum liberal dan konservatif, dan akhirnya intervensi eksternal (seperti pembantaian pekerja perkebunan pisang). Meskipun perang berakhir, kesendirian keluarga Buendía tidak pernah berakhir. Kesendirian di sini adalah konsekuensi fatalistik dari ketidakmampuan benua untuk melepaskan diri dari siklus kekerasan dan kesalahan politik masa lalu.
Realisme Magis: Eksternalisasi Trauma Politik
Marquez memelopori Realisme Magis (MR) sebagai teknik sastra untuk menarasikan realitas Amerika Latin yang seringkali terlalu absurd atau tragis untuk diceritakan secara konvensional. MR memadukan elemen fantastis—seperti mayat yang sangat tampan atau orang tua bersayap —ke dalam latar yang realistis.
Fungsi utama MR dalam konteks ini adalah sebagai alat kritik sosial implisit terhadap politik dan elit. Dengan menjadikan hal yang luar biasa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, MR menantang persepsi konvensional tentang realitas, mengundang pembaca untuk merenungkan bagaimana mitos membentuk identitas budaya sambil sekaligus mendiagnosis penyakit sosial dan politik. Magis adalah perpanjangan dari sejarah yang absurd, sebuah eksternalisasi dari trauma kolektif yang dialami benua tersebut. Solitude keluarga Buendía adalah bukti bahwa kegagalan untuk mengatasi trauma sejarah dan politik ini tidak hanya merusak individu tetapi juga mengutuk seluruh keturunan mereka pada takdir yang berulang.
Solitude Dinasti Buendía: Warisan Genetik dan Fatalisme
Di tingkat tekstual, kesendirian adalah takdir keluarga yang diwariskan, diperkuat oleh siklus tak terhindarkan. Kesendirian adalah tema yang paling dominan dalam novel tersebut. Karakter pria Buendía—khususnya José Arcadio Buendía, sang pendiri, dan Kolonel Aureliano Buendía—secara khusus mewujudkan mitos kesendirian. Kolonel Aureliano, yang memiliki 17 putra dan lolos dari puluhan upaya pembunuhan, meninggal dalam kesendirian yang menyedihkan di samping pohon tempat ayahnya meninggal bertahun-tahun sebelumnya, menandai siklus yang tidak terputus.
Struktur naratif novel bersifat non-linier, mencerminkan sifat siklus waktu dan sejarah. Karakter-karakter Buendía mengulangi kesalahan dan beban leluhur mereka dari generasi ke generasi. Solitude dalam Marquez bersifat sanksi atau hukuman. Ini adalah kegagalan untuk mencapai cinta, kebahagiaan, atau pengetahuan yang berkelanjutan, yang semuanya selalu berakhir dengan isolasi.
Melalui analisis ini, terlihat bahwa kesendirian Marquez adalah produk dari fatalisme sejarah. Karakter-karakternya tidak dapat melepaskan diri dari pengulangan kesalahan leluhur mereka karena sejarah (siklus politik dan kolonial) menjebak mereka di Macondo. Solitude melampaui pengalaman pribadi, mewakili identitas budaya kolektif dan kritik terhadap masalah sosial-politik Amerika Latin. Satu-satunya pembebasan dari kesendirian ini disarankan oleh Marquez adalah melalui akhir apokaliptik dari garis keturunan dan kota itu sendiri, yang menyiratkan bahwa pembebasan sejati membutuhkan jeda total dari kerangka sejarah yang diwariskan.
Representasi Solitude dalam Sastra Jepang Kontemporer: Kasus Haruki Murakami
Haruki Murakami menggambarkan kesendirian sebagai kondisi yang inheren dalam masyarakat urban modern. Berbeda dengan Marquez yang menekankan dimensi sejarah dan politik, Murakami memfokuskan pada dimensi psikologis dan eksistensial, yang berakar pada trauma sosial Jepang pasca-perang.
Konteks Sosio-Historis: Krisis Identitas Pasca-Perang
Latar belakang sastra Murakami adalah Jepang pasca-Perang Dunia II, periode yang ditandai oleh modernisasi agresif dan kehancuran cita-cita tradisional. Sastra pasca-perang Jepang bergumul dengan trauma psikologis, perasaan bersalah penyintas, dan pencarian makna di tengah hilangnya nilai-nilai tradisional.
Setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang menghadapi hegemoni budaya Amerika yang meluas, menciptakan ambivalensi budaya di kalangan generasi muda. Karakter seperti Toru Watanabe dalam Norwegian Wood bingung tentang budaya tradisional Jepang mereka dan dipengaruhi oleh budaya Barat. Meskipun terdapat dorongan untuk memupuk individualisme dan liberalisme pasca-perang, yang merupakan fondasi institusi Barat , dorongan ini sering kali gagal dan justru diterjemahkan menjadi alienasi dan kurangnya identitas diri (self-identity) di dalam masyarakat postmodern.
Solitude: Alienasi Eksistensial dan Ruang Bawah Sadar
Murakami menggambarkan kesendirian sebagai melodi melankolis. Karakter-karakternya adalah orang-orang yang terisolasi secara emosional meskipun dikelilingi oleh hiruk pikuk kota. Mereka menjadi “pria tanpa wanita,” “pulau bagi diri mereka sendiri,” menghadapi bayangan kesendirian mereka dengan nostalgia yang pedih.
Kesendirian bagi protagonis Murakami, yang seringkali pasif atau hanya menjadi penonton dalam kehidupan mereka sendiri , adalah hasil dari penarikan psikologis postmodern akibat kekacauan modernitas. Solitude adalah perjalanan soliter yang diperlukan untuk menemukan jati diri yang hilang (sense of self). Misalnya, pencarian Toru Okada terhadap kucing dan istrinya yang hilang dalam The Wind-Up Bird Chronicle adalah metafora untuk pencarian makna diri yang telah hilang selama bertahun-tahun.
Metafora ruang bawah sadar sangat penting dalam karyanya. Penggambaran sumur, yang seharusnya menjadi sumber kehidupan dalam budaya Jepang, justru merujuk pada alienasi, kematian yang diromantisasi, dan pencarian di alam bawah sadar. Sumur berfungsi sebagai simbol keterasingan dan ruang terisolasi untuk introspeksi mendalam. Ini menjadikan solitude Murakami sebagai tindakan yang fundamental bersifat introspektif, berbeda dengan solitude Marquez yang bersifat historis.
Implikasi Sosio-Religius
Alienasi yang digambarkan Murakami bukan hanya urusan pribadi, melainkan kritik terhadap kegagalan masyarakat Jepang modern untuk menyediakan koneksi yang bermakna.
Rasa isolasi dan alienasi yang mendalam, terutama di kalangan elit dan terdidik, mendorong mereka untuk mencari komitmen sosial dan makna yang hilang, bahkan melalui organisasi keagamaan yang radikal. Contohnya adalah para pelaku serangan gas Sarin di kereta bawah tanah Tokyo, yang merupakan orang-orang berpendidikan tinggi yang mencari makna dalam organisasi seperti Aum Shinrikyo. Murakami mengambil sudut pandang yang berbeda, mewawancarai para pengikut Aum, untuk memahami suara mereka yang teralienasi dari arus utama masyarakat.
Kesendirian di sini sejajar dengan filsafat eksistensialisme (absurdisme Camus), di mana individu harus menghadapi absurditas kehidupan sendirian. Dalam konteks Murakami, ini adalah upaya untuk merebut kembali agensi pribadi—mencari kedamaian batin dan kesadaran diri melalui refleksi yang terisolasi (seperti Zen) di tengah krisis identitas yang disebabkan oleh modernitas yang kacau.
Analisis Komparatif: Vektor Kultural dan Fungsi Realisme
Perbandingan antara Marquez dan Murakami mengungkapkan bahwa meskipun keduanya mengeksplorasi kondisi terasing yang sama-sama universal, akar penyebab dan fungsi naratif dari kesendirian tersebut sangatlah berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik, dan filosofis mereka.
Perbedaan Fungsi Non-Realisme
Kedua penulis terkenal karena penggunaan elemen non-realistis dalam karya mereka, namun, tujuan sastra dari teknik tersebut sangat kontras.
- Realisme Magis (Marquez): Realisme Magis pada dasarnya adalah alat untuk mengenali realitas politik dan sejarah yang terlalu mengerikan untuk diungkapkan secara langsung. Elemen magis adalah perpanjangan dari sejarah yang absurd dan kolektif yang dialami Amerika Latin. Fungsinya adalah eksternalisasi trauma, sebuah cara untuk mendiagnosis penyakit politik dan sosial suatu benua, di mana solitude adalah konsekuensi politik dari kegagalan kolektif.
- Surealisme/Postmodernisme (Murakami): Surealisme Murakami adalah alat untuk menggali realitas psikologis. Fantasi, absurdisme, dan elemen dunia bawah tanah berfungsi sebagai metafora untuk keadaan psikologis individu, mewakili trauma yang terinternalisasi, krisis identitas, dan alam bawah sadar yang terfragmentasi. Solitude adalah ruang operasi mental tempat protagonis berusaha menyembuhkan dirinya sendiri dari fragmentasi modernitas.
Pengaruh Latar Belakang terhadap Interpretasi Tema
Perbedaan fungsi ini berakar pada vektor kultural yang sangat berbeda:
Politik dan Sejarah:
Bagi Marquez, solitude bersifat sanksi/hukuman. Itu adalah kutukan yang datang dari trauma politik masa lalu—perang sipil, intervensi asing, dan kediktatoran—yang menjebak individu dalam siklus sejarah. Solitude menuntut pertanggungjawaban kolektif atas penderitaan bersama.
Bagi Murakami, solitude bersifat reaksioner. Itu adalah pelarian dari kekosongan spiritual dan tekanan sosial dalam masyarakat urban pasca-industrial dan pasca-trauma. Ini memfasilitasi penanggulangan pribadi dan ketahanan psikologis di lingkungan di mana politik kolektif terasa tidak berarti atau berbahaya.
Waktu dan Siklus:
Karakter Buendía Marquez terjebak dalam waktu siklus, di mana takdir leluhur terus berulang. Solitude adalah konsekuensi dari waktu yang stagnan, hukuman historis.
Sebaliknya, karakter Murakami hidup dalam waktu linier yang kacau dan terfragmentasi (postmodern). Solitude adalah usaha untuk menghentikan fragmentasi waktu, mencari momen keabadian atau makna di tengah dislokasi dari masa lalu tradisional.
Dampak Gender dan Hubungan:
Dalam Marquez, solitude sering kali dipersonifikasikan oleh kegagalan pria patriarkal (Kolonel Buendía) yang tidak mampu menjalin hubungan cinta sejati karena obsesi mereka pada perang atau ilmu pengetahuan, yang memperkuat kutukan keluarga.
Dalam Murakami, solitude sering dipicu oleh hilangnya atau kesulitan koneksi dengan figur wanita. Hal ini menyoroti kegagalan hubungan intim dalam masyarakat modern yang membuat pria-pria pasif menjadi ‘pulau’.
Tabel Sintesis Komparatif Kultural
Tabel berikut menyajikan pemetaan yang jelas mengenai perbedaan kunci dalam interpretasi tema “Kesendirian” oleh kedua penulis, berdasarkan latar belakang kultural dan fungsi sastra mereka.
Perbandingan Vektor Kultural dalam Representasi Solitude
| Dimensi Komparatif | Gabriel Garcia Marquez (Amerika Latin) | Haruki Murakami (Jepang Kontemporer) |
| Konteks Sosio-Politik Utama | Trauma sejarah, siklus kekerasan, kolonialisme, dan kegagalan politik kontinental | Krisis identitas pasca-Perang Dunia II, modernisasi agresif, ambivalensi budaya Barat dan keruntuhan nilai tradisional |
| Interpretasi Solitude (Tema) | Kutukan kolektif, warisan yang diulang, dan ketidakmampuan untuk menciptakan sejarah non-destruktif. | Alienasi eksistensial, isolasi urban, dan pencarian jati diri yang hilang. |
| Realisme Sastra | Realisme Magis: Eksternalisasi trauma kolektif, berakar pada mitos dan sejarah, kritik politik. | Surealisme/Postmodernisme: Internalisasi trauma, berfungsi sebagai metafora psikologis untuk alam bawah sadar. |
| Fungsi Solitude | Diagnosis terhadap kondisi politik makro. Solitude adalah hukuman kolektif. | Refleksi introspektif terhadap kondisi psikologis mikro. Solitude adalah pencarian pribadi yang ambigu. |
| Konsep Waktu | Siklus (Sejarah berulang, fatalistik) | Linier/Fragmentaris (Dislokasi dari masa lalu tradisional, fokus pada kekosongan masa kini) |
| Akar Filosofis/Keagamaan | Tradisi Katolik yang berpadu dengan fatalisme/mitos lokal, menekankan takdir. | Pengaruh Eksistensialisme Barat dan tradisi kontemplatif Timur (Zen), menekankan introspeksi diri yang terasing. |
Kesimpulan dan Implikasi Sastra Dunia
Sintesis Temuan Utama
Kajian komparatif lintas budaya terhadap tema kesendirian dalam karya Gabriel Garcia Marquez dan Haruki Murakami mengungkapkan divergensi yang mendalam dalam pemaknaan dan fungsi sastra. Meskipun keduanya menggunakan elemen non-realistis untuk mengekspresikan trauma, tujuan dan dampak kulturalnya sangat berbeda. Bagi Marquez, kesendirian adalah sebuah kutukan kolektif yang didorong oleh sejarah politik yang fatalistik; itu adalah kegagalan benua untuk mematahkan siklus dominasi dan kekerasan. Realisme Magis digunakan untuk memproyeksikan beban sejarah ini ke dunia luar, menuntut pengakuan dan pertanggungjawaban politik.
Sebaliknya, bagi Murakami, kesendirian adalah kondisi eksistensial yang didorong oleh krisis identitas pasca-perang dan fragmentasi modernitas urban. Ini adalah kegagalan untuk menciptakan identitas yang koheren. Surealisme digunakan untuk memfasilitasi perjalanan batin yang sepi—sebuah upaya psikologis untuk menemukan makna dan ketenangan (inner peace), sering kali dengan mengacu pada tradisi kontemplatif Zen, yang bertentangan dengan kekacauan eksternal.
Oleh karena itu, kesendirian dalam Marquez adalah hukuman kolektif yang tidak dapat dihindari, sedangkan dalam Murakami, kesendirian adalah kebutuhan pribadi yang ambigu—satu-satunya tempat yang tersisa untuk introspeksi diri.
Kontribusi Perbandingan Lintas Budaya
Perbandingan ini menegaskan nilai Sastra Bandingan sebagai disiplin ilmu. Dengan menganalisis narasi Amerika Latin dan Jepang secara bersamaan, laporan ini menunjukkan bagaimana Global South (Amerika Latin) dan Global East (Jepang), masing-masing dengan jalur modernitas mereka yang unik, merespons trauma sejarah dan struktural. Marquez dan Murakami, meskipun hidup di benua yang berbeda, sama-sama mendistorsi mekanisme naratif Barat—seperti realisme dan individualisme—untuk menceritakan kondisi kultural mereka sendiri.
Analisis komparatif ini memperkaya pemahaman tema universal dengan menelusuri konteks kultural yang mendasarinya. Dengan memetakan bagaimana latar belakang politik (siklus Macondo), sosial (hegemoni pasca-perang Jepang), dan agama (fatalisme Katolik versus introspeksi Zen) membentuk interpretasi penulis terhadap kesendirian, laporan ini memberikan kerangka kerja yang solid untuk memahami bahwa pengalaman manusia yang paling pribadi sekalipun (seperti kesendirian) sangat terpengaruh oleh kekuatan geopolitik dan struktural yang lebih besar.