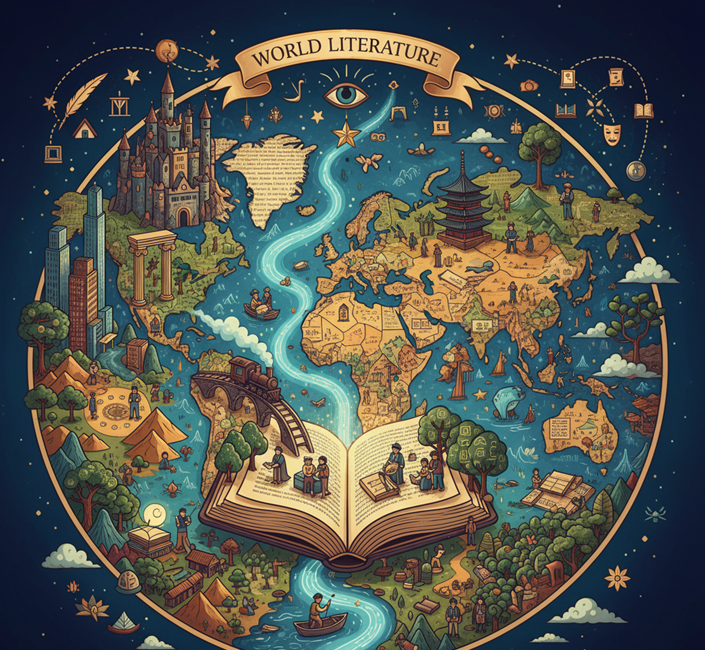Latar Belakang dan Relevansi Sastra Dunia di Abad Ke-21
Di tengah ketidakpastian global yang ditandai oleh berbagai tantangan kontemporer, seperti pandemi, konflik internasional, krisis iklim, dan migrasi massal, terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali cara manusia memahami sejarah, bahasa, dan sastra melalui perspektif yang melampaui batas-batas budaya tunggal. Narasi sejarah global cenderung terpusat pada sudut pandang dominan, yang sering kali mengabaikan pengalaman dan kontribusi penting dari budaya non-Barat. Demikian pula, penggunaan bahasa dan perkembangan sastra secara tradisional kerap kali memperkuat hierarki budaya tertentu, sehingga membatasi keberagaman representasi pengalaman manusia.
Sastra Dunia (World Literature) muncul sebagai medium vital untuk dialog antarbudaya. Fungsinya melampaui sekadar apresiasi estetika; sastra memposisikan diri sebagai sarana untuk merekonstruksi narasi sejarah yang lebih adil dan membangun pemahaman silang budaya. Oleh karena itu, ulasan ini berfokus pada dua pertanyaan krusial dalam konteks pendidikan modern: pertama, sejauh mana kurikulum sastra di sekolah dan universitas telah mencakup secara memadai karya-karya non-Barat, dan kedua, mengapa pengajaran sastra global merupakan suatu urgensi pedagogis yang tidak dapat dihindari.
Evolusi Konsep Sastra Dunia: Dari Weltliteratur Goethe menuju Model Sirkulasi Damrosch
Konsep Sastra Dunia memiliki sejarah panjang. Johann Wolfgang Goethe, pada awal abad ke-19, menggunakan istilah Weltliteratur untuk mendeskripsikan sirkulasi dan resepsi karya sastra secara internasional di Eropa. Minat Goethe saat itu sudah meluas, mencakup karya-karya non-Barat seperti novel Tiongkok atau puisi Persia dan Serbia. Namun, seiring waktu, konsep ini, terutama di Amerika Utara dan banyak negara yang mengadopsi model akademik Barat, terdefinisi secara sempit sebagai kanon mapan yang terdiri dari mahakarya Eropa (Western European literature).
Definisi tradisional yang eurosentris ini kini menghadapi tantangan signifikan dari perspektif global yang muncul. Para sarjana kontemporer, seperti David Damrosch, menggeser paradigma Sastra Dunia dari sekadar daftar teks kanonis menuju sebuah mode sirkulasi dan pembacaan. Menurut Damrosch, sebuah karya memasuki ranah Sastra Dunia melalui proses ganda: pertama, dibaca sebagai sastra, dan kedua, bersirkulasi melampaui titik asal linguistik dan budayanya. Kunci dari paradigma ini adalah penekanan bahwa karya sastra global adalah karya yang “memperoleh nilai tambah dalam proses penerjemahan” (gains in translation), bergerak di ruang elips yang dibentuk antara budaya sumber dan budaya penerima.
Pergeseran ini secara fundamental mendemokratisasi kurikulum sastra. Jika Sastra Dunia didefinisikan oleh sirkulasi, maka teks dari geografi mana pun, asalkan berhasil diterjemahkan dan memicu dialog lintas batas, berhak diklaim sebagai Sastra Dunia. Hal ini memberikan justifikasi teoretis yang kuat untuk inklusi karya non-Barat, memaksa kurikulum berfokus pada dinamika resepsi dan konteks global ketimbang pada nilai intrinsik yang ditetapkan secara Eurosentris. Selain faktor sirkulasi teks, peran infrastruktur turut menentukan: Venkat Mani menyoroti bahwa proses “menduniakan” literatur difasilitasi oleh transfer informasi yang dihasilkan oleh penerbit, penjual buku yang terjangkau, dan peran penting perpustakaan publik dalam membuat karya-karya tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas.
Tabel 1: Pergeseran Paradigma Konsep Sastra Dunia (Weltliteratur hingga World Literature)
| Dimensi Konseptual | Era Awal (Goethe, Awal Abad ke-19) | Era Kontemporer (Damrosch, Abad ke-21) | Justifikasi Inklusi Non-Barat |
| Fokus Utama | Masterpiece Eropa Barat (Kanon) dan sirkulasi internasional karya Barat. | Karya yang bersirkulasi di luar batas budaya dan bahasa asalnya (mode sirkulasi). | Menuntut inklusi karya dari linguistik dan geografi minoritas. |
| Kriteria Karya | Kehebatan (Masterpiece); nilai estetika universal (seringkali berbasis Barat). | Sifatnya yang “berpindah” (gains in translation); proses pembacaan sebagai sastra di konteks baru. | Penekanan pada terjemahan, resepsi, dan adaptabilitas lintas budaya, bukan hanya nilai kanonis. |
| Nilai Inti Kurikuler | Dialog antar-bangsa Eropa; pencarian kemanusiaan universal yang berbasis Barat. | Dekolonisasi narasi; representasi keberagaman manusia; dialog lintas budaya. | Kurikulum harus proaktif mengatasi hierarki budaya dominan dan menciptakan narasi yang lebih adil. |
Analisis Kritis Kurikulum Sastra: Isu Representasi Non-Barat
Dominasi Narasi dan Kanon Barat dalam Kurikulum
Secara historis, kurikulum sastra di banyak institusi pendidikan global telah menjadi refleksi dari hegemoni budaya. Kurikulum ini sering kali didasarkan pada kanon Eropa, memperkuat hierarki budaya tertentu dan secara inheren membatasi keberagaman representasi pengalaman manusia. Fenomena ini terlihat jelas di mana narasi sejarah global sering berpusat pada sudut pandang dominan, yang secara efektif mengabaikan kontribusi dan pengalaman budaya non-Barat.
Perspektif global kontemporer secara eksplisit menantang kategori tradisional ini, termasuk fokus Eropa dan konsep “mahaputra” (masterpiece) itu sendiri. Dalam kerangka kritik pascakolonial, pentingnya Sastra Dunia terletak pada kemampuannya untuk menawarkan ruang bagi sejarah alternatif, bahasa minoritas, dan pandangan dunia yang telah lama dipinggirkan. Oleh karena itu, ketersediaan dan pengajaran karya non-Barat menjadi penentu apakah suatu kurikulum sastra mampu mengatasi warisan hegemoni budaya atau justru terus melestarikannya.
Evaluasi Representasi Karya Non-Barat di Kurikulum Pendidikan Sekolah dan Universitas
Tinjauan terhadap kurikulum sastra di Indonesia mengungkapkan bahwa integrasi karya sastra global—terutama yang non-Barat—menghadapi berbagai tantangan struktural dan praktis yang serius.
Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (sekolah), fokus kurikulum sering diarahkan pada Sastra Nasional (misalnya, dalam Kurikulum Merdeka). Meskipun penting untuk memperkenalkan dan menghargai warisan budaya bangsa , fokus ini seringkali kurang eksploratif terhadap karya-karya global di luar kanon wajib. Hambatan utama di tingkat sekolah terletak pada faktor praktis, termasuk instabilitas kurikulum yang berganti-ganti, yang menyebabkan kebingungan bagi guru dalam penerapan. Selain itu, sarana dan prasarana pengajaran sastra di sekolah masih sangat minim, termasuk ketersediaan buku yang memadai. Apabila akses terhadap buku sastra nasional yang memadai saja sulit, upaya untuk mengintegrasikan karya-karya dari Afrika, Amerika Latin, atau Timur Tengah yang berkualitas, yang memerlukan penerjemahan dan pengadaan materi pengajaran spesifik, menjadi tantangan logistik yang jauh lebih besar.
Pada tingkat pendidikan tinggi (universitas), meskipun terdapat kajian teoretis mendalam, seperti adopsi Teori Pascakolonial dalam kritik sastra , terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Keterbatasan akademisi dalam mengikuti dan mempelajari perkembangan kajian sastra dan teori-teori mutakhir secara maksimal menghambat implementasi kurikulum yang benar-benar inklusif dan dekolonial. Hal ini menciptakan kontradiksi: teori yang mendukung inklusi non-Barat dan dekolonisasi tersedia, tetapi kapasitas untuk mengimplementasikannya secara efektif dan kritis di ruang kelas sangat terbatas.
Analisis menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan untuk menciptakan ruang bagi sejarah alternatif dan Sastra Dunia sangat mendesak , kurangnya aksesibilitas teks non-Barat, infrastruktur yang minim, dan masalah kapasitas guru menjadi penghalang nyata. Kegagalan untuk mengatasi hambatan infrastruktur ini berarti bahwa upaya inklusi karya non-Barat berisiko hanya menjadi superfisial, gagal mencapai tujuan dekolonisasi epistemologis yang menjadi inti dari Sastra Dunia kontemporer.
Urgensi Pedagogis Sastra Global: Mengapa Kita Harus Mengajarkannya?
Pengajaran sastra global, khususnya karya-karya non-Barat, merupakan imperatif pedagogis yang melampaui tujuan peningkatan keterampilan berbahasa. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang cakap secara kognitif, peka secara sosial, dan bertanggung jawab sebagai warga negara global.
Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis, Analitis, dan Reflektif
Sastra dalam kurikulum memfasilitasi pembelajaran kritis, memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan analitis dan reflektif yang diperlukan di era kompleks ini. Siswa tidak hanya membaca teks, tetapi diharapkan untuk mengkritisi dan merefleksikannya dalam konteks kehidupan mereka. Melalui analisis teks sastra, peserta didik dapat mempelajari berbagai aspek kehidupan, termasuk peran individu dalam masyarakat, perbedaan kelas sosial, serta nilai-nilai etika dan moral.
Model pedagogi modern, seperti Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning), dapat memanfaatkan teks sastra untuk meminta siswa menganalisis konflik, karakter, dan pesan moral, yang secara langsung mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Sastra global non-Barat menyediakan materi unik yang memaksa siswa untuk menerapkan kemampuan analitis mereka pada struktur sosial dan filosofis yang asing, sehingga mengasah pemikiran kritis lintas budaya.
Sastra Global sebagai Media Pembentukan Empati dan Kesadaran Sosial
Salah satu manfaat terbesar pengajaran sastra adalah kemampuannya mempersiapkan siswa menjadi individu yang lebih peka terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Sastra berperan krusial dalam membangun empati antarbudaya. Pedagogi Kritis dalam pembelajaran sastra secara eksplisit dapat digunakan untuk membangun kesadaran sosial.
Karya sastra global yang beragam memperkenalkan siswa pada berbagai pandangan dunia dan tantangan sosial yang berbeda (misalnya, dampak kolonialisme, krisis ekologis di Global South). Dengan mempelajari karakter, konflik, dan penyelesaian masalah dari latar budaya yang berbeda, siswa dapat memperoleh wawasan sosial-budaya yang memperkaya pemahaman mereka tentang keberagaman dan toleransi. Selain itu, kurikulum sastra yang terintegrasi membantu membentuk karakter siswa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam karya, seperti tanggung jawab, kesetiakawanan, dan rasa hormat terhadap perbedaan.
Membangun Kompetensi Multikulturalisme dan Kewarganegaraan Global
Pendidikan sastra berbasis multikultural adalah elemen penting untuk memastikan peserta didik memahami dan menerima perbedaan kebudayaan sebagai keniscayaan dan heterogenitas bangsa. Dalam konteks pendidikan global, peserta didik membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan mereka berinteraksi dan membuat keputusan saat berhadapan dengan sesama dari berbagai ras, etnis, budaya, bahasa, dan agama.
Sastra multikultural memungkinkan siswa menganalisis bagaimana stigma sosial (misalnya, peran domestik perempuan) dibentuk dan diperkuat oleh struktur sosial budaya. Dengan mengajarkan sastra global non-Barat, kurikulum mengekspos siswa pada berbagai upaya dekonstruksi stigma yang dilakukan oleh budaya lain, sehingga membentuk kewarganegaraan yang sadar akan ketidakadilan global. Lebih jauh, jika sastra diajarkan untuk menyampaikan nilai-nilai moral , maka memasukkan perspektif non-Barat (misalnya, pandangan dunia Pribumi tentang ruang dan waktu yang berbeda dari konsepsi Barat ) adalah upaya untuk mendekolonisasi etika yang diajarkan, memastikan bahwa nilai-nilai tersebut bersifat multikultural, bukan sekadar refleksi moralitas Barat yang dominan.
Tabel 2: Manfaat Inti Pengajaran Sastra Global/Non-Barat dalam Pendidikan
| Kategori Manfaat | Manfaat Spesifik | Landasan Pedagogis | Relevansi Sastra Non-Barat |
| Kognitif dan Analitis | Mengembangkan pemikiran kritis, kemampuan analitis, dan reflektif. | Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL), Analisis unsur intrinsik/ekstrinsik. | Menyediakan lensa alternatif untuk menganalisis konflik sosial dan filosofis. |
| Sosial dan Kultural | Membangun empati, toleransi, dan kesadaran terhadap isu sosial/kemanusiaan. | Pedagogi Kritis, Analisis Perbedaan Kelas Sosial dan Hierarki Budaya. | Mengatasi hierarki budaya dan memperluas wawasan sosial-budaya di luar konteks lokal/Barat. |
| Afektif dan Etis | Membentuk karakter positif (tanggung jawab, kejujuran) dan menghargai nilai-nilai etika. | Integrasi nilai moral dan sosial budaya (termasuk nilai lokal). | Menantang konsepsi moralitas universal yang seringkali berakar tunggal (misalnya, pandangan dunia non-Barat tentang ruang/waktu). |
| Multikultural dan Dekolonial | Memahami perbedaan kebudayaan; melawan hegemoni naratif; mengenali pandangan dunia non-Barat. | Pendidikan Sastra Berbasis Multikultural, Model Sinektik. | Memvalidasi sastra lokal dan bahasa minoritas sebagai bagian dari dialog global yang lebih besar. |
Sastra Dunia Dan Agenda Dekolonisasi Pendidikan
Sastra Global sebagai Perspektif Lintas Budaya (Cross-Cultural Perspective)
Pengajaran Sastra Dunia harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk melawan hegemoni narasi. Pendekatan lintas budaya sangat penting untuk merekonstruksi narasi sejarah yang lebih adil, menghargai keberagaman linguistik, dan memposisikan sastra sebagai media untuk dialog antarbudaya yang substantif.
Memperkuat perspektif lintas budaya adalah langkah vital dalam membangun ketahanan budaya, memperdalam empati global, dan memupuk solidaritas internasional di tengah tantangan kontemporer. Ini berarti menciptakan ruang yang memadai untuk sejarah alternatif, bahasa minoritas, dan Sastra Dunia yang menentang sentralitas Barat. Pengarusutamaan perspektif lintas budaya dalam kurikulum sastra memastikan bahwa siswa tidak hanya belajar apa yang dipikirkan dunia, tetapi juga bagaimana dunia yang berbeda berpikir dan merespons tantangan.
Melawan Hegemoni Epistemologis Barat
Karya-karya non-Barat sering kali menawarkan tantangan langsung terhadap konsepsi universal yang berakar pada pandangan dunia Barat. Salah satu isu penting dalam agenda dekolonisasi pendidikan adalah menantang pandangan Barat tentang ruang dan waktu, yang mungkin sangat berbeda dengan pandangan dunia Pribumi atau budaya lainnya.
Gerakan dekolonisasi sastra tidak bertujuan untuk sekadar membandingkan diri dengan Barat, melainkan untuk menentukan nasib sendiri dan mengembangkan kedaulatan dalam pendidikan. Sastra non-Barat menjadi alat kritis untuk mengenali dan memvalidasi kerangka epistemologis dan etis lokal atau Pribumi. Dalam konteks ini, Sastra Dunia kontemporer berperan sebagai fasilitator untuk pembebasan intelektual, memungkinkan siswa melihat bahwa dunia tempat mereka tumbuh hanyalah satu versi dari realitas yang jauh lebih luas.
Strategi Pengarusutamaan Budaya Lokal sebagai Bagian Integral Sastra Dunia
Paradigma Sastra Dunia yang berbasis sirkulasi memungkinkan kita untuk melihat sastra lokal dan daerah sebagai bagian integral dari dialog global. Pendidikan sastra berbasis multikultural dapat diwujudkan melalui pemanfaatan potensi budaya daerah. Ini adalah upaya ganda: mengenalkan dan memanfaatkan budaya multikultural di tingkat lokal sambil mempersiapkan karya tersebut untuk sirkulasi global.
Sastra lokal memiliki kontribusi besar dalam mengajarkan dan menjaga nilai keluhuran budi, kejujuran, toleransi, dan cinta kasih di tingkat akar rumput. Dengan mengajar sastra lokal secara kritis dan kreatif, kurikulum tidak hanya melestarikan warisan budaya tetapi juga melatih siswa untuk menjadi agen yang mampu “menduniakan” karya lokal mereka sendiri. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan apresiasi produktif (seperti parafrase atau pementasan). Model pengajaran seperti Model Sinektik (Synectics) dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas melalui metafora dan analogi, secara organik menghubungkan sastra dan budaya dalam konteks multikultur. Sastra daerah dapat dianggap sebagai ‘potensi Sastra Dunia’ yang belum mencapai sirkulasi luas (terjemahan) dan, melalui pengajaran yang tepat, dapat diperkenalkan sebagai landasan etis sebelum membahas etika global.
Hambatan Dan Tantangan Implementasi Kurikulum Sastra Global
Implementasi reformasi kurikulum yang inklusif terhadap Sastra Dunia menghadapi tantangan struktural, logistik, dan pedagogis yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Faktor Struktural dan Infrastruktur
Tantangan struktural utama adalah instabilitas kurikulum. Kurikulum yang berganti-ganti menyebabkan kebingungan bagi guru dalam penerapan di sekolah, yang secara langsung menghambat upaya integrasi materi kompleks seperti Sastra Dunia. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pengajaran sastra di sekolah masih sangat minim. Kurangnya ketersediaan buku bekas saja sudah menjadi masalah, yang mengindikasikan bahwa pengadaan teks non-Barat yang berkualitas dan kredibel—seringkali hanya tersedia dalam terjemahan yang mahal—merupakan hambatan logistik yang besar. Aksesibilitas teks non-Barat yang kredibel dan berkualitas di lingkungan akademik menjadi penghalang nyata bagi reformasi kurikulum yang inklusif.
Faktor Guru dan Kualifikasi Pedagogis
Kualitas implementasi sangat bergantung pada pendidik. Kurangnya motivasi dan kreativitas guru menjadi hambatan utama dalam pembelajaran sejarah sastra dan apresiasi sastra secara umum. Meskipun metode pembelajaran yang menyenangkan (seperti apresiasi reseptif/produktif) direkomendasikan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa , implementasi ini sulit tanpa pelatihan dan sumber daya yang memadai.
Lebih mendasar lagi, terdapat kritik bahwa akademisi (dan implisitnya guru) di Indonesia terkadang memiliki keterbatasan waktu atau kemampuan untuk mengikuti dan mempelajari perkembangan kajian sastra dan teori-teori mutakhir secara maksimal. Kurikulum sastra global memerlukan teori kritis seperti Pascakolonialisme dan Ekokritik untuk menempatkan teks non-Barat dalam konteks yang benar. Jika pendidik tidak menguasai teori-teori kritis ini, mereka akan cenderung kembali ke model pengajaran yang paling mereka kenal—yang sering didasarkan pada kanon Barat atau pendekatan formalis. Akibatnya, setiap upaya inklusi sastra non-Barat berisiko menjadi superfisial, gagal menantang hierarki budaya yang ada, dan memperkuat dominasi narasi lama. Kesenjangan antara teori dekolonisasi yang dipelajari dan praktik pengajaran di kelas merupakan hambatan epistemologis yang perlu diatasi.
Model Dan Rekomendasi Untuk Reformasi Kurikulum Sastra Inklusif
Reformasi kurikulum sastra harus bersifat komprehensif, mencakup perubahan struktural, pedagogis, dan kebijakan.
Pengusulan Struktur Kurikulum Sastra Spiral Adaptif
Kurikulum sastra yang progresif harus mengadopsi struktur spiral, di mana pemahaman atas teks tidak dibentuk dalam satu waktu, tetapi terus dikembangkan melalui paparan ulang, reinterpretasi, dan dialog lintas disiplin. Model ini memungkinkan mahasiswa membangun pemahaman bertingkat yang kaya dan kontekstual.
Selain itu, kurikulum harus dirancang untuk menjadi inklusif, responsif gender , dan adaptif, disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan peserta didik, terutama dalam konteks pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Sastra Dunia menyediakan materi yang sempurna untuk menguji responsivitas gender dan inklusivitas sosial, misalnya melalui perbandingan representasi peran perempuan dalam berbagai budaya.
Strategi Pengajaran Berbasis Pedagogi Kritis dan Lintas Budaya
Pendidik harus menerapkan strategi pengajaran yang menumbuhkan keterlibatan kritis:
- Pedagogi Kritis: Menerapkan Pedagogi Kritis untuk secara eksplisit membahas isu-isu sosial, politik, dan humaniora yang diangkat oleh karya sastra global non-Barat. Pembelajaran harus mengacu pada ide-ide kritis dari tokoh-tokoh seperti Edward Said, Gayatri Spivak, dan Ngũgĩ wa Thiong’o, yang menyoroti perlunya meninjau kembali narasi sejarah yang bias.
- Apresiasi Reseptif dan Produktif: Menggunakan pendekatan apresiasi reseptif (emosi, pendidikan, analisis) dan apresiasi produktif (parafrase, pementasan) untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam menghasilkan karya sastra dan memahami gaya penulisan melalui proses intertekstual.
- Model Multikultural: Memanfaatkan potensi budaya daerah melalui model pembelajaran berbasis multikultural, seperti Model Sinektik (Synectics) yang mengembangkan kreativitas melalui analogi dan metafora, menghubungkan pengalaman lokal siswa dengan tema-tema global.
Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Profesionalisme Pendidik Sastra
Transformasi kurikulum hanya dapat berjalan apabila didukung oleh kebijakan pendidikan yang progresif dan berorientasi pada keberlanjutan. Rekomendasi kebijakan meliputi:
- Peningkatan Profesionalisme Guru: Reformasi sistem guru harus mencakup peningkatan kompensasi, profesionalisme, dan pelatihan berkala, dengan fokus khusus pada Teori Sastra Mutakhir (Pascakolonialisme, Ekokritik, Feminisme) dan pedagogi kritis untuk mengajar teks non-Barat.
- Insentif Penerjemahan dan Pengadaan: Pemerintah dan institusi pendidikan tinggi harus menyediakan dana dan insentif yang memadai untuk penerjemahan karya-karya sastra non-Barat yang dianggap krusial bagi kurikulum, sekaligus meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana (buku) sastra berkualitas untuk mengatasi keterbatasan aksesibilitas yang saat ini menghambat integrasi. Kebijakan ini merupakan langkah praktis untuk mendukung definisi Sastra Dunia Damrosch sebagai karya yang harus bersirkulasi.
Penutup Dan Prospek Masa Depan
Sastra Dunia modern menuntut kurikulum yang bergeser dari fokus kanonis yang statis dan eurosentris menuju mode sirkulasi yang dinamis. Inklusi karya non-Barat bukan sekadar isu representasi, tetapi merupakan imperatif pedagogis untuk membentuk warga negara yang kritis, empatik, dan sadar multikultural, serta merupakan langkah esensial menuju dekolonisasi pendidikan.
Meskipun urgensi teoretis untuk dekolonisasi kurikulum telah diakui dalam diskursus akademik, implementasi di lapangan menghadapi hambatan struktural yang signifikan, termasuk minimnya sarana prasarana dan instabilitas kurikulum, ditambah dengan keterbatasan kapasitas guru dalam menguasai teori kritis mutakhir.
Kurikulum sastra masa depan harus diarahkan pada model yang adaptif, berkelanjutan, dan menghubungkan sastra lokal secara organik dengan isu-isu global. Keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang progresif, investasi dalam aksesibilitas teks non-Barat melalui penerjemahan, dan peningkatan profesionalisme pendidik yang berkomitmen pada Pedagogi Kritis dan perspektif lintas budaya. Hanya melalui upaya terpadu ini, kurikulum sastra dapat memenuhi janji Sastra Dunia untuk mewakili keberagaman pengalaman manusia secara adil dan mendalam.