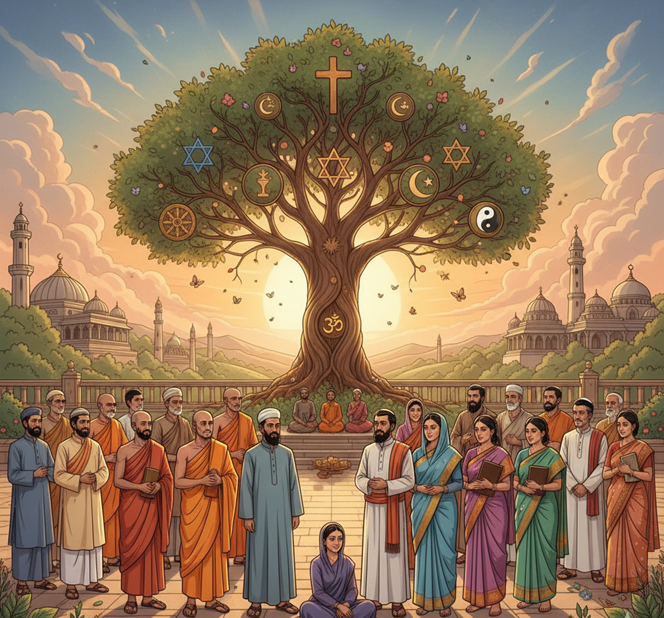Koeksistensi agama, yang merupakan inti dari tatanan sosial yang damai, melampaui konsep toleransi sederhana. Laporan ini mengeksplorasi tipologi koeksistensi yang berhasil di seluruh dunia, membedah faktor-faktor yang memungkinkan harmoni bertahan, serta menganalisis kerangka filosofis dan struktural yang mendukungnya. Koeksistensi yang berkelanjutan harus dilihat bukan sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai praktik interaksi sosial yang produktif dan saling melengkapi di tengah perbedaan.
Definisi dan Spektrum Koeksistensi
Studi mengenai kerukunan agama menuntut definisi yang jelas mengenai tingkat interaksi yang berbeda. Spektrumnya berkisar dari toleransi pasif hingga harmoni konstruktif. Toleransi didefinisikan sebagai penerimaan keragaman dan praktik interaksi sosial yang dilakukan dengan penuh penghargaan terhadap perbedaan antar individu dan kelompok. Namun, toleransi seringkali hanya berarti menerima perbedaan tanpa adanya interaksi substansial yang menghasilkan kerja sama.
Pluralisme, dalam konteks ini, dipandang sebagai sikap yang jauh lebih aktif—menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai cita-cita mulia dalam bingkai keberagaman. Pola pikir ini sangat penting karena hal-hal yang berbeda tidak selalu bertentangan secara diametral; justru, perbedaan dapat saling melengkapi. Dalam studi agama, pluralisme tidak dipahami sebagai penyamaan semua agama, sebab itu adalah mengingkari sunnatullah yang telah berlaku. Setiap agama dipandang unik, dan keberagaman ini harus disikapi secara terbuka dan dialektis, menghindari dikotomi atau kategori yang saling bertolak belakang.
Dalam Islam, pluralisme agama mendapatkan tempat yang kuat dalam gagasan normatif, di mana Islam mengakui eksistensi agama lain, tidak hanya dalam kerangka hubungan kemanusiaan tetapi juga dalam tempat mereka di sisi Tuhan. Koeksistensi yang berhasil menerjemahkan pengakuan normatif ini ke dalam kehidupan nyata yang saling mendukung.
Fondasi Filosofis dan Etika Universal
Upaya membangun koeksistensi global didasari oleh kerangka filosofis yang menekankan kesamaan etika universal antaragama. Hans Küng, melalui gagasannya tentang Etika Global (Global Ethics), menekankan bahwa tidak akan ada perdamaian antarnegara tanpa perdamaian antaragama, dan perdamaian antaragama memerlukan dialog yang substansial. Prinsip ini menegaskan kembali imperatif dialog antaragama yang bertujuan menciptakan persaudaraan sejati berdasarkan spirit kebenaran universal agama.
Titik temu yang paling kuat untuk kerja sama lintas agama terletak pada ajaran yang bersifat universal, yaitu bahwa “berbuat kebajikan di muka bumi adalah hal yang imperatif dan terpuji”. Nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan empati menjadi elemen kunci dalam memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik.
Di Indonesia, Pancasila memberikan fondasi struktural yang unik. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” tidak hanya menjadi simbol keimanan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen vital dalam menciptakan kerukunan. Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, yang secara inheren mendukung harmoni di tengah masyarakat multikultural. Penerapan nilai ini terlihat dalam sikap saling membantu antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang perbedaan.
Peran Kebijakan Negara dan Moderasi Terkelola
Koeksistensi yang berhasil seringkali memerlukan dukungan, atau setidaknya pengelolaan, dari pihak negara, terutama dalam menanggapi tekanan ideologis.
Model Negara Sentris (UEA)
Uni Emirat Arab (UEA) dipromosikan sebagai model sukses negara yang mewakili Islam moderat, didukung oleh diplomasi Emirat yang cemerlang. Model koeksistensi ini didukung penuh oleh negara (top-down), dengan manifestasi nyata seperti pendirian Rumah Keluarga Ibrahim (Abrahamic Family House), yang mewujudkan toleransi antaragama dan memperkuat bukti nyata dokumen “Manusia Persaudaraan” (Human Fraternity). Keberhasilan ini adalah hasil dari state will yang jelas dan intervensi kebijakan yang terstruktur untuk mempromosikan Islam sebagai agama yang toleran dan berbasis moralitas.
Ancaman Ideologi Kontra-Koeksistensi
Di sisi lain, koeksistensi menghadapi ancaman serius dari ideologi yang merubah agama menjadi platform politik yang tertutup dan agresif. Kelompok garis keras yang mengklaim kebenaran tunggal cenderung merasa berhak memaksakan pemahaman mereka terhadap orang lain. Ideologi ini berimplikasi pada mentalitas ketakutan untuk bergaul dengan tradisi agama lain karena takut akidah akan “tercemar,” padahal pesan agama sendiri dengan jelas menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama.
Perbedaan antara koeksistensi yang didukung negara dan koeksistensi organik sangat menonjol di sini. Meskipun UEA berhasil menciptakan toleransi yang dikelola secara diplomatik, model bottom-up di wilayah lain rentan terhadap penyusupan ideologi transnasional yang agresif. Keberlanjutan harmoni global memerlukan kemauan politik yang kuat untuk melawan ekstremisme ideologis yang menolak pluralisme, bukan hanya mengandalkan interaksi spontan masyarakat.
Kesenjangan Sosial sebagai Pemicu Konflik
Analisis kritis terhadap konflik agama menunjukkan bahwa agama seringkali disalahkan sebagai penyebab, padahal faktor dominan yang sebenarnya adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, penindasan, dan ketidakadilan. Kerusuhan yang melibatkan umat beragama seringkali memiliki pemicu kompleks yang berakar pada masalah ekonomi dan politik. Jika ajaran agama dipahami secara benar (yang menyerukan cinta kasih dan kebajikan), konflik tersebut tidak akan terjadi.
Oleh karena itu, setiap model koeksistensi yang sukses dan berkelanjutan—terutama di tingkat komunitas—harus secara eksplisit atau implisit mengatasi ketidakadilan sosio-ekonomi. Jika ketimpangan struktural ini diabaikan, harmoni agama yang tercipta cenderung rapuh atau hanya bersifat pseudo harmoni, karena konflik dapat dengan mudah dipicu kembali dan disamarkan di bawah narasi agama.
Warisan Sejarah dan Fragilitas Geopolitik: Studi Kasus Kota Global
Kota-kota yang berada di persimpangan peradaban, seperti Toledo, Sarajevo, dan Yerusalem, memberikan studi kasus yang berharga mengenai dinamika koeksistensi, mulai dari sinergi intelektual hingga keruntuhan yang disebabkan oleh tekanan politik dan etnis.
Toledo, Spanyol: Laboratorium Convivencia Abad Pertengahan
Toledo dikenal sebagai salah satu contoh klasik convivencia (hidup bersama) abad pertengahan, di mana budaya Yahudi, Kristen, dan Islam bertemu dan berinteraksi secara substansial.
Mekanisme utama yang mendorong koeksistensi ini adalah Sekolah Penerjemah Toledo (Toledo School of Translators). Sekolah ini adalah pusat kolaborasi intelektual fungsional di mana karya-karya filosofis dan ilmiah Islam dan Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Lati. Koeksistensi di Toledo didorong oleh kebutuhan pragmatis dan kepentingan bersama—kebutuhan dunia Latin untuk mendapatkan akses ke ilmu pengetahuan yang diawetkan dalam peradaban Islam dan Yahudi.
Model ini dapat dikategorikan sebagai koeksistensi instrumental. Harmoni yang terjalin sangat kuat karena ia melayani tujuan yang lebih besar, yaitu kemajuan intelektual. Namun, sejarah Toledo juga menyoroti kerentanan model ini. Ketika kepentingan politik berubah, terutama setelah Reconquista dan penguatan ideologi homogenisasi agama oleh penguasa Kristen, koeksistensi instrumental ini tidak dapat bertahan, yang menunjukkan bahwa harmoni fungsional dapat runtuh ketika kepentingan bersama telah dipenuhi atau digantikan oleh agenda politik eksklusif.
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina: Pelajaran dari Keruntuhan Pseudo-Harmoni
Sarajevo, yang secara historis dikenal karena multi-etnisitasnya, menyajikan narasi peringatan mengenai kerapuhan koeksistensi. Perang Bosnia (1992-1995) menunjukkan keruntuhan parah, diwarnai oleh kampanye pembersihan etnis yang menewaskan lebih dari 100.000 orang dan membuat sekitar dua juta orang mengungsi .
Analisis krisis ini menunjukkan bahwa harmoni yang ada sebelumnya hanya bersifat permukaan, atau pseudo harmoni. Harmoni artifisial ini gagal karena adanya perbedaan tahap kemajuan kultural dan struktural yang tidak terkelola, yang pada akhirnya memicu gerakan separatis dan disharmoni.
Koeksistensi pasca-perang di Bosnia diatur oleh Perjanjian Damai Dayton pada tahun 1995, yang secara militer menghentikan konflik tetapi secara politis menginstitusionalisasi perpecahan. Perjanjian tersebut membagi wilayah Bosnia menjadi 51% untuk Federasi Muslim-Kroasia dan 49% untuk Serbia-Bosnia. Koeksistensi yang dihasilkan adalah koeksistensi politik-teritorial yang didasarkan pada pemisahan yang dikelola (managed separation). Model ini berhasil mengakhiri kekerasan, namun ia secara efektif mempertahankan identitas kelompok yang terfragmentasi. Koeksistensi yang didasarkan pada pemisahan politik, meskipun menawarkan stabilitas jangka pendek, bukanlah model yang ideal untuk rekonsiliasi sejati.
Yerusalem: Koeksistensi yang Dikelola (Managed Coexistence) dan Tantangan Status Quo
Yerusalem mewakili kasus koeksistensi yang paling menantang, mengingat persilangan konflik agama, politik, dan teritorial yang mendalam. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung sekitar 71 tahun, dan upaya perdamaian mengalami perkembangan yang stagnan.
Di situs-situs suci, koeksistensi diatur oleh mekanisme kompleks yang disebut Status Quo. Status Quo adalah serangkaian perjanjian historis yang mengatur akses dan kontrol untuk menghindari konflik langsung. Namun, ini adalah contoh koeksistensi yang murni manajerial, bertujuan untuk mengelola konflik alih-alih menyelesaikan perbedaan fundamental.
Pada tingkat resolusi politik yang lebih luas, solusi dua negara dipandang sebagai solusi terlayak dalam kerangka liberalisme ideasional, karena koeksistensi memerlukan kerangka hidup yang didefinisikan oleh kesepahaman dalam batas wilayah, institusi politik, dan regulasi sosio-ekonomik.
Kondisi Yerusalem menunjukkan bahwa koeksistensi agama di area konflik ideologis tinggi sangat bergantung pada resolusi politik dan kepercayaan. Perdamaian tidak akan tercipta jika masih timbul kecurigaan serta ketidakhormatan good-will dalam setiap usaha diplomasi. Oleh karena itu, harmoni agama di Yerusalem adalah hasil sampingan dari komitmen politik untuk mengatasi kecurigaan dan mencapai kerangka politik yang komprehensif.
Koeksistensi Berbasis Kearifan Lokal (Bottom-Up Models)
Model koeksistensi yang berakar pada kearifan lokal seringkali menunjukkan ketahanan yang luar biasa karena didasarkan pada ikatan sosial, adat istiadat, dan persaudaraan, dibandingkan dengan kebijakan negara.
Komunitas Tolotang dan Masyarakat Muslim di Sidrap, Sulawesi Selatan
Studi kasus komunitas Tolotang (penganut kepercayaan Dewata Suae yang berafiliasi ke agama Hindu secara politik) dan masyarakat Muslim di Kelurahan Arateng, Kabupaten Sidrap, menunjukkan keberhasilan koeksistensi yang berbasis pada komunitas.
Koeksistensi ini diwujudkan melalui lima bentuk toleransi yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari :
- Terjalinnya aktivitas sosial kemasyarakatan: Meliputi interaksi dan kerja sama informal dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
- Persaudaraan: Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang erat.
- Kebebasan beragama: Penghormatan terhadap hak praktik keyakinan masing-masing.
- Bersahabat dengan semua penganut kepercayaan.
- Menghormati hari besar keagamaan: Menghargai tradisi dan praktik satu sama lain.
Mekanisme kerja sama implisit ini diperkuat oleh kesadaran akan keragaman, komunikasi yang baik, dan kehendak untuk berbagi.
Meskipun koeksistensi harian berjalan harmonis, Komunitas Tolotang menghadapi tantangan dalam praktik kewargaan, terutama dalam mengakses layanan dasar. Kebijakan Orde Baru yang mengafiliasikan mereka ke dalam agama resmi negara (Hindu) berdampak pada kurikulum keagamaan di sekolah, memaksa siswa mempelajari keyakinan yang bukan merupakan agama mereka. Namun, fakta bahwa tingkat toleransi harian tetap tinggi menunjukkan bahwa kekuatan hubungan kekeluargaan (kinship) dan ikatan sosial yang mendalam berfungsi sebagai penyangga yang kuat terhadap tekanan kebijakan identitas sentralistik yang bersifat mengintervensi.
Tana Toraja: Budaya sebagai Jembatan Kohesi Sosial
Di Tana Toraja, kearifan lokal memiliki peran sentral dalam memediasi hubungan antaragama, terutama melalui ritual adat. Upacara adat Rambu Solo’ (pesta kedukaan/pemakaman, yang merupakan ritual wajib bagi seluruh masyarakat Toraja tanpa memandang afiliasi agama (Kristen, Muslim, atau Aluk Todolo), berfungsi sebagai ruang komunal untuk memperkuat koeksistensi.
Kerukunan ini juga diperkuat melalui dakwah keteladanan, yang fokus pada nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan empati. Model ini terbukti mampu membentuk jembatan sosial yang efektif dan mencegah konflik.
Kekuatan model Toraja terletak pada integrasi ritual komunal. Dengan menempatkan kewajiban adat di atas perbedaan doktrinal pada momen krusial kehidupan (kematian), komunitas secara efektif menciptakan ruang sakral bersama (shared sacred space) yang memprioritaskan kohesi sosial. Kearifan lokal bertindak sebagai cultural anchor yang mengatasi eksklusivisme agama.
Mekanisme Resolusi Konflik Berbasis Adat
Mekanisme resolusi konflik berbasis adat di berbagai wilayah menunjukkan prinsip restoratif yang vital untuk koeksistensi yang langgeng. Di Aceh, resolusi damai (peaceful resolution) berbasis adat bertujuan menciptakan keseimbangan. Prinsip kuncinya adalah: “uleu bee matee ranteng bek patah” (ular mati, ranting jangan patah). Ini berarti penyelesaian konflik harus memenuhi rasa keadilan tanpa menimbulkan pihak yang merasa menang atau kalah.
Mekanisme adat juga menjunjung tinggi kesetaraan di depan hukum (equality before the law), tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, atau ekonomi. Untuk mengoptimalkan dampaknya, mekanisme adat perlu diperkuat melalui pelatihan bagi tokoh-tokoh adat dalam mediasi dan negosiasi, serta diintegrasikan dengan sistem hukum formal. Integrasi ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa berbasis adat efektif dalam memberikan akses keadilan.
Institusionalisasi Harmoni: Inisiatif dan Jaringan Global
Koeksistensi yang berhasil juga didukung oleh upaya terstruktur, mulai dari diplomasi multilateral hingga pembangunan kapasitas akademik dan gerakan akar rumput.
Diplomasi Agama dan Inisiatif Multilateral
Dialog antaragama telah menjadi alat penting dalam politik luar negeri dan pembangunan perdamaian. Institusi multilateral seperti Religion Twenty (R20), bersama Forum Perdamaian Dunia, menjadi keniscayaan yang harus dirawat untuk mengatasi ketegangan agama dan mendorong dialog. Di Indonesia, Kementerian Agama aktif dalam dialog plurilateral seperti Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, yang menyerukan penguatan toleransi.
Inisiatif seperti Humanitarian Islam juga mencerminkan fokus pada perdamaian global. Praktik ini menegaskan pergeseran agama menjadi alat diplomasi soft power. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada legitimasi negara penyelenggara dalam mempromosikan perdamaian. Ini menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian harus berasal dari banyak sudut pandang, mulai dari dialog global hingga inisiatif akar rumput.
Jaringan Akademik dan Pendidikan Lintas Agama
Jaringan akademik memainkan peran krusial dalam menyebarkan wawasan multikultural. Perguruan tinggi Islam, seperti UNISMA dan INSIMA, aktif dalam memperkuat jejaring internasional, riset kolaboratif, dan program pertukaran untuk menyebarkan wawasan inklusif. Upaya ini berfokus pada mengaitkan pemikiran tokoh lokal yang moderat (seperti Buya Hamka) dengan multikulturalisme global, memberikan kontribusi teoritik pada pengembangan konsep koeksistensi agama.
Namun, meskipun jejaring akademik ini kuat, implementasi pendidikan lintas agama di tingkat publik menghadapi tantangan. Sejarah menunjukkan bahwa toleransi dan intoleransi terjadi di mana-mana, dan agama yang sebenarnya mengajarkan kerukunan sering disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Koeksistensi dalam pengalaman hidup sebagian besar masyarakat masih bersifat eksklusif, di mana ajaran agama ditransformasikan hanya kepada komunitasnya sendiri, mengakibatkan kurangnya pengalaman untuk hidup rukun dan saling menghormati. Ini menyoroti adanya disosiasi antara wawasan akademik inklusif dengan kurikulum publik yang masih terbatas dalam menerapkan pendidikan lintas agama.
Inisiatif Akar Rumput dan Pemberdayaan Komunitas
Inisiatif perdamaian yang paling tangguh sering kali berasal dari gerakan akar rumput, seperti kegiatan filantropi dan LSM yang diinisiasi oleh pemuda. Jaringan komunal terbukti sangat penting dalam membina rekonsiliasi, bahkan di bawah bayang-bayang kekerasan agama.
Pembangunan perdamaian berkelanjutan memerlukan pemberdayaan suara-suara marginal. Namun, komunitas agama marginal seringkali menghadapi tantangan dalam representasi media; liputan keragaman cenderung dihindari jika melibatkan kelompok kontroversial. Oleh karena itu, strategi masa depan harus fokus pada pemanfaatan jaringan komunal, pemberdayaan suara-suara marginal, dan dorongan literasi agama untuk membangun harmoni yang berkelanjutan.
Pelajaran Universal dan Rekomendasi untuk Harmoni Antaragama
Sintesis Pelajaran Kunci dari Koeksistensi yang Berhasil
| Kasus Studi | Jenis Koeksistensi Utama | Mekanisme Pendorong Kunci | Tantangan Utama yang Dihadapi | Pelajaran Kritis |
| Toledo (Abad Pertengahan) | Intelektual/Fungsional | Sekolah Penerjemah | Perubahan Rezim Politik (Reconquista) | Koeksistensi fungsional rapuh terhadap pergeseran kekuasaan politik. |
| Uni Emirat Arab (Kontemporer) | Negara-Sentris/Diplomatis | Kebijakan Toleransi Resmi, Rumah Keluarga Ibrahim | Tekanan Ideologi Transnasional | Membutuhkan kehendak politik yang kuat dan intervensi kebijakan yang terstruktur untuk keberlanjutan. |
| Sarajevo (Pasca-Dayton) | Politik-Teritorial | Perjanjian Pembagian Wilayah | Pseudo-Harmony, Perpecahan Etnis Mendalam | Penyelesaian konflik tanpa rekonsiliasi tidak menghasilkan harmoni sejati; pemisahan yang dikelola bukanlah solusi rekonsiliatif. |
| Tolotang, Sidrap (Indonesia) | Komunal/Sosiologis | Persaudaraan, Aktivitas Sosial, Penghormatan Hari Besar | Intervensi Politik Agama Negara | Harmoni akar rumput berbasis kekerabatan dapat menjadi penyangga terhadap kebijakan diskriminatif sentralistik. |
| Tana Toraja (Indonesia) | Budaya/Kearifan Lokal | Upacara Adat Rambu Solo’ | Konflik Doktrinal/Eksklusivisme | Budaya dan Adat dapat berfungsi sebagai domain komunal yang mengatasi perbedaan doktrinal demi kohesi sosial. |
Faktor Universal Keberhasilan Koeksistensi
Koeksistensi agama yang sukses di seluruh dunia bergantung pada perpaduan antara kemauan politik, ikatan sosial yang kuat, dan komitmen terhadap nilai-nilai di luar dogma eksklusif.
Pertama, keberlanjutan harmoni bergantung pada penyelesaian masalah ketidakadilan sosio-ekonomi dan politik. Jika akar masalah non-agama ini dibiarkan, setiap upaya harmoni agama akan rentan dan mudah dimanipulasi. Kedua, koeksistensi harus didukung oleh resolusi politik di wilayah konflik, seperti yang ditunjukkan oleh kebutuhan akan kerangka politik yang komprehensif di Yerusalem. Ketiga, mekanisme berbasis adat dan kearifan lokal (seperti prinsip restoratif “uleu bee matee ranteng bek patah” di Aceh) memberikan kerangka kerja yang teruji secara budaya untuk resolusi konflik dan kerja sama. Akhirnya, fokus pada nilai universal dan berbuat kebajikan di muka bumi adalah titik temu yang paling imperatif untuk kerja sama lintas agama.
Rekomendasi Kebijakan dan Arah Masa Depan
- Integrasi Pendidikan Lintas Agama Inklusif: Pemerintah harus memprioritaskan peninjauan dan penyusunan kurikulum baru yang mengintegrasikan pendidikan lintas agama secara eksplisit, mengurangi praktik hidup koeksistensi yang bersifat eksklusif, dan memastikan bahwa generasi muda memiliki pengalaman hidup rukun dan saling menghormati.
- Mewujudkan Keadilan Struktural: Inisiatif koeksistensi harus selalu dikaitkan dengan kebijakan yang mengatasi kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Koeksistensi hanya dapat bertahan jika masalah struktural yang sering memicu konflik dihilangkan.
- Penguatan Mekanisme Hukum Adat: Di negara-negara multikultural, perlu adanya investasi dalam memperkuat kapasitas tokoh adat melalui pelatihan mediasi dan negosiasi. Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat harus diintegrasikan dengan sistem hukum formal untuk meningkatkan akses keadilan restoratif.
- Meningkatkan Representasi Suara Marginal: Upaya diplomasi agama global harus berhati-hati agar tidak hanya berfokus pada elit agama. Penting untuk memberdayakan jaringan komunal dan suara-suara marginal, serta mendukung inisiatif akar rumput, untuk memastikan bahwa harmoni yang diupayakan benar-benar mewakili seluruh lapisan masyarakat.