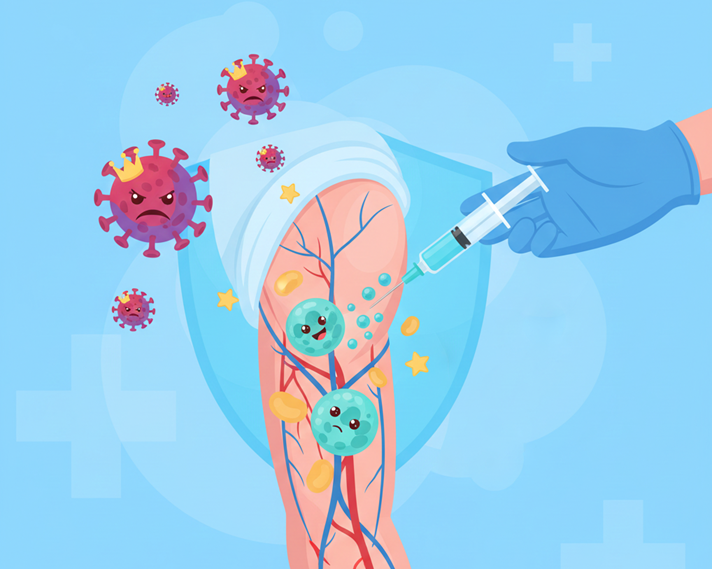Pendahuluan: Pelajaran Kritis dari Ketidaksetaraan Akses COVID-19
Pandemi COVID-19 berfungsi sebagai uji stres yang tak tertandingi terhadap sistem kesehatan dan tata kelola global. Meskipun pengembangan vaksin COVID-19 dalam waktu singkat mewakili pencapaian ilmiah yang monumental, respons global terhadap distribusi vaksin mengungkap kegagalan etika dan struktural yang mendalam, terutama dalam hal pemerataan akses antara negara berpenghasilan tinggi (HIC) dan negara berpenghasilan rendah (LIC) atau negara berkembang (LMIC). Kegagalan untuk memastikan “ekuitas vaksin” pada fase awal pandemi memiliki dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan secara global.
Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai akar penyebab ketidaksetaraan ini, mengkritisi kinerja mekanisme multilateral seperti COVAX dan WHO, mengidentifikasi hambatan struktural di luar paten, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada tata kelola, kemandirian manufaktur, dan penguatan logistik untuk membangun ketahanan kesehatan yang lebih adil di masa depan. Ekuitas vaksin, yang didefinisikan sebagai prinsip pendistribusian vaksin secara adil, menyadari bahwa setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda dan membutuhkan bantuan dalam derajat yang berbeda, harus menjadi landasan strategi kesehatan global di masa mendatang.
Diagnosis Ketidaksetaraan Global (Pelajaran Kritis dari COVID-19)
Kontras Akses: Nasionalisme Vaksin dan Advance Purchase Agreements (APA)
Fase awal peluncuran vaksin COVID-19 ditandai oleh praktik “nasionalisme vaksin”—sebuah mentalitas ‘negaraku yang utama’—yang secara efektif memonopoli pasokan vaksin yang terbatas. Kontras ini didukung oleh data statistik yang mencengangkan, yang menunjukkan kesenjangan distribusi yang sangat besar. Pada awal 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa lebih dari 87% dosis vaksin telah didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas. Sebaliknya, negara berpenghasilan rendah secara keseluruhan hanya menerima 0,2% dari total pasokan vaksin global.
Ketidakseimbangan ini juga tercermin dalam tingkat cakupan per individu: rata-rata, satu dari empat orang di HIC telah menerima vaksin virus corona, dibandingkan dengan hanya satu dari lebih dari 500 orang di negara berpenghasilan rendah. Kondisi serupa juga dicatat oleh World Bank, di mana per Januari 2022, hanya 10% masyarakat di negara-negara ekonomi rendah yang telah menerima dosis pertama, berbanding terbalik dengan 80% cakupan di negara maju.
Mekanisme utama yang mendorong disproporsi ini adalah penggunaan Advance Purchase Agreements (APA). Negara-negara maju, memanfaatkan kemampuan finansial mereka, dapat mengikat kontrak pembelian yang menjamin akses diprioritaskan ke banyak vaksin dari pengembang utama. Tindakan ini secara langsung membatasi kemampuan negara berkembang untuk memperoleh vaksin secara tepat waktu. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri, telah mengecam praktik nasionalisme vaksin dan distribusi yang tidak adil dan tidak merata ini.
Secara hukum dan etika, praktik APA menimbulkan masalah serius. Analisis hukum internasional menunjukkan bahwa penggunaan APA untuk mengamankan akses prioritas dengan mengorbankan negara berkembang tidak dapat diterima. Hal ini dianggap melanggar hak atas kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip itikad baik (good faith), serta melampaui ketentuan Deklarasi TRIPS tentang Kesehatan Publik tahun 1995. Ketidakseimbangan ini bukan hanya kegagalan moral; kegagalan untuk menerapkan prinsip ekuitas—yang mengakui adanya kebutuhan yang berbeda dan karenanya memerlukan bantuan dalam derajat yang berbeda —menunjukkan bahwa kerangka etika global tidak memiliki otoritas penegakan di tengah krisis akut, memungkinkan kepentingan komersial dan kedaulatan nasional mengalahkan mandat kesehatan global.
Dampak Epidemiologis dan Ekonomi Kesenjangan Akses
Kesenjangan akses vaksin yang parah memiliki konsekuensi epidemiologis yang langsung. Bukti klinis, seperti yang ditunjukkan dalam studi terkait vaksinasi COVID-19, menegaskan bahwa vaksinasi adalah metode pencegahan yang direkomendasikan oleh WHO karena secara signifikan mengurangi tingkat keparahan penyakit dan mortalitas. Status tidak divaksinasi berkorelasi dengan peningkatan risiko kematian yang signifikan (HR = 7.52 untuk usia > 60 tahun; HR untuk status tidak divaksinasi versus divaksinasi adalah 0.10, p<0.001). Oleh karena itu, populasi yang tidak divaksinasi di negara-negara berpenghasilan rendah menanggung beban kesehatan yang sangat besar.
Dampak kesenjangan vaksin meluas melampaui pandemi COVID-19 itu sendiri. Gangguan layanan kesehatan rutin, yang dipicu oleh fokus global pada COVID-19 dan gangguan rantai pasok, telah menyebabkan resurgensi penyakit lama yang dapat dicegah oleh vaksinasi rutin. WHO mencatat adanya peningkatan kasus campak global sebesar 43% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Di wilayah tertentu, seperti Afrika Timur, kasus difteri dilaporkan melebihi 6.000 kasus dalam satu tahun, sementara wabah polio muncul kembali di Filipina. Kesenjangan ini menunjukkan kerentanan sistem imunisasi dasar akibat fokus yang bergeser.
Secara ekonomi, kegagalan imunisasi dan kesenjangan akses mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang. Anak-anak yang tidak divaksinasi lebih rentan sakit, menyebabkan ketidakhadiran di sekolah dan berkurangnya produktivitas keluarga karena biaya dan waktu perawatan yang meningkat. Studi Bank Dunia (2024) memperkirakan bahwa setiap US$1 yang diinvestasikan dalam imunisasi menghasilkan pengembalian ekonomi hingga US$21 dalam jangka panjang melalui pengurangan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, ketidaksetaraan vaksin bukan hanya masalah kesehatan, tetapi penghalang mendasar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Evaluasi Mekanisme Multilateral (Peran WHO dan COVAX)
COVAX: Analisis Kegagalan Struktural
COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) didirikan sebagai inisiatif global yang bertujuan untuk memastikan akses setara terhadap vaksin COVID-19. Dipimpin oleh GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), WHO, dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), COVAX mewakili upaya multilateral paling signifikan untuk mengatasi ketidakadilan distribusi.
Meskipun memiliki mandat yang mulia, COVAX menghadapi kegagalan struktural yang mendasar. Mekanisme ini dirancang dengan harapan baik dan mengandalkan donasi dan janji, namun terbukti tidak berdaya melawan kekuatan pasar yang didorong oleh Advance Purchase Agreements (APA) negara-negara maju. Negara-negara maju mampu mengamankan pasokan secara langsung, seringkali melewati COVAX demi alasan politik atau komersial. Fenomena bilateralisme ini secara langsung menghambat kemampuan COVAX untuk mengumpulkan dosis yang cukup, seperti yang disuarakan oleh Direktur Jenderal WHO bahwa pengaturan bilateral semacam itu “berisiko mengipasi api ketidakadilan vaksin”.
Selain tantangan pasokan, COVAX juga menghadapi kesulitan logistik yang luar biasa. Operasi pengadaan dan distribusi globalnya dicirikan sebagai “tantangan logistik paling kompleks dalam sejarah” terutama dalam mengelola cold chain dan pengiriman last-mile di berbagai negara berkembang.
Kegagalan COVAX menunjukkan dengan jelas bahwa realpolitik dan kepentingan nasional jangka pendek akan selalu mendominasi komitmen multilateral dalam keadaan darurat, terutama ketika mekanisme multilateral tersebut didasarkan pada voluntarism (sukarela). Tata kelola krisis global saat ini tidak memberikan WHO atau aliansi yang dipimpinnya (seperti COVAX) alat yang kuat atau kewenangan yang mengikat untuk memaksakan alokasi yang adil, meskipun WHO memiliki kerangka etika yang jelas tentang ekuitas dan hak asasi. Oleh karena itu, reformasi tata kelola di masa depan harus memindahkan mekanisme alokasi sumber daya penting dari ranah donasi dan niat baik ke dalam kerangka kewajiban hukum yang harus ditegakkan.
Hambatan Struktural: HKI, Logistik, dan Kepercayaan
Ketidaksetaraan akses vaksin tidak hanya disebabkan oleh kegagalan kebijakan pembelian, tetapi juga oleh hambatan struktural yang mendalam terkait dengan kekayaan intelektual, logistik, dan penerimaan publik.Selama pandemi, debat mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi pusat perhatian dalam upaya untuk meningkatkan produksi vaksin di LMIC. Pada tahun 2020, India dan Afrika Selatan mengajukan proposal kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mencabut sementara The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Tujuan proposal ini adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan akses vaksin dengan memungkinkan produksi lokal.
Meskipun proposal tersebut didukung oleh puluhan negara berkembang dan didesak oleh WHO , negara-negara maju awalnya menentang, khawatir bahwa pencabutan HKI akan mengurangi insentif untuk inovasi farmasi. Setelah proses yang panjang, WTO akhirnya menyetujui waiver tersebut pada tahun 2022. Namun, keputusan ini datang terlambat dan memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas: pengecualian ini hanya berlaku untuk hak paten vaksin dan secara eksplisit mengecualikan terapeutik dan diagnostik—dua alat penting lainnya dalam penanggulangan pandemi. Pengecualian ini juga hanya berlaku selama lima tahun.
Keterbatasan waiver ini membuktikan bahwa hambatan nyata terhadap kemandirian produksi di LMIC seringkali bukan hanya paten formal. Meskipun paten ditangguhkan, negara-negara berkembang tetap kekurangan know-how (pengetahuan teknis dan resep rahasia), bahan baku, dan fasilitas infrastruktur kompleks yang diperlukan untuk memproduksi vaksin mRNA. Perjanjian TRIPS Pasal 7 sendiri menyatakan bahwa perlindungan HKI seharusnya berkontribusi pada transfer teknologi dan kesejahteraan sosial. Namun, tanpa mekanisme penegakan yang kuat, klausul ini tidak efektif. Keputusan WTO, dengan mengecualikan diagnostik dan terapeutik, secara tersirat menunjukkan perlindungan investasi farmasi HIC diutamakan, bahkan jika hal tersebut menghambat manajemen klinis yang efektif di seluruh dunia.
Logistik Rantai Dingin dan Kendala Last-Mile
Distribusi vaksin COVID-19, terutama vaksin mRNA yang memerlukan suhu ultra-rendah, menyoroti kerentanan logistik global. Cold chain logistik—sistem yang memastikan produk sensitif suhu tetap berada dalam kondisi suhu tertentu melalui fasilitas penyimpanan, transportasi, dan pemantauan suhu terkontrol—adalah tulang punggung distribusi vaksin.
Di banyak LMIC, terutama di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan wilayah konflik, kurangnya infrastruktur cold chain yang memadai menjadi hambatan utama last-mile. Di wilayah-wilayah ini, vaksin sering rusak sebelum mencapai penerima, berkontribusi pada cakupan imunisasi terendah di dunia. Tantangan ini semakin diperburuk oleh biaya tinggi dan investasi awal yang besar yang diperlukan untuk membangun fasilitas penyimpanan dan transportasi berpendingin.
Untuk memitigasi risiko ini, teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk pemantauan suhu dan lokasi secara real-time. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi ini telah membantu memastikan keamanan dan integritas vaksin selama pengiriman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi. Investasi pada teknologi dan infrastruktur dual-use (untuk pandemi dan imunisasi rutin) adalah imperatif strategis.
Ancaman Keraguan Vaksin (Vaccine Hesitancy)
Bahkan ketika vaksin tersedia, hambatan psikososial berupa keraguan vaksin (vaccine hesitancy) tetap menjadi tantangan signifikan, terutama di negara-negara yang berjuang melawan disinformasi yang merajalela. Keraguan ini diperburuk oleh penyebaran disinformasi dan teori konspirasi yang terjadi lebih cepat daripada klarifikasi dari otoritas kesehatan.
Di Indonesia, misalnya, keragu-raguan terhadap dosis booster dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti kurangnya pengetahuan tentang kemanjuran dan keamanan vaksin. Hal ini secara langsung mengancam keberhasilan program imunisasi rutin, seperti terlihat dari kembalinya wabah campak dan polio di beberapa wilayah setelah program imunisasi dasar terganggu. Kerangka etika WHO menekankan perlunya transparansi dan konsistensi dalam komunikasi risiko untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa mengatasi keraguan vaksin, investasi logistik dan pasokan akan sia-sia.
Membangun Ketahanan di Masa Depan (Pilar Reformasi)
Untuk mencegah terulangnya ketidakadilan distribusi pada krisis kesehatan global berikutnya, diperlukan reformasi struktural, tata kelola, dan teknologi.
Reformasi Tata Kelola Global: Perjanjian Pandemi WHO
Menyadari kesenjangan yang terjadi selama COVID-19, negara-negara anggota WHO mulai menegosiasikan Perjanjian Pandemi (Pandemic Agreement) dan Amandemen Peraturan Kesehatan Internasional (IHR). Tujuan inti dari perjanjian ini adalah untuk menegosiasikan kesepakatan yang mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan dalam mencegah, menghadapi, dan menanggapi pandemi di masa depan.
Namun, proses negosiasi berjalan lambat dan sulit, ditandai dengan “kebuntuan” dan perpanjangan target penyelesaian hingga Sidang WHA tahun depan. Hambatan utama terletak pada konflik antara kedaulatan nasional dan kebutuhan akan kewajiban global yang mengikat, terutama terkait klausul pembagian patogen dan transfer teknologi.
Meskipun WHO telah mengklarifikasi bahwa Perjanjian Pandemi tidak memberikan kewenangan kepada Sekretariat atau Dirjen WHO untuk mengarahkan atau menetapkan kebijakan nasional yang mengikat , risiko bahwa perjanjian akhir menjadi kompromi politik yang lemah sangat nyata. Jika klausul ekuitas, terutama yang berkaitan dengan transfer teknologi wajib dan alokasi pasokan yang adil, tidak bersifat mandatory, Perjanjian Pandemi tidak akan efektif dalam mencegah terulangnya nasionalisme vaksin. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam negosiasi ini sambil tetap menegaskan komitmen global untuk ketahanan kesehatan.
Kemandirian Manufaktur dan Model Transfer Teknologi mRNA WHO
Membangun kemandirian regional dalam produksi vaksin adalah strategi paling penting untuk mengatasi ketidaksetaraan akses jangka panjang. Hal ini mengurangi ketergantungan LMIC pada ekspor dan donasi HIC, sekaligus mengatasi hambatan non-paten yang melemahkan efektivitas TRIPS Waiver.
Salah satu inisiatif paling transformatif dalam hal ini adalah Program Transfer Teknologi mRNA (mRNA TT Hub) yang diluncurkan oleh WHO di Afrigen, Cape Town, Afrika Selatan. Program ini bertujuan untuk membangun produksi regional mRNA yang berkelanjutan di LMIC, dengan fokus pada kesiapsiagaan pandemi dan keberlanjutan di antara keadaan darurat kesehatan. Afrigen telah berhasil mengembangkan teknologi vaksin mRNA-nya sendiri dan mulai mentransfer know-how ini kepada mitra (spokes) di LMIC, termasuk Biovac di Afrika Selatan, serta pusat regional di Brazil dan Argentina.
Model ini mengatasi masalah know-how yang diabaikan oleh TRIPS Waiver dengan menyediakan pelatihan, teknologi, dan keahlian. Selain itu, program ini kini berfokus pada pengembangan vaksin berbasis mRNA untuk penyakit prioritas LMIC lainnya, memastikan bahwa kapasitas fasilitas manufaktur bersifat dual-use dan dapat dialihkan dengan cepat untuk merespons pandemi baru. Indonesia, dengan industri farmasi yang didukung oleh entitas seperti Bio Farma, memiliki peluang untuk kembali memimpin industri vaksin di negara berkembang dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui kemitraan teknologi.
Mekanisme Pendanaan dan Kemitraan Strategis
Kesiapsiagaan pandemi memerlukan mekanisme pendanaan yang stabil dan terencana, tidak hanya bergantung pada respons krisis. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) memainkan peran penting dalam pendanaan Penelitian dan Pengembangan (R&D) vaksin untuk penyakit menular yang berpotensi pandemi. Indonesia telah menunjukkan komitmen finansialnya melalui kontribusi sebesar US$1 juta kepada CEPI.
Kemitraan dengan CEPI memungkinkan Indonesia memperkuat industri kesehatannya, memperoleh akses ke informasi R&D terbaru, dan memungkinkan industri farmasi domestik (seperti Bio Farma, yang telah dipilih sebagai mitra manufaktur CEPI) menjadi pemain kunci dalam jejaring vaksin global.
Selain pendanaan R&D, alokasi dana global harus memprioritaskan investasi dalam:
- Imunisasi Rutin: Mengingat tingginya pengembalian ekonomi (21:1) dari investasi ini, pendanaan harus diarahkan untuk mengatasi resurgensi penyakit lama.
- Infrastruktur Logistik: Mekanisme pendanaan harus mendukung investasi awal yang besar dan kompleks dalam cold chain logistik yang canggih dan terdigitalisasi, yang sangat penting untuk mencapai distribusi yang merata di daerah terpencil.
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan (Roadmap to Equity)
Sintesis Pelajaran Kunci
Analisis Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kegagalan ekuitas vaksin berakar pada sistem tata kelola global yang rentan. Mekanisme yang bergantung pada niat baik dan kontribusi sukarela, seperti COVAX, akan selalu dikalahkan oleh insentif pasar dan nasionalisme vaksin yang dieksekusi melalui Advance Purchase Agreements (APA). Kesenjangan ini diperburuk oleh hambatan struktural: perlindungan HKI yang ketat dan kegagalan dalam transfer know-how teknologi, serta defisit infrastruktur logistik last-mile di LMIC.
Masa depan vaksinasi global harus didasarkan pada pergeseran paradigma dari voluntarism ke kewajiban yang mengikat secara hukum dan investasi strategis dalam kemandirian manufaktur regional.
Rekomendasi Kebijakan Mendalam (Roadmap Lima Pilar)
Laporan ini merekomendasikan lima pilar utama yang saling terkait untuk memastikan ekuitas vaksin dan memperkuat ketahanan kesehatan global:
- Pilar I: Penguatan Wewenang Multilateral melalui Hard Law
Perjanjian Pandemi WHO harus diakhiri dengan mekanisme yang mengikat secara hukum (berbeda dari mandat WHO yang lemah sebelumnya) untuk alokasi vaksin, diagnostik, dan material biologis. Mekanisme ini harus memberikan kewenangan prioritas kepada WHO atau badan global lain dalam pengadaan awal untuk LMIC, secara efektif membatasi ruang gerak Advance Purchase Agreements (APA) yang inekuitas selama fase darurat.
- Pilar II: Mandat Transfer Teknologi yang Mengikat
Untuk mengatasi kegagalan TRIPS Waiver yang terbatas , forum global harus menyepakati mekanisme yang mewajibkan transfer know-how, data klinis, dan teknologi manufaktur (bukan hanya paten) dari produsen yang didanai publik ke regional manufacturing hubs di LMIC. Model WHO mRNA TT Hub harus didanai dan diperkuat secara permanen sebagai infrastruktur penting untuk kemandirian teknologi.
- Pilar III: Investasi Infrastruktur Logistik Dual-Use
Pendanaan global, termasuk dari GAVI dan CEPI, harus diinvestasikan secara jangka panjang untuk membangun infrastruktur cold chain yang canggih, terdigitalisasi (menggunakan teknologi IoT), dan mampu melayani baik kebutuhan imunisasi rutin (yang menghasilkan pengembalian ekonomi 21:1 9) maupun kesiapsiagaan pandemi.
- Pilar IV: Kemitraan R&D Global yang Adil
Memanfaatkan kemitraan strategis, seperti kontribusi Indonesia kepada CEPI , untuk memastikan negara berkembang berpartisipasi dalam pengembangan R&D (riset dan pengembangan) dan menjadi produsen penting, bukan hanya sebagai pasar penerima. Kerangka kerja ini harus mendukung kapasitas domestik seperti Bio Farma.
- Pilar V: Komunikasi Risiko dan Pembangunan Kepercayaan Publik
Menerapkan strategi komunikasi risiko yang transparan dan konsisten, sesuai dengan kerangka etika 2, untuk melawan disinformasi yang menyebabkan keraguan vaksin (vaccine hesitancy) dan mengancam cakupan imunisasi rutin. Peningkatan literasi kesehatan adalah investasi penting dalam modal sosial yang mendukung efektivitas semua program vaksinasi.
Untuk menyimpulkan, tata kelola vaksin global di masa depan harus menjamin bahwa prinsip ekuitas tidak hanya menjadi pedoman etika, tetapi juga menjadi kewajiban yang diterapkan dan didukung oleh infrastruktur dan kapasitas manufaktur regional yang kuat.
Tabel 4: Evaluasi Mandat dan Keterbatasan Organisasi Kunci dalam Akses Vaksin (Lesson Learned)
| Organisasi/Mekanisme | Mandat Utama | Pencapaian Kunci (COVID-19) | Keterbatasan Kritis (COVID-19) | Rekomendasi Strategis Masa Depan |
| WHO | Kepemimpinan Kesehatan Global, Etika, Panduan Teknis | Menginisiasi COVAX, advokasi kuat melawan nasionalisme vaksin | Kurangnya kekuatan memaksa, mandat yang tereduksi menjadi soft law | Pemberian wewenang alokasi yang mengikat dalam Perjanjian Pandemi |
| COVAX | Akses Vaksin Global yang Setara | Menyediakan dosis ke LMICs di bawah tekanan pasar | Gagal bersaing dengan APA bilateral; rentan terhadap politisasi | Digantikan oleh mekanisme wajib kontribusi/alokasi yang didanai penuh |
| WHO mRNA TT Hub | Transfer teknologi dan kapasitas regional berkelanjutan | Afrigen mengembangkan teknologi sendiri; transfer ke 14+ spokes | Tantangan pendanaan keberlanjutan dan skala produksi komersial | Jaminan pendanaan jangka panjang dan fokus pada penyakit prioritas LMIC |
| WTO (TRIPS) | Perlindungan HKI dan transfer teknologi | Menyetujui waiver terbatas untuk paten vaksin | Gagal mengatasi hambatan non-paten; waiver tidak komprehensif | Merevisi TRIPS untuk kewajiban lisensi wajib dan transfer know-how dalam keadaan darurat |