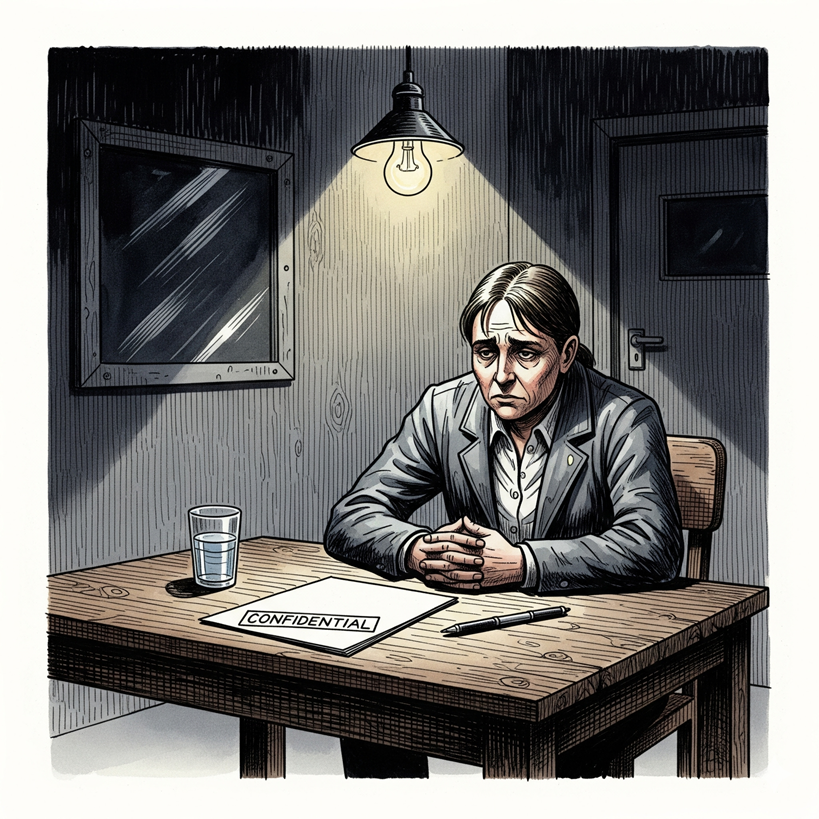Dalam upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum sering menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengungkap dan memberantas kejahatan yang terorganisir (organized crime) dan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kejahatan seperti korupsi, terorisme, dan peredaran narkotika cenderung dilakukan secara sistematis dan melibatkan jaringan pelaku yang terstruktur, sehingga sulit untuk diurai hanya dengan bukti-bukti konvensional. Para pelaku kejahatan ini seringkali menutupi perbuatan mereka dengan rapi, menyebabkan penyelidikan, penuntutan, dan pembuktian menjadi proses yang kompleks dan berlarut-larut.
Dalam konteks inilah, peran Justice Collaborator (JC) menjadi sangat relevan dan strategis. Keberadaan seorang pelaku yang bersedia bekerja sama dapat menjadi kunci untuk membuka tabir kejahatan. Dengan memberikan informasi yang akurat, JC membantu aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, dalam menemukan kebenaran materiil. Peran ini mencakup pengungkapan struktur organisasi kejahatan, identifikasi pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, serta pelacakan dan pengembalian aset atau hasil kejahatan kepada negara. Tanpa kontribusi dari individu yang berada di dalam lingkaran kejahatan tersebut, kasus-kasus besar dan terorganisir seringkali sulit untuk diselesaikan secara tuntas.
Definisi dan Karakteristik Justice Collaborator
Secara etimologis, istilah Justice Collaborator berasal dari bahasa Inggris yang berarti “kolaborator keadilan.” Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, JC sering disebut sebagai “saksi pelaku yang bekerja sama.” Definisi ini secara formal diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Pasal tersebut mendefinisikan Saksi Pelaku sebagai “tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.
Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik kunci yang membedakan seorang Justice Collaborator dari saksi biasa. Pertama, individu yang mengajukan diri sebagai JC adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan mengakui kejahatan yang dilakukannya. Kedua, dan yang paling fundamental, seorang JC bukanlah pelaku utama atau tokoh intelektual (mastermind) dari kejahatan yang diungkapnya. Kriteria ini menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan UU PSK. Ketiga, JC harus bersedia memberikan keterangan yang substansial dan bukti-bukti signifikan yang dapat mengungkap tindak pidana tersebut secara efektif serta pelaku-pelaku lain yang terlibat.
Titik Tolak Historis dan Perkembangan Konsep JC
Ide mengenai konsep Justice Collaborator tidak muncul begitu saja dalam sistem hukum Indonesia, melainkan berawal dari adopsi gagasan yang berkembang di kancah internasional. Titik tolak utama adalah ketentuan dalam instrumen hukum internasional, seperti Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Konvensi-konvensi ini mendorong negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memfasilitasi pelaku kejahatan untuk memberikan informasi yang berguna bagi penyelidikan dan pembuktian.
Secara lebih spesifik, konvensi tersebut mengarahkan negara-negara untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian keringanan hukuman atau bahkan kekebalan dari tuntutan bagi seorang terdakwa yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan. Gagasan inilah yang kemudian diadopsi dan diadaptasi ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia melalui berbagai regulasi, yang pada akhirnya memunculkan payung hukum bagi Justice Collaborator.
Analisis Mendalam: Paradoks Hukum dan Keadilan Instrumental
Keberadaan konsep Justice Collaborator merepresentasikan sebuah paradoks yang strategis dalam sistem peradilan pidana. Secara tradisional, hukum pidana didasarkan pada prinsip keadilan retributif, di mana setiap pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Setiap pelaku dianggap bertanggung jawab penuh atas tindakannya, dan hukuman berfungsi sebagai pembalasan yang adil. Namun, dalam kasus seorang Justice Collaborator, prinsip ini seolah-olah dikesampingkan.
Sistem hukum secara pragmatis mengkompromikan hukuman maksimal bagi satu pelaku (yang “tidak utama”) demi mencapai tujuan yang lebih besar dan sulit dicapai melalui jalur konvensional. Tujuan tersebut adalah membongkar seluruh jejaring kejahatan yang tersembunyi, mengidentifikasi otak kejahatan, dan memulihkan kerugian yang diderita oleh negara atau masyarakat. Dengan demikian, Justice Collaborator berfungsi sebagai alat instrumental untuk mencapai keadilan substantif yang lebih luas. Ini adalah sebuah pertukaran fungsional yang berfokus pada hasil akhir: sistem hukum mengorbankan sebagian kecil keadilan formal—yaitu menghukum seorang pelaku dengan vonis maksimal—demi keadilan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.
Landasan Yuridis dan Syarat Kualifikasi
Kerangka Hukum Nasional Indonesia
Secara normatif, konsep Justice Collaborator di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang tersebar di berbagai peraturan. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Pasal 10A UU PSK secara eksplisit mengatur bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan “penanganan secara khusus” dan “penghargaan” atas kesaksian yang diberikan.
Selain UU PSK, pengaturan yang lebih terperinci mengenai Justice Collaborator juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. SEMA ini berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam mempertimbangkan pemberian keringanan hukuman bagi pelaku yang bersedia bekerja sama. Keberadaan SEMA ini menunjukkan pengakuan formal terhadap peran JC, meskipun secara prosedural belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketiadaan pengaturan yang eksplisit, spesifik, dan komprehensif dalam satu undang-undang, seperti KUHAP, sering kali menyebabkan hambatan dan masalah dalam implementasi di lapangan.
Syarat dan Kriteria Kualifikasi
Proses penetapan status Justice Collaborator tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Seorang tersangka atau terdakwa harus memenuhi serangkaian syarat ketat yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU PSK. Syarat-syarat tersebut meliputi:
- Bukan Pelaku Utama: Ini adalah syarat fundamental. Pelaku yang mengajukan diri sebagai JC harus terbukti bukan sebagai otak kejahatan (mastermind) atau memiliki peran dominan dalam tindak pidana yang diungkapkan.
- Pengakuan dan Kerja Sama: Yang bersangkutan harus mengakui perbuatan pidana yang dilakukannya. Pengakuan ini harus disertai dengan kemauan untuk bekerja sama secara konsisten dengan aparat penegak hukum.
- Keterangan yang Signifikan: JC harus mampu memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan, akurat, dan dapat membantu penyidik atau penuntut umum mengungkap kasus secara efektif, termasuk mengidentifikasi pelaku lain yang memiliki peran lebih besar atau mengembalikan aset hasil kejahatan.
- Ancaman Nyata: Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, baik secara fisik maupun psikis, terhadap diri JC atau keluarganya jika kebenaran diungkap. Hal ini menegaskan urgensi perlindungan yang harus diberikan.
Perlu ditekankan bahwa inisiatif untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator umumnya berasal dari terdakwa itu sendiri. Permohonan tersebut kemudian diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Kejaksaan, yang selanjutnya akan diverifikasi dan dipertimbangkan oleh majelis hakim di persidangan.
Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
LPSK memiliki peran krusial dalam mekanisme Justice Collaborator. Meskipun regulasi belum sepenuhnya terpadu, LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan menelaah permohonan saksi pelaku. Setelah menerima permohonan, LPSK akan melakukan penilaian komprehensif untuk memastikan bahwa pemohon memenuhi syarat sebagai JC, termasuk evaluasi terhadap tingkat ancaman yang dihadapi dan signifikansi informasi yang diberikan.
Rekomendasi dari LPSK, bersama dengan pengajuan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), menjadi salah satu pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam memutuskan apakah status JC dapat diberikan. Peran LPSK memastikan bahwa hak-hak JC terpenuhi dan perlindungan yang dibutuhkan diberikan secara efektif, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.
Analisis Mendalam: Fragmentasi Regulasi dan Ketidakpastian Hukum
Kerangka hukum untuk Justice Collaborator di Indonesia, yang tersebar di berbagai instrumen hukum seperti UU PSK, SEMA, dan Peraturan Bersama, menciptakan tantangan serius. Kurangnya satu undang-undang yang khusus dan komprehensif mengenai JC menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapannya di lapangan. Fenomena ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi dan pemahaman di antara aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim.
Dampak dari fragmentasi ini terlihat dalam putusan-putusan pengadilan yang tidak selaras, di mana ada kasus yang memberikan keringanan hukuman kepada JC, sementara kasus lain dengan situasi serupa tidak. Misalnya, dalam kasus korupsi KTP elektronik, putusan hakim menunjukkan adanya inkonsistensi, di mana hakim dianggap membuat hukum baru alih-alih menggunakan ketentuan yang sudah ada. Kondisi ini melemahkan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan dapat mengurangi efektivitas JC sebagai instrumen hukum. Sinkronisasi regulasi dan persamaan persepsi antarlembaga penegak hukum menjadi prasyarat esensial untuk mengatasi kendala ini.
Hak, Perlindungan, dan Penghargaan
Bentuk-bentuk Perlindungan dan Hak Istimewa
Seorang individu yang berstatus Justice Collaborator menghadapi risiko ancaman yang sangat besar dari pelaku kejahatan lain yang merasa dirugikan oleh kesaksiannya. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan yang komprehensif. Bentuk perlindungan ini diatur dalam UU PSK dan praktik yang telah berjalan, mencakup:
- Perlindungan Fisik dan Psikologis: LPSK bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda JC dari ancaman fisik maupun psikis.
- Penanganan Khusus: Dalam proses peradilan, JC mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini meliputi pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana dari pelaku kejahatan lainnya.
- Kerahasiaan Identitas: Identitas JC dan data terkait prosesnya dijamin kerahasiaannya untuk melindungi keselamatan dirinya dan keluarganya.
- Kesaksian Tanpa Bertatap Muka: JC berhak memberikan kesaksian di persidangan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkapkan kejahatannya. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan tekanan psikologis dan ancaman yang mungkin terjadi.
Insentif dan Penghargaan Utama: Keringanan Hukuman
Keringanan hukuman adalah bentuk penghargaan paling signifikan yang diberikan kepada Justice Collaborator. Penghargaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan imbalan atas kontribusi substansial JC dalam membantu penegak hukum. Keringanan hukuman ini dapat berbentuk:
- Pidana Paling Ringan: Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang sama.
- Pidana Percobaan: Dalam kasus-kasus tertentu, hakim dapat menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus.
- Remisi dan Pembebasan Bersyarat: Bagi JC yang sudah berstatus narapidana, penghargaan dapat berupa remisi tambahan atau pembebasan bersyarat.
Penjatuhan keringanan hukuman ini merupakan domain mutlak dari majelis hakim setelah mempertimbangkan rekomendasi dari JPU dan LPSK, serta menilai secara mendalam kontribusi yang diberikan oleh JC.
Analisis Mendalam: Keringanan Hukuman sebagai Kompromi Strategis
Pemberian keringanan hukuman kepada seorang pelaku kejahatan seringkali menimbulkan perdebatan. Namun, dari sudut pandang hukum yang instrumental, keringanan ini adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan yang lebih sulit dan lebih besar, yaitu pemulihan kerugian negara dan penegakan hukum yang menyeluruh terhadap jaringan kejahatan. Insentif ini memungkinkan penegak hukum untuk mengungkap pelaku-pelaku utama yang seringkali memiliki pengaruh dan kekuasaan lebih besar, yang jika tidak diungkapkan, akan terus merugikan masyarakat. Keringanan hukuman, dalam hal ini, dipandang sebagai harga yang wajar untuk dibayar demi memastikan bahwa keadilan substantif tercapai, aset-aset kejahatan dapat dikembalikan, dan seluruh jejaring kejahatan dapat dihancurkan.
Analisis Komparatif dan Konsep Serupa
Perbedaan Mendalam: Justice Collaborator vs. Whistleblower
Seringkali terjadi kekeliruan dalam memahami perbedaan antara Justice Collaborator (JC) dan Whistleblower. Meskipun keduanya sama-sama berperan dalam mengungkap kejahatan, perbedaan fundamental terletak pada status hukum dan keterlibatannya. Whistleblower didefinisikan sebagai pelapor yang memberikan informasi atau laporan mengenai suatu tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi, tanpa terlibat dalam perbuatan pidana tersebut. Ia adalah individu dari luar lingkaran kejahatan yang termotivasi oleh kesadaran moral untuk melaporkan pelanggaran. Sebaliknya, seorang Justice Collaborator adalah pelaku yang aktif terlibat dalam kejahatan, mengakui perbuatannya, dan bekerja sama untuk mengungkap pelaku lain.
Perbandingan Kritis: Justice Collaborator vs. Saksi Mahkota (Crown Witness)
Konsep Saksi Mahkota (Crown Witness) memiliki kemiripan yang signifikan dengan Justice Collaborator karena keduanya berasal dari salah satu pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang memisahkan keduanya, baik secara normatif maupun praktis, sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut:
| Kriteria | Justice Collaborator (JC) | Saksi Mahkota (Crown Witness) |
| Status Hukum | Terdakwa/tersangka yang statusnya tidak selalu dicabut saat bersaksi. | Terdakwa yang statusnya dicabut dan diangkat menjadi saksi untuk terdakwa lain. |
| Jenis Kejahatan | Dikhususkan untuk tindak pidana serius dan terorganisir (misalnya korupsi, terorisme). | Dapat digunakan untuk semua jenis tindak pidana. |
| Inisiatif Pengajuan | Inisiatif berasal dari terdakwa itu sendiri melalui permohonan kepada penegak hukum. | Inisiatif berasal dari Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan salah satu terdakwa menjadi saksi. |
| Motivasi | Keringanan hukuman dan perlindungan. | Keterangan diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa lain. |
| Landasan Regulasi | UU No. 31/2014 dan SEMA No. 4/2011. | Praktik hukum dalam KUHAP, meskipun konsepnya menuai perdebatan. |
Analisis Mendalam: Pendekatan Filosofis yang Berbeda
Perbedaan antara Justice Collaborator, Whistleblower, dan Saksi Mahkota mencerminkan pendekatan filosofis yang berbeda dalam mengungkap kebenaran dalam suatu perkara pidana. Whistleblower merepresentasikan peran moral dari masyarakat sipil yang berdiri di luar lingkaran kejahatan. Saksi Mahkota adalah alat prosedural yang lahir dari kebutuhan praktis penegak hukum untuk mengatasi kesulitan pembuktian. Sementara itu, Justice Collaborator adalah sebuah “kesepakatan” yang pragmatis, di mana sistem hukum menawarkan imbalan kepada pelaku yang bersedia kooperatif. Memahami ketiga konsep ini sangat penting karena hal tersebut menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana berupaya beradaptasi dengan kompleksitas kejahatan modern yang terorganisir, menggunakan berbagai mekanisme untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif.
Studi Kasus dan Penerapan Empiris
Peran Justice Collaborator dalam Kasus-kasus Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa di mana peran Justice Collaborator sangat dibutuhkan. Kasus-kasus korupsi sering melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir, sehingga sulit diungkap secara menyeluruh. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kasus korupsi KTP elektronik, yang menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto.
Setya Novanto sempat mengajukan permohonan untuk menjadi Justice Collaborator kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru bicara KPK pada saat itu, Febri Diansyah, menjelaskan bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan jika Setya Novanto memenuhi tiga syarat utama: mengakui perbuatannya, bersedia membuka peran pihak lain yang lebih besar, dan memberikan keterangan yang konsisten selama proses penyidikan dan persidangan. Kasus ini menunjukkan bahwa penetapan status JC tidak bisa hanya didasarkan pada permohonan semata, melainkan memerlukan verifikasi ketat terhadap kontribusi yang diberikan. Kasus lain, seperti putusan terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus yang sama, juga menyoroti adanya disharmoni dan inkonsistensi putusan hakim terkait perlakuan terhadap JC.
Studi Khusus: Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo
Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, menjadi tonggak penting dalam penerapan konsep Justice Collaborator di Indonesia. Kasus ini bukan hanya menyoroti kejahatan, tetapi juga menguji kredibilitas sistem peradilan di mata publik.
Peran kunci dalam pengungkapan kasus ini dimainkan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang pada awalnya adalah salah satu terdakwa. Eliezer mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dan memberikan keterangan yang jujur, yang bertentangan dengan skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Kesaksiannya menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap kronologi kejadian yang sebenarnya, termasuk peran Ferdy Sambo sebagai otak kejahatan.
Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan peran Eliezer sebagai Justice Collaborator sebagai salah satu faktor yang meringankan. Akibatnya, ia divonis 1,5 tahun penjara, jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa dan putusan terhadap pelaku lainnya. Sementara itu, Ferdy Sambo divonis mati (kemudian diringankan menjadi seumur hidup di tingkat kasasi), dan pelaku lain menerima hukuman yang berat.
Analisis Mendalam: Validasi Empiris dan Kepercayaan Publik
Kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak hanya menjadi contoh konkret penerapan Justice Collaborator, tetapi juga memberikan validasi empiris dan legitimasi publik yang kuat terhadap mekanisme ini. Mengingat tingginya skeptisisme publik terhadap kemungkinan impunitas pejabat, putusan yang diberikan kepada Eliezer mengirimkan sinyal kuat bahwa sistem hukum menghargai kejujuran dan kerja sama dalam mengungkap kebenaran.
Putusan tersebut sejalan dengan prinsip yang diatur dalam SEMA No. 4/2011 dan UU PSK, di mana keringanan hukuman diberikan sebagai penghargaan atas kontribusi signifikan seorang JC. Putusan ini berhasil memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menunjukkan bahwa Justice Collaborator bukan sekadar jargon hukum, melainkan alat yang efektif untuk mencapai keadilan.
| Nama Kasus | Nama Justice Collaborator (JC) | Jenis Kejahatan | Peran Utama JC | Bentuk Keringanan Hukuman |
| Kasus E-KTP | Setya Novanto (memohon) | Korupsi | Memohon status JC untuk mengungkap aktor lain. | Tidak dikabulkan karena dianggap pelaku utama dan tidak konsisten. |
| Kasus Ferdy Sambo | Richard Eliezer Pudihang Lumiu | Pembunuhan Berencana | Memberikan kesaksian yang membongkar skenario pelaku utama. | Divonis 1,5 tahun penjara, jauh lebih ringan dari pelaku lain. |
Problematika, Tantangan, dan Rekomendasi
Kendala Implementasi dan Tantangan Normatif
Meskipun memiliki peran strategis, implementasi konsep Justice Collaborator di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utama berasal dari sisi normatif, yaitu ketiadaan regulasi tunggal yang secara eksplisit, jelas, dan pasti mengatur tentang JC. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menciptakan keseragaman persepsi di antara aparat penegak hukum. Selain itu, keterangan yang diberikan oleh JC masih memerlukan pembuktian secara yudisial, dan keandalan informasi yang diberikan menjadi elemen yang sangat krusial dalam proses peradilan.
Pro-Kontra dan Perdebatan Hukum
Pemberian keringanan hukuman bagi pelaku kejahatan, meskipun berstatus JC, seringkali memicu pro-kontra di tengah masyarakat. Salah satu perdebatan hukum yang muncul adalah mengenai waktu penetapan status JC. Ada pandangan, seperti yang dikemukakan oleh Hakim Agung Surya Jaya, bahwa status JC seharusnya diberikan pada tahap penyidikan, bukan setelah putusan pengadilan, untuk menghindari adanya “transaksi dan alat negosiasi” yang dapat mencederai keadilan. Perdebatan ini menyoroti risiko etis dan prosedural yang melekat pada penerapan konsep ini, di mana ada kekhawatiran bahwa JC bisa menjadi alat tawar-menawar untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan tanpa kontribusi yang signifikan.
Prospek dan Rekomendasi Kebijakan
Untuk mengoptimalkan peran Justice Collaborator, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif. Pertama, pengaturan mengenai JC harus diintegrasikan ke dalam revisi KUHAP. Hal ini akan memberikan pedoman dan dasar hukum yang jelas, sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi di antara para penegak hukum dan menghindari tumpang tindih regulasi.
Kedua, perlu adanya peningkatan sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dengan LPSK. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan dan penghargaan bagi JC dapat terwujud secara optimal.
Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan program khusus untuk perlindungan JC dari ancaman serius, sebagaimana praktik yang telah diterapkan di beberapa negara lain.
Analisis Mendalam: Perbaikan Struktural dan Budaya
Perbaikan terhadap mekanisme Justice Collaborator tidak hanya membutuhkan perubahan pada level regulasi, tetapi juga pada level struktural dan budaya di dalam lembaga penegak hukum. Analisis menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada inkonsistensi implementasi dan perbedaan pemahaman kolektif. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus mencakup tidak hanya perbaikan normatif, tetapi juga pelatihan, koordinasi, dan perubahan budaya kelembagaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsep JC dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik dan dapat menjadi instrumen yang benar-benar efektif dalam memberantas kejahatan terorganisir di Indonesia.
Kesimpulan
Laporan ini menyimpulkan bahwa konsep Justice Collaborator adalah instrumen yang vital dan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam upaya mengungkap kejahatan terorganisir dan luar biasa. Keberadaannya, yang berakar dari adopsi konvensi internasional dan diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA, menunjukkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif murni menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil.
Meskipun penerapan JC telah terbukti efektif dalam kasus-kasus besar, seperti kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan kasus korupsi, masih terdapat tantangan signifikan. Tantangan utama adalah fragmentasi regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan, serta perlunya persamaan persepsi di antara aparat penegak hukum.
Maka dari itu, jalan ke depan bagi Justice Collaborator di Indonesia adalah melalui reformasi yang terpadu, baik secara normatif maupun implementatif. Integrasi aturan JC ke dalam KUHAP, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan pembangunan budaya kelembagaan yang mendukung kejujuran dan kerja sama menjadi kunci untuk memastikan bahwa Justice Collaborator dapat terus menjadi alat yang efektif dan tepercaya dalam mewujudkan keadilan di masa depan.